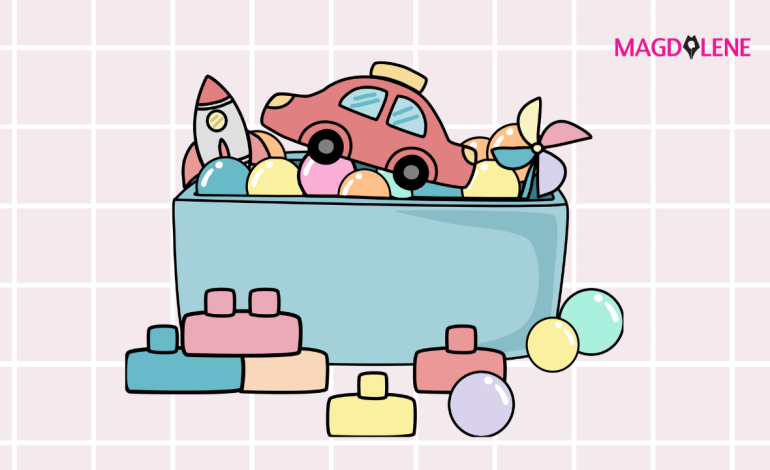Saya Ngobrol dengan Anak Buruh Migran tentang Luka ‘Ditinggal’ Orang Tua

Setiap tahun, ratusan ribu warga Indonesia pergi ke luar negeri untuk bekerja. Lebih dari lima juta pekerja migran Indonesia (termasuk orang tua yang sudah memiliki anak) bekerja di lebih dari 25 negara di seluruh dunia. Jumlahnya terus bertambah dalam kurun tiga tahun, dari 72.624 pada 2020 menjadi 274.964 pada 2023.
Ada banyak diskusi mengenai perlindungan dan keselamatan pekerja migran Indonesia selama mencari nafkah di negeri orang. Namun, kondisi anak-anak yang mereka tinggalkan sering kali luput dari perhatian.
Studi terbaru kami menemukan bahwa anak-anak yang ditinggalkan pekerja migran sangat rentan mengalami masalah sosial dan emosional akibat tinggal terpisah dari orang tua mereka. Sering kali, mereka tidak menerima dukungan moral, emosional, sosial, dan finansial yang memadai dari masyarakat, pemerintah, maupun organisasi nonpemerintah.
Dalam riset ini, kami mewawancarai 24 anak berusia 14-18 tahun yang ditinggalkan orang tuanya bekerja ke luar negeri. Pengumpulan data berlangsung selama beberapa bulan di Kabupaten Belu dan Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kedua kabupaten tersebut bersama kabupaten lain di NTT mengirim ratusan tenaga kerja ke luar negeri setiap tahun. Anak-anak yang ditinggalkan biasanya diasuh oleh anggota keluarga besar lain, seperti kakek-nenek, tante, dan paman.
Baca juga: Sulitnya Anak Buruh Migran Sekolah di Malaysia, Apa Kendalanya?
Tantangan Sosial
Penelitian sebelumnya di beberapa negara lain melaporkan bahwa anak-anak yang ditinggalkan orang tua pekerja migran mengalami berbagai tantangan sosial. Ini serupa dengan anak-anak yang kami wawancara di Indonesia.
Mereka mengalami persoalan dalam relasi sosial dengan teman-temannya, seperti diejek, dicemooh, dan diberi label negatif sebagai anak yang tidak memiliki orang tua. Hal ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan kehidupan sosial mereka.
Seorang anak perempuan yang ditinggalkan kedua orang tuanya bermigrasi ke Kalimantan bercerita:
“Kadang saya berdebat dengan teman-teman saya, dan yang membuat saya sedih adalah beberapa dari mereka mengatakan bahwa saya adalah anak yang tidak memiliki orang tua. Mereka juga sering mengejek jika saya menangis, mereka berkata: ‘Kamu tidak memiliki orang tua di sini, sedih hidup tanpa ibu dan ayah’. Jadi, saya tidak ingin bergaul dengan mereka.”
Anak-anak yang ditinggalkan juga mengalami perubahan peran dalam keluarga. Mereka terpaksa ikut bertanggung jawab untuk pekerjaan rumah tangga sehari-hari, seperti membersihkan rumah, mencuci, memasak, mengasuh anak, dan memelihara ternak. Ini bukan hal yang mudah bagi anak-anak seusia mereka.
Tanggung jawab dan tugas rutin seperti ini sering kali membatasi, bahkan mencegah partisipasi mereka dalam aktivitas sosial dan kegiatan ekstrakurikuler dengan teman-temannya seusai sekolah. Hal ini berdampak negatif terhadap relasi, kehidupan, dan kesejahteraan sosial anak pekerja migran.
Seorang anak laki-laki yang ayahnya bekerja ke Malaysia sejak beberapa tahun lalu, mengatakan:
“Saya rasa banyak sekali yang harus dilakukan di rumah sejak ayah saya pergi. Saya harus memberi makan babi dan ayam di pagi dan sore hari. Saya harus mengambil rumput untuk sapi setiap sore. Saya juga menjaga adik-adik di rumah. Saya hampir tidak pernah bergaul dengan teman-teman sejak ayah pergi. Terkadang, saya merasa kesal dan stres, tetapi saya harus membantu ibu.”
Baca juga: Derita Anak Buruh Migran: Ditinggalkan Orang Tua, Jadi Korban Kekerasan
Tantangan Psikologis
Hasil wawancara dengan anak-anak tersebut juga mengungkapkan berbagai tantangan psikologis yang mereka hadapi.
Mereka mengalami keretakan ikatan emosional dengan orang tua yang bermigrasi. Hal ini tercermin dari perasaan sedih yang mendalam dan berkepanjangan, stres, kehilangan minat terhadap aktivitas harian, dan kerinduan mereka akan kehadiran orang tua.
Salah satu anak perempuan yang kami wawancara merasa mengalami keretakan ikatan emosional dengan ayahnya yang bermigrasi ke Malaysia. Ia mengatakan:
“Rasanya seperti kehilangan ayah. Saya sangat dekat dengannya, selalu tidur di sampingnya setiap malam sebelum ia pergi. Saya sering menangis selama berbulan-bulan. Saya sangat sedih. Butuh waktu berbulan-bulan bagi saya untuk belajar hidup tanpa ayah di rumah.”
Riset kami menemukan dampak emosional yang dialami anak-anak didorong pula oleh beberapa faktor lain, seperti tidak dilibatkannya mereka dalam pembahasan mengenai rencana migrasi orang tua. Mereka tidak dipersiapkan untuk hidup tanpa orang tua dan secara mendadak hanya diberi tahu bahwa orang tuanya akan pergi. Berbagai kendala pun menyebabkan terputusnya komunikasi mereka dengan orang tua setelah bermigrasi.
Selain itu, transisi ke dalam situasi kehidupan baru bersama pengasuh, berdampak negatif terhadap keadaan mental mereka. Anak-anak perlu upaya ekstra untuk beradaptasi dengan rutinitas dan kehidupan baru. Hal ini sering membuat mereka merasa terbebani, stres, sedih, dan marah.
Salah satu anak berkata:
“Tante dan suaminya punya aturan dalam keluarga mereka yang harus saya patuhi; rutinitas sehari-hari terasa memberatkan. Saya sering merasa stres, dan marah, tetapi saya hanya bisa menangis. Rasanya sangat menyedihkan saat itu.”
Tidak hanya itu, sikap kasar dan tindakan disiplin pengasuh yang dirasakan berbeda dari sikap dan perilaku orang tua mereka menyebabkan anak-anak merasa takut, sedih dan tersakiti.
Studi kami menemukan tidak terpenuhinnya kebutuhan dasar anak-anak dalam keluarga berpengaruh negatif terhadap kondisi kesehatan mental mereka. Akibat berbagai kesulitan yang dihadapi, anak-anak pekerja migran sering merasa tidak puas dan sedih dengan situasi kehidupannya, serta kasihan terhadap ibu ataupun pengasuh mereka.
Dua orang anak perempuan yang kami wawancara bercerita:
“Kakek dan nenek sangat kesulitan untuk menyediakan makanan bagi kami. Kadang-kadang kami hanya makan singkong.”
“Saya merasa sedih dan kasihan kepada ibu. Ibu berjuang mati-matian untuk mengurus kami semua. Terkadang saya melihat ibu menangis, dan itu benar-benar menyakitkan bagi saya.”
Beberapa anak juga bercerita mengenai tidak terpenuhinya kebutuhan sekolah mereka. Mereka tidak mampu membayar uang sekolah, sulit membeli alat tulis maupun seragam. Hal ini membuat mereka malu, sedih, dan rendah diri. Salah satu anak berkata:
“Saya tidak punya buku, pensil, pulpen, dan seragam baru. Saya sedih. Ibu saya tidak mampu membeli.”
Anak lainnya berkata:
“Biaya sekolah saya sering terlambat dibayarkan. Saya sering merasa sangat malu.”
Baca juga: Pengasuh atau PRT? Perhatian Kurang, Tuntutan Kerja Rangkap Tinggi
Pentingnya Perhatian Pemerintah
Temuan dalam studi ini menyoroti pentingnya membentuk inisiatif dalam masyarakat, seperti bimbingan sebaya, serta kegiatan ekstrakurikuler maupun rekreasi.
Inisiatif seperti ini dapat menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi mereka, sekaligus mendorong hubungan positif dengan orang lain di dalam komunitas.
Temuan ini juga diharapkan dapat mendorong pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kebijakan terkait program sosial dan memastikan program-program tersebut mencakup keluarga yang merawat anak-anak yang ditinggalkan orang tua perkerja migran.
Nelsensius Klau Fauk, Senior Research Fellow, public health, Torrens University Australia and Paul Ward, Professor of Public Health, Torrens University Australia.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.