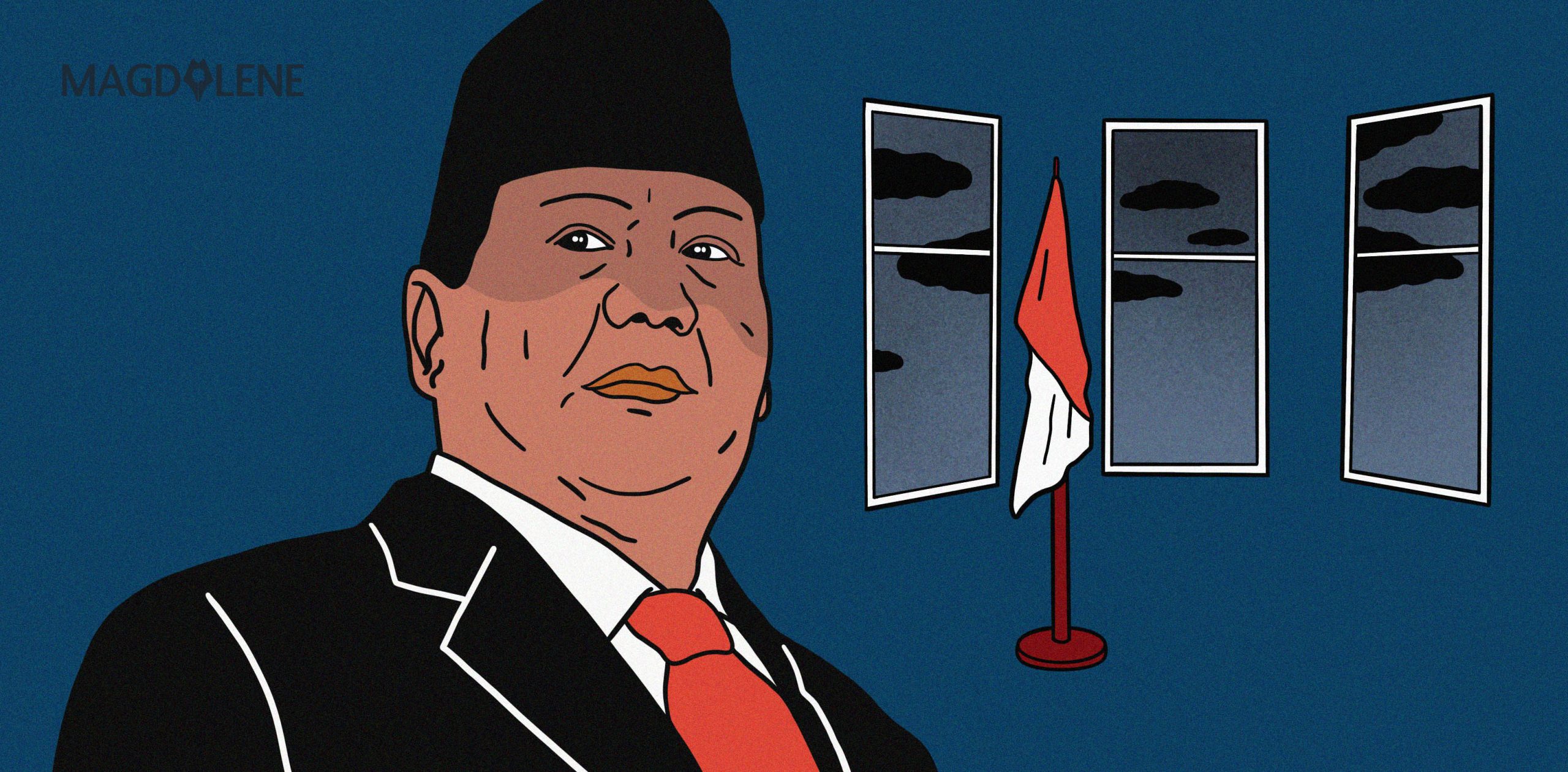Minoritas Paling Tertindas di Dunia: Kenapa Rohingnya juga Isu Feminis
Predikat Rohingya sebagai “minoritas yang paling tertindas di dunia” bukan isapan jempol belaka. Kekerasan yang mereka alami berlapis dan kebebasannya perlu dibela.

Kejadian bermula saat para mahasiswa dari Universitas Al Washliyah, Universitas Abulyatama dan Bina Bangsa Getsem melakukan unjuk rasa di depan Gedung Balee Meuseuraya Aceh (BMA) di Aceh pada 27 Desember lalu. Di dalam gedung itu terdapat ratusan pengungsi Rohingnya yang tengah mencari suaka sementara.
Para mahasiswa berorasi dan berteriak “usir mereka keluar” dan “tolak etnis Rohingya di Aceh”. Tak lama mereka pun berlari masuk ke basemen tempat para pengungsi berada. Di sana, para mahasiswa menarik paksa, menendang barang-barang, bahkan melempar botol air mineral ke arah pengungsi yang didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Tangisan pecah tak terbendung. Salah satunya berasal dari Rohimatun, ibu tunggal tiga anak yang pergi ke Aceh karena menerima ancaman yang bertubi-tubi di kamp Cox Bazar, Bangladesh.
“Kami sangat ketakutan dan kesakitan, sehingga menangis. Karena saudara seiman, saya tidak menyangka mereka memperlakukan kami dengan tidak manusiawi seperti itu,” katanya.
Persekusi mahasiswa Aceh atas Rohingnya ini sontak mendapat kecaman dari masyarakat dunia, tak terkecuali dari perempuan jurnalis muslim Palestina, Hebh Jamal. Dalam unggahan Instagram Story yang disusul dengan unggahan feeds akun Instagram dan X pribadinya, Jamal menegaskan bahwa Palestina tidak membutuhkan dukungan dari masyarakat yang melakukan tebang pilih pada kemanusiaan.
Ia bilang masyarakat Indonesia (yang membenci dan mempersekusi Rohingnya) sebagai munafik. Menurut Jamal, pembelaan mati-matian terhadap Palestina tidak akan berarti apa-apa jika di saat bersamaan masyarakat Indonesia tidak mendukung pembebasan dan kelangsungan hidup pengungsi di mana pun.
Baca Juga: Pengungsi Rohingya di Tengah Ketidakpastian: 3 Solusi buat Pemerintah
Persekusi yang Jadi Warisan Kolonialisme Inggris
Rohingya dinobatkan sebagai “minoritas yang paling tertindas di dunia” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah genosida Rwanda dan Yugoslavia. Julukan ini disematkan bukan tanpa sebab. Nyatanya, Rohingnya memang telah mengalami kekerasan sistematis dan berlapis selama puluhan tahun lamanya dan ini bermula sejak kolonialisme Inggris.
Mengutip dari penelitian History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya Muslims (2018) dan artikel The Conversation, selama periode kolonialisasi yang berlangsung lebih dari satu abad Inggris menggalakkan berbagai pembangunan. Karena kebutuhan atas pekerja kasar, Inggris mendorong migrasi massal pekerja dari India sampai Bangladesh yang mayoritas beragama Islam.
Salah satu destinasi dari migrasi massal ini adalah Arakan (sekarang negara bagian Rakhine, tempat sebagian besar orang Rohingya tinggal). Para pekerja muslim dari Bengal dan Chittagong sengaja dipindahkan untuk bekerja di lahan kosong untuk menanam padi, buah-buahan, dan tembakau untuk kepentingan kolonial.
Selama periode ini, Inggris menjanjikan Rohingya tanah terpisah yang mereka sebut sebagai “Wilayah Nasional Muslim” sebagai ganti kerja dan dukungan mereka karena telah berpihak ke Inggris selama Perang Dunia II. Sesudah perang, Inggris menghadiahi Rohingya posisi-posisi birokrasi pemerintahan yang cukup bergengsi tetapi janji soal tanah terpisah ini tak juga dipenuhi.
Perlakukan Inggris pada Rohingnya ini jadi awal sentimen orang-orang Buddha di Myanmar. Mereka menilai Inggris sudah berlaku tidak adil dan orang Islam (Rohingnya) telah merebut paksa tanah mereka. Nasionalisme berlandaskan agama pun mulai tumbuh menjadi pendorong gerakan pembebasan masyarakat Myanmar dari kolonialisme di Inggris.
Sayangnya, di saat bersamaan nasionalisme ini juga diantagonisasi untuk mempersekusi kelompok Rohingnya. Sesudah kemerdekaan, masyarakat Rohingya meminta wilayah otonom yang dulu dijanjikan, tetapi pemerintah Myanmar menolak permintaan mereka. Pemerintah juga menolak memberikan kewarganegaraan dengan berpegang pada gagasan bahwa tanah Myanmar adalah milik orang Budha, asli Myanmar sedangkan Rohingnya adalah orang asing yang perlu diusir.
Pada 1950, beberapa orang Rohingya memberontak terhadap kebijakan pemerintah Myanmar ini, tetapi gerakan pemberontakan berhasil dihancurkan. Selang dua belas tahun, pada 1962 berkat kudeta militer Myanmar menjadi negara militer satu partai. Selama 60 tahun militer berkuasa, demonisasi Rohingnya semakin kuat dilakukan untuk menggalang dukungan masyarakat Buddha di Myanmar.
Para pejabat mencap kelompok minoritas ini sebagai ancaman terhadap identitas nasional. Mereka mulai melarang organisasi-organisasi sosial dan politik Rohingya. Mereka lalu memindahkan kuasa usaha swasta milik Rohingya kepada pemerintah demi melemahkan kelompok tersebut secara finansial.
Tak sampai situ saja, kelompok Rohingya juga mengalami kerja paksa, penahanan tanpa peradilan, dan serangan fisik. Pada 1977, tentara meluncurkan program nasional pencatatan warga, orang-orang Rohingya dianggap warga ilegal. Lebih dari 200.000 melarikan diri ke Bangladesh pada saat itu karena banyak dari mereka dibunuh dan para perempuannya diperkosa. Para pejabat negara menyebutkan larinya Rohingnya ke Bangladesh sebagai bukti status ilegal mereka.
Persekusi Rohingnya semakin tak terelakkan manakala Undang-undang Kewarganegaraan Myanmar disahkan pada 1982. UU ini mensyaratkan leluhur seseorang haruslah kelompok ras yang ada di Myanmar sebelum penjajahan Inggris. Rohingnya secara formal lalu ditolak pemerintah sebagai bagian dari warga negara Myanmar karena masih dikelompokkan sebagai imigran ilegal yang diizinkan masuk oleh penjajah Inggris.
Namun, menurut laporan Human Rights Watch walaupun ada migrasi massal pekerja muslim ke Burma selama kolonialisme Inggris, Rohingya nyatanya sudah lama menetap di wilayah itu. Dalam catatan sejarah, Rohingnya dianggap sebagai bagian dari kerajaan Mrauk-U (Mrohaung) di Arakan yang berdiri secara independen dari kerajaan-kerajaan Burma di delta Irrawaddy dan Burma tengah, serta Benggala dan Mogul di sebelah barat.
Para pedagang Muslim datang ke daerah tersebut pada abad ke-8 ketika dinasti lokal duduk di Wesali, tidak jauh dari Mrauk-U saat ini dan beberapa pedagang menetap di sepanjang pantai. Lebih banyak pelaut Muslim yang datang ke wilayah Arakan pada abad ke-12 dan 13. Para migran juga secara bertahap masuk ke Arakan dari negara tetangga, Benggala Muslim. Lewat catatan sejarah ini klaim bahwa Rohingnya murni adalah imigran gelap yang “diselundupkan” Inggris sebenarnya telah dibantah.
Baca Juga: Perempuan Pengungsi di Indonesia dalam Belenggu Diskriminasi
Diperlakukan layaknya Bukan Manusia di Negara Sendiri dan Orang lain
Penyangkalan kewarganegaraan membuat kelompok Rohingnya mengalami kekerasan berlapis. Salah satu kekerasan yang terdokumentasikan ini adalah sistem apartheid atau kejahatan kemanusiaan yang berupa sistem segregasi rasial yang dilembagakan. Amnesty Internasional pada 2017 melaporkan Rohingnya mengalami pembatasan gerak yang ketat. Pembatasan ini diterapkan melalui jaringan hukum nasional yang diturunkan lewat pembangunan pos pemeriksaan, pagar kawat berduri yang mengelilingi desa-desa dan kamp pengungsian, pemberlakukan jam malam, dan prosedur perizinan.
Dalam praktiknya, warga Rohingnya tidak diperbolehkan menggunakan jalan raya dan hanya dapat melakukan perjalanan melalui jalur air dan ke desa-desa Muslim lainnya. Bahkan ketika warga Rohingya berhasil mendapatkan izin, kekerasan tetap tidak terelakan. Warga Rohingnya yang harus melewati pos pemeriksaan—sebagian besar dikelola oleh Polisi Penjaga Perbatasan (BGP) sering dilecehkan, dipaksa membayar suap, diserang secara fisik atau ditangkap.
Saat melakukan penelitian untuk laporan tersebut, staf Amnesty International melihat secara langsung seorang penjaga perbatasan menendang laki-laki Rohingya di sebuah pos pemeriksaan. Staf Amnesty International juga mendokumentasikan setidaknya satu kasus eksekusi di luar hukum, ketika petugas BGP menembak mati laki-laki berusia 23 tahun yang sedang melakukan perjalanan selama pemberlakuan jam malam.
Pembatasan pergerakan ini lebih lanjut disampaikan dalam laporan Human Rights Watch termanifestasi dalam pembatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Sebagian besar akses kesehatan warga Rohingnya terbatas pada klinik dasar di kamp yang dioperasikan oleh organisasi non-pemerintah. Klinik yang dalam beberapa tahun terakhir juga mulai sedikit mendapatkan bantuan dana karena memang dibatasi oleh pemerintah Myanmar.
Satu-satunya rumah sakit umum, yaitu Rumah Sakit Umum Sittwe memerlukan biaya mahal dan proses rujukan yang sulit, bahkan untuk kasus-kasus yang mengancam jiwa. Jika berhasil masuk, pasien Muslim tetap mengalami diskriminasi. Mereka dirawat di bangsal terpisah dengan penjagaan dan donor darah hanya diperuntukkan bagi etnis Rakhine Buddhis saja. Tak mengherankan, kematian ibu selama persalinan dan bayi baru lahir pun jadi kasus umum yang ditemui.
“Sulit untuk mencegah masalah selama persalinan. Para perempuan di kamp melahirkan dengan pendamping tidak terlatih. Mereka kurang mendapatkan perawatan medis, jadi seringkali ibu dan anak meninggal,” kata Myo Myint Oo, kata salah satu warga Rohingnya tentang risiko yang mengancam jiwa bagi ibu hamil dan bayi baru lahir.
Masalahnya tidak berakhir di Myanmar saja. Ketika Rohingnya mencari suaka sementara ke negara lain, mereka juga mengalami persekusi yang kurang lebih sama. Di Bangladesh, negara yang paling banyak menampung pengungsi Rohingnya sejak Desember 2021 telah melarang sekolah-sekolah yang didirikan oleh para guru Rohingya. Bangladesh juga melarang kelompok kemanusiaan memberikan pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya di luar kelas dasar, informal, dan tingkat dasar.
“Pertama, pemerintah memblokir pendidikan yang berarti bagi anak-anak Rohingya, kemudian menutup sekolah-sekolah yang didirikan oleh orang-orang Rohingya, dan sekarang pemerintah mengancam akan membuang guru dan siswa ke pulau seperti penjara,” kata Bill Van Esveld, direktur asosiasi hak-hak anak di Human Rights Watch.
Toko-toko kecil yang didirikan oleh warga Rohingya sebagai sumber pendapatan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar juga jadi sasaran otoritas Bangladesh. Mulai bulan Oktober 2021, para pejabat mulai melibas toko-toko di beberapa kamp, seringkali tanpa pemberitahuan. Lebih dari 3.000 toko hancur dan berdampak pada puluhan ribu pengungsi.
Ketika pemerintah Bangladesh mulai memindahkan pengungsi Rohingnya, Bhasan Char sebuah pulau di Upazila Hatiya, Bangladesh kehidupan mereka pun tak jua membaik. Walaupun dijanjikan hidup layak, Southeast Asia Globe pada 2022 menyebutkan dalam laporannya Bhasan Char adalah “Pulau Penjara” dengan sedikit lapangan pekerjaan, pembatasan pergerakan, dan minimnya akses layanan kesehatan.
Akses ke dan dari Bhasan Char dikontrol ketat oleh angkatan laut dan penjaga pantai Bangladesh. Pulau ini dikelilingi pagar kawat berduri, dan masuk ke pulau ini tanpa izin yang disetujui otoritas Bangladesh merupakan tindakan ilegal. Pembatasan ini membuat kunjungan keluarga semakin sulit. Pulau ini juga bukan tempat bagi orang sakit karena fasilitas kesehatan terbatas dan biaya pengobatan yang mahal.
Menorah Begum, pengungsi Rohingnya yang pindah Bhasan Char kehilangan putranya karena ia tak bisa mendapatkan perawatan kesehatan. Ketika dia meminta bantuan petugas untuk mendapatkan perawatan medis, mereka menyuruhnya menunggu. Namun saat putranya diizinkan pergi, putranya sudah menhembuskan nafas terakhir.
Baca juga: Kenapa Serangan Israel ke Palestina adalah Isu Feminis
Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender Menghantui Perempuan Rohingnya
Jika Rohingnya disebut sebagai minoritas paling tertindas di dunia, julukan ini nampaknya masih belum cukup menggambarkan kedalaman ketertindasan yang secara spesifik dialami oleh perempuan Rohingnya. Dalam laporan Oxfam, organisasi nirlaba dari Inggris pada 2018 dijelaskan perempuan Rohingnya merupakan kelompok rentan yang mengalami kekerasan berbasis gender berlapis dan berulang.
Masyarakat Rohingya adalah masyarakat konservatif yang mengamini norma-norma budaya patriarki. Perempuan jadi bagian struktur sosial terbawah yang tidak diakui otonomi atas tubuh dan agensinya sebagai manusia. Di kamp-kamp pengungsian, anak-anak perempuan dikawinkan paksa dengan dalih untuk meringankan beban ekonomi keluarga.
Ketika ingin keluar dari perkawinan paksa, tidak sedikit pula yang akhirnya terjebak dalam lingkaran perdagangan manusia dan mengalami eksploitasi seksual. Peran tradisional sebagai pengasuh juga jadi biang kerok kekerasan yang dialami perempuan Rohingnya. Perempuan terutama mereka yang kepala keluarga tidak hanya terbebani oleh kerja perawatan dan nafkah keluarga, tapi juga terbebani stigma sosial.
Dalam Rencana Respons Bersama PBB pada 2017 terctat 62 persen pengungsi tidak dapat berkomunikasi (angka yang disinyalir lebih tinggi diperoleh pengungsi permpuan) dengan penyedia bantuan. Oxfam menyebutkan hal ini adalah dampak langsung dari peran tradisional perempuan bahwa mereka harus tinggal di rumah dan tidak berinteraksi dengan laki-laki di luar keluarga dekat mereka.
Tak ayal, rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan pun jadi yang paling kecil kemungkinannya menerima informasi atau berbagai jenis bantuan. Situasi ini mendorong mereka mengambil pekerjaan ilegal dan berbahaya yang justru membuat posisinya semakin rentan dieksploitasi.
Persilangan patriarki dalam etnis mereka sendiri dan kekejaman pemerintah Myanmar sayangnya juga memperdalam jurang ketertindasan atas mereka. Layaknya banyak pemerintah yang mengandalkan kuasanya lewat agresi militer, pemerintah Myanmar menggunakan logika penaklukan berdimensi gender dalam melakukan pembersihan etnis Rohingnya. Ini tak lain adalah lewat pemerkosaan.
Penelitian berjudul Sexual and Gender-Based Violence in the Rohingya Genocide (2022) menyebutkan dari beberapa penelitian dan laporan atas genosida Rohingnya pada 2017, banyak perempuan Rohingya dari anak-anak hingga lansia diperkosa dan dibunuh di depan keluarga mereka. Perempuan hamil dan menyusui dijadikan sasaran mutilasi. Payudara mereka disayat, perutnya digorok, ditendang atau dipukuli, kemudian ditembak dan dilemparkan ke dalam gedung yang terbakar, juga di depan masyarakat/anggota keluarga.
Perempuan dan anak perempuan dibawa ke gedung-gedung terdekat dan diperkosa beramai-ramai, kemudian dilepaskan pada pagi hari. Karena sampai saat ini tidak ada angka pasti atas pemerkosaan massal ini, Amy Rosenberg selaku peneliti memberikan perkiraan dampak kekerasan seksual melalui data jumlah pengungsi Rohingya yang hamil di Bangladesh setelah genosida oleh militer Myanmar pada Agustus 2017. Genosida yang menurut laporan surat kabar Israel Haaretz juga berkaitan erat dengan hubungan militer Israel dan Myanmar.
Antara tanggal 25 Agustus dan 28 September 2017, PBB mencatat terdapat 501.000 pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh. 335.670 di antaranya adalah perempuan, dan 70.000 diantaranya sedang hamil (20,8) persen. Oleh Rosenberg, sebanyak 65.170-66.710 perempuan Rohingya disimpulkan hamil akibat pemerkosaan.
Razia Sultana, pengacara dan peneliti Rohingnya memperkuat klaim Rosenberg. Dalam mengadvokasi hak-hak perempuan Rohingnya, Razia sempat mendokumentasikan ratusan cerita-cerita perempuan Rohingnya yang kabur dari Myanmar selama genosida berlangsung. Cerita yang ia dapat banyak di antaranya merupakan pemerkosaan oleh pasukan keamanan Myanmar yang kemudian ia terbitkan dalam dua laporan, yaitu Witness to Horror dan Rape by Command.
Catharine A. MacKinnon, pengacara dan aktivis feminis Amerika Serikat mengatakan pemerkosaan memang seringkali menjadi alat genosida. Pemerkosaan dalam genosida bekerja dengan cara yang sama seperti kekerasan seksual dalam patriarki. Ia bekerja untuk dengan cara meneror, mengendalikan, dan menundukkan. Alhasil, pemerkosaan meninggalkan rasa takut dan menghasilkan dominasi laki-laki atas kelompok sasaran yang secara langsung menyerang martabat, identitas, dan keamanan individu dan suatu kelompok. Dalam sebuah kelompok yang tertindas, pemerkosaan sangat efektif dalam meredam perlawanan dan membatas habis kemampuan dan keinginan suatu kelompok untuk bertahan hidup.
Myanmar boleh jadi menandatangani CEDAW atau The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Pemerkosaan karenanya dilarang di bawah hukum pidana. Tetapi ironi, perempuan Rohingnya tidak bisa menuntut pemerkosaan yang terjadi atas dirinya. Alasannya sederhana, secara hukum mereka tidak pernah diakui sebagai warga negara Myanmar. Sehingga dalam konstitusi, eksistensi mereka tidak dilindungi oleh pemerintah.
Pada akhirnya, pengalaman ketertindasan perempuan Rohingya adalah bukti nyata jalinan kompleks patriarki, gender, seksualitas, agama, dan etnis. Buat para feminis, ini disebut sebagai interseksionalitas. Kimberlé Crenshaw, profesor hukum Amerika yang menciptakan istilah feminisme interseksional pada 1982 mengatakan ketertindasan beroperasi dengan saling tumpang tindih atau bersinggungan satu sama lain.
Karena itu, feminisme interseksional menuntut kita untuk saling bersolidaritas tanpa tebang pilih. Kita perlu mempertanyakan struktur kekuasaan dan menentang akar penyebab ketidaksetaraan dalam rangka untuk membasmi semua bentuk penindasan.
“Berbahaya jika kita melihat ketidaksetaraan sebagai masalah “mereka” atau masalah yang terpisah dengan kita. Kita harus terbuka untuk melihat semua sistem yang mereproduksi ketidaksetaraan ini, dan itu termasuk hak-hak istimewa dan juga kerugiannya,” katanya dalam wawancara Times pada 2020.
Dengan interseksionalitas, kita membayangkan dan menciptakan kembali sebuah dunia yang bebas dari sistem eksploitasi gender, ras, dan ekonomi yang menghilangkan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Karena itu meminjam ungkapan aktivis Amerika Serikat Fannie Lou Hamer yang diutarakan oleh Hebh Jamal.
“Tidak ada yang benar-benar bebas sampai semua orang bebas.”
Ilustrasi oleh: Karina Tungari