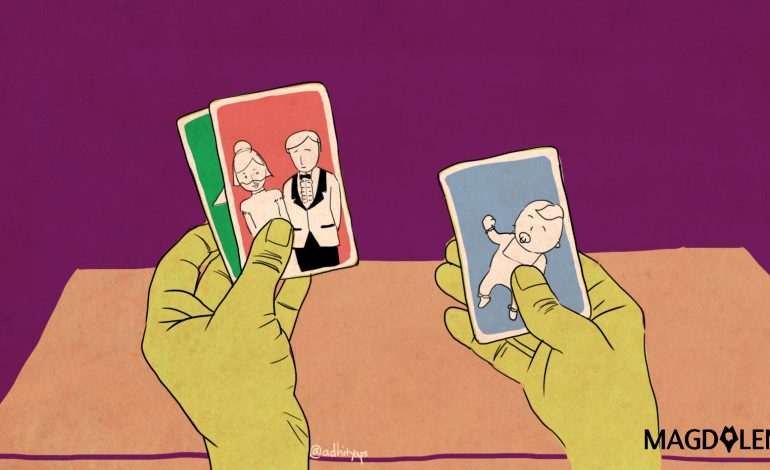‘Saya dan Keadilan’: Ubah Paradigma Lingkungan yang Berpusat pada Manusia

Masyarakat Indonesia baru-baru ini tersentak dengan berita ditemukannya bangkai paus sperma di sekitar Pulau Kapota, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dengan perut yang berisi 1.000 potongan plastik sampai 6 kilogram.
Hal ini juga menjadi sorotan media internasional, lengkap dengan referensi Indonesia adalah negara kepulauan dengan tingkat pencemaran limbah plastik di laut terbesar kedua setelah Cina. Indonesia menghasilkan sekitar 3,2 juta ton sampah plastik setiap tahun, dengan 1,29 juta ton di antaranya berakhir ke laut.
Kondisi krisis lingkungan ini, menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nur Hidayati, tidak terlepas dari pola konsumsi manusia.
“Ketika kita mengonsumsi sesuatu, hampir selalu menghasilkan sampah, dan sampahnya tidak biodegradable. Ini merupakan permasalahan yang pelik, dan ini diakibatkan pola konsumsi dan produksi dari barang-barang yang kita gunakan sehari-hari,” ujarnya dalam temu wicara “Saya dan Keadilan”, Kamis (29/11), pekan lalu di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat.
Temu wicara ini diselenggarakan oleh Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam (UE) serta Badan PBB untuk Program Pembangunan di Indonesia (UNDP Indonesia), melalui proyek EU-UNDP Support to the Justice Sector Reform in Indonesia (SUSTAIN), bekerja sama dengan Magdalene.
Nur mengatakan, lingkungan hidup kita saat ini sedang mengalami banyak permasalahan mulai dari kerusakan hutan, pencemaran air, serta perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrem.
“Saat ini kondisi hutan di Indonesia mengalami kerusakan yang sangat parah. Ini menimbulkan dampak besar pada ketidakseimbangan ekosistem yang menimbulkan risiko terjadinya banjir, tanah longsor serta deforestasi hutan,” kata Nur.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa deforestasi di Indonesia saat ini mencapai 479.000 hektar per tahun, atau setara dengan satu setengah lapangan bola setiap menit.
“Dampak dari perubahan iklim di Indonesia juga sudah terlihat, seperti musim yang tidak teratur. Sekarang kita tidak tahu apakah kita sedang di musim panas, kemarau, hujan, atau pancaroba. Lalu cuaca ekstrem, di mana dalam satu hari kita bisa merasakan panas terik dan hujan deras,” katanya.
Pada 2030, ujar Nur, suhu akan naik melebihi 1,5 derajat Celsius akibat perubahan iklim. Kondisi ini akan berdampak besar bagi ekosistem bumi seperti punahnya berbagai spesies, hingga pencairan es di kutub yang akan mempengaruhi pola arus dan pola angin global.
Aktris Nadine Alexandra Dewi, yang merupakan Duta Orang Utan untuk Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) mengatakan, aktivitas deforestasi dan konversi hutan dalam 20 tahun terakhir menyebabkan populasi orang utan berkurang drastis dan terancam punah.
.jpg)
Aktivis dan aktris Nadine Alexandra
Ia mengatakan, sejak 1999, Indonesia telah kehilangan kurang lebih 150.000 orang utan. Sekarang hanya tersisa sekitar 57.000 di Kalimantan dan sekitar 14.000 di Sumatera.
“Dalam 50 tahun, dengan cara hutan ditebas dan dibakar, orang utan akan punah dan lenyap di muka bumi. Artinya dalam kurun waktu kurang dari 100 tahun, manusia akan menghapus seluruh populasi orang utan,” ujar Nadine.
Hak atas air
Selain kondisi hutan yang sudah parah, kata Nur, kita juga mengalami pencemaran air, sehingga air menjadi barang ekonomi karena kelangkaan karena sumber air telah dirusak dan diambil dalam skala besar untuk kepentingan industri. Padahal Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan sumber air terbesar.
Nur mengatakan, menurut data KemenLHK pada 2016, 105 sungai di Indonesia sudah tercemar berat.
“Ini yang mengakibatkan air tidak bisa dikonsumsi walaupun banyak sungai. Kalau mau diolah untuk menjadi air minum pun akan membutuhkan biaya pengolahan yang sangat mahal,” ujar Nur.
Masyarakat masih harus berjuang dan melawan untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhinya hak atas air.
Pencemaran air ini memperburuk pemenuhan hak atas air di Indonesia, menurut Siti Rakhma Mary Herwati. Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu mengatakan, meskipun tidak secara eksplisit, namun pemenuhan hak atas air sudah diatur dalam berbagai aturan internasional melalui konvensi dan deklarasi. Indonesia juga mengatur hak ini dalam beberapa pasal dalam Undang-undang,
“Hak atas air tidak bisa dipisahkan dari hak-hak asasi manusia lainnya, karena hak atas air merupakan bagian dari hak atas kehidupan yang layak, dan merupakan kewajiban negara dalam memenuhi hak itu,” kata Rakhma.
Kriteria penyediaan air adalah adanya sumur, kualitas air yang layak minum, tidak tercemar dan tidak mengandung materi-materi yang berbahaya bagi kesehatan, aksesibilitas akan air yang mudah dijangkau masyarakat, juga kemampuan masyarakat untuk membayar air dengan harga terjangkau.
“Ketika negara tidak mampu untuk menyediakan air bagi warganya, maka negara harus melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pemenuhan hak atas air. Negara juga berkewajiban untuk mencegah pihak ketiga memonopoli akses terhadap air,” ujarnya.
Rakhma memaparkan sejarah privatisasi air di Indonesia, yang dimulai pada 1995, ketika Presiden Soeharto saat itu menginstruksikan menteri pekerjaan umum untuk membentuk tim persiapan privatisasi perusahaan air minum (PAM) Jaya dan mengikutsertakan beberapa pihak swasta. Hingga pada 2012, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menggugat privatisasi air tersebut dan hakim memenangkan gugatan tersebut, yakni bahwa kontrak perusahaan swasta harus dibatalkan dan pengelolaan air harus kembali pada negara.
“Nyatanya sampai sekarang eksekusinya tidak dilaksanakan, bahkan Menteri Keuangan melakukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan tersebut,” jelas Rakhma.
Ia mengatakan, privatisasi air masih menjadi paradigma pemerintah dan pemerintah juga masih gagap membuat peraturan terkait hak akan air.
“Masyarakat masih harus berjuang dan melawan untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhinya hak atas air,” katanya.
Kejahatan lingkungan
Isu yang selalu menjadi dilema dalam keadilan lingkungan adalah tarik-menarik antara sektor ekonomi dan sektor lingkungan hidup. Dalam kasus orang utan, menurut Nadine, ada industri kelapa sawit yang selama 35 tahun terakhir menjadi ancaman terbesar bagi orang utan dan hutan hujan Kalimantan.
Ia menjelaskan, Indonesia merupakan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia, tahun lalu menghasilkan 42 juta ton minyak sawit dengan menggunakan 21 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit. Di posisi kedua adalah Malaysia, yang tahun lalu memproduksi 19 juta ton minyak sawit dengan hanya menggunakan lahan sebesar 5,8 juta hektar.
“Artinya, kita memiliki sekitar empat kali lebih banyak lahan, tapi hanya memproduksi minyak sawit dua kali lebih banyak dibandingkan dengan Malaysia,” jelas Nadine.
“Ketika satu-satunya tujuan negara adalah pertumbuhan ekonomi yang singkat tanpa melihat dampak lingkungan, kita semua menderita,” ujarnya.
Korporasi merupakan pihak yang sulit dimintai pertanggungjawaban saat merusak lingkungan. Koordinator Sektor Pelatihan EU-UNDP SUSTAIN Bobby Rahman mengatakan bahwa kejahatan lingkungan bukan kejahatan yang sederhana karena melibatkan banyak kepentingan dan aktor.
“Kejahatan lingkungan juga hampir selalu diimbangi kejahatan lain seperti gratifikasi dan pencucian uang, sehingga kejahatan lingkungan ini bisa disebut sebagai extraordinary crime,” kata Bobby.
Karenanya, pendekatan terhadap kejahatan lingkungan tidak bisa dilakukan secara spasial atau sendiri-sendiri, melainkan secara multi-door atau melalui banyak pintu, ujarnya.
“Ketika kita bekerja sama untuk menghadapi satu kejahatan tunggal yang dimensinya banyak, maka kita memerlukan banyak pendekatan, memperluas rezim hukum, dan memperbanyak penegak hukum. Itu semua membutuhkan koordinasi,” jelas Bobby.
Ia mengatakan, ada tiga aspek penegakan hukum lingkungan yang bisa dipakai, yaitu hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata yang mencakup pemulihan hak yang dilanggar serta pemenuhan kewajiban ganti rugi kerusakan lingkungan.
“Jika dilakukan dengan multi-door, maka penegakan hukum harus dilakukan ketiganya, karena satu saja tidak cukup ampuh untuk mengentas kejahatan lingkungan,” katanya.
Ubah paradigma
Nur mengatakan bahwa kesadaran masyarakat di Indonesia tentang pentingnya lingkungan sudah cukup tinggi, disusul dengan berbagai instrumen hukum terkait lingkungan. Namun krisis lingkungan tetap terjadi karena paradigma kita yang masih belum berorientasi pada keberlangsungan ekosistem, katanya.
Paradigma yang kita anut saat ini lebih berpusat pada manusia, ujar Nur.
“Yang kita inginkan adalah melihat bumi serta isinya, termasuk manusia, sebagai suatu komponen utuh terintegrasi yang tidak terpisahkan dan saling bergantung satu sama lain, dan ada interaksi keduanya yang saling berdampak satu sama lain,” jelasnya.
Nur mengatakan, sebagai individu, kita bisa mulai dengan lebih sadar terhadap jejak ekologis kita, yakni apa yang kita konsumsi dan gunakan agar tidak menyumbang banyaknya sampah. Selain itu, sebagai makhluk politik, kita memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan.
“Melalui saluran demokrasi yang ada, kita sebagai warga negara harus dorong negara agar pro-lingkungan dan masyarakat,” katanya.
Nadine mendorong masyarakat untuk menjadi konsumer yang cerdas dan memilih produk-produk yang berkelanjutan.
“Saya rasa boikot produk tidak akan efektif, tapi konsumen harus lebih bijaksana memilih produk dan menuntut adanya sertifikasi berkelanjutan, seperti untuk produk-produk minyak kelapa sawit. Dengan banyak tuntutan konsumen, produsen akan harus memenuhi tuntutan itu jika produknya ingin dibeli,” ujarnya.
Pola konsumsi seperti itu, kata Nadine, diharapkan bisa mendorong produsen minyak kelapa sawit dan produk-produk turunannya untuk memastikan aspek-aspek berkelanjutan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
“Kita bisa menciptakan dunia yang seimbang dengan pilihan yang kita buat, menjadi warga negara yang proaktif dan sadar, menggunakan purchasing power kita untuk mendorong perusahaan agar menjadi perusahaan dengan visi berkelanjutan, dan menjadi bagian aktif dari dialog yang konstruktif dan positif,” tambah Nadine.
Bobby mengatakan bahwa penting untuk mulai meningkatkan kesadaran lingkungan dari diri kita sendiri untuk mengambil peran dalam merawat dan menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup kita.
“Karena bumi sebenarnya fine-fine saja tanpa kita. Kita yang membutuhkan lingkungan, tapi kita sendiri juga yang merusaknya. Maka kita harus berperan aktif dalam menjaga lingkungan dimulai dari diri sendiri. Karena lingkungan hidup sangat mahal jika tidak kita jaga,” kata Bobby.
* Foto oleh Elma Adisya, Magdalene
Baca bagaimana sistem hukum yang tidak berperspektif gender melanggengkan kekerasan terhadap perempuan.