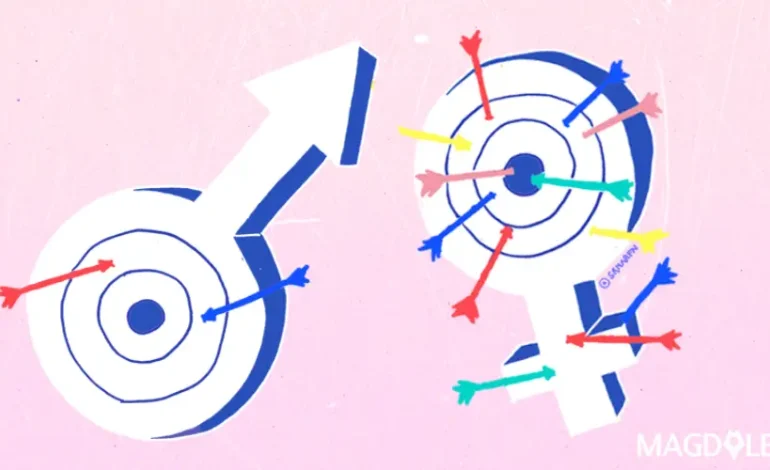Dari Dapur ke Ladang: Siasat Perempuan Siyono Hadapi Krisis Iklim

“Kami memang adoh ratu cedak watu mbak, tapi kami ingin jadi batu itu! Batu yang tangguh, yang kuat. Pada akhirnya, kami memang hanya bisa berharap pada diri kami sendiri, pada satu sama lain di sini” – Ida Mandalawangi-
Gunungkidul sering dilekatkan pada stigma “tertinggal” dan “terbelakang”. Tapi ketika saya berbincang dengan Ida Mandalawangi, perempuan muda asal Gunungkidul yang memilih tinggal dan menetap di desa, stigma itu terasa goyah. Ida menghidupkan ikhtiar-ikhtiar lewat kerja perawatan bersama para ibu dan perempuan lain di Dusun Siyono, Desa Petir, Gunungkidul. Bagi mereka, rumah, kandang, dan ladang bukan sekadar latar hidup, melainkan ruang untuk menyusun siasat dan menanam harapan.
Ida memang bukan petani. Namun bagi saya, ia adalah perempuan muda yang percaya pada nilai, pilihan, dan kekuatan harapan. Dan ia tidak bergerak sendirian. Bersama para perempuan dan pemuda di desanya, Ida meniti ikhtiar melalui ruang kolektif belajar bernama SeDusun. Ruang ini tidak hanya mengumpulkan orang, tetapi juga menghubungkan pengalaman, pengetahuan, dan daya tahan warga.
Dari SeDusun inilah saya mulai melihat Gunungkidul dari sudut yang berbeda. Selama ini, Gunungkidul kerap dipahami dari kacamata “kekurangan”: akses yang terbatas, infrastruktur yang tidak merata, peluang ekonomi yang sempit. Namun gerakan yang dihidupkan Ida bersama SeDusun menunjukkan spirit yang khas: bahwa Siyono memiliki cara sendiri untuk menerjemahkan “kemajuan” dan “kesejahteraan”. Bagi mereka, kemajuan tidak melulu soal pertumbuhan berbasis angka. Keterbatasan tidak selalu menjadi tembok penghalang, melainkan kondisi yang memaksa lahirnya siasat—ikhtiar yang memberdayakan, setidaknya bagi mereka sendiri.
Masyarakat Siyono hidup dengan basis mata pencaharian utama sebagai petani dan peternak. Umumnya setiap keluarga memiliki lahan atau ladang untuk dikelola, sekaligus ternak yang mereka pelihara. Saat berkunjung ke sana, satu hal yang paling mencuri perhatian saya adalah “kelimpahan” singkong kering atau yang biasa disebut gaplek. Banyak singkong dijemur dan dihamparkan, dari atas genteng sampai halaman rumah. Sebagian lainnya disimpan dalam bagor atau karung.
Mengapa singkong begitu menonjol di Siyono? Rupanya, sama seperti banyak wilayah lain di Gunungkidul, singkong menjadi salah satu tanaman yang paling banyak dihasilkan dari tanah warga, sekaligus pangan lokal khas. Warga memiliki teknologi pengawetan untuk mengolah singkong menjadi gaplek. Hasilnya bukan hanya bahan makanan, melainkan bentuk penyimpanan nilai yang bisa dipakai saat diperlukan.
Singkong yang dihasilkan setiap tahun tidak selalu langsung dijual. Ia “ditabung” dalam bentuk gaplek. Saat berbincang dengan Bu Partilah dan Bu Trisni, saya memahami bahwa gaplek yang mereka simpan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan keluarga, tetapi juga sebagai cara menabung dan membangun ketahanan ekonomi. Dalam kondisi serba tidak pasti, menyimpan gaplek adalah bentuk perhitungan sekaligus perlindungan.
Baca Juga: #MerekaJugaPekerja: Kenapa Kerja Perawatan Masih Diremehkan?
Menghidupkan Siasat dari Dapur Hingga Ladang
Beberapa waktu belakangan, warga Dusun Siyono, terutama para perempuan, dihadapkan pada pola musim dan cuaca yang kian tidak menentu. Dampaknya terasa sampai ke hasil panen dan singkong yang mereka tanam. Musim hujan dan kemarau yang semakin sulit diprediksi membuat proses penjemuran gaplek menjadi lebih riskan. Singkong yang dijemur tidak cepat kering, lalu membusuk, dan harga gaplek mengalami penurunan.
Bagi keluarga yang menjadikan gaplek sebagai “tabungan” dan penopang kebutuhan, penurunan harga bukan sekadar urusan pasar. Ia berubah menjadi keresahan sehari-hari. Bagaimana mengelola kebutuhan rumah tangga ketika cara menabung mereka terganggu? Bagaimana memastikan stok pangan dan ekonomi keluarga tetap bertahan?
Merespons itu, Ida dan para perempuan petani yang terhubung dengan SeDusun mencoba membangun siasat yang bergerak dari dapur sampai ladang. Para ibu harus menata ulang strategi penjemuran agar gaplek tidak busuk. Di saat yang sama, berbekal jejaring dan pengalaman berkomunitas, Ida yang terhubung dengan beberapa akademisi dan praktisi kampus melakukan eksperimen untuk mengolah hasil panen singkong menjadi produk pangan lain yang lebih tahan, bernilai, dan memiliki manfaat yang lebih beragam.
Dapur kemudian menjadi ruang eksperimen. Bersama kelompoknya, Ida menghidupkan proses belajar yang berangkat dari bahan yang sudah mereka miliki, yakni singkong dari ladang mereka sendiri. Uji coba pembuatan tepung mocaf hingga brownies singkong dilakukan dengan fasilitasi jejaring praktisi kampus yang datang ke Siyono. Di sini, pengetahuan perempuan lokal tidak digeser atau dianggap “kalah” oleh pengetahuan luar. Ia justru bertemu dan bernegosiasi dengan teknologi pangan yang lebih kekinian.
Dari dialog dan eksperimen itulah terbuka harapan dan proyeksi bahwa singkong tidak hanya berakhir sebagai gaplek yang rentan cuaca dan harga, melainkan bisa diolah menjadi bentuk lain yang memberi pilihan lebih luas. Bahwa krisis iklim yang mengganggu siklus musim tidak harus membuat mereka berhenti, tetapi memaksa mereka menemukan cara baru untuk bertahan.
Baca Juga: #PerempuanRawatBumi: Kisah Perempuan Penenun Sampah
Bukan heroisme personal, melainkan kerja yang saling terhubung
Melalui Ida dan para ibu yang bergerak bersama SeDusun, saya memahami bahwa perjuangan tidak harus identik dengan heroisme personal yang berisik. Ia juga tidak harus bertumpu pada satu sosok sentral yang “paling hebat”. SeDusun adalah hasil dari solidaritas yang dirakit—dari agensi kolektif yang digerakkan Ida, para perempuan petani, dan ruang hidup serta sumber daya yang mereka jaga dan yang menghidupi mereka: tanah, air, ladang, singkong, dapur, tungku, dan lain-lain.
Para ibu dan perempuan di SeDusun menjadikan kerja-kerja perawatan harian sebagai bagian dari rangkaian perjuangan itu sendiri. Dapur, kandang, dan ladang adalah medan juang sekaligus laboratorium yang mereka hidupkan melalui pengetahuan, pengalaman, dan harapan yang ditumbuhkan dari, oleh, dan untuk mereka sendiri. Kerja perawatan yang sering dianggap “biasa” justru menjadi bentuk ketahanan yang paling nyata, karena ia terus berlangsung bahkan ketika keadaan berubah-ubah.
Di saat yang sama, mereka tidak menutup diri untuk belajar dan berjejaring dengan entitas di luar komunitas. Keterhubungan dengan praktisi kampus dan komunitas lain menjadi jalan untuk memperluas proses belajar dan inovasi, tanpa tercerabut dari akar pengalaman mereka sendiri. Ada keberanian untuk mencoba, dan ada kehati-hatian untuk tetap mengakar.
Kacamata pembangunan yang positivistik dan antroposentris mungkin kerap memiliki keterbatasan ketika memaknai kondisi masyarakat lokal yang khas dan kompleks, hanya menjadi angka, data, atau populasi. Namun kacamata ekofeminisme berupaya melihat hal lain. Bahwa warga Dusun Siyono, terutama para ibu dan perempuan, adalah subjek yang memiliki pengetahuan dan cara tersendiri untuk menerjemahkan hidup. Nilai, budaya, pengalaman, dan inovasi yang mereka kembangkan membentuk ekosistem kehidupan yang saling terhubung.
Agensi perempuan yang terbangun di Siyono juga bukan hasil dari kekuatan tunggal. Ia muncul dari jaring solidaritas sosial, ekonomi, dan ekologi yang terhubung dengan tanah, ladang, air, singkong, hingga teknologi pangan. Semua entitas itu saling mempengaruhi. Ketika cuaca berubah, dapur ikut berubah. Ketika ladang terganggu, strategi rumah tangga ikut beradaptasi. Dan ketika pilihan ekonomi menyempit, pengetahuan kolektif menjadi ruang untuk mencari kemungkinan.
Melalui Ida dan para ibu yang menghidupi SeDusun, saya memetik satu nilai penting. SeDusun bukan hanya hamparan ruang fisik, melainkan ruang yang hidup dan menghidupi masyarakat melalui kerja-kerja perawatan yang dimulai dari rumah, kandang, hingga ladang. Di sana, perempuan, terutama kaum ibu, bukan sekadar “membantu” kehidupan desa. Mereka adalah pemilik dan penggerak pengetahuan yang termanifestasi lewat cara mereka mengelola ruang hidup dan sumber penghidupannya, sembari terus menyusun siasat untuk bertahan di tengah krisis iklim yang kian nyata.