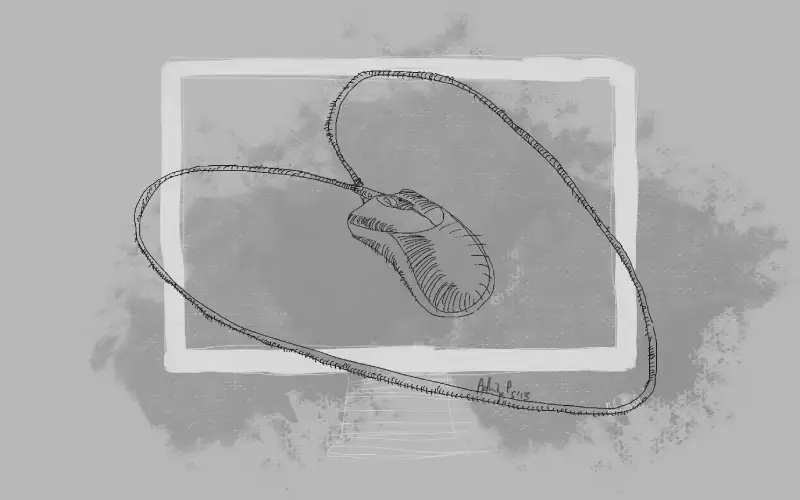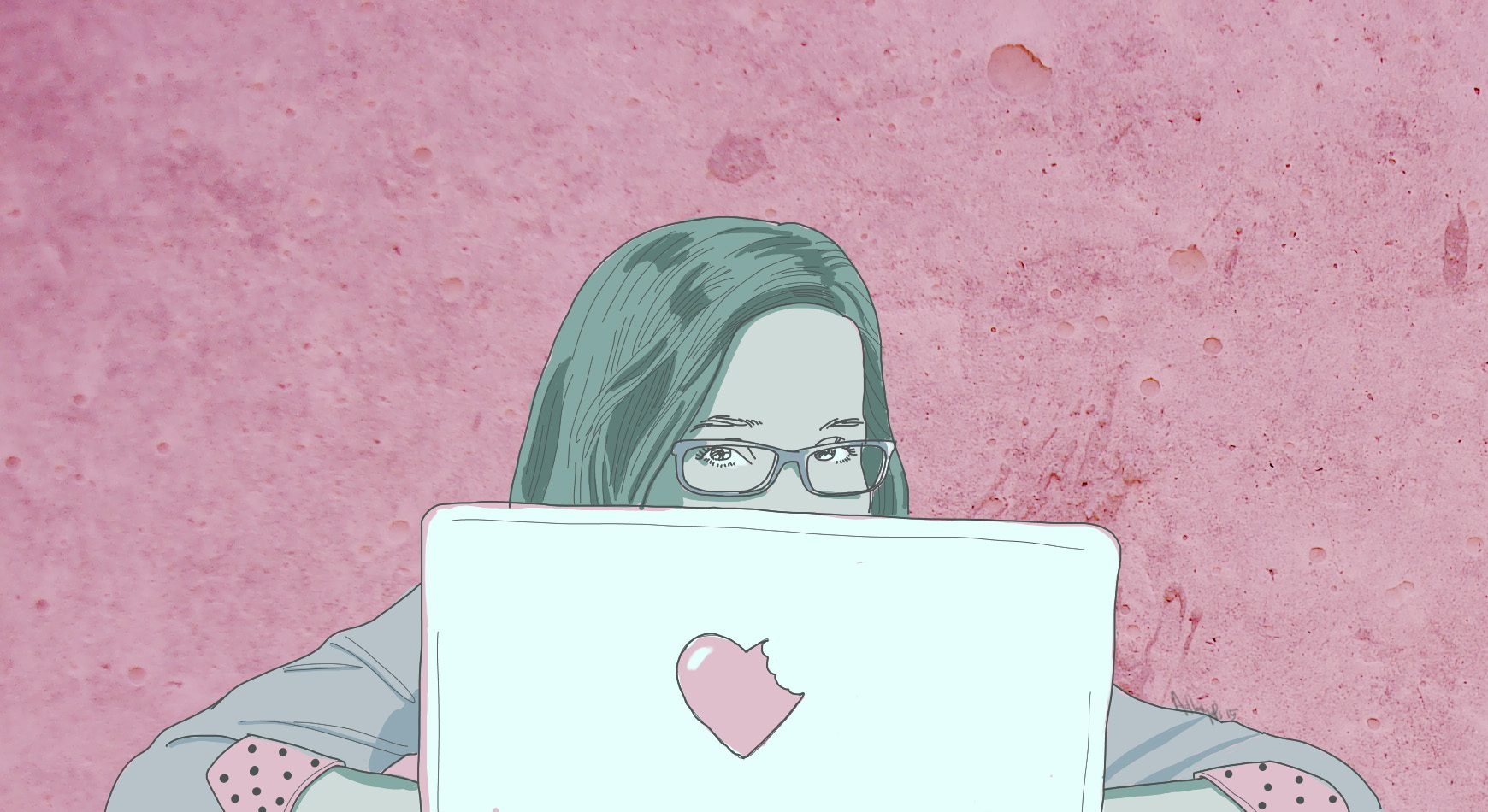‘Social Distancing’ dengan Orang Tua Toksik Tak Cuma Selama Corona

Sudah hampir seminggu sahabat saya, “Ulfa”, tinggal di rumah saya. Setelah menjalani drama berbabak-babak dengan sang ibu nan abusive sejak kecil, ia akhirnya memutuskan hengkang dari rumahnya.
Puncak konflik yang memicu Ulfa pergi terjadi setelah ibunya mendapati dia diam-diam berpindah agama sejak tahun lalu. Sang ibu yang ultrabenci terhadap agama baru Ulfa tidak bisa menerima dan memaki-maki perempuan 26 tahun itu tanpa henti selama beberapa hari. Sampai Ulfa hendak pergi pun, ibunya terus mencecar, bahkan mengancam akan menahan semua dokumen terkait identitas dan riwayat pendidikannya, berikut barang-barang Ulfa yang diklaim dibayari orang tuanya—padahal sebagian merupakan hasil jerih payah dia sendiri.
Perkara pindah agama Ulfa ini hanya secuil dari gunung es kepenatan dan trauma atas perlakuan buruk yang pernah ia terima dari orang yang melahirkannya ini. Sikap merendahkan, kekerasan fisik, ancaman, sikap mendikte, dan melarang dari sang ibu adalah beberapa bongkah lain pembentuk gunung es tersebut.
Baca juga: Tak Semua Orang Tua Mulia: Relasi Anak-Anak dengan Orang Tua Toksik
Pada malam ketika Ulfa sampai di rumah saya—dengan membawa sebuah ransel yang penuh dan tas-tas besar berisi barang penting yang sekenanya ia bawa, kakaknya datang sambil membawa sebagian lain barang Ulfa. Ia singgah sebentar seraya mengobrol di teras dengan adiknya, sementara saya dan salah satu teman lain yang sedang mampir duduk di dekatnya ikut mendengarkan.
Singkat cerita, karena tak banyak memahami kondisi Ulfa yang tertekan dan terganggu mentalnya, plus hanya menangkap sebagian adegan puncak konflik Ulfa dan sang ibu, sang kakak berharap agar Ulfa cepat berekonsiliasi dengan ibu mereka. Di kacamata kakaknya, Ulfa hanya reaktif dan tak benar-benar serius mau meninggalkan rumah.
Sehari berselang, ayah tiri Ulfa pun datang dan meminta Ulfa untuk bisa berbaikan dengan istrinya. Sebenarnya ia pun bukan tipe orang tua yang suka menahan anak untuk tetap di rumah, tapi karena Ulfa pergi tidak secara “baik-baik”, plus ini adalah kali pertama Ulfa tinggal terpisah dari orang tua, tak gampang bagi laki-laki itu untuk merelakan kepergian Ulfa dan percaya bahwa ia baik-baik saja di luar sana.
Baca juga: Lepas dari Aturan Keluarga, Terkungkung dalam Rumah Tangga
Yang saya tahu, Ulfa memang sudah lama punya rencana keluar dari rumah karena tidak tahan akan beracunnya sikap sang ibu. Ulfa sepertinya punya modal lebih dari cukup untuk bertahan hidup tanpa dukungan dari orang tua. Saya yakin, tak ada yang lebih baik bagi Ulfa dibanding pergi dari rumah tempat relasi tak sehat tumbuh subur, sambil memulihkan diri dan menjernihkan pikiran.
Berjarak malah sehat
Saya heran dan sedikit menyayangkan, tak bisakah orang-orang itu menunggu? Tidakkah munafik bila kembali ke rumah, bermaaf-maafan, tetapi amarah belum kunjung reda dan badai trauma masih menerpa? Tak pahamkah bila rekonsiliasi tidak melalui proses yang cuma semalam saja, apalagi bila sudah ada kekerasan sejak Ulfa kanak-kanak?
Tak tebersitkah di benak mereka bila Ulfa tetap di rumah, lukanya yang perlahan mengering bisa terbuka lagi bahkan bertambah lebar bila sikap ibu Ulfa tak juga berubah, hanya bak gunung berapi yang sesekali waktu bisa meletus dan tertidur? Tidakkah berjarak saat ini menjadi pilihan paling sehat bagi kedua belah pihak?
Mungkin berat sekali bagi banyak orang, apalagi orang tua, ketika melihat anak pergi dari rumah setelah bertengkar hebat dengan anggota keluarga. Ketika pertengkaran melibatkan anak dan orang tua, reaksi yang paling sering muncul adalah, “Dasar anak durhaka tidak tahu terima kasih!” atau “Kualat (atau menyesal) kamu nanti”. Duduk bersama dan membicarakan masalah baik-baik dianggap sebagai hal ideal yang semestinya orang seperti Ulfa lakukan setelah bertengkar. Lebih sedikit yang berpikir bahwa berjarak adalah hal sehat yang tidak boleh diabaikan juga, malah perlu dilakukan.
Saya adalah bagian dari sedikit orang itu.
Sejak SMA, saya selalu mendamba untuk bisa tinggal sendiri. Pertengkaran-pertengkaran dengan ibu yang menumpuk sejak sekolah dasar dan sepanjang masa remaja mendorong saya berkeinginan begitu. Maka ketika saya kuliah dan letak kampusnya berjauhan dari rumah, saya girang bukan kepalang karena berkesempatan untuk ngekos. Setelah kerja, saya terus memilih tidak tinggal bersama orang tua bahkan setelah ibu tidak ada. Bagi saya, salah satu hal terbaik yang pernah saya putuskan adalah mengambil jarak dengan mereka.
Begitu saya berjarak dengan keluarga, kondisi emosi saya jauh lebih stabil. Tidak ada orang yang memantau saya seperti elang hanya untuk mencari kesalahan saya dan mengomel. Saya bebas melakukan kegiatan apa pun selama saya tahu dan menjalani konsekuensinya. Perasaan tertekan, marah, dan benci yang sempat pasang perlahan menyurut. Saya pun tidak lagi membalas dengan nada tinggi ketika orang tua saya berbicara dengan menghakimi.
Baca juga: Cintai Perempuan dengan Membebaskannya
Psikolog saya mengafirmasi pilihan saya, bahwa ini adalah hal yang baik diambil sebelum meraih gol lebih jauh: Memaafkan dan rekonsiliasi. Perbaiki dulu dirimu sebelum memperbaiki yang lain.
Tinggal berjarak membuka mata saya bahwa sepakat untuk tidak sepakat masih sangat mungkin diterapkan tanpa harus setiap waktu menciptakan perdebatan. Terpisah dari siapa pun yang membuat kita marah, benci, bahkan trauma memberikan ruang dan waktu bagi kita untuk melihat dari sisi yang berbeda.
Dulu saya enggak tahu kenapa Ibu selalu marah-marah, ada saja yang dikritik dari saya. Tapi lama setelah berjarak, bahkan lama setelah kematiannya, saya bisa memahami keletihannya mengurus rumah sehingga sangat mungkin memicunya mudah emosi atau depresi karena saya pun mengalami beratnya mengurus rumah.
Perasaan berelasi dengan pengalamannya kian tegas saat saya sempat menjadi ibu rumah tangga selama beberapa bulan setelah anak saya lahir, meski ini tetap tidak menjustifikasi sejumlah tindakan buruknya yang sampai kini terus terngiang di kepala saya. Saya semakin terasah untuk berpikir mengapa seseorang berlaku begini atau begitu karena saat berjarak, informasi yang saya terima makin kaya.
Berjarak tidak berarti lari dari masalah atau memutus komunikasi. Ini adalah jalan untuk membenahi kondisi diri, introspeksi, sebelum bersiap menghadapi orang-orang yang pernah memicu seluruh emosi buruk. Berjarak juga bisa menciptakan kerinduan tersendiri pada sesuatu yang taken for granted semisal makanan rumah atau rasa nostalgia ketika rebahan di kamar tempat kita menghabiskan masa kecil dan remaja.
Berjarak tidak berarti lari dari masalah atau memutus komunikasi, melainkan jalan untuk membenahi kondisi diri, introspeksi, sebelum bersiap menghadapi orang-orang yang pernah memicu seluruh emosi buruk.
Ketika saya sesekali kembali ke rumah, tidak ada lagi perasaan jenuh dan monoton karena rumah orang tua saya kini jadi tempat berkunjung, bukan bangunan tempat saya menetap lagi. Satu perubahan lain yang saya dapati setelah berjarak adalah terbukanya kesempatan mengobrol dengan orang rumah, walau masih sekadar basa-basi dan obrolan ringan. Ini adalah sesuatu yang “wah” bila dibandingkan dengan absennya pembicaraan dua orang sedarah dan seatap beberapa belas tahun lalu.
Segala manfaat yang saya bicarakan soal memberi jarak dengan orang-orang yang memicu emosi buruk saya kira adalah keistimewaan pada masa-masa seperti sekarang ini. Saya bicara tentang mereka yang masih berkutat dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Yang dengan segala keterbatasannya—ekonomi, akses ke tempat aman, perlindungan hukum—terpaksa masih tinggal bersama sang penyiksa.
Pun tidak semua orang berani memutuskan pergi sebagaimana Ulfa. Tidak semua orang juga bisa mengamini bahwa berjarak dengan siapa pun yang toxic, termasuk keluarga atau orang tua, adalah hal yang lebih logis, sehat, dan bermanfaat dibanding percaya pada konsep tabu, aib, durhaka, dan sejenisnya.
Maka ketika kondisi lingkunganmu semakin membikin nyeri tak terperi, dan opsi istimewa untuk mengambil jarak ada di depan mata, masihkah terpikirkan untuk melewatkannya saja dan terus percaya kalau semua akan berubah sendirinya sementara kita terus bertahan?
Semua bisa baik-baik saja, bila kita memilih dan berusaha untuk demikian, bukan menunggu orang lain untuk membuat semua baik-baik saja bagi kita.