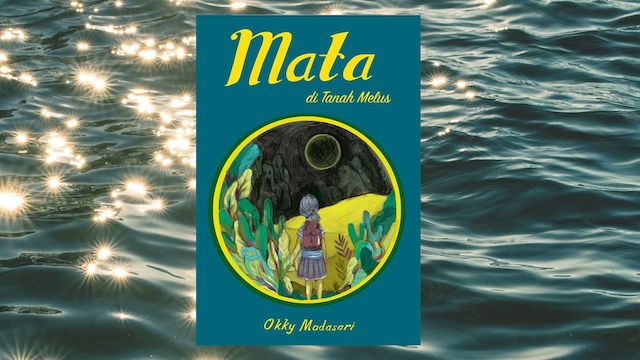Bisnis ‘Daycare’ Menjamur, Perempuan Masih Sulit Akses ‘Daycare’ yang Layak?

Adit, 33 adalah ibu pekerja. Ia memiliki anak laki-laki, “Nara”, berusia 3,5 tahun. Ia mengasuh Nara seorang diri karena kebetulan sang suami bekerja di luar kota dan ia enggan menitipkan Nara ke ibunya karena menyadari perbedaan pola pengasuhan. Peran berlapis sebagai ibu dan pekerja tak ayal membuat Adit mengalami mother burn out. Regulasi emosi dan stres Adir sempat kacau balau. Hal ini membuatnya jadi lebih sensitif dan mudah marah.
Beruntung Adit cepat sadar. Tak mau pertumbuhan dan ikatan emosional dengan anak jadi taruhannya, Adit mengambil langkah besar. Ia putuskan untuk menitipkan Nara ke daycare atau Tempat Penitipan Anak. Sayang, mencari daycare yang cocok bukan perkara mudah. Adit banyak melakukan survei dan harus bolak-balik ke tiga daycare karena mendapati daycare yang ia sambagi “kurang layak”.
“Aku sempet ke daycare yang tempatnya di ruko, sempit banget. Tempat bermain anak dan tempat tidur beda lantai. Masukin anak yang waktu itu baru 2 tahun buat naik turun bahaya banget. Terus tempat tidur buat rame-rame, enggak bersih, banyak debu, enggak terang juga. Satu lagi di rumah, tapi enggak rapi dan kotor,” curhatnya.
Beruntung di percobaan keempatnya, Adit menemukan daycare yang sesuai. Daycare itu Cahaya Bunda Daycare yang berada di Sawangan, Depok dan berjarak 15 menit dari rumahnya. Kini setiap pagi jam delapan ia mengantar Nara ke daycare. Selepas dari daycare, Adit bisa bernapas lega melanjutkan kerja domestik dan pekerjaan profesionalnya.
“Sekarang aku jadi lebih bisa balance sama kehidupanku. Anakku sadar. Dia pernah bilang ‘Aku happy deh sekarang ibu enggak suka marah-marah lagi, dulu aku sedih ibu marah-marah terus’,” ceritanya.
Baca Juga: ‘Saya dan Keadilan’: Ubah Paradigma Lingkungan yang Berpusat pada Manusia
Perempuan Pekerja Masih Dibebankan Kerja Perawatan Tak Berbayar
Keputusan Adit menitipkan ke daycare adalah bagian tren baru di kalangan para orang tua milenial. Early Dewi Nuriana National Project Officer of Care Economy ILO mengatakan kecenderungan generasi milenial memilih daycare karena sebagai orang tua mereka dinilai lebih melek dengan kebutuhan anak. Ini mulai dari fasilitas, makanan sehat, permainan yang seru, hingga pendidikan yang kebetulan pula sudah banyak ditawarkan bisnis daycare saat ini.
“Dengan meningkatnya literasi pengasuhan berkualitas, keluarga muda cenderung memilih untuk tidak menitipkan lagi anak mereka ke keluarga inti atau orang tua yang memang secara pola pengasuhan juga berbeda. Makanya memasukan anak ke daycare jadi pertimbangan pengasuhan yang berkualitas buat mereka,” jelasnya pada Magdalene, Selasa (24/9) lalu.
Tapi lebih dari itu, Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Kurniawati Hastuti Dewi menambahkan tren generasi milenial menitipkan anak di daycare dipengaruhi oleh perubahan ekonomi global baru di Asia sejak krisis ekonomi global 2008.
Lewat penelitiannya Social Policy and Practices of Childcare Services in Jakarta: An Assessment, Kurniawati menjelaskan krisis ekonomi global tahun 2008 menandai perubahan struktur kekuatan politik dan ekonomi global. Tadinya urusan itu dipegang oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, mulai berubah ke Cina, negara Asia Tenggara, dan kawasan Asia Pasifik.
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik, tren urbanisasi mulai muncul di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Ini membuat semakin banyak orang berpindah dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Jika ditelusuri lebih spesifik, tren ini berpengaruh pada meningkatnya jumlah perempuan yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja dari tahun ke tahun.
Di Indonesia tren urbanisasi ini berpengaruh pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan. Walau masih sedikit, TPAK perempuan Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Dalam lima tahun terakhir saja misalnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) TPAK yang berada pada 51,81 persen pada 2019 perlahan naik hingga mencapai 54,52 persen pada 2024.
Sayangnya walau meningkat, harapan bagi pekerja perempuan untuk dapat menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan, termasuk dalam mengasuh anak masih sulit untuk diwujudkan. Perempuan masih banyak dibebankan dengan kerja perawatan.
Dalam laporan Investments in childcare for gender equality in Asia and the Pacific yang diterbitkan International Labor Organization (ILO), disebutkan bahwa di Asia dan Pasifik, rata-rata perempuan menghabiskan 4,1 kali lebih banyak waktu dibandingkan laki-laki dalam melakukan kegiatan perawatan yang tidak dibayar.
Beban kerja perawatan perempuan membuat kehadiran daycare jadi semacam penyelamat. Dengan menitipkan anak di daycare, perempuan jadi tetap bisa berkarier tanpa dibebani kerja perawatan tambahan di luar batas kemampuan harian mereka. Hal tersebut dapat memengaruhi kualitas pekerjaan dan beban kerja yang lebih tidak adil buat perempuan.
Baca Juga: Energi Terbarukan Muncul di Desa, Pemerintah Harus Dukung
Daycare Menjamur
Kebutuhan daycare terefleksikan lewat menjamurnya bisnis ini di daerah perkotaan. Dalam penelusuran Magdalene melalui Google Maps di Depok contohnya terdapat setidaknya 12 daycare di hanya satu kecamatan saja, Kecamatan Sukmajaya. Dari 12 daycare ini, Shanti Kumara Daycare menjadi yang paling banyak mendapat ulasan bagus dari pengguna Google. Saya mengobrol langsung dengan Wulan, pemilik daycare ini.
Awal membuka daycare, Wulan terinspirasi pengalaman sendiri yang kesulitan berbagi peran sebagai ibu dan pekerja. Di tengah kesulitannya mencari pengasuh pasca kelahiran anak ketiganya, Wulan pernah mencicipi rasanya commuter dari Depok ke Jakarta tiap hari. Ia juga kerap berpergian ke luar kota sehingga terpaksa meninggalkan buah hatinya.
Dari pengalaman ini, ia berpikir untuk mendirikan daycare bagi para ibu yang senasib dengan dirinya. Wulan lalu mulai melakukan survei ke posyandu demi mencari tahu jumlah anak usia dini di area sekitar komplek rumahnya. Dari survei itu, Wulan mengajak ngobrol para perempuan ini.
“Dari ngobrol itu saya jadi tau deh ternyata banyak ibu yang memang butuh (daycare) apalagi sekarang kan cari pengasuh yang pas itu enggak gampang. Sekalinya ada daycare tuh mahal banget. Saya kaget dan itu jatuhnya banyak di ruko bukan di rumah. Makanya saya diriin daycare sendiri dengan konsep home daycare,” kata Wulan.
Dibantu koneksi suaminya yang bekerja di bidang pendidikan, pada 2017 Wulan resmi mendirikan Shanti Kumara Daycare. Tak mau daycare-nya jadi dicap abal-abal, Wulan mengaku banyak mengacu pada petunjuk teknis penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak (TPA) yang sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sejak 2015.
“Pokoknya ikutin semua arahan pemerintah aja. Pemerintah itu udah detail banget ngasih petunjuk ke pelaku usaha daycare, tinggal kita pelajari saja terus gimana cara ngembanginnya,” kata Wulan.
Jika ditotal kini, ada sekitar 50 anak yang dipercayakan di Shanti Kumara Daycare. Anak-anak tersebut setiap harinya (Senin – Jumat) diasuh serta didampingi oleh sebelas pengasuh (caregiver). Mereka di antaranya memiliki latar belakang S1 Kesehatan atau SMK Keperawatan. Jika lulusan SMA, para pengasuh sudah mendapatkan pelatihan pengasuhan dan perawatan dari Dinas Pendidikan lewat mitra usaha Persatuan Pemilik dan Pengelola Daycare Indonesia atau P3DI.
Formasi kerja sebelas caregiver ini lalu disesuaikan dengan rasio yang sudah ditetapkan pemerintah. Untuk kelompok usia lahir-2 tahun, maka rasio guru dan peserta didik adalah 1:4. Sedangkan kelompok usia 2-4 tahun memiliki rasio guru dan peserta didik 1:8 dan kelompok usia 4-6 tahun memiliki rasio 1:15.
Selain formasi kerja, program per kelompok usia di Shanti Kumara Daycare juga berpegangan pada jenis kegiatan daycare arahan Kemendikbud. Program ini semakin diperkuat dengan fasilitas yang tersedia di Shanti Kumara yang meliputi halaman yang dilengkapi tempat bermain, aneka mainan, tempat tidur AC, hingga ruang makan terpisah.
“Jadinya anak-anak kecil di Shanti Kumara bisa terpenuhi kebutuhan fisiologi dasar dan perkembangan fisik motoriknya. Mereka makan, tidur, mendapatkan stimulasi, dan berinteraksi dengan teman-temannya yang lain,” jelas Wulan.
Dengan kelengkapan fasilitas dan para pengasuh yang sesuai standar pemerintah, Shanti Kumara Daycare mematok biaya pendaftaran sebesar Rp1 juta dan biaya bulanan sebesar Rp1,5 hingga Rp2,5 juta tergantung kelompok usia anak.
Baca juga: Problem Perempuan Penjaga Hutan: Akses Minim hingga Kesenjangan Upah
Tidak Semua Perempuan Pekerja Bisa Akses Daycare
Shanti Kumara Daycare bisa dibilang adalah daycare idaman incaran para ibu pekerja. Sayangnya dengan biaya yang diklaim Wulan sudah cukup terjangkau, Shanti Kumara Daycare masih belum bisa dijangkau oleh banyak masyarakat yang berpenghasilan sesuai atau bahkan lebih rendah dari Upah Minimum Regional (UMR).
Dalam data yang sempat dihimpun Bincang Perempuan 2022 lalu, total biaya daycare dalam setahun di Depok bisa menguras Rp20.436.786. Sedangkan rata-rata penghasilan penghasilan pertahun dan pengeluaran per kapita Rumah Tangga untuk pekerja formal masing-masing sebesar Rp 51.188.580 dan Rp27.659.298. Jika diselisihkan, tiap keluarga cuma memegang sisa uang Rp3.092.496. Dana sekecil ini tentunya tidak cukup untuk menutup biaya kebutuhan lain seperti cicilan rumah, biaya transportasi, biaya darurat, dan bayar asuransi ataupun pajak.
Selisih ini sayangnya semakin besar bagi para pekerja informal bahkan hingga mencapai angka minus yakni sebesar Rp17.724.252.
Kondisi di Jakarta lebih memprihatinkan lagi. Di wilayah Jakarta Selatan, rata-rata penghasilan per tahun pekerja informal berada pada angka Rp24.218.496, sedangkan total biaya daycare dalam setahun melampaui Rp57.657.382.
Disparitas antara penghasilan dan biaya daycare tentunya berdampak pada keputusan perempuan pekerja milenial berpenghasilan UMR atau kurang dari itu untuk tidak memasukan anaknya ke daycare. Rara, 34, adalah salah satunya.
Baik Rara dan suaminya adalah freelancer berdomisili di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jika ditotal, penghasilan mereka berdua sebulan berkisar di angka Rp15 juta. Tiap bulannya penghasilan tersebut sudah habis duluan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya lain seperti membayar Kredit Tanpa Agunan, asuransi pendidikan anak, serta rumah kontrakan mereka.
Rara bercerita ia sempat mencari berbagai daycare untuk anak keduanya, “Langit” yang berusia dua tahun karena kewalahan. Suaminya sering keluar bertemu klien, sehingga Rara yang lebih banyak bekerja di rumah mau tidak mau harus mengemban peran ganda.
Ia sempat mempertimbangkan mendaftar ke salah satu perusahaan yang menawarkan fasilitas daycare. Namun dari pencarian daycare dekat rumah sampai usahanya mendaftar perusahaan tersebut berakhir gagal total karena terkendala biaya yang sangat mahal.
“Rata-rata daycare bagus di daerah rumahku (Jakarta Selatan) itu harganya dua jutaan. Itu baru SPP-nya, belum uang gedungnya. Kantor yang ada daycare itu SPP per bulannya 3.5 juta, terus uang gedungnya 5 jutaan per 6 bulan. Aduh, enggak kuat deh,” keluh Rara.
Selain terkait biaya, hal lain yang jadi pertimbangan Rara adalah soal kualitas pengasuh. Rara punya trauma dengan pengasuh karena Langit pernah diomeli dan dicubit oleh pengasuh yang ia pekerjakan hingga mengalami trauma. Kejadian tersebut semakin membekas pada Rara apalagi tak berapa lama kemudian masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan kasus penganiayaan anak di daycare Wensen School, Depok. Dari kasus ini Komisioner KPAI Diyah Puspitarini menyebut, dari seratusan jumlah daycare di Depok, hanya ada 12 yang resmi mengantongi izin.
Secara nasional KPAI pernah melakukan riset kelayakan daycare di 20 kabupaten/kota di 9 provinsi pada 2019 lalu. Tak hanya daycare milik pemerintah, tetapi juga yang terletak di perkantoran atau kantor pemerintah daerah, hingga yang dibiayai KPAI mencatat sebanyak 44 persen daycare tidak memiliki izin atau pun legalitas.
Lebih lanjut, 20 persen daycare yang disurvei tidak memiliki kelengkapan kelembagaan. Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati bilang kelengkapan kelembagaan ini sebenarnya berpengaruh pada kualitas pelayanan, misalnya Standar Operasional Prosedur (SOP). Jika tidak ada SOP, daycare jadi tidak memiliki jadwal rutin kegiatan yang standar, mulai dari pengasuhan hingga keamanan yang tak layak.
Terkait SDM sendiri, sebanyak 66,7 persen pegawai pelaksana layanan tidak bersertifikat. Temuan KPAI ini tercermin dari hasil kajian Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) soal daycare pada 2023 lalu. Saat menelusuri unggahan lowongan kerja untuk pengasuh anak di daycare Instagram, Seknas FITRA menyatakan masih terdapat daycare yang tidak mensyaratkan kualifikasi pendidikan khusus di bidang anak ataupun pengasuhan anak. Standar minimal yang diberikan adalah tamatan SMA atau sederajat dan itu tanpa ada informasi bahwa mereka butuh sertifikasi atau mendapatkan pembekalan atau pelatihan terkait pengasuhan dan perawatan terlebih dahulu.
Sebelumnya perlu diketahui standar daycare telah diatur lewat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pendirian Taman Anak Sejahtera. Kemudian Peraturan Menteri Kemendikbud Nomor 137 tahun 2014 dan disusul oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) lewat Standarisasi Taman Pengasuhan Anak (TPA) Berbasis Hak Anak/Daycare Ramah Anak pada 2020. Walaupun sudah ada regulasi terkait standarisasi daycare, Early Dewi Nuriana National Project Officer of Care Economy ILO mengatakan ini saja masih belum cukup karena sifatnya yang masih sektoral sehingga mendorong registrasi daycare dengan syarat berbeda-beda.
“Kebutuhan daycare tinggi, tapi di sisi regulasi masih sektoral. Belum ada undang-undang mandatory khusus soal childcare. Perizinan yang tersebar bikin bingung pelaku usaha. Ini mau ikut Kemendikbud, Kemenpppa, atau Kemensos? Ini kenapa jadinya banyak daycare belum berizin,” jelas Early.
Lebih dari persoalan regulasi sektoral, maraknya daycare belum berizin tak luput disebabkan oleh keruwetan perizinan mendirikan daycare itu sendiri. Sebagai pelaku usaha, Wulan sempat membagikan kendalanya. Kendala pertama yang ia hadapi adalah soal indikator jumlah anak dan periode operasional sebagai prasyarat perizinan.
Saat ingin mendaftar perizinan ke Dinas Pendidikan provinsi, pihak Dinas Pendidikan mengatakan bahwa daycare baru diperbolehkan mengurus izin jika sudah memiliki minimal 20 anak didik dengan estimasi dua tahun telah menjalankan usaha. Buat Wulan yang waktu itu masih baru mendirikan daycare, syarat ini tentu cukup memberatkan. Ia masih berusaha membangun rapor baik dan membujuk para orang tua sekitar kompleksnya untuk memasukkan anak mereka ke Shanti Kumara Daycare.
Kedua, daycare tak boleh berbentuk badan usaha PT. Ini yang kemudian membuat Wulan harus mengurus izin Shanti Kumara dari nol dan menjadikannya sebagai badan usaha sosial berbentuk Yayasan. Untungnya Wulan cukup beruntung. Karena sang suami bekerja di bidang pendidikan, ia mendapatkan banyak koneksi yang bisa membantunya mengurus izin tersebut.
Terakhir, masalah perizinan juga datang dari Izin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sesuai peraturan Dinas Pendidikan, bangunan daycare tidak boleh memakai IMB tempat tinggal. Padahal mengurus IMB tutur Wulan sudah sulit setengah mati.
“Saya yang punya konsep home daycare kan bingung. Masa harus di ruko? Itu sempet jadi masalahnya sih. Untung Shanti Kumara waktu itu udah jadi Yayasan, Dinas pendidikan melunak. Akhirnya diizinkan, (IMB) rumah tinggal boleh. Nah kalau yang lain gimana? Makanya banyak kan yang jadinya di ruko terus tidak berizin,” kata Wulan.
Menilik Praktik Baik Negara Lain
Permasalahan daycare di Indonesia dicermati oleh Seknas Fitra bisa berdampak pada karier perempuan. Perempuan masih dilekatkan peran gender tradisional, sehingga kewajiban pengasuhan dibebankan sepihak kepada mereka. Ini tercermin dalam laporan ILO pada 2022 bahwa 40 persen perempuan Indonesia keluar dari pekerjaannya dengan alasan menikah dan mengasuh anak. Mereka kemudian mencari nafkah dengan bekerja sebagai pekerja perawatan yang tidak dibayar.
Disebutkan juga bahwa rata-rata jam kerja ibu rumah tangga di Indonesia adalah 13,5 jam di rumah. Jumlah tersebut dikatakan dua kali lebih lama dari rata-rata jam kerja perempuan di Asia Pasifik. Padahal menurut Bank Dunia, jika TPAK perempuan dapat ditingkatkan menjadi 58 persen, maka ekonomi Indonesia diprediksi akan tumbuh sekitar 62 miliar dolar AS.41.
Sayangnya, menurut laporan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) 2021, sejauh ini anggaran pemerintah Indonesia untuk pengasuhan dan pengembangan anak usia dini hanya sekitar 0,04 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh di bawah rekomendasi OECD sebesar 1 persen dari PDB. Dalam penelusuran Seknas Fitra sendiri berdasarkan data Dapodik misalnya ditemukan jumlah daycare yang dikelola oleh pemerintah hanya 32 daycare, sedangkan daycare yang dikelola oleh swasta berjumlah 2.424.
Disparitas ini lanjut Seknas Fitra harusnya jadi perhatian khusus pemerintah. Masalahnya pembangunan keluarga berkualitas termasuk pengasuhan telah tercantum dalam agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024. RPJMN ini disesuaikan dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2019, yaitu dalam Prioritas Nasional ke III Pembangunan SDM dan Prioritas Nasional Ke IV Pembangunan Revolusi Mental, yaitu Membangun Manusia kedepan unggul dan berdaya saing dan Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.
Indonesia kata Kurniawati sebenarnya bisa banyak mengambil contoh negara-negara lain yang sudah sukses menjalankan kebijakan nasional terkait daycare. Dalam artikelnya yang pernah ia terbitkan di The Conversation secara umum, kebijakan pengasuhan anak di seluruh dunia diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, daycare disediakan dan didanai oleh pemerintah lewat pajak tahunan warga negaranya, seperti di negara-negara Nordik (Swedia, Finlandia, Denmark). Kedua, daycare dikelola oleh swasta, namun tetap diawasi oleh pemerintah, seperti di Inggris dan Amerika Serikat (AS).
Swedia adalah salah satu negara pelopor penyedia daycare bersubsidi. Pemerintah Swedia membuka layanan daycare untuk publik sejak 1975 untuk kalangan manapun yang mau mengaksesnya. Daycare di Swedia sendiri ditujukan untuk anak dari orang tua pekerja, pelajar, serta pihak-pihak yang sedang mencari pekerjaan. Dalam rentang usia 1-5 tahun, anak-anak mereka berhak mendapatkan layanan daycare yang pengelolaanya berada di bawah tanggung jawab pemerintah kota.
Sedangkan di Asia, ada Jepang. Kurniawati yang sempat melanjutkan pendidikan doktoral di sana menceritakan bagaimana daycare (hoikuen) yang dikelola pemerintah pasti tersedia di tiap kecamatan atau cho/machi (町). Siapa pun boleh mendaftar ke hoikuen, tapi tetap akan ada skala prioritas yang diberlakukan oleh pemerintah Jepang.
“Jadi ada prioritas siapa dan berapa pendapatan rumah tangga. Untuk siapa, pemerintah memprioritaskan ibu pekerja dan single parent yang enggak punya orang tua di rumah. Anak saya dulu saya titipkan di hoikuen. Itu bagus fasilitasnya, sangat murah karena ditanggung besar oleh pemerintah, dan pengasuhnya sudah terakreditasi,” lanjutnya.
Dengan terus meningkatnya kebutuhan daycare, sudah saatnya pemerintah memegang kendali dan tanggung jawab terhadap pengelolaan daycare. Sebelum “mencontek” kebijakan sukses negara lain, pemerintah perlu meramu kebijakan sentral terkait daycare. Early menekankan kebijakan sentral ini penting agar seluruh daycare di Indonesia memiliki standar yang sama bagusnya, baik dari sisi manajemen maupun perekrutan calon pengasuh anak. Kebijakan ini pula tambah Early harus mandatory alias wajib.
Shanti Kumara Daycare bisa jadi contoh daycare bagus, tapi nyatanya tidak semua perempuan pekerja bisa mengaksesnya karena tidak terjangkau oleh banyak masyarakat yang berpenghasilan sesuai atau bahkan lebih rendah dari Upah Minimum Regional (UMR).
Dalam data yang sempat dihimpun Bincang Perempuan 2022 lalu, total biaya daycare dalam setahun di Depok bisa menguras 20.436.786 sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita Rumah Tangga di Depok untuk pekerja formal Selama pada 27.659.298. Jika diselisihkan, tiap keluarga cuma memegang sisa uang 7.659.298. Dana ini tentunya tidak cukup untuk menutup biaya kebutuhan lain.
Artikel ini diproduksi oleh Magdalene.co sebagai bagian dari kampanye #WaveForEquality, yang didukung oleh Investing in Women, inisiatif program Pemerintah Australia.
Series artikel lain bisa dibaca di sini:
Cerita #MilenialMenua: Saat Kerja Kerasmu Tak Ada Artinya (Bagian I)
Cerita #MilenialMenua: Saat Kerja Kerasmu Tak Ada Artinya (Bagian II)
Bahagia dan Kejar Mimpi Pasca-Bercerai: Cerita Tiga Perempuan
Di Balik Milenial ‘Childfree’: Ada Masalah Struktural Ekonomi yang Jarang Dibahas
Ketika Bapak Rumah Tangga Bicara Stigma hingga Omongan Tetangga
Rumah untuk Milenial: Bahkan Kerja Selamanya pun Masih Tak Terbeli (Bagian 1)
Rumah untuk Milenial: Bahkan Kerja Selamanya pun Masih Tak Terbeli (Bagian 2)
Maaf, Usia 30 Dilarang Kerja: Ageisme yang Masih Hantui ‘Job Seeker’
Nasib Perempuan Pekerja: Batas Umur di Loker Lebih Merugikan Perempuan?
Ijazah ‘Wah’, Cari Kerja Susah: Di Balik Maraknya Pengangguran Gen Z