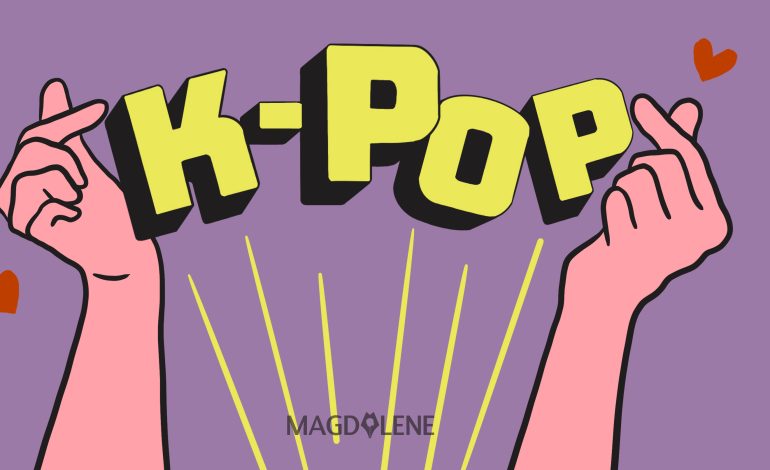Superhero Perempuan dan Problematika Representasinya

Beberapa minggu lalu saya menonton film The Batman besutan Matt Reeves bersama adik laki-laki saya. Saya sangat menyukai film ini karena berhasil mengembalikan hakikat karakter Batman sebagai The World’s Greatest Detective. Namun, kendati film ini memuaskan dahaga saya akan genre crime thriller, ada dua hal yang masih tetap mengganjal di hati saya hingga saat ini.
Pertama, Batman layaknya karakter superhero laki-laki lainnya, sudah diproduksi terlalu sering, malah cenderung berlebihan. Setidaknya, karakter ini sudah memiliki tujuh film solonya sendiri mulai dari Batman (1989), Batman Returns (1992), Batman Forever (1995), Trilogi The Dark Knight (2005, 2008, dan 2012), hingga yang terbaru The Batman. Belum lagi film-film reuni superheroes macam Batman and Robin (1997), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), dan Justice League (2017).
Nasib Batman sangat berbanding terbalik dengan Catwoman, misalnya. Pencuri perhiasan ini memulai debutnya sebagai “The Cat” di Batman #1 pada 1940, tapi sampai sekarang cuma punya satu film solo, Catwoman (2004) yang dibintangi oleh Halle Berry. Itupun dianggap gagal total di banyak aspek, terutama naskah dan plot cerita.
Kedua, selama saya menonton The Batman besutan Reeves saya menemukan pola sama yang dilakukan sineas laki-laki pada karakter perempuannya. Apalagi kalau bukan, membuat mereka sebagai karakter sampingan yang seduktif nan seksi. Mereka hadir sebagai superhero tangguh, tapi tubuhnya masih di objektifikasi habis-habisan. Sering kali juga dibikin hyper-feminine, tapi cua demi tujuan jadi penggoda.
Jujur saja, saya lumayan kecewa menonton karakter perempuan lagi-lagi dibuat dalam bingkai internalisasi seksisme-misogini seperti ini. Karena menurut saya, sebagai superhero perempuan, karakter mereka punya potensi besar untuk dieksplorasi bagus. Namun, pasar komik dan superhero sering kali diklaim sebagai ranah laki-laki, sehingga pola pemasarannya sering kali menggunakan male gaze.
Baca Juga: Imagining What Life Would Be If I’d Seen Captain Marvel as a Girl
Genre yang Secara Esensial Tercipta untuk Laki-Laki
Genre superhero tidak pernah terlepas dari laki-laki. Secara esensi genre ini lahir sejak debut prototipikal superhero Superman pada 1938 dalam Action Comics #1. Dengan karakter superhero laki-laki yang digambarkan dengan maskulin, genre ini pun kemudian mendapatkan target pasarnya sendiri. Laki-laki kulit putih cishetero.
Dilansir dari Statista misalnya menunjukkan pangsa orang dewasa yang menjadi penggemar buku komik di Amerika Serikat per April 2019 masih didominasi laki-laki kulit putih dengan bahwa 43 persen pria mengatakan bahwa mereka adalah penggemar buku komik, dibandingkan dengan 24 persen perempuan.
Demografi penikmat komik genre ini yang kebanyakan laki-laki kulit putih juga tidak terlepas dari bagaimana orang-orang yang terlibat dalam industrinya juga masih didominasi oleh laki-laki. Tim Hanley, seorang sejarawan dan peneliti komik asal Amerika Serikat, pada 2014 meneliti siapa yang berada di balik kumpulan rilisan bulanan komik genre ini. Ia menghitung penulis, artis, editor, penciler (seniman yang mengerjakan pembuatan karya seni visual), dan lain-lain.
Dalam penelitiannya ini ia menemukan bahwa jumlah laki-laki melebihi jumlah perempuan dengan perbandingan sembilan banding satu di belakang layar baik di DC maupun Marvel. Ia juga memperkirakan 79 persen orang yang mengerjakan komik-komik genre ini berkulit putih.
Minimnya representasi perempuan dalam komik genre superhero pun akhirnya berujung pada adaptasi layar kaca atau serial. Genre superhero yang kini telah menjadi komoditas mahal pendulang profit sayangnya masih minim representasi karakter superhero perempuan begitu pula dengan sineas perempuan yang terlibat di dalamnya.
Untuk karakter superhero perempuan misalnya dapat dilihat dari karakter Wonder Woman. Karakter Wonder Woman pertama kali muncul pada Desember 1941 di All Star Comic. Wonder Woman kemudian menjadi salah satu karakter buku komik paling populer dalam sejarah. Namun, setelah lebih dari 70 tahun menjadi ikon buku komik, baru pada 2014 Wonder Woman memiliki solo filmnya sendiri yang juga disutradarai oleh perempuan, Patty Jenkins.
Baca Juga: Captain Marvel: Another Blockbuster, Another Bunch of Misogynist Haters
Karakter Perempuan yang Digambar dalam Male Gaze
Dominasi laki-laki utamanya kulit putih dalam menciptakan serta mengembangkan genre ini pun termanifestasi nyata dari penggambaran superhero perempuannya. Dari pakaian superhero misalnya perempuan superhero selalu dikaitkan dengan tipe tubuh tertentu. Pinggang kecil, payudara besar, dan pinggul melengkung. Mereka tidak digambarkan memiliki tubuh kekar berotot seperti superhero laki-laki, melainkan apa yang digambarkan sebagai tubuh perempuan “ideal”.
Hiperseksualisasi karakter perempuan ini semakin menghilangkan legitimasi mereka. Orang-orang hanya melihat mereka sebagai tubuh yang indah dan “enak” dipandang daripada perempuan yang kuat dan berdampak yang memiliki suara dan kekuatan seperti teman-teman superhero laki-laki mereka.
Objektifikasi tubuh superhero perempuan pun ditambah dengan penggambaran prototipe klasik feminim yang dilekatkan pada mereka. Seperti karakter Catwoman yang dimainkan oleh Zoë Kravitz, superhero perempuan yang ditulis laki-laki hampir selalu digambarkan sebagai sosok seksi seduktif. Mereka menggunakan pesona femininnya, menggoda laki-laki untuk mempermudah mereka mendapatkan informasi atau menjalankan misi balas dendamnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Black Widow dalam semesta film Marvel yang ditulis oleh laki-laki.
Selain itu, dalam penelitian Representasi Superhero Perempuan pada Film Justice. League dan The Avengers Age of Ultron (2018) Hartini Basaria Natasya Sitanggang menjelaskan bagaimana superhero perempuan sekuat apapun mereka, superhero perempuan acap kali digambarkan menggunakan pesona “perempuan” mereka sebagai penetral diantara rekan kelompok mereka yang sebagian besar adalah laki-laki.
Karakter Black Widow dalam Avengers Age of Ultron (2015) misalnya menjadi karakter yang bisa menenangkan amarah Bruce Banner yang kala itu mengamuk setelah menjadi Hulk. Apa yang dilakukan Black Widow lagi-lagi mengukuhkan stereotip gender di masyarakat, bagaimana perempuan diposisikan sebagai seseorang yang lemah lembut dan seorang caretaker dari laki-laki yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri.
Baca Juga: ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ Runtuhkan Stereotip Perempuan Asia
Mulai Berbenah dengan Melibatkan Perempuan di Dalamnya
Untuk menciptakan genre lebih inklusif jauh dari penggambaran berbahaya yang lekat dengan stereotip gender, maka tidak ada cara selain dengan melibatkan perempuan di dalamnya. Caranya adalah dengan mendorong representasi perempuan melalui penggarapan berbagai film dan serial dengan protagonis perempuan yang tentunya melibatkan tim perempuan di dalamnya.
Victoria Alonso, produser film dan Presiden Fisik, Pasca Produksi, VFX dan Animasi di Marvel Studios dalam wawancaranya bersama Cnet misalnya mengungkapkan komitmen Marvel Studios untuk lebih banyak melibatkan perempuan dalam pembuatan film atau series Marvel.
“Kami bertekad untuk memiliki lebih banyak sutradara perempuan. Kami bertekad untuk memiliki lebih banyak kepala departemen yang perempuan dan kami bertekad untuk memiliki lebih banyak keseimbangan dalam karakter kami sehingga semua orang dapat terwakili,” jelasnya.
Komitmennya ini terlihat jelas dari bagaimana selain DC yang pada 2014 dan 2019 mengeluarkan film solo Wonder Woman, Marvel pada 2019 pada akhirnya membuat film superhero pertamanya yang disutradarai oleh perempuan. Dengan disutradarai oleh Anna Boden, Captain Marvel (2019) memberikan angin segar bagi genre superhero.
Pasalnya, karakter Carol Danvers yang awalnya tercipta hanya sebagai love interest Captain Mar-Vell dan pada prosesnya karakternya hanya dijadikan penunjang cerita karakter superhero laki-laki lainnya (dalam komik aslinya ia bahkan diperkosa yang membuatnya mengidap gejala stres pasca-trauma atau PTSD).
Dalam Captain Marvel (2019), Anna Boden memutuskan untuk tidak mengadaptasi karakter Carol Danvers dari akar seksis misoginisnya ini. Sebaliknya, ia mengadaptasi karakter Carol Danvers dari karya besutan Kelly Sue DeConnick. DeConnick memberikan kejelasan pada plot karakter yang berantakan dan sejarah yang rumit. Ia memberikan arti pada gelar Captain Marvel dengan penggambaran perempuan kuat yang independen dan pada adaptasi filmnya menjadi salah satu ikon feminisme dalam genre superhero.
Tidak hanya film, Marvel juga mendorong representasi perempuan dalam industrinya juga melalui serial TV. Ms. Marvel yang akan tayang Juni nanti adalah buktinya. Dengan karakter Ms. Marvel yang merupakan superhero muslim pertama yang pernah mengudara dan dua sutradara perempuan (Meera Menon dan Sharmeen Obaid-Chinoy) yang akan menyutradarai serial ini, maka akan lebih banyak karakter perempuan yang dibangun dengan kompleksitas yang sama dengan karakter laki-laki lainnya.
Pada gilirannya, representasi memang penting. Representasi tidak hanya akan mengubah paradigma atau penggambaran karakter perempuan dalam genre yang dicap sebagai domain laki-laki, namun juga mengubahnya lebih inklusif dengan memasukkan berbagai identitas perempuan di dalamnya. Semoga ini menjadi langkah awal menuju perubahan dan kita nantinya yang akan menjadi saksi hidup akan perubahan besar ini.