Surat Terbuka untuk KPU dari Minoritas Agama, Kenapa Pemilu Harus di Rabu Abu?
Pemilu 2024 sengaja dimajukan di Rabu Abu, agar tak mengganggu ibadah umat Islam, puasa Ramadan. Tapi bagaimana dengan ibadah umat Katolik dan Protestan?
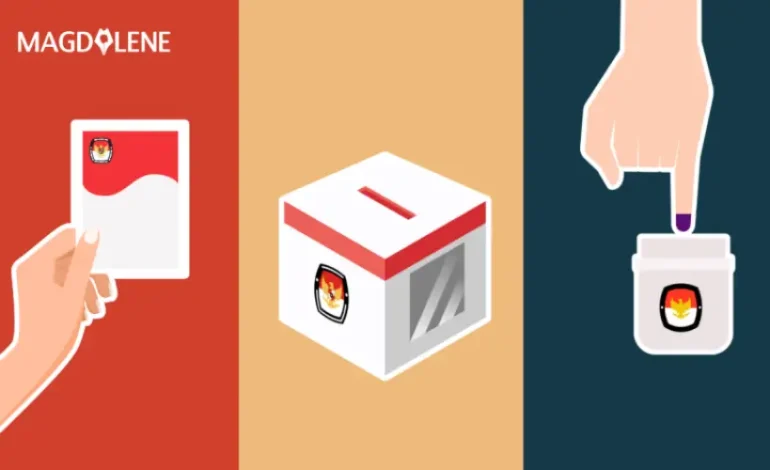
Yth. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI),
Saya ingat, Oktober lalu, Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) mengimbau gereja paroki maupun umat Katolik, untuk tidak melaksanakan Misa Rabu Abu di pagi hari. Langkah ini diambil KAJ demi mendukung berjalannya Pemilu 2024. Sebagai gantinya, umat Katolik dapat mengikuti misa pada (13/4) sore, atau sore hari di hari raya.
Saat membaca pemberitahuan tersebut, ada dua hal yang saya pikirkan sebagai umat Katolik: Gereja begitu mengutamakan demokrasi, dan respons atas kepentingan minoritas agama yang dikesampingkan.
Namun, surat ini ingin menyinggung yang kedua—mengingat alasan utama KPU menetapkan 14 Februari sebagai hari pemungutan suara. KPU berdalih ingin menghormati bulan Ramadan dan perayaan Idulfitri, yang jatuh pada Maret dan April 2024. Alasan itu disampaikan oleh Ketua KPU Ilham Saputra pada Januari 2022, berdasarkan kesepakatan Komisi II DPR bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Rasanya, jajaran pemerintah cenderung memperhatikan umat Islam yang merupakan mayoritas—86,7 persen dari populasi nasional berdasarkan catatan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISCC) pada 2023, dan abai pada minoritas agama.
Soalnya, ini bukan pertama kali Pemilu dilaksanakan bersamaan dengan hari besar keagamaan lho. Apakah KPU lupa, penyelenggaraan Pemilu 2019 bertepatan dengan ritus Semana Santa? Ritus itu bagian dari perayaan Pekan Suci Paskah, yang dirayakan umat Katolik di Larantuka, Flores Timur.
Salah satu warga Larantuka Dionisius Fernandus, sempat mengungkapkan kekesalannya pada BBC Indonesia perihal ini. Ia menyayangkan pemerintah, yang enggak mencari waktu lain untuk Pemilu. Sementara KPU mengaku sulit mengubah hari pemungutan suara, gara-gara Pemilu dilaksanakan serempak.
Padahal, tradisi Semana Santa berlangsung sejak 500 tahun silam. Begitu pun Rabu Abu—dirayakan sejak abad ke-11 setiap 40 hari sebelum Paskah. Sebenarnya, keduanya bisa diperhitungkan saat menentukan jadwal pemilu, meski enggak termasuk hari besar nasional.
Lalu, kenapa KPU mengulangi hal yang sama?
Baca Juga: Dear Pemilih Abah Anies Baswedan, Ini yang Perlu Kamu Tahu Sebelum Nyoblos
Cerminan Ketidakadilan Epistemik dalam Beragama
Saya punya tiga asumsi terkait pemilihan tanggal pemungutan suara: Fokus bahwa Rabu adalah hari paling baik dan rasional untuk menarik partisipasi masyarakat, Bapak dan Ibu jajaran KPU enggak tahu soal perayaan Rabu Abu, atau enggak memikirkan kepentingan kelompok minoritas agama dalam mengambil keputusan. Semoga yang ketiga salah.
Namun, dengan sikap yang terlihat enggak mempertimbangkan kepentingan umat kristiani, saya menyadari adanya ketidakadilan epistemik dalam kehidupan beragama di Indonesia. Lewat Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing (2007), Miranda Ficker mendefinisikannya sebagai ketidakadilan yang dibentuk oleh bias, atau prasangka sosial dalam mendapatkan pengetahuan. Penyebabnya adalah ketidakseimbangan relasi kuasa di masyarakat, yang menguat ketika dialami kelompok rentan.
Contohnya dalam perbincangan di X—dulunya Twitter—terkait pelaksanaan Pemilu berbarengan dengan Rabu Abu. Segelintir umat Islam mengesampingkan, dan menyandingkan dengan Pilpres 2014 yang berlangsung pada bulan Ramadan.
Berdasarkan penjelasan Ficker, hal tersebut termasuk ketidakadilan hermeneutis, yang terjadi karena minimnya pengetahuan dan pemahaman untuk menerangkan suatu peristiwa. Mereka tak memahami kehidupan kelompok minoritas agama dalam bermasyarakat, yang kerap diliyankan dan menerima sikap intoleran.
Kalau Bapak dan Ibu jajaran KPU menyadari, realitasnya hak-hak kami dalam hidup beragama masih luput dari perhatian. Kita lihat sulitnya pendirian gereja.
Dalam reportase Magdalene November lalu, pendeta dan penatua di sebuah gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Bekasi, menceritakan penyerangan dan penggerudukan oleh ratusan massa. Mereka dianggap mengganggu, dan tak punya izin mendirikan bangunan (IMB). Sampai saat ini, jemaat HKBP tersebut menggunakan bangunan sementara, sambil terus berjuang demi mendapatkan IMB.
Pengalaman serupa pernah saya alami semasa SD, di Gereja Kalvari Paroki Lubang Buaya dan Gereja Santo Leo Agung Paroki Jatiwaringin. Kedua gereja yang saat itu masih berbentuk bedeng, menampung ribuan umat beribadah. Enggak cukup layak terutama saat merayakan hari besar agama.
Butuh waktu 30 tahun, sampai Gereja Kalvari menerima IMB pada 2021. Saat itu, Anies Baswedan yang menyerahkan surat izin selaku Gubernur DKI Jakarta. Sementara Gereja Santo Leo Agung menantikan selama 19 tahun, hingga bisa membangun gereja pada 2016. Sebelumnya juga pernah terjadi pembakaran bangunan oleh massa pada 1996.
Bapak dan Ibu jajaran KPU, peristiwa tersebut merupakan akibat dari pengabaian negara, terhadap diskriminasi dan sikap intoleran pada kelompok minoritas agama. Negara seharusnya memfasilitasi hak beribadah masyarakatnya.
Ujung-ujungnya, kelompok minoritas agama menginternalisasi dan menoleransi sikap diskriminatif negara. Salah satunya menggeser jadwal misa—seperti dilakukan KAJ, demi kelangsungan “pesta demokrasi”. Meski di beberapa paroki merayakan Rabu Abu sehari sebelumnya lumrah, untuk mengurangi jumlah umat yang membeludak.
Baca Juga: Skenario Terburuk Jika Prabowo Menang Jadi Presiden RI
Internalisasi Sikap Diskriminatif dan Intoleran
Beragam respons datang dari netizen X sewaktu masalah ini dibicarakan. Ada yang menyesal jadwal ibadah umat Katolik terganggu, ada yang menganggap umat Islam disudutkan karena menyebut kepentingan mereka sebagai mayoritas lebih dipertimbangkan, ada juga umat Katolik yang nrimo dan menekankan toleransi.
Perbincangan itu mempertemukan saya dengan “Vicky”, 23, kemudian kami ngobrol lebih lanjut. Vicky mengatakan, lahan sekitar Gereja Kristen Indonesia (GKI) di bilangan Bekasi—tempat orang tuanya beribadah—digunakan untuk tempat parkir dan titik kumpul kumpul Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kebetulan, letaknya bersebelahan dengan sekretariat RT/RW.
Menurut Vicky, GKI tersebut belum menginfokan pelaksanaan ibadah Rabu Abu, ataupun soal pergeseran jadwal. Namun, orang tuanya merasa enggak punya pilihan untuk mengupayakan hak beribadah. Terlebih jika dilaksanakan pada Selasa malam, lantaran ada kegiatan yang harus diikuti.
“Kalau mau ibadah, mungkin harus cari gereja lain yang tetep mengadakan Rabu Abu,” kata Vicky. Ia juga bersikap nrimo, merujuk pada surat pada kitab Roma 13:1-7 yang menyebutkan, setiap orang harus takluk pada pemerintah karena mereka utusan Allah.
Sayang, kata “takluk” dalam surat tersebut sering dimaknai, sudah sepantasnya masyarakat menerima perlakuan pemerintah. Ini diperkuat ayat dalam surat yang sama, mengatakan bahwa siapa pun yang melawan pemerintah berarti melawan ketetapan Allah sehingga akan dihukum.
Tapi, itu menjadi tanggung jawab umat kristiani dalam menafsirkan Alkitab. Sebab, pemerintah yang dimaksud pada surat kitab Roma yang memiliki kekuasaan terbatas, mampu menegakkan keadilan, kebenaran, dan membuat hidup sejahtera.
Baca Juga: Jika Ganjar Pranowo Jadi Presiden
Perihal menghapus intoleran dan diskriminatif masih menjadi tanggung jawab jajaran pemerintah, termasuk KPU. Namun, penulisan surat ini enggak berharap penggantian tanggal pemilu yang kurang dari 24 jam kok. Toh esensi Rabu Abu enggak hilang karena pergeseran hari.
Saya cuma ingin menyampaikan, kelompok minoritas agama berhak hidup dan merayakan hari keagamaan. Harapannya, KPU dan pemerintah lainnya cukup peduli dengan kepentingan beribadah kami. Begitu pun dengan peran masyarakat secara menyeluruh, untuk merangkul dan menyuarakan ketidakadilan yang dialami kelompok agama minoritas. Tujuannya hanya satu: ketenangan beribadah bukan lagi jadi privilese, seperti milik umat mayoritas saat ini.













