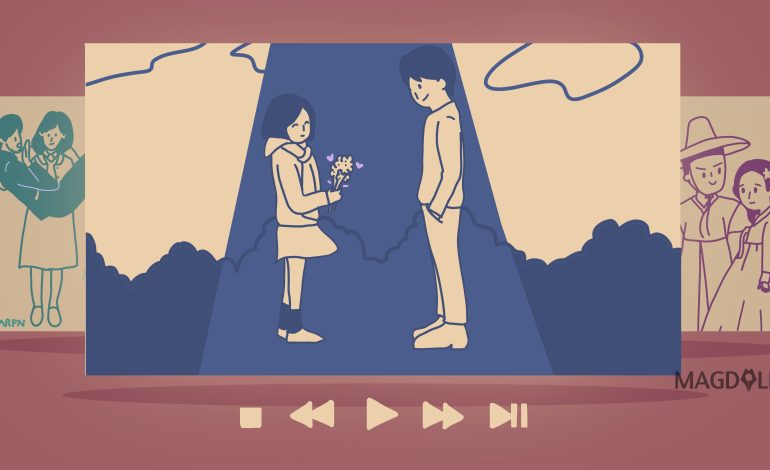‘The Umbrella Academy 2’ dan Sejarah Kelam Rasialisme

Vanya Hargreeves tahu betul bagaimana pedihnya diperlakukan berbeda oleh sang ayah, hanya karena ia dianggap tidak memiliki bakat yang sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Beranjak dewasa, ia baru mengetahui kalau ternyata alasan pengucilan itu bukan karena ia tidak berbakat tapi karena sang ayah tahu ada kekuatan besar dalam dirinya yang bisa membahayakan dunia. Pengucilan menahun itu kemudian jadi trauma dan pesakitan yang membentuk Vanya jadi bom yang bisa meledak kapan saja.
Begitulah kira-kira garis besar musim pertama The Umbrella Academy yang tayang di Netflix tahun lalu. Serial ini menawarkan plot yang bukan tipikal cerita pahlawan super pada umumnya. Selama ini penggambaran superhero selalu identik dengan memberantas kejahatan di dunia dan menyelamatkan umat manusia. The Umbrella Academy tidak hanya menampilkan penyelamatan dunia secara heroik, tapi juga menghadirkan sisi-sisi kehidupan para pahlawan super yang ternyata tidak kalah menyedihkan serta traumatis dibanding kehidupan orang biasa. Konflik keluarga yang dibangun di serial ini membuat penonton lebih relate dengan jalan ceritanya.
Diadaptasi dari komik besutan vokalis My Chemical Romance, Gerard Way, The Umbrella Academy bercerita tentang tujuh anak berkekuatan super yang diadopsi oleh miliarder Reginald Hargreeves. Sebagai ayah angkat, Hargreeves yang berdarah dingin dan misterius melatih mereka sejak kecil agar bisa mengembangkan serta mengontrol kekuatan yang ada dalam tubuh mereka. Alih-alih memberikan kehangatan keluarga, Hargreeves membesarkan anak-anak itu seperti di kamp militer.
Di akhir cerita musim satu, Number Five, si anak penjelajah dimensi membawa keenam saudaranya menjelajah mesin waktu agar bisa menyelamatkan dunia yang mau kiamat karena Vanya.
Baca juga: Konspirasi Wahyudi: 5 Rekomendasi Film Bertema Yahudi Ortodoks di Netflix
Rasialisme, fanatisme, dan homofobia
Akhir cerita musim pertama cukup membuat kesal karena menggantung. Tapi kekecewaan itu terbayar di musim kedua. The Umbrella Academy 2 bahkan mendapat respons positif dari kritikus di Rotten Tomatoes dengan skor 91 persen dibanding yang pertamanya, 75 persen.
Kali ini, ketujuh anak Hargreeves kembali ke tahun 1960-an, tapi masing-masing sampai di tahun berbeda. Klaus dan Ben yang tiba di 1960, Allison di 1961, Luther pada 1962, sementara Diego, Five, dan Vanya saat 1963.
Di tahun-tahun tersebut tersebut white supremacy dan rasialisme yang parah masih terjadi di Amerika. Allison sebagai satu-satunya perempuan berkulit hitam di antara ketujuh saudaranya, merasa kaget ketika ia tiba di tahun tersebut. Ia diusir dari restoran khusus orang kulit putih, dan kemudian bertahan hidup dengan bekerja di salon orang kulit hitam, yang ternyata merupakan organisasi bawah tanah melawan rasialisme kala itu.
Kisah Allison digambarkan dengan sangat menyentuh. Bagaimana buruknya situasi saat itu, ketika segregasi masih kuat dijalankan. Ceritanya mengambil sejarah gerakan hak sipil tanpa jalan kekerasan di AS pada 1960an, di mana orang-orang kulit hitam melakukan protes diam dengan hanya duduk di restoran untuk orang kulit putih lalu minta dilayani. Sudah tentu, bukannya dilayani mereka malah dilaporkan ke polisi karena dianggap memberontak.
Di tahun 1960-an gerakan anti kekerasan melawan rasisme itu dipelopori oleh Marthin Luther King yang terinspirasi oleh ajaran Mahatma Gandhi. King percaya jika gerakan ini bisa menjadi alternatif perlawanan untuk mendapatkan hak-hak sipil yang setara bagi orang kulit hitam di Amerika.
Baca juga: ‘Anne with an E’, Serial Berlatar Abad 19 dengan Isu yang Masih Relevan
Di tengah isu Black Lives Matter, cerita yang diangkat The Umbrella Academy ini terasa sangat relevan.
Selain konflik kehidupan Allison, kisah lain yang tak kalah menarik adalah Klaus, yang punya kemampuan berkomunikasi dengan orang meninggal. Bisa dibilang bagian komedi dari film ini banyak dibawakan oleh Klaus. Ia yang sering mengeluarkan kata-kata bijak dan satir berhasil membuatnya dianggap sebagai nabi oleh pengikutnya. Meski terlihat hanya guyonan untuk menambah bumbu komedi di film ini, tapi plot ini menyampaikan pesan soal fanatisme berlebihan. Klaus bahkan sampai harus menghindar dari pengikutnya yang fanatik karena merasa itu sudah tidak lagi sehat bagi dirinya.
Klaus juga merupakan representasi kelompok queer, dengan love interest Dave yang bergabung dengan militer pada saat Perang Vietnam. Di sini terangkat isu maskulinitas toksik dan homofobia, lewat karakter paman Dave yang benci Klaus dan terus memaksa Dave jadi tentara.
Isu homofobia juga ada di plot Vanya, yang menjalin hubungan dengan Sissy. Keluarga Sissy menganggap lesbian adalah virus yang harus dijauhi dan dimusnahkan.
Meski berlatar tahun 1960-an di Amerika, isu-isu ini terasa dekat dan, sedihnya, masih jamak ditemukan di Indonesia hingga saat ini. Bagaimana komunitas LGBTQ yang selalu mendapat perundungan bahkan persekusi. Bagaimana maskulinitas toksik sudah mendarah daging, ditambah fanatisme agama yang makin ke sini makin mengkhawatirkan.