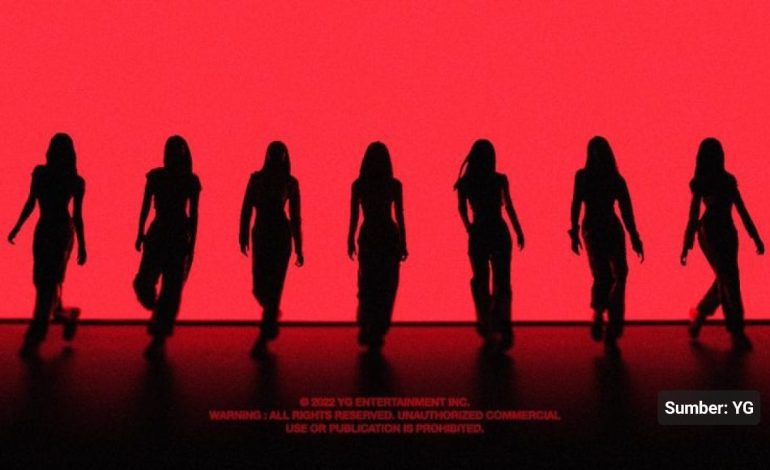Tidak Menjadi Perempuan Sunda

Terlahir di tengah keluarga dengan latar belakang suku dan budaya berwarna, bikin aku tumbuh lebih toleran dengan perbedaan. Ayahku adalah lelaki Sunda, sedangkan ibu berdarah Lampung. Konon, mereka bertemu di Yogyakarta sampai akhirnya memutuskan menikah. Karena latar belakang inilah, dalam obrolan sehari-hari, tak pernah ada pakem bahasa yang kami gunakan. Kadang kami ngobrol dengan Bahasa Jawa, Bahasa Sunda, atau Bahasa Melayu.
Baca juga: Jualan Sentimen Agama dan Ras dalam Bisnis Kamar Kos
Sejak kecil, aku dan saudara-saudara tinggal dan bersekolah di lingkungan tempat ayah dibesarkan, di salah satu daerah Jawa Barat. Enggak usah ditanya, sudah otomatis mayoritas temanku adalah orang Sunda. Meski berada dalam lingkungan pergaulan yang homogen, untungnya keluarga tetap mengajakku untuk berpikiran terbuka, apalagi jika menyangkut soal suku dan budaya.
Dalam hal ini, aku juga cenderung tak berusaha mendefinisikan diri sebagai orang Sunda atau identitas suku lain. Sebaliknya, aku lebih nyaman menyebut diri sebagai orang Indonesia. Tentu aku menyukai dan mengagumi keindahan budaya kedua suku yang menjadi identitas kedua orang tuaku. Namun, rasanya sulit memutuskan salah satu identitas kesukuan yang cukup merepresentasikan kepribadianku.
Keyakinanku ini tak jadi soal, sampai suatu hari aku diberikan berbagai stereotip dari lingkungan sekitar. Kenapa orang-orang terbiasa melakukan simplifikasi dalam mengidentifikasi identitas dari daerah asal, tanpa mau susah payah menelusuri lebih lanjut latar belakang orang lain?
Misalnya, saat sedang mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Jawa Tengah, salah satu rekan tim melabeliku “suka dandan”, sembari menyinggung daerah asalku. Padahal sehari-hari, selama KKN, aku tak menggunakan pulasan makeup sedikit pun atau berdandan secukupnya. Lantas, kenapa orang-orang ini tetap melontarkan stereotip tersebut meski sama sekali tak relevan?
Lagi pula apa yang salah dengan kecenderungan perempuan suka berdandan? Mengapa pula harus diasosiasikan dengan perilaku negatif? Padahal kegemaran ini bisa menjadi sarana bagi perempuan untuk berekspresi dan mengapresiasi diri sendiri. Banyak pula perempuan yang lewat kegemarannya ini memilih jalan produktif untuk menjadi makeup artist dan beauty influencer. Kesuksesan mereka telah berhasil menginspirasi banyak perempuan untuk lebih berani mengaktualisasikan diri dan terus produktif berkarya.
Baca juga: Kami Perempuan Melanesia, Kami Ada, dan Kami Cantik!
Tak cuma sekali aku dilekati stereotip berdasarkan suku asal. Saat sudah bekerja, rekan laki-laki berusaha menggodaku dengan bersikap genit. Aku cuek bebek, sehingga tampaknya ia kecewa dengan responsku yang dingin dan mengabaikannya. Lalu dengan entengnya, ia bilang sikapku tidak seperti perempuan Sunda pada umumnya yang senang menggoda dan digoda. Memangnya susah, banget mengakui diri sebagai sosok kurang ajar dengan menggoda rekan kerja, ketimbang menyinggung asal sukuku?
Stereotip lain juga ajeg sampai di telingaku. Orang-orang umumnya memprovokasiku dengan menyebut perempuan Sunda pemalas dan matrealistis, lelaki Sunda tak setia dan hobi selingkuh. Jujur, semua stereotip ini membuat aku tak nyaman. Padahal selama bersinggungan dengan teman dari berbagai latar belakang, karakter-karakter itu bisa saja melekat pada semua orang.
Baca juga: Stop Pandang Kulit Putih Lebih Superior
Celakanya, stereotip ini tak cuma menimpa perempuan Sunda, tapi juga Jawa yang dicap penuh basa-basi; orang Batak yang kasar; maupun orang Minang yang pelit. Dalam hemat saya, stereotip ini bisa tumbuh subur karena industri media dan hiburan kita mengekalkannya. Ini dibenarkan dalam Cross-Cultural and Intercultural Communication (2003). Bahwa stereotip, terutama yang bersifat normatif, terbentuk dari pendidikan, media massa, dan atau pengalaman sejarah.
Jadi, selama media masih memotret orang-orang dari suku tertentu secara apriori dan simplisistik, maka stereotip negatif itu akan terus lestari. Padahal jika dipikir-pikir, bukankah lebih indah jika kita bisa menyikapi perbedaan identitas itu dengan arif, alih-alih melekatkannya dengan prasangka dan cap buruk?
Opini yang dinyatakan di artikel tidak mewakili pandangan Magdalene.co dan adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis.