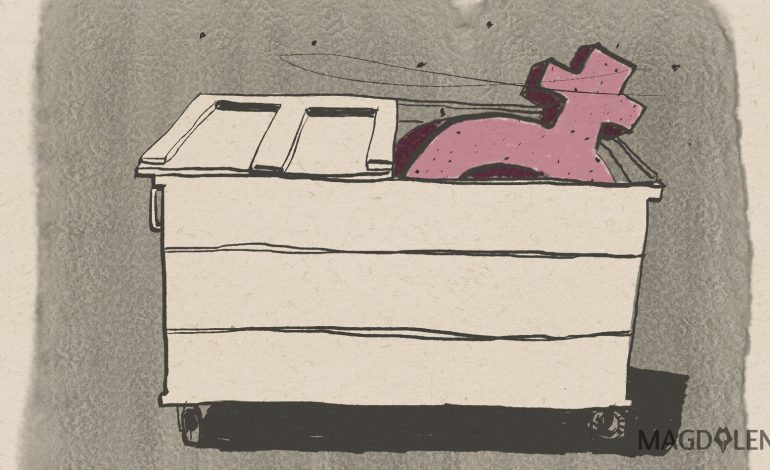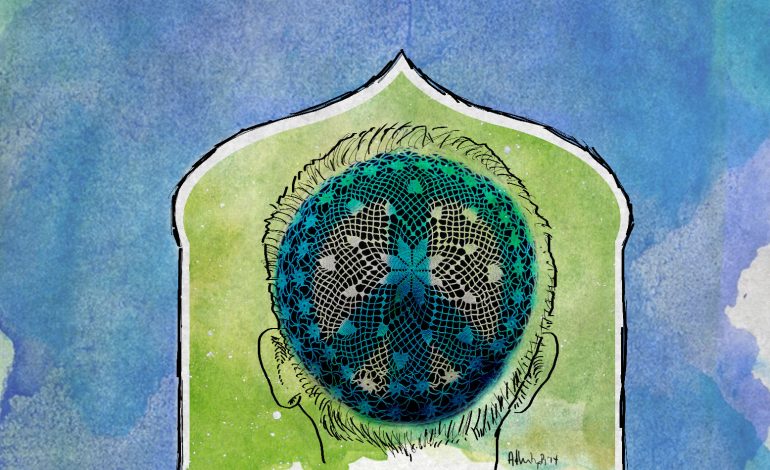Uang Indikator Feminisme?

“Perempuan harus kerja, dong. Jangan mau tinggal di rumah. Itu namanya kemunduran! Punya uang sendiri, bisa beli apa pun sendiri!”
“Oh, ya, setuju lah. Feminis jangan mau tinggal diam di rumah! Itu bukan sikap feminis!”
Saya yakin, bukan hanya saya yang pernah mendengar percakapan bernada sama. Atau bahkan jadi orang yang mengutarakannya. Saya tersentil juga mendengar percakapan tadi. Mungkin ada yang bertanya-tanya. Memang kenapa? Bukankah hak perempuan untuk bekerja di luar rumah memang salah satu hal yang diperjuangkan feminisme? Artikel ini mencoba mengungkapkan, ada apa dengan cara pandang tersebut, dan hubungannya dengan kapitalisme.
Sebelumnya, mari kita kembali ke percakapan tadi. Ada dua hal yang bisa disimpulkan dari sana. Pertama, bahwa menurut mereka, perempuan dikatakan telah mendukung feminisme jika bekerja di luar rumah, dan perempuan yang tidak bekerja di luar rumah, adalah simbol ketidakfeminisan perempuan. Mereka menetapkan indikator keberhasilan feminisme hanya dari kemampuan perempuan untuk menghasilkan uang lalu membeli barang saja. Mereka, sekali lagi, tidak mempertimbangkan hal lain.
Mereka juga bersikap tidak setuju pada perempuan yang tidak bisa menghasilkan uang sendiri. Secara tidak langsung, penilaian tersebut menghapuskan makna feminisme itu sendiri. Karena, hal itu mengasosiasikan feminisme dengan kapitalisme, melalui konsumerisme. Padahal, feminisme dan kapitalisme seharusnya bertolak belakang.
Profesor Sejarah dari AS, P.N. Stearns, dalam bukunya yang berjudul Consumerism in World History: The Global Transformation of Desire menggambarkan konsumerisme sebagai masyarakat yang anggotanya banyak menjadikan perolehan barang yang tidak dibutuhkan sebagai sebagian tujuan hidupnya. Mereka membeli apa yang mereka inginkan, bukan butuhkan. Karenanya, mereka menjadi sasaran empuk kapitalisme.
Guru Besar Sosiologi Ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Bagong Suyanto, menyampaikan bahwa kapitalis, alias pemilik modal, melakukan beragam cara agar konsumen terus membeli produk. Pada suatu titik, konsumen tidak bisa lagi membedakan kebutuhan dan keinginan.
Lalu apa hubungan itu semua dengan feminisme? Akademisi Nicki Lisa Cole dan Alison Dahl Crossley dari University of California di Santa Barbara, pada artikel jurnalnya yang berjudul On Feminism in the Age of Consumption, menuliskan bahwa akar dari feminisme adalah penghapusan ketidaksetaraan. Awalnya adalah ketidaksetaraan terhadap perempuan. Sedangkan kapitalisme—hal yang didukung oleh konsumerisme—adalah bentuk dominasi, dalam hal ini, dominasi pemilik modal. Adanya dominasi tentunya menimbulkan ketidaksetaraan. Dasar dari feminisme dan kapitalisme bertolak belakang—feminisme melawan dominasi, dan kapitalisme adalah mendominasi. Maka adalah hal yang kurang tepat apabila mereka berjalan beriringan.
Bukan berarti bahwa perempuan yang tidak bekerja di luar rumah sudah pasti lepas dari konsumerisme. Pembelian barang yang tidak dibutuhkan bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk ibu rumah tangga. Begitu juga dengan perempuan yang bekerja, tidak selamanya menganut konsumerisme. Uang hasil bekerja banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau untuk kebutuhan sendiri. Saya tekankan, bahwa yang menjadi permasalahan bukanlah kepemilikan uang, namun ke mana uang ini mengalir.
Masalah kedua yang ada di percakapan di awal artikel, mengenai ketidakfeminisan perempuan yang tidak bekerja di luar rumah. Bahwa jika hal itu dilakukan, maka aturan feminisme telah dilanggar.
Feminisme bukan tentang berubah menjadi laki-laki. Banyak orang yang masih berpikir bahwa bekerja di luar rumah—agar seperti laki-laki, bukan semata-mata karena kemauan—adalah hal yang feminis. Bagi saya, itu merupakan paradoks feminisme. Apabila feminisme adalah menjadi laki-laki, bukankah hal itu berarti menilai bahwa laki-laki memang lebih superior daripada perempuan? Bahwa perempuan harus menjadi laki-laki untuk menjadi feminis?
Feminisme, pada dasarnya, adalah pemberian hak pada perempuan untuk memilih. Selama pilihan tersebut diputuskan tanpa paksaan siapa pun dan dengan kesadaran. Mau bekerja di luar rumah? Di rumah saja? Atau bahkan tidak menikah? Boleh saja. Perempuan yang tidak bekerja tidak sedang melakukan kesalahan. Bila itu merupakan pilihan, maka sesungguhnya, itu feminis.
Maka saya bisa simpulkan, bahwa menetapkan kemampuan perempuan untuk menghasilkan uang sebagai indikator feminisme adalah hal yang kurang tepat. Hal itu “membawa” feminisme menuju kapitalisme, hal yang tidak feminis.
Bersama-sama, mari kita lihat diri kita masing-masing. Apa kita sudah menjadi feminis, atau malah mendukung hal yang sebaliknya? Apakah kita sudah menghargai keputusan-keputusan perempuan lain? Lebih jauh lagi, apakah indikator feminisme kita sudah tepat?
Khairina F. Hidayati adalah seorang mahasiswi. Selain kuliah, ia suka membaca dan menulis esai, novel, dan cerita pendek. Ia membenamkan sebagian besar tulisan itu di memori internal komputernya. Namun beberapa telah diterbitkan. Bisa dibaca di akun Twitter dan Instagram @krnfad, dan juga blog kacamatakai.wordpress.com.