Indonesia Punya PP Tunas untuk Lindungi Anak di Internet, Apa itu?
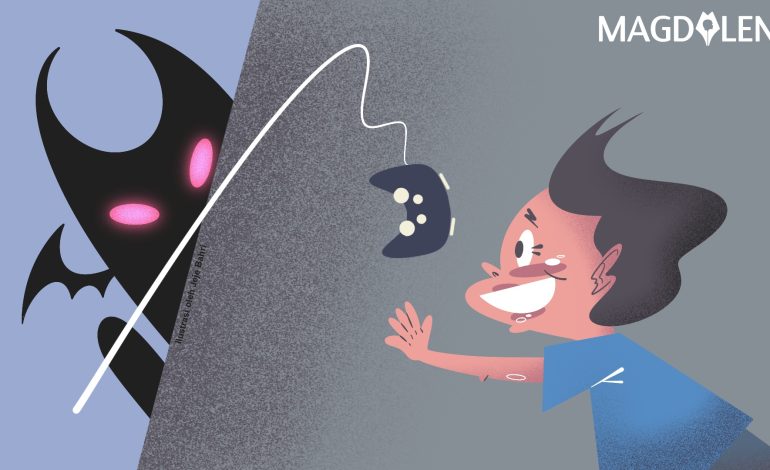
Apakah anak-anak perlu dibatasi menggunakan media sosial?
Pertanyaan ini pernah diajukan perusahaan riset independen IPSOS pada 2025 kepada 23.700 orang dewasa di 30 negara. Hasilnya, Indonesia menjadi negara yang paling setuju dengan pembatasan tersebut, sebanyak 87 persen responden mendukung. Prancis menyusul dengan 85 persen, sementara Australia berada di posisi keenam dengan 79 persen.
Besarnya dukungan ini tak lahir dari ruang hampa. Di Indonesia, relatif banyak anak yang menghabiskan waktu lebih lama dengan gawai mereka. Ini berbanding terbalik dengan ketersediaan pendampingan orang tua.
“Saya sibuk kerja di Depok. Anak saya ‘Iman’ (bukan nama sebenarnya) tinggal di Temanggung sama neneknya,” kata Emon, 38.
Perempuan pemilik nama asli Sutiyem itu sudah merantau ke Depok sejak dua puluh tahun terakhir. Karena itu, ia mengaku waswas soal pendampingan aktivitas anaknya di media sosial dan gim daring. Selain soal jarak, ia juga terbentur hambatan keterbatasan sinyal, waktu, dan komunikasi.
Saya lantas meminta Emon untuk membuka dua platform favorit anaknya TikTok dan Roblox. Tujuannya untuk menilai seberapa yakin ia soal keamanan dua platform tersebut. Satu menit pertama menjelajah Tiktok, Emon cukup terganggu dengan banyaknya konten dewasa yang kurang pantas untuk anaknya yang masih berusia 11 tahun itu. Misalnya, konten tarian yang menampilkan gerakan vulgar atau bahasa kasar.
Emon sendiri tak terlalu paham TikTok punya batasan usia minimal 13 tahun dan fitur Family Pairing untuk mendukung pengawasan orang tua. Saat ini banyak anak cenderung bisa memalsukan usia aslinya. “Saya aja enggak paham, apalagi nenek Iman,” imbuhnya.
Senada dengan TikTok, menurut Emon, Roblox juga kurang sesuai buat anaknya. Ia menemukan ada iklan judi daring yang muncul di aplikasi itu. “Ini bukan buat anak kecil. Tapi gimana lagi, saya kerja jauh, enggak mungkin dampingi anak terus. Saya takut dia lihat hal-hal yang enggak pantas, atau tiba-tiba jadi ikut judi online” ujar Emon, (3/12).
Ketakutan Emon juga dirasakan oleh Kinasih, 26, ibu tunggal dari Yogyakarta. Saat membuka aplikasi video di YouTube yang sering ditonton putrinya yang berusia empat tahun, konten edukatif muncul berdampingan dengan iklan permainan dan video komersial yang tidak sesuai usia.
“Saya kira aman, tapi kadang muncul video aneh. Saya enggak bisa cek semua karena harus kerja,” katanya lewat telepon, (3/12).
“Kalau ada aturan yang batasi, saya setuju. Asal ada gantinya biar anak tetap bisa belajar secara interaktif,” imbuhnya.
Pengalaman Emon dan Kinasih mencerminkan kondisi yang terbilang semakin umum. Anak-anak menjelajah internet dengan pendampingan terbatas, terutama di keluarga pekerja dan orang tua tunggal. Dalam kondisi ini, standar perlindungan digital dari platform maupun negara pun jadi krusial.
Inilah alasan utama pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Regulasi ini menetapkan kerangka bagi platform digital untuk menyesuaikan akses dan fitur berdasarkan usia dan tingkat risiko.
Direktur Ekosistem Media, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Farida Dewi menjelaskan pada (25/11), PP Tunas semangatnya menjamin perlindungan anak di ruang digital. Berbeda dengan peraturan serupa dari negara lain seperti Australia, PP Tunas tak saklek menutup akses anak terhadap internet, melainkan menyesuaikan fitur dan konten sesuai usia anak.
Baca juga: Ekskul Roblox di Sekolah: Inovasi Pendidikan atau Eksperimen Berbahaya?
Alasan Lain Kenapa PP Tunas Mendesak
Data Statistik Telekomunikasi Indonesia dari Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan 72,78 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet, dengan 96 persen rumah tangga memiliki ponsel pintar. Sebanyak 39,71 persen anak usia dini sudah memakai telepon seluler dan lebih dari sepertiganya mengakses internet. Angka ini menggambarkan paparan digital pada anak terjadi sangat dini, jauh sebelum mereka mampu memilah konten yang aman.
Sejumlah riset global menggambarkan besarnya risiko yang dihadapi anak. Studi longitudinal JAMA pada Juni 2025, dilansir NPR dalam artikel “Screen addiction and suicidal behaviors are linked for teens, a study shows,” menemukan remaja dengan kecanduan gawai memiliki risiko 2–3 kali lebih tinggi mengalami pikiran dan perilaku bunuh diri. Kecanduan tersebut ditandai penggunaan ponsel sebagai cara melupakan masalah, bukan semata durasi pemakaian.
Sebelas dua belas, mengutip artikel Bloomberg Technoz berjudul “Pakar: Anak Diasuh Algoritme Medsos Rentan Bunuh Diri & Terorisme” menunjukkan remaja kini “diasuh algoritme” karena konten ekstrem seperti misogini, kekerasan, hingga radikalisasi dapat terus muncul kendati akun sumbernya diblokir.
Investigasi BBC dalam “Teens still exposed to harmful social media posts” (14/11) menunjukkan pola paparan berbeda berdasarkan gender. Dalam hal ini, anak perempuan biasanya menerima konten depresi, perundungan, dan kekerasan berbasis gender. Sementara anak laki-laki disajikan video senjata, kekerasan terhadap hewan, dan konten agresi.
Sementara, child grooming juga relatif meningkat untuk semua gender. Media yang sama melaporkan satu dari tujuh anak mengalami grooming daring, pola yang juga muncul dalam berbagai laporan kasus di Indonesia.
Baca juga: #HariAnak2025: Anakmu Kecanduan Gim Anomali? ‘Parenting’ Digital Berbasis Pancasila Bisa Jadi Kunci
Tren Global Pembatasan Akses Digital Anak
Sejumlah negara telah menerapkan kebijakan lebih ketat dibanding Indonesia. Laporan Helen Livingstone untuk BBC News Indonesia, “Australia larang anak di bawah 16 tahun pakai medsos – Bagaimana caranya?” (21/11), menyebut Australia kini mewajibkan platform mencegah anak di bawah 16 tahun membuat akun mulai 10 Desember 2025. Akun yang sudah ada pun harus dinonaktifkan. Kebijakan ini diberlakukan setelah studi pemerintah menemukan 96 persen anak usia 10–15 tahun menggunakan media sosial dan tujuh dari sepuluh di antaranya terpapar konten berbahaya. Platform dapat dikenai denda hingga US$32 juta jika terjadi pelanggaran.
Untuk memastikan kebijakan berjalan, platform harus menerapkan verifikasi usia menggunakan kartu identitas pemerintah, pemindaian wajah atau suara, serta age inference. Namun, sebagaimana dicatat dalam laporan yang sama, sejumlah pakar menilai teknologi pemindaian wajah kurang akurat untuk kelompok usia remaja.
Dalam laporan Kamila Meilina di Katadata.co.id berjudul “Deret Negara Larang Anak Main Media Sosial Selain Malaysia” (26/11), Prancis disebut merekomendasikan larangan media sosial bagi anak di bawah 15 tahun tanpa izin orang tua, serta mengusulkan “jam malam digital” bagi remaja. Denmark dan Norwegia menyiapkan regulasi serupa.
Spanyol mengajukan RUU yang mewajibkan persetujuan wali untuk anak di bawah 16 tahun. Cina membatasi jam penggunaan ponsel anak antara 22.00 hingga 06.00. Di Amerika Serikat, Negara Bagian Florida melarang anak di bawah 14 tahun memiliki akun media sosial mulai 1 Januari 2025.
Indonesia memilih jalur berbeda. Lewat PP Tunas, pemerintah tidak menerapkan larangan total, tetapi menekankan tata kelola risiko berbasis usia, verifikasi identitas, dan pembatasan fitur.
Baca juga: Apa itu ‘Child Grooming’, Semua Fakta yang Harus Kamu Tahu
Apa Isi PP Tunas dan Mengapa Implementasinya Mungkin Tak Mudah
PP Tunas mewajibkan platform menetapkan batas usia penggunaan, melakukan penilaian risiko produk digital, serta memastikan seluruh akun anak berada dalam pengaturan default high privacy. Fitur parental control harus tersedia dan mudah digunakan. Platform juga dilarang memprofilkan anak untuk kepentingan komersial atau menggunakan praktik manipulatif untuk mendorong anak memberikan data.
Akses platform dibagi berdasarkan kategori usia. Anak di bawah 13 tahun hanya boleh menggunakan aplikasi risiko rendah dengan izin orang tua. Anak usia 13–15 tetap membutuhkan persetujuan, sedangkan usia 16–17 dapat menyetujui sendiri, meski orang tua akan mendapat notifikasi dan kesempatan membatalkan.
Namun, laporan Intan Rakhmayanti Dewi di CNBC Indonesia berjudul “Terbit Kilat demi Lindungi Anak, PP Tunas Masih Membingungkan” (22/10/2025) mencatat belum adanya daftar resmi platform “risiko rendah–sedang–tinggi.” Kondisi ini menyulitkan orang tua yang membutuhkan panduan praktis.
SAFEnet menambahkan kekhawatiran mengenai verifikasi usia berbasis biometrik yang dapat membuka celah pengumpulan data sensitif anak.
Berkaca dari pengalaman Australia menunjukkan pelarangan dapat mendorong anak menggunakan VPN atau akun palsu. Hal serupa dapat terjadi di Indonesia jika regulasi tidak diiringi edukasi dan alternatif digital yang aman.
“Kalau cuma disuruh ngawasin, saya enggak sanggup. Saya juga harus cari uang,” kata Emon mengenai keterbatasan waktu dan dukungan keluarga.
Kinasih menambahkan, “Anak boleh dibatasi, tapi harus ada alternatif biar mereka tetap belajar. Jangan cuma larang.”
PP Tunas menjadi langkah negara untuk memperjelas tanggung jawab platform dan mengurangi beban pengawasan yang selama ini dipikul keluarga. Namun, efektivitasnya bergantung pada SOP teknis, transparansi algoritma, literasi digital, serta penyediaan opsi aman bagi anak.
Masa transisi dua tahun yang diberikan kepada platform akan menentukan sejauh mana regulasi ini dapat berjalan.
Tulisan ini didukung oleh Komdigi






















