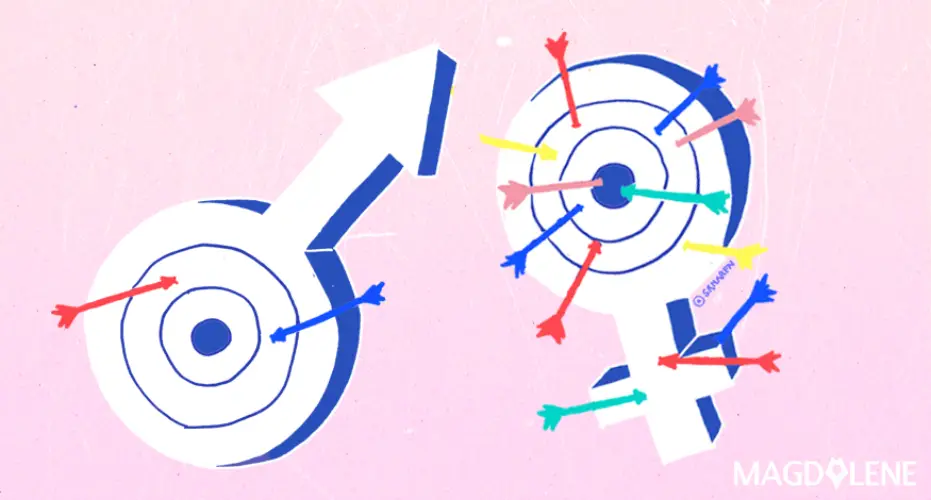Obrolan Candid dengan Gina S. Noer, Sutradara ‘Like & Share’: “I Walk the Talk”

Dalam pertemuan lewat zoom Februari 2022 lalu, Gina S Noer sempat cerita pada saya tentang calon naskah film terbarunya. “Gue lagi nulis tentang persahabatan perempuan,” katanya.
Hari itu kami banyak mengobrol tentang isu kekerasan seksual dan perlindungan korban di industri film. Gina memang dikenal sebagai salah satu sutradara yang vokal dengan isu ini. Ia jadi salah satu filmmaker yang berjuang untuk memasukan klausul anti-kekerasan dalam kontrak produksi film, sekaligus yang menerapkan SOP penanganan kasus kekerasan seksual di sebuah produksi film—dua hal baru dalam industri film kita.
Baca juga: Sepotong Sore Dekat Iduladha Bersama Shinta Ratri
Konsistensi menyuarakan isu ini juga tergambarkan dalam film-film Gina. Dua Garis Biru, film debutnya 2019 lalu, dapat kritik baik dalam mengemas isu sensitif: pernikahan dini dan kehamilan yang tidak direncanakan. Isu-isu perempuan serta kesetaraan otomatis menempel pada figur Gina.
Isu kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender online (KBGO), seksualitas perempuan remaja, kecanduan pronografi, sampai hubungan anak perempuan dan ibunya kembali lagi jadi center di film terbaru Gina, Like & Share. Ceritanya memang tentang persahabatan dua perempuan remaja, Lisa dan Sarah, yang diperankan Aurora Ribero dan Arawinda.
Seperti Dua Garis Biru yang sempat menuai kontroversi, Like & Share juga sempat tak habis-habis jadi obrolan di media sosial. Terutama, setelah banyak orang mengaitkan film ini dengan masalah personal yang sedang dihadapi salah satu aktor utamanya, Arawinda. Tak semujur Dua Garis Biru yang tetap berhasil menembus box office, Like & Share harus turun dari bioskop lebih cepat karena jumlah penonton yang tak sesuai ekspektasi.
Akhir Desember kemarin, saya menyambangi Gina di kantornya, Wahana Kreator untuk mengobrol tentang proses pembuatan Like & Share. Sepulang mengambil rapor anaknya, Gina menyambut Magdalene dengan gembira.
Di beberapa interview sebelumnya, lo sempat bilang kalau plot porn addiction di film ini terinspirasi dari twit anonim remaja perempuan 18 tahun di Twitter. Gimana ceritanya twit itu berubah jadi Lisa dan Sarah? Kenapa part itu akhirnya jatuh ke Lisa?
Menurut gue, menarik ketika ngomongin hubungan yang hilang. Anak-anak yang dalam masa pertumbuhannya, sebetulnya butuh sekali koneksi dengan ibunya. Dan kadang-kadang ibu ini bukan ibu pekerja biasa, tapi juga ibu rumah tangga, yang harusnya (punya hubungan) erat (dengan anaknya). Tapi, gagasan ideal tentang hubungan itu yang sebenarnya bahaya, to some extend. Sebenarnya ini kasus klasik lah, dua orang yang punya hubungan darah, yang bahkan tinggal satu atap, tapi gak pernah kenal satu sama lain. Dari situ, akhirnya dieksplorasilah karakter Lisa ini. Awalnya, Lisa ini anak yang tinggal di perumahan militer. Jadi, ayahnya militer, ibunya tinggal di rumah. Gak bisa cerai, karena masalah jabatan. Kita udah cari lokasi lah, ketemu sama beberapa aparat, mau kasih kesempatan datang ke lingkungan rumah mereka. Tentu, ditolak.
Dari situlah mencari lagi, mengksplorasi lagi. Ketika riset Lisa dan Sarah, ketemu Arawinda dan Aurora Ribero. Awalnya Ara adalah Lisa, dan Aurora adalah Sarah. Ketika melihat, dan dieksplor lagi, dibaliklah karakter ini. Kemudian, ketika melihat Lisa ini malah jadi intriguing, karena Aurora Ribero. Gimana ya, anak remaja belasteran melihat identitas mereka?
Sebenarnya membuat insting itu muncul, dengan rasa ingin tahu ini karena gue tumbuh di masa Orde Baru—jadi ketika karya fiksi itu bener-bener enggak boleh membahas soal suku, agama, ras, dan seks. Bahkan kadang-kadang sampai saat ini tuh, ketika ada kompetisi karya fiksi baik buku atau film, berusaha dihindarilah membahas sara dan seks itu. Tapi, akhirnya jadi menarik kan bagaimana kalau kita benar-benar membahas sara dan seks itu di sebuah karakter yang benar-benar komprehensif pembahasannya. Bukan sekadar eksploitatif, tapi juga eksplorasi. Karena kita juga enggak mungkin lepas gitu. Ketika kita tidak bisa merayakan diri kita seotentik-otentiknya, maka di situ kita bisa kehilangan dengan hubungan dengan yang justru dekat sama kita dan di situ kecanduan bisa terjadi.
Isu ini sensitif. Ada tanggung jawab sosial yang besar yang harus dibawa. Secara teknis juga, lo bahkan bikin SOP pengadeganan intim (intimacy scene), yang setahu gue belum pernah dibikin produksi lain. Gimana meyakinkan Pak Parwez untuk bikin film yang lumayan ribet ini?
Pertama beruntung sih kerja sama Pak Parwez, baik Stavision dan Wahana Kreator. Kalau Wahana Kreator udahlah, orang-orangnya udah sefrekuensi, makanya kita nyambung. Pak Parwez? Kita nyambung sama beliau karena punya frekuensi yang sama. Dan bagai ragam filmnya Pak Parwez itu ada benang merah. Dia percaya sekali sama value apa yang mau disampaikan dengan penonton. Jadi, kalau mau kerja sama Pak Parwez itu adalah tentang value apa yang mau dikasih sama penonton. Nah, Pak Parwez juga adalah orang yang bikin The Virgin, Perempuan Berkalung Sorban—sama gue. Dari situ sih, setelah Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga, kemudian gue ngasih beberapa sinopsis lagi, baik di Wahana Kreator dan Starvision, terpilih lah Like & Share ini.
Kenapa SOP untuk intimacy scene ini jadi penting?
Gue itu tuh selalu percaya, kalau kita ingin mengubah sesuatu tuh kita enggak bisa melakukannya per individu atau per projek, kita harus mengubah sistem. Dan mengubah sistem tuh ribet, ribet di awal aja, tapi.
Lama-lama, ketika kita udah establish (memantapkan) sistemnya, itu akan membuat sebuah snow ball effect yang positif, di mana semua orang akan bekerja dengan lebih baik. Bisa saling menghormati, dan bagaimana pun business wise, ketika kita bekerja dengan etik, maka lebih banyak yang positif yang datang ke orang-orang yang menjadi produsennya.
Nah, gue bersyukur kerja sama teman-teman di Wahana Kreator, yang memang percaya sama sistem. Jadi gak cuma sekadar ngomongin isu, abis itu udah. Tapi, juga ngomongin apa sih legacy-nya? Apa sih warisan untuk industri ke depan? Untuk Indonesia ke depannya. Dari situ, ketika kita ingin punya SOP. Setelah punya SOP antikekerasan seksual, SOP (bekerja dalam situasi) Covid-19—ternyata ketika punya SOP ini kerja tuh jadi lebih matang, kerja tuh jauh lebih nyaman, dan merasa aman. Jadi ketika mau bikin Like & Share, yang ditulis dengan sebebas-bebasnya, terus ada beberapa adegan yang intim biasa aja sampai skalanya perkosaan, reaksi pertama gue adalah siapa nih teman-teman yang diajak bikin dan ribet bersama.
Dalam visi pertama gue juga enggak mau semuanya perempuan. Kalau kita ekslusif di perempuan aja, kita enggak bisa mendorong laki-laki atau gender apa pun untuk sama-sama kerja barengan. Justru padahal ketika kita kerja barengan nih, kerja sama—kerja baik yang barengan, kita tuh jadi lebih enak. Semua orang bisa menjadi spokeperson untuk SOP ini, dan ternyata mereka (laki-laki yang terlibat) juga punya kebanggaan baru, bahwa kita bisa kok bikin ini.
DOP gue, Deska Binarso dengan teman-temannya, kru-krunya, akhirnya ketika keluar dari film ini punya kebanggaan baru. Bukan sekadar jadi film bagus, tapi kami sebagai laki-laki bisa kok berada dalam sebuah sistem kerja yang amat sangat sulit, tapi bisa punya hubungan kerja yang enak dan menghargai satu sama lain.
Nah, sistem ini ketika pun disusun, enggak ribet-ribet banget. Ilmu tuh banyak banget di internet. Kita bisa dapat dari Youtube, yang Normal People. Ada lagi Amelya Oktavia, yang memimpin membuat SOP ini, mencari website-website yang lain. Dan ketika kita ngobrol, ternyata acting coach kita Rumana, dia itu lulusan asal Singapur, dan di sana diajarin bagaimana sih cara melakukan SOP ini.
Awalnya kita mau ideal, kita mau hire intimacy coach dari luar—dari Australia, dari Inggris—dan itu kemahalan. Dan masalah kedua itu Covid-19. Kita coba ke intimacy coach di Phillipine, mereka baca skenarionya, ditolak. Karena mereka juga enggak berani dengan konteks sosial yang ada. Dan akhirnya setelah itu kita harus mencoba bikin SOP ini. Jadi kita kumpulin semua yang kontekstual, dan make sense untuk dilakukan dan akhirnya dengan paling penting mindset-nya, ini dibuat seakan-akan kita buat film action. Jadi kalau kita mau rela bikin SOP, kita mau rela ribet demi melindungi orang dari patah tulang, memar, geger otak, dan bahkan meninggal, harusnya kita punya kesadaran yang sam auntuk melindungi para aktor agar mereka enggak punya mental breakdown setelah bikin film ini.
Alhamdulillah, karena SOP ini juga ada aktor-aktor yang mau ikut peran serta dalam film ini. Kalau enggak sih, akhirnya kita kayak jadi apa ya… berangan-angan dengan skenarionya, tapi enggak ada yang mau kerjaan sulitnya, enggak ada yang mau terlibat.
Naskah sama sekali enggak diganggu gugat?
Enggak.
Walaupun udah ditolak Phillipine tadi?
Enggak. Kerjain aja. Hahaha
Pilihannya ada dua, ketika setelah Cinta Pertama, Kedua, Ketiga, apakah bikin yang sesimple Dua Garis Biru, atau challenge accepted (alias pilihan yang lebih susah)? Karena gue cuek aja anaknya, gue embrace failure (ketawa).
Selama pra-produksi, tantangan terbesarnya apa?
Untuk intimacy scene, kita bikin koreografinya sama dua staff actor, Bismo sama Anne Jasmine. Setelah itu, baru sama aktor, sama Sarah—sama Arawinda, sama Jerome (Devan). Yang rekam langsung udah Deska. Rekam, rekam, rekam. Kemudian diedit Mba Aline Jusria. Ketika sudah selesai diedit, present-lah ke co-produser dan eksekutif produser Wahana Kreator. Di situ perdebatan kencang. Ketika scene menuju hotel kedua Sarah dan Devan. Mereka bilang, kita enggak mau nyensor bagaimana adegannya, tapi adegan itu harus punya pondasi yang kuat. Makanya, dialog yang kemudian ditambahkan adalah adegan consent-nya Sarah. Dia bilang, “Aku enggak mau ngapa-ngapain”. Terus Devannya bilang, “Kamu kayak enggak tau aku aja.”
Nah, kalau ditanya dalam sebuah struktur skenario paling penting, nah di situ tuh di dua dialog itu yang penting. Agar adegan setelahnya tuh lebih masuk akal bagi banyak orang.
Awalnya gue enggak mau ada dialog itu, karena sebenernya perempuan bilang enggak mau, yaudah gapapa. Nah, di situlah untungnya punya co-produser yang kritis ya. Di situ ada Chida, dia orang legal, dan dia kerja di pemerintahan, dia staf di Istana. Kita tuh keluar dari bubble kita jadinya. Dia bilang, “Core pemahaman consent lo, Gin, itu beda dari pemahaman orang di luar sana. Bahkan yang kita bikin sekarang aja tuh masih belum diterima sama banyak orang di luar sana.”
Makanya tuh akhirnya dua dialog itu ada. Agar orang tuh lebih paham bahwa ada ketidaksepakatan di awal, lalu ditipulah si Sarah dalam hotel itu.
Selain kekerasan seksual yang eksplisit, grooming kan juga eksplisit di story ini. Kenapa mau masukin grooming ke cerita ini?
Ini menarik. Gue sama suami tuh umurnya jauh, jarak sembilan tahun. Terus anak-anak tuh, tuh SMP, SD suka becandain, “Are you being groomed, Mommy?” Mereka becandaannya memang suka dark. (Ketawa) Tapi itu jadi menarik, pertanyaan itu jadi merefleksikan kapan sih beda umur itu bisa jadi grooming?
Gue juga pernah dulu pacaran yang gap umurnya lebih jauh, age gap-nya lebih dari sembilan tahun. Jadi akhirnya jadi paham gitu, kapan jarak umur itu bisa jadi grooming, kapan tidak. Nah, self-reflection itu yang kemudian dituliskanlah dalam film ini. Dan ketika reading, kemudian diskusi, riset dan lain-lain, ternyata banyak sekali anak-anak yang ketika usia belasan, pacarnya tuh usia sepuluh tahun, belasan tahun lebih tua. Dan dianggap normal sama teman-teman si cowoknya. Dan akhirnya makin ngerasa perlu ditulis dan dibahaslah.
Hal itu jauh lebih familiar dan dianggap normal, padahal bisa jadi misbehave yang berbahaya. Terutama ke perempuan dan laki-laki yang jauh lebih muda dari pasangannya.
Statement apa yang ingin dikasih Like & Share tentang grooming?
Sebenernya statement-nya ingin bilang, cuma dengan menghargai eksplorasi para perempuan, kita bisa memberdayakan mereka dan membebaskan mereka seutuhnya. Jadi, ketika kita menghargai eksplorasi orang lain, maka kita paham tidak boleh mengeksploitasi.
Yang paling membantu gue jadi filmmaker itu adalah proses jadi orang tua dan pasangan yang lebih baik. Caranya gimana? Gue belajar, gue ke psikolog, baca buku, dan lain-lain. Kesadaran yang paling besar itu adalah anak kita enggak hidup dalam bubble.
Buat gue, filmmaking adalah usaha memendekkan jarak-jarak lebar tentang banyak pemahaman di Indonesia, syukur-syukur dunia. Jadi, ketika misalnya ada orang yang pemahaman sex education-nya lebih tinggi, tapi ada juga yang enggak diajarin sama sekali di rumah karena emang masih canggung, dengan film-film seperti ini bisa jadi lebih pendek tuh jaraknya.
Negara itu kan makin dibilang makmur ketika jarak-jarak gap informasi, ekonomi, dan kekuasaan, dan lainnya tuh makin pendek kan. Makin sejahtera karena jarak-jarak (kesenjangan) itu makin kecil. Usaha-usaha dalam filmmaking gini sih, dalam bercerita, yang diperlukan. Karena cerita itu menyatukan banyak orang.
Makanan dan ASMR jadi alat yang sangat kentara di film ini. What’s the reason behind it? Do you find something interesting in the process?
Kalau makanan itu tertarik karena setelah instagram naik, gue baca-baca itu ada istilah foodporn. Dulu kan enggak pernah kebayang foodporn. Tapi, menarik juga kalau kita belajar lagi soal makanan, gue belajar lagi soal apa yang kita makan. Misalnya, kayak gula. Dulu orang enggak kebayang kalau gula itu adalah penyebab kecanduan. Taunya lemak. Tapi, ternyata itu adalah penelitian yang diubahlah demi urusan-urusan gula.
Ternyata tuh gula menyebabkan kecanduan, menyebabkan obesitas, dan lain-lain. Banyak juga orang yang craving. Terus kalau ada masalah mereka akan makan, stress-eating dan banyak mengonsumsi gula. Kurang lebih komparasi itu tuh yang mirip dengan pornografi. Bahwa apa yang kita konsumsi dengan tidak sehat itu berbahaya buat tubuh. Seks gak masalah, makan gak masalah. Tapi, ketika konsumsi gula berlebihan, ketika kita belajar atau terlalu banyak mengonsumsi pornografi yang efeknya buruk ke dalam diri kita sendiri.
Dan menariknya lagi, ketika ngomongin makanan dalam konteks masyarakat Indonesia, orang Indonesia amat sangat menghargai makanan. Makanan kita itu beragam, kita amat sangat menghargai keragaman makanan kita, bahkan kita bisa membanggakannya. Kita juga bisa bilang, eh si A gak suka pedas, dia alergi cumi. Dan kita bisa menghargai keotentikan orang terhadap pilihan-pilihan makanannya. Tapi, ketika berhadapan dengan manusia lain yang terutama kaum-kaum marginal, kita tiba-tiba mendadak enggak bisa menghargai keotentikan mereka.
Kalau kita bisa menghargai makanan segitunya, kok kita gak bisa menghargai manusia dengan sama?
Baca juga: ‘Ngeri-ngeri Sedap’ dan Film Batak yang Berusaha Lepas dari Jakartasentris
Kalau ASMR?
Kalau ASMR, karena dari foodporn juga. Dari sekian banyak video soal ASMR, ada berbagai macam bentuknya. Ada yang cuma mulutnya doang, ada yang dibikin cantik, ada yang benar-benar dibikin seksi dan kotor. Itu sama seperti bagaimana pornografi ditampilkan, ada yang estetik. Estetiknya tuh kayak ini pornografi yang dibuat sama studio menghargai perempuan, ada pornografi yang bener-bener kayak fast food (makanan cepat saji), atau bahkan ada pornografi yang kayak kita makan makanan eksotis yang harusnya enggak dimakan, gitu. Kayak kelelawar atau makanan yang bisa berbahaya buat manusia.
ASMR sendiri punya dua efek buat manusia, ada yang nyaman, ada juga yang jijik setelah mendengarnya. Itu juga reaksi yang ingin gue tes ke penonton, bagaimana mereka bisa menghadapi ketidaknyamanan ini. Jadi, pilihan-pilihan kenapa sih begitu ASMR itu enggak cuma di makanan, tapi juga di adegan-adegan seksnya. Nah, biasanya di adegan seks di film tuh kan, kita jarang banget denger suara yang pok-pok-pok-nya, nah itu yang mau didengerin di sini.
Kalau emosi yang muncul adalah enggak nyaman, marah, dan gelisah, dan kesel, kenapa harusnya gak segitunya? Harusnya itu adalah perasaan yang sama, yang muncul waktu kita ngomongin isu kekerasan seksual. Dan itu harusnya rasa gak nyaman dan rasa marah yang harus dijaga, dan bisa diluapkan dengan bijaksana. Agar gak terjadi lagi kasus-kasus (serupa), dan kita gak jadi pelaku, dan gak bagiin video sembarangan.
Gue bersyukur setelah Dua Garis Biru, dikasih Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga yang dapet mixed review. Waktu itu, gue kayak, ah mau bikin film yang bosen banget, kayak bikin album foto. Dan ternyata itu juga yang dirasakan penontonnya. Buat yang masih muda, belum ada di situasi kayak gitu, mereka gak relate. Tapi, buat yang sedang dalam proses serupa—merawat orang tua yang makin tua—banyak juga yang relate.
Male gaze yang domain-mainin, diobrak-abrik sama lo adalah salah satu yang menurut gue menonjol banget di film ini. Gina S Noer sendiri ngeliat male gaze gimana? Apa male gaze buat lo?
Male gaze itu sesimpel gimana kita memandang dan menginterpretasikan sebuah cerita. Skenario itu siapapun yang nulis, pada akhirnya cuma blueprint yang bebas nilai (sebelum dilempar ke publik). Yang bisa membuatnya punya value dalam audio-visual adalah orang-orang yang menilainya, jadi ketika kita menilainya dengan sudut pandang laki-laki aja, atau perempuan aja, maka ya itu akan muncul di layar dan akan jadi norma buat penontonnya. Terlepas itu female or male gaze. Kalau dalam Like & Share, ya dengan sengaja mau main-mainin male gaze, itu juga kenapa DOP-nya laki-laki.
Sebenernya di Like & Share itu kita ngomongin soal dualisme. Kenapa (karakternya) Lisa dan Sarah, kenapa strukturnya Lisa kemudian Sarah, kemudian kenapa warna-warni tapi (ceritanya) dark, kenapa ada seks yang dosa banget, tapi juga ada Islam. Kemudian banyak sudut pandang perempuan, tapi di beberapa titik sengaja pakai male gaze, terutama ketika Sarahnya mulai mendekat ke Devan.
Terus ada video-video yang juga—menariknya video yang cut-to-cut tuh objektif banget sudut pandangnya tuh, itu emang sengaja banget dimainin. Tapi, yang paling menarik sebenernya, gue tuh sadar konsumsinya (konsumsi pornografi) tuh banyak sekali di laki-laki. Jadi butuh sekali, untuk tetap nyelipin male gaze di plot ini. Tapi ue tuh seneng, banyak yang dateng juga perempuan dan memang kecanduan. Ada yang bilang mau berhenti nonton porn. Jadi, (fokus mereka waktu nonton) bukan ke Devan, tapi ke Lisa.
Tapi, justru point of view Lisa tuh juga perlu ada sentuhan male gaze-nya. Jadi mereka gak ngerasa itu cuma perempuan aja, jadi mereka juga ngerasain ada dualism waktu nonton.
Sebagian besar akademisi feminist atau filmmaker feminist berargumen kalau male gaze itu sebenarnya adalah semua yang ada di film. Karena, industrinya sendiri dibangun dengan situasi dominan laki-laki dan patriarki. Jadi, kalaupun filmnya ditulis atau disutradarai perempuan, belum tentu male gaze itu hilang. What do you think about this? Gimana caranya bisa sampai punya kesadaran untuk main-mainin gaze?
Itu proses sih. Justru kita disadarkan tentang sudut pandang itu ketika syuting sih. Biasanya ketika, sama DOP–kebetulan DOP-nya cowok semua—ada beberapa shot yang mereka tuh bingung, kenapa (kameranya) ditaruhnya di situ. Misalnya, ada juga ada beberapa shot yang DOP-nya bilang, kenapa shot-nya gak ke arah pantat karakter perempuannya. Enggaklah enggak kayak gitu. Di situ tuh baru sadar, oh iya ya, there’s such thing like male gaze. Awalnya gak terlalu mikirin. Setelah momen-momen seperti itu jadi percaya diri, bahwa titik kamera gue tuh harus di sini, karena ini menyuarakan apa buat karakter dan dari sudut pandang siapa.
Jadi ketika ngomongin female gaze itu bukan cuma sekadar apa yang akan ditonton audiens. Karena pada dasarnya di dalam sebuah film mau ada male gaze atau female gaze, tapi ketika kita mengonsumsi film itu adalah tentang gimana kita me. Tapi buat perempuan filmmaker sendiri, terutama sutradara, itu akan ngaruh banget. Gimana voice mereka bisa keluar atau enggak ketika dalam ruang yang embracing suara dan sudut pandang-sudut pandang yang merayakan perempuan. Dan itu tuh ngaruh banget.
Misalnya, ketika gue jadi penulis skenario doang, dan ada di lingkungan yang enggak gitu peduli sama isu atau sudut pandang perempuan, bisa aja dijagain di skenario. Tapi, belum tentu hadir di filmnya. Atau bakal diediting, banyak juga cutting point yang berubah. Tergantung sama siapa yang punya suara relasi kuasa itu. Jadi sutradara itu, kurang lebih bisa menjaga suaranya.
Gua gak akan berani stick to the script kalau gak ada support system yang baik sih. Gue gak kebayang di ruang editing kalau gak sama Mba Aline. Dengerin orang terengah-engah di ruang editing. Kebayang gak sih lo? (Tertawa)
Gue tuh tumbuh dan terbentuk dari penulis skenario, yang ketika lo bilang A, semua orang langsung: eh belum tentu A lagi. Mari kita berpikir mana yang lebih baik. Dan harusnya menurut gue, accountability itu yang dimiliki semua orang. Jadi maksimal kerja kelompoknya.
Gue juga suka banget breaking the fourth wall di ujung film ini. Sempat nungguin, kira-kira kapan nih Lisa atau Sarah bakal beneran menerobos layar dan langsung menatap ke arah penonton. Teknik ini kan makin sering digunakan filmmaker feminis buat karakter-karakter perempuan mereka untuk mengkritisi male gaze. Pertanyaannya, kenapa breaking fourth the wall-nya ditaruh di belakang banget?
Ini disengaja banget. Skenario draf satu tuh lebih gila-gilaan. Ending-nya tuh, ketika mereka dipanggil ke sekolah terus pelukan, kemudian muncul beberapa montase di mana mereka ngerasa dihakimi, terus tiba-tiba di satu titik mereka berhenti, terus menatap ke kamera tapi sebentar… “Kenapa kita doang ya yang disalahin?”
Terus kamera mundur, terus jadi tempat syuting—
Tempat syuting?
Iya hahaha, namanya nulis draft satunya gila-gilaan. (Tertawa) Terus mereka duduk gitu, di sebuah meja panjang. Terus karakter-karakter yang lain diajak masuk ke dalam. Gitu. “Mereka juga dong yang harusnya diituin, kok cuma kita?”
Pak Parwez ngamuk. “Arthouse banget!” Dari Aris (Salman Aristo, suami Gina yang juga penulis naskah dan sutradara), diskusinya lebih ke yang lo lakuin ini gak ada argumennya di depan (pembuka naskah). Argumennya apa sampai ke breaking the fourth wall? Akhirnya bikin argumen lebih rapi lagi.
Kalau film-film yang lo suka belakangan apa aja, Mba?
Gue suka Portrait Lady On Fire, gue suka Bong Jun-Ho, gue suka aduh banyak banget. Yang stay dalam pikiran gue dan suka banget tonton ulang tuh Children of Men (Alfonso Cuaron).
Sama banget—
Yaay kita sama.
Yang lo suka apanya?
Gue suka di antara bleak itu ada harapan. Gue kayak I’m sucker for hope (ketawa). Sama craftmanship-nya gila banget sih. Fleabag juga gue suka.
Isu ini berat, pertanggungjawabannya besar. Risikonya juga. Sebagai filmmaker yang statement-nya jelas anti-kekerasan seksual, lo dan karya lo akan dipantau lebih kritis. Setelah nonton filmnya, gue ngerasa lo emang taking this issue seriously. Kenapa mau kerja keras segitunya? Kan bisa aja bikin film yang lebih ringan, lebih less-risk?
Gue tuh takut kalau bikin film gini tuh cuma echo chamber, cuma sesama perempuan doang yang nonton. Ngapain. Kayak nyiramin hutan yang udah subur. Perlu. Tapi, effort-nya apakah harus segini banyak? Gak kan, ini membuka diskusi ke orang-orang yang bahkan gak pernah kepapar isu ini atau gak peduli. Film ini sengaja dibikin untuk membuat diskusi sih.
Mungkin penontonnya 46ribu lah. Film ini flop. Gua harus merayakan dengan film ini flop. But it’s gonna be cult. Gue percaya itu sih.
Akan ada di streaming?
Harus ada di streaming, dan kalau bisa dengan modul-modul yang bisa mendampingi. Buat penonton di Indonesia nih, harus jadi challenge juga akan gimana bisa ketemu sama penontonnya.
Salah satu yang gue perhatikan, dan menurut gue menarik adalah, gimana Like & Share sempat tur duluan sebelum tanggal rilisnya. Kerja sama dengan LBH Apik juga, kan.
Iya, mereka adalah pendamping hukum kita juga. Ada satu titik, LBH Apik bahkan, yang “Kalo lo nge-ditch gitu aja kasus Arawinda, kita tinggalin.”
Kalau ada yang bilang gue hipokrit dan macem-macem, no no no, I walk my talk. Justru dalam kasus ini. Itu gue lagi belajar banget, kalo lo serius sama isu ini, lo harus berani dengan konsekuensi ini.
Kalau ada yang bilang, nyari duit pakai isu perempuan gampang, enggak lah. Di mana dulu? Di tempat yang sangat patriarkis dan hal gini tuh masih diantagonisasi banget, jelas masih susah ya, menurut gue. Ngomongin aja, masih sering disalahartikan. Menurut gue, itu ada hubungannya sama akses tadi.
Tahun ini gue diuji banget sih, gue kehilangan bokap, gue kehilangan ibaratnya gue menjaga image ini, split second ilang aja. Film yang lo bikin sepenuh hati, flop.
It must been hard. I’m sorry, Mba. I can only imagine, it must been hard. Gimana lo taking care of yourself?
Gue tuh di awal-awal bikin, sebelum bikin film, gue intens banget ke psikolog. Skrip belum jadi. Sampai akhirnya ke titik gue harus bikin filmnya. Gue nanya ke psikolog gue, gimana cara bikin supaya gak bikin yang nonton triggering. Jadi tuh banyak banget orang yang dalam produksinya sendiri korban. Yang baca skenarionya tuh gemetaran, yang pas syuting gemeteran. Psikolog gue tuh bilang, lo tuh harus lihat cerita tuh apa? Atau trauma dalam hidup tuh dilihat dari dua hal: do you own your story or your story owns you?
Jadi seperti gue bilang tadi, kita bisa memaknainya, kita bisa menceritakannya dalam kontrol kita. Tapi, kalau the story owns you, ketika kita bercerita, melakukan sesuatu dalam hidup kita, itu tuh (trauma) menjadi bagian identitas kita. Semua hidup kita, itu dikendalikan sama trauma kita. Itu yang belum boleh. Dia nanya, lo yang mana? Setelah gue pikir-pikir, gue own the story.
Tapi kalau setelah kasusnya itu, berbulan-bulan ini tough banget ke gue. Mungkin support system ya. Bukan cuma ke gue ya, tapi juga ke partner produser gue. Tangis-tangisan bareng deh. Berasanya tuh kayak dizalimi juga tuh. Industri banyak yang diam, bahkan kayak sekadar statement dukungan aja enggak. Gue kagum juga sama semua sinefil-sinefil itu, dan filmmaker-filmmaker lain yang masih tetap support film ini.
Di tengah semua orang mau cancel, dibilang buzzer, masih ada yang mau tetap ngobrolin filmnya.
Cancel culture dan mock mentality ini menurut gue dunia baru, yang ditanggapi pake PR thingy dengan cara konvensional. Jadi enggak nyambung. Enggak nyambung cara berkomunikasinya.
Yang paling gue gelisah sebenernya, Dam. Dunia macam apa sebenernya ini? Tentang film flop satu hal, tentnag industri satu hal. Tapi, dunia macam apa sebenernya ini? Gue itu masih bisa bikin film isu, sebagai usaha gue memendekkan jarak-jarak kesenjangan itu tadi, tapi di dunia yang cancel culture. Dan apa ya, efeknya negatif banget. Dan post-truth, di mana seniman dan jurnalis ada di dunia seperti ini? Itu juga jadi pertanyaan gue. Apa yang bisa dilakukan? Cuma ini ngeri sih menurut gue.
Trauma juga menurut gue jadi tema besar di film ini. Semua karakter lo punya trauma, dan trauma itu bikin mereka jadi relatable dan masuk akal. Kayak, kita enggak bisa beneran marah sama Ibu Lisa, karena banyak dari kita yang punya ibu kayak dia juga. Gimana cara lo menulis ini? Cara lo menuliskan trauma.
Gue tuh gak percaya, kalau seniman: baik aktor, sutradara, penulis itu menggunakan traumanya dia sebagai alat berkarya dia. Itu juga dalam konteks trauma, ketika nge-direct pemain ketika masa reading maupun akting, (gue bilang ke mereka) gak boleh menggunakan traumanya sedikit pun. Mereka boleh menggunakan traumanya di masa lalu untuk melihat karakternya, tapi gue gak mau nyuruh mereka, misalnya, oke bayangkan lo di situasi ini—karena itu namanya mengeksploitasi. Kita kan konsepnya memberdayakan, bukan mengeksploitasi. Makanya, dalam reading-nya itu ada kurikulum. Jadi ada kurikulum menggunakan fisik, jadi mereka menggunakan dialog naik ke atas meja, jongkok, baring, dan segala macem. Jadi tubuh mereka ingat. Jadi method-nya bukan method acting yang mendalami. Sengaja menghindari proses eksploitasi trauma itu.
Gue juga gitu waktu nulis. (Saat nulis) Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga, gua belum memahami konsep orang tua menua, dan gua belum mendewasa. Gue belum selesai dengan rasa bersalah gue, gue belum bisa merawat maksimal orang tua gue, dan gue mengerjakannya, Dam. It is personal, tapi apakah sudah ada wisdom dalam proses mengerjakan itu? Belum.
Itu keliatan banget, ketika gue di situasi krisis, tekanan, Covid, dan lain-lain, gue masih bingung meletakkan kamera gue di mana. Sebagai pencerita, gue belum ajeg. Ketika di Like & Share, gue lebih ajeg. Gue udah berproses dengan trauma itu, udah belajar parenting (lebih dalam), udah punya harapan, udah tahu gimana mau membesarkan anak-anak gue. Kemudian membuat ini (Like & Share).
Makanya waktu nulis, gue gak mulai dari premis dulu. Tapi, dari argumen Aristoteles, jadi gue baca buku—tau kan lo, di Gramedia ada buku Aristoteles tentang logika. Jadi gue baca tentang itu, untuk membuat struktur skenario. Emang main eksperimen sih.
Semua orang sebelum syuting ditanya dulu. Traumanya apa, bersedia gabungkah, terus punya carakah untuk menghadapi trauma ketika dia muncul. Nanti sesuai obrolan itu, kita bikin batasan-batasan kerjanya. Misalnya, ada yang mau join, tapi bilang nanti pas adegan intim, gak bisa lihat ke layar. Ada adjustment yang kita lakukan sesuai kebutuhan semua orang, masing-masing.
Balik lagi ke niat giving back ke industri, mikirin kebutuhan kita yang mengerjakannya. Balik lagi, karena gue percaya sistem. Jadi berpikirnya ada saintifiknya, ada keilmuannya. Jadi bikinnya lebih komprehensif.
Jadi pas bikin film bukan ngomongin oke, kita bikin apa, nanti penontonnya berapa, dapat award apa, menurut gue itu tuh akhirnya jangka pendek. Jadi, kita tuh kerja buat masa depan. Mungkin kita, by the time gue meninggal, soal kekerasan seksual enggak langsung hilang. Tapi paling enggak, gap knowledge-nya beberapa orang enggak nol. Mungkin di lima (orang) lah. Tapi, dari lima ini kita enggak tahu siapa yang bikin perubahan dua puluh tahun ke depan. Itu sih yang enggak bikin capek.
Sebenarnya soal sensor, gue tuh pengen tahu sebenarnya sensor (Lembaga Sensor Film) kita tuh bisa men-tackle cerita sampai sejauh mana sih. Kita enggak pernah dikasi tahu kan batasan sebenarnya itu kayak apa? Ini adalah film yang jadinya bikin kita tahu, kalau kita bisa ngebahas suku, agama, ras, dan seksual sejauh gini. Nah ini kan jadi standar baru. Kita bisa bercerita sebebas ini. Jadi lebih clear, nanti yang 13 sejauh mana. Jadi gue tuh pengen banget tahu standar itu. Jadi film ini tuh eksperimen banget sih, eksperimen di labour-nya, censorship-nya, ceritanya, bagaimana pendekatan terhadap audiensnya.
Gina S Noer juga dikenal dengan dialog-dialog jitu di film-filmnya. Dan itu jadi salah satu faktor terkuat di film ini. Ada treatment khusus?
Dialog tuh verbal action. Misalnya, kita ngeliat adegan, di dalam adegan itu ada dua aksi untuk karakter bisa mendapatkan tujuannya. Action yang told by the pictures, aksi mereka. Sama dialognya. Jadi dialog apa pun yang harus keluar itu harus bisa memajukan konflik. Nanti di dalamnya ada pemilihan kata, itu craftmanship sih. Kenapa rasanya enak? Karena make sense sama konfliknya. Kalau misalnya spesifik di film ini, gue tuh membayangkan dialognya tuh kayak lirik gitu. Jadi kayak pemilihan kata, suku kata yang berulang tuh memang sengaja diulang. Jadi punya subteks yang lain lagi gitu.
Misalnya, kayak adegan Lisa dan Sarah di kolam renang, “Nanti kita di sana melihara anjing ya.” “Wah susah sih kalau melihara anjing, ribet tau…” terus bla bla bla bla, terus ada “Anjing!”. Nah, kata anjing itu memang sengaja secara struktur. Ada anjing yang enggak ada masalah, sama anjing yang “Anjing!” gitu. Pengulangan kata yang gitu banyak, untuk menebalkan konteks situasi mereka sebagai karakter. Gue lebih rajin soal dialog di sini, daripada film lain. Gue tuh perlu banget dialog yang convincing, baut penonton.
Baca juga: Prof Azyumardi Azra, Intelektual Islam Jadi ‘Sir’ Pertama dari Indonesia
Kepedulian lo tentang labour dan psikologi ada kaitannya dengan identitas lo sebagai perempuan?
Pasti. Pasti. Kita sebagai individu itu kan pasti enggak bisa terlepas dari peran-peran lainnya. Misalnya, lo sebagai jurnalis pasti enggak bisa terlepas dari peran lainnya kayak anak, pacar, saudara, sahabat, gitu. Ya, mau enggak mau memengaruhi sih. Jadi gimana misalnya, gue percaya sistem karena gue nikah sama orang yang percaya sistem. Jadi kayak, siapa yang berada di sekitar kita akan membantu membuat kebijakan-kebijakan itu. Gue amat sadari ya, di film itu itu—membuat film bagus di Indonesia tuh privilese. Enggak semua orang punya resources, bukan masalah resource dana aja ya. Mereka dikelilingi orang-orang yang kayak mana ketika proses pembuatan juga. Jadi, ketika ada sutradara yang bikin film bagus terus, lo gak bisa lihat dia sebagai satu orang aja. Lo harus lihat, dia itu siapa sih, backgroundnya, misalnya dia punya leverage, entah koneksi, atau secara ekonomi bikin dia punya pilihan. Jadi membantu dia enggak harus terus dalam situasi day-to-day bikin film, jadi enggak sempat mikirin estetika aja, sama siapa aja. Itu tuh perlu dilihat sungguh-sungguh.
Makanya, karena gue pernah merasakan dalam lingkungan yang enggak privilese, dalam artian lo udah kerja mati-matian bikin skenario, tapi hasilnya enggak sesuai keinginan lo, ketika gue bikin film sebagai sutradara atau produser yang punya kuasa lebih dalam produksinya, gue tuh berusaha bikin sistem yang gue bayangin nanti bisa buat siapapun–mahasiswa, atau siapapun–yang masuk (ke industri) dan mau bikin film enggak perlu ngerasain enggak privilese itu. Karena gue tahu banget rasanya bikin mati-matian sebuah skenario, kemudian jadinya gitu doang. Dan orang gampang banget nyalahin skenarionya.
Ya idealnya, impiannya, ketika orang-orang masuk ke dunia bikin film, standar-standarnya itu udah makin sama. Mereka punya sistem perlindungan diri seperti pekerja yang baik, sehingga mereka bisa puas mengeksplorasi diri. Kekecewaannya tuh enggak perlu mulai dari nol kayak dulu.
Tapi, itu dilihat sama industri gak?
Lumayan sih. Sekarang Aprofi (Asosiasi Produser Film Indonesia) udah punya kode etik produser, di dalamnya ada SOP intimacy scene, anti-kekerasan seksual, dan lain-lain. BPI (Badan Perfilman Indonesia) sekarang udah punya Dewan Etik untuk kasus kekerasan seksual, mereka juga nanti bikin kode etik. Kemudian, partneran juga sama orang yang lebih concern lagi untuk nanti di mahasiswa (film) gimana.