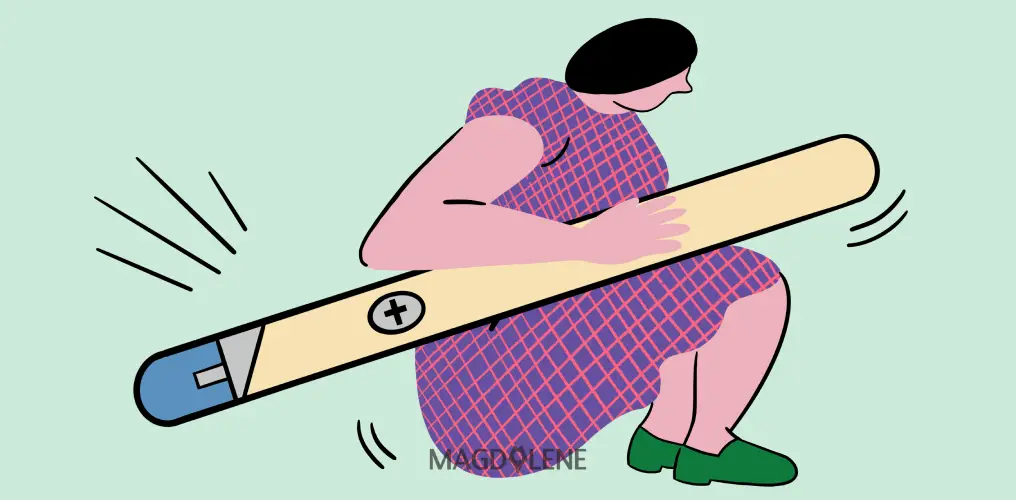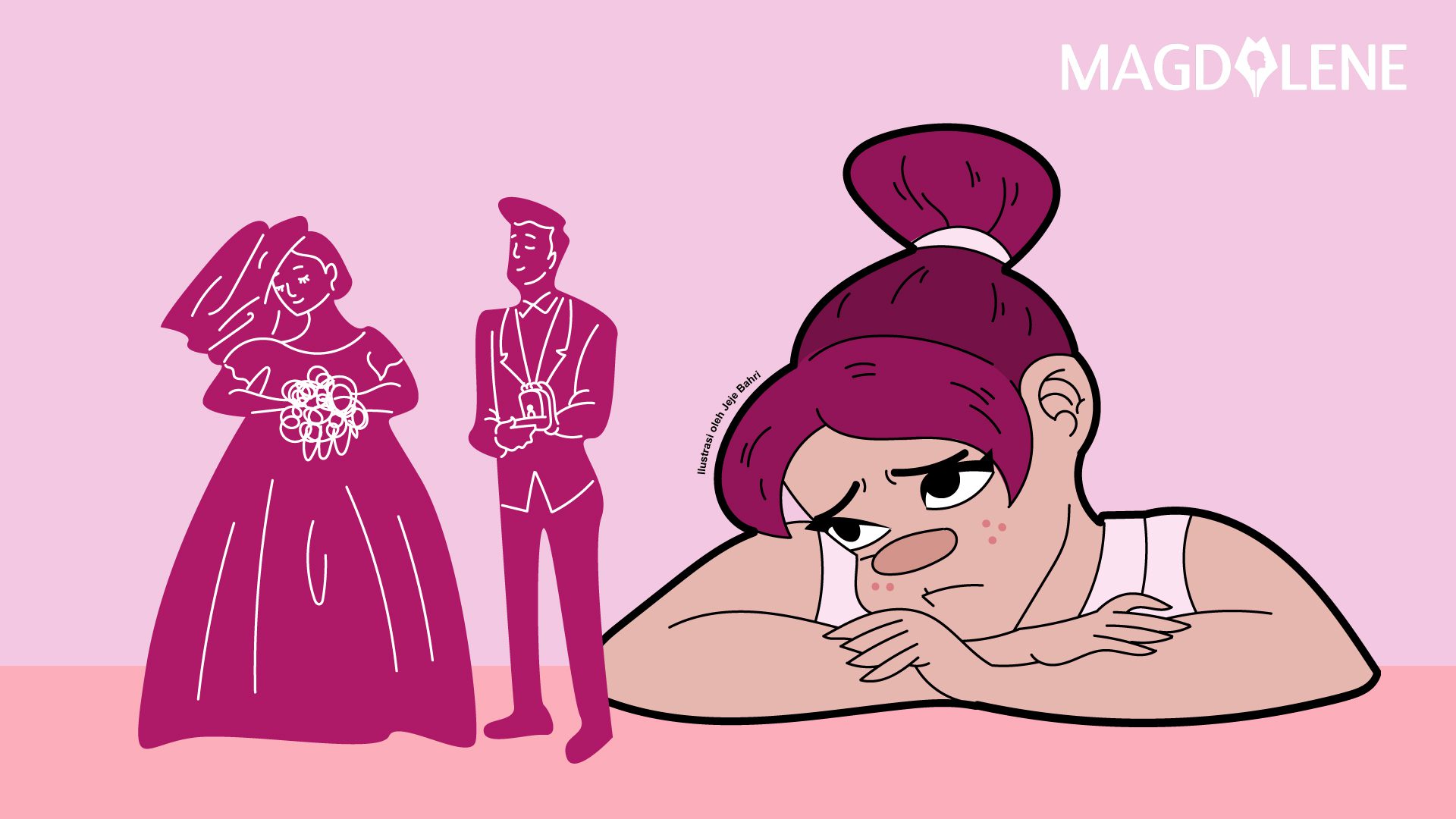#HariKartini2025: Tubuh Perempuan dan Hak yang Tak Pernah Diajarkan

*Peringatan pemicu: Gambaran kekerasan seksual.
Dulu, saya selalu bilang pada anak perempuan saya: “Cuma dokter yang boleh menyentuh bagian tubuh di balik bajumu untuk alasan medis, Nak.” Terdengar logis tapi seiring maraknya kekerasan oleh tenaga kesehatan, saya jadi merasa ngeri. Masalahnya enggak tanggung-tanggung, dalam kurun Maret-April 2025 saja, sudah ada empat laporan kasus kekerasan yang melibatkan nakes di Malang, Bandung, Garut, hingga Jakarta.
Laporan Tempo mencatat, Dokter Anestesi Priguna Anugrah kedapatan memerkosa sejumlah perempuan di RS Hasan Sadikin, Bandung. Ia membius dan memerkosa penyintas dalam kondisi tak sadar. Di Garut, Dokter Spesialis Kandungan Syafril Firdaus melakukan pelecehan di kos dan klinik tempat ia praktik. Di Jakarta, Muhammad Azwindar Eka Satria merekam seorang mahasiswi yang tengah mandi.
Dari kasus-kasus tersebut, saya belajar jas putih tak selalu berarti etika. Ruang medis, yang mestinya steril dan aman, justru jadi tempat tubuh perempuan kehilangan rasa amannya.
Baca juga: #TadabburRamadan: Kartini Ternyata Jauh Lebih ‘Islami’ dari yang Kita Duga
Hari Kartini dari KELAPA MUDA
Rentetan kasus ini menjadi titik balik bagi kami. Di Sumatera Utara, perempuan akar rumput dalam Kelas Belajar Perempuan Mandiri Berbudaya—KELAPA MUDA, menjadikan isu ini tema utama peringatan Hari Kartini tahun ini.
Kami mulai membongkar tabu: Bicara soal tubuh, hak, dan rasa tidak nyaman di meja periksa. Karena ruang medis seharusnya menyembuhkan, bukan melanggengkan kekerasan. Kami tak ingin hanya bersuara saat ada kasus besar. Kami ingin menumbuhkan keberanian yang bertahan—untuk bertanya, menolak, dan berkata: “Saya tidak nyaman,” tanpa takut tak dilayani.
Cerita-cerita dari Perempuan Akar Rumput
Di satu desa, seorang ibu muda bercerita tentang pemeriksaan kehamilan yang membuatnya merasa dipermalukan. “Saya disuruh buka celana, diperiksa, tapi tidak dijelaskan apa-apa,” katanya pelan. “Saya malu tapi takut bertanya. Nanti dibilang bodoh.”
Di tempat lain, perempuan dari pesisir, penerima bantuan Program Keluarga Harapan bilang, ia trauma kalau harus melahirkan di rumah sakit swasta di kotanya. “Omongan dari bidan menyakitkan. Katanya, ‘Dulu waktu bikin anak diam-diam aja, pas mau melahirkan menjerit-jerit.’” Sakit hati mendengarnya.
Mereka tidak tahu istilah kekerasan di ruang medis. Pun tak tahu mereka berhak bertanya atau menolak. Namun mereka tahu rasanya disentuh tanpa izin. Mereka tahu rasanya dilihat tanpa rasa hormat. Mereka tahu rasanya takut di ruang yang seharusnya menyembuhkan.
Di satu desa, seorang ibu muda bercerita tentang pemeriksaan kehamilan yang membuatnya merasa dipermalukan. “Saya disuruh buka celana, diperiksa, tapi tidak dijelaskan apa-apa,” katanya pelan. “Saya malu tapi takut bertanya. Nanti dibilang bodoh.”
Baca juga: Panggil Kartini Manusia Biasa Saja
Kekuasaan yang Diam-diam Bekerja
Kekerasan seksual di ruang medis bukan hanya soal pemerkosaan oleh oknum yang masuk berita. Ia juga hadir dalam bentuk halus: Prosedur tanpa penjelasan, komentar tak relevan, sentuhan tanpa izin. Namun, semua itu bisa terus terjadi karena kita diajarkan untuk percaya pada jas putih dan diam.
Inilah bentuk kekuasaan pengetahuan—ketika hanya tenaga medis yang dianggap tahu tentang tubuh perempuan, sementara perempuan sendiri tidak diberi ruang untuk memahami, apalagi mempertanyakan. Perempuan jadi merasa tidak pantas bertanya, merasa salah kalau menolak. Seperti kata Sandra Bartky, tubuh perempuan bukan hanya dikendalikan secara fisik, tapi juga secara simbolik—dibuat merasa asing terhadap tubuhnya sendiri.
Saya sering mendampingi perempuan ke rumah sakit. Di sana, mereka tak hanya berhadapan dengan dokter yang irit bicara, tapi juga dengan jurang kelas, bahasa, dan pendidikan yang membuat posisi mereka jauh lebih rendah. Bahkan untuk bertanya, “Itu obat apa ya, Dok?” bisa dianggap menyulitkan.
Saya pun sering harus menyisipkan kalimat hati-hati saat meminta penjelasan. “Hasil pemeriksaan dan obat ini, boleh ya saya tahu, karena itu hak pasien juga, kan Dok?” Dan reaksi yang muncul sering bukan jawaban, tapi pertanyaan balik ke keluarga pasien, “Itu siapa?”
Perempuan dari kalangan akar rumput, tidak berani melakukan itu. Mereka takut tidak dilayani, takut dibilang banyak cakap, takut dicoret dari daftar BPJS. Dan ketakutan ini membuat kekerasan menjadi halus, terus-menerus, dan tak terdokumentasi.
Baca juga: Kartini Was Not a Feminist, But Maybe She Was The Heroine We Needed
Hak yang Tak Pernah Diajarkan
Perempuan punya hak atas tubuhnya—bahkan ketika sakit, lemah, atau tak berdaya di depan dokter. Saya belajar dari pengalaman saya, dan dari suara-suara perempuan miskin yang tak punya BPJS, dari lorong-lorong rumah bersalin tanpa tirai. Mereka bukan aktivis, tapi mereka tahu bagaimana sebuah ruangan yang terang bisa begitu dingin, menyimpan bayangan ketakutan.
Banyak perempuan akar rumput tak tahu bahwa mereka bisa menolak. Dan itu bukan salah mereka. Itu hasil dari sistem yang mengajarkan diam, patuh, bersyukur—bahkan saat merasa ada yang salah. Di sinilah kita melihat bagaimana patriarki bekerja tidak hanya lewat kekerasan fisik, tapi lewat pengetahuan yang disembunyikan. Pengetahuan tentang tubuh, tentang hak, dan tentang keberanian itu sendiri. Seperti dikatakan Bell Hooks, “Pengetahuan adalah alat pembebasan. Tapi sistem patriarkal menjadikannya milik segelintir orang saja.”
Menghadapi ancaman kekerasan di ruang medis yang semakin tak masuk akal, kita tidak bisa diam atau hanya berharap pada sistem yang lambat berubah. Kami mulai dari tempat yang paling sering diabaikan: komunitas perempuan akar rumput. Dalam forum diskusi di KELAPA MUDA, kami bicara soal tubuh. Mulai dari hak, persetujuan medis, ruang periksa yang aman, hingga trauma saat hamil dan melahirkan. Kami mulai dari yang paling dasar: bertanya.
Tak perlu lulusan sekolah tinggi untuk bertanya, “Itu obat apa ya, Dok?” atau “Boleh saya tahu prosedurnya?” Bertanya bukan kurang ajar—itu bentuk kesadaran atas hak. Kali ini, kami ajarkan anak-anak perempuan, bahwa: tak seorang pun boleh menyentuh tubuh mereka tanpa izin—bahkan dokter di ruang medis.
Kami juga ingin mendesak rumah sakit dan puskesmas memiliki standar etik berbasis gender: privasi harus dijaga, bahasa harus menghormati, dan setiap prosedur harus dijelaskan—ini akan menjadi agenda advokasi selanjutnya. Privasi bukan kemewahan. Hormat bukan pilihan. Itu seharusnya kewajiban.
Membuat Terang dari Akar
“Habis gelap terbitlah terang. Tapi terang itu tidak jatuh dari langit. Kita sendiri yang harus mengusahakannya.”
— R.A. Kartini
Karena Kartini hari ini, bukan hanya yang menulis, tapi juga yang berani berkata:
“Prosedur pemeriksaannya kayak apa? Saya tidak nyaman, saya butuh teman.”
Selamat Hari Kartini!
Laili Zailani adalah ibu rumah tangga, pendiri HAPSARI—organisasi perempuan akar rumput di Sumatera Utara. Fellow Ashoka Internasional (Indonesia, 2000), dan masih aktif mendampingi komunitas hingga hari ini.
Ilustrasi oleh Karina Tungari