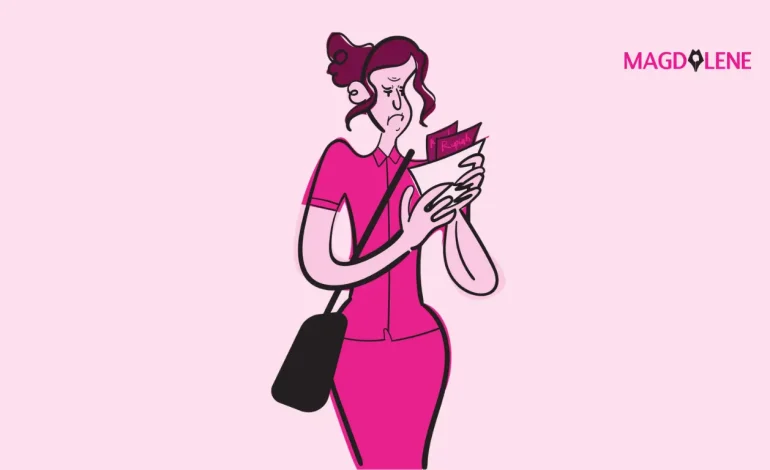#MerdekainThisEconomy: Korupsi itu Patriarkal, Pancasila itu Emansipatoris

Kadang saya merasa negeri ini tak pernah sungguh ingin sembuh dari korupsi. Seperti orang yang tahu penyakitnya parah, tapi memilih menutup mata. Bedanya, yang menanggung sakit bukan penguasa, melainkan rakyat miskin, perempuan di desa, dan anak-anak yang mimpinya terhenti di tengah jalan.
Ini bukan tuduhan tanpa dasar. Waktu masih menjadi anggota DPR, saya menggagas pendirian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)—unit yang seharusnya jadi garda depan untuk menindaklanjuti laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelumnya, temuan-temuan BPK sering kali hanya berhenti di tumpukan kertas. Tak menjadi agenda rapat komisi, apalagi sampai menindak pejabat yang bersalah.
Baca juga: Benarkah Feminisme Pancasila Jawaban untuk Perempuan Indonesia?
Selama periode 2009–2014, BAKN yang saya inisiasi merekomendasikan tiga belas kasus untuk dibawa ke sebelas komisi DPR. Lebih dari delapan kasus akhirnya dibawa ke ranah hukum, dan beberapa di antaranya berujung vonis pengadilan. Ada anggota DPR yang terseret hingga ke penjara. Saat itu saya percaya, inilah bukti politik masih bisa bekerja untuk rakyat, dan sistem masih bisa diperbaiki.
Kemudian, datang aturan baru yang mematikan langkah BAKN. Pimpinan DPR memutuskan, hasil kajian BAKN tidak boleh langsung dikirim ke komisi. Harus lewat persetujuan mereka terlebih dahulu. Seperti yang bisa ditebak, banyak rekomendasi akhirnya berhenti di meja pimpinan. Tak ada tindak lanjut. Tak ada sidang. Tak ada keadilan.
Di titik itu, saya menyadari: Melawan korupsi di negeri ini bukan hanya melawan orang-orang yang mencuri uang negara. Kita juga harus melawan sistem yang sengaja dibuat berlapis-lapis, sehingga kebenaran sulit menembusnya.
Yang lebih menyakitkan, sistem itu sering kali dibungkus dengan wajah ramah demokrasi. Padahal di dalamnya penuh intrik untuk melindungi mereka yang berkuasa. Celakangnya, sering kali, perempuan—terutama perempuan muda—jadi korban paling awal dan akhir dari sistem yang rusak ini.
Saya sendiri dibesarkan untuk jadi perempuan tangguh, cerdas, dan peduli. Namun di jagat politik kita, ketangguhan sering kali dihadapkan pada tembok yang dingin dan tebal. Ruang untuk melawan korupsi begitu sempit, dan negara terasa semakin jauh dari rakyatnya. Bukan karena kita kurang tekad atau kemampuan, tetapi karena bahkan upaya melawan korupsi pun ikut dikorup.
Data mendukung kegelisahan saya ini. Berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) 2024, Indonesia meraih skor 37 dan berada di peringkat 99 dunia, jauh di bawah rata-rata global yang berada di angka 43. Memang kita enggak termasuk dalam daftar negara “terkorup” secara absolut, tetapi juga tidak menunjukkan kemajuan berarti.
Pada 2020 justru menjadi titik terbaik kita, dengan skor 40 dan peringkat 85. Artinya, dalam lima tahun terakhir, tren kita memburuk. Di kawasan ASEAN, Indonesia hanya berada di posisi kelima setelah Singapura (84), Malaysia (50), Timor Leste (44), dan Vietnam (40).
Di usia 80 tahun kemerdekaan, kita patut bertanya: Kemerdekaan macam apa yang kita wariskan kepada generasi sekarang, termasuk perempuan muda. Terutama jika bangsa ini terus dikuasai budaya korupsi yang mengakar, bertolak belakang dengan Pancasila yang seharusnya emansipatoris, dan berwajah patriarkal?
Baca juga: Sejarah Perempuan yang Terlupakan: Seruan Feminisme Pancasila untuk Keadilan
Korupsi dan Patriarki
Struktur kekuasaan di negeri ini masih timpang. Ia terkonsentrasi di tangan segelintir elite yang mayoritas laki-laki—serta sebagian perempuan yang ikut memelihara nilai-nilai patriarki demi mempertahankan posisi.
Kekuasaan ini bukan hanya soal jabatan, tapi juga jaringan kolusi yang terjalin rapi dan penuh perhitungan. Mereka membentuk lingkaran eksklusif yang nyaris kedap terhadap kontrol publik. Dalam ruang-ruang tertutup itu, keputusan besar diambil, bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan demi melanggengkan status quo yang menguntungkan mereka.
Tak heran jika daftar pelaku korupsi di negeri ini nyaris menjadi cerminan langsung dari wajah politik patriarki: Dominan laki-laki, menduduki jabatan tinggi, memiliki akses pada sumber daya besar, serta bergerak dalam jejaring politik dan bisnis yang sangat maskulin.
Saya sendiri dibesarkan untuk jadi perempuan tangguh, cerdas, dan peduli. Namun di jagat politik kita, ketangguhan sering kali dihadapkan pada tembok yang dingin dan tebal. Ruang untuk melawan korupsi begitu sempit, dan negara terasa semakin jauh dari rakyatnya. Bukan karena kita kurang tekad atau kemampuan, tetapi karena bahkan upaya melawan korupsi pun ikut dikorup.
Mereka terbiasa dengan meritokrasi palsu. Maksudnya mengangkat orang bukan karena prestasi atau integritas, melainkan loyalitas dan hubungan pribadi. Dalam ekosistem seperti ini, transparansi dipandang sebagai ancaman, kritik dianggap pembangkangan, dan suara-suara yang berbeda—terutama dari perempuan—cenderung dibungkam atau diabaikan.
Dampaknya serius, ia membentuk kenyataan sehari-hari yang membebani kehidupan masyarakat, terutama perempuan di lapisan paling rentan. Ketika dana publik diselewengkan, layanan kesehatan ibu dan anak menjadi korban pertama. Ketika anggaran pembangunan dikorupsi, akses air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar yang menopang kehidupan sehari-hari ikut lenyap. Di banyak desa, perempuan harus berjalan lebih jauh hanya untuk mendapatkan air layak pakai, atau mengorbankan waktu bekerja demi mengurus keluarga yang sakit akibat sanitasi buruk.
Korupsi juga memutus jalur mobilitas sosial. Beasiswa yang dikorupsi atau program pendidikan yang dibatalkan, menghilangkan peluang perempuan muda dari keluarga sederhana untuk melanjutkan sekolah atau kuliah. Dalam jangka panjang, ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus: Anak perempuan kehilangan pendidikan yang layak, peluang kerja terbatas, dan mereka tetap terjebak dalam sistem sosial yang tidak memberi ruang untuk berkembang.
Yang sering luput dari pembicaraan adalah bagaimana korupsi ini juga berdampak pada rasa percaya diri dan aspirasi perempuan. Ketika mereka melihat politik dan kekuasaan dikuasai oleh kelompok kecil yang kebal hukum, pesan yang tersirat adalah perubahan itu mustahil, partisipasi itu percuma. Inilah bentuk kekerasan struktural yang paling senyap, tapi paling menghancurkan karena membunuh harapan sebelum ia sempat tumbuh.
Baca juga: #HariAnak2025: Anakmu Kecanduan Gim Anomali? ‘Parenting’ Digital Berbasis Pancasila Bisa Jadi Kunci
Pancasila sebagai Ideologi Emansipatoris
Bung Karno menyebut Pancasila sebagai leitstar—bintang penuntun menuju masyarakat adil dan makmur. Nilai-nilainya menolak ketimpangan, menuntut partisipasi setara, dan menegaskan korupsi adalah pengkhianatan terhadap moral bangsa.
Pancasila bukan slogan kosong; ia adalah panduan hidup, keberpihakan kepada rakyat kecil, dan keberanian melawan kekuasaan yang menyimpang.
Sila keadilan sosial menuntut penghapusan segala bentuk penindasan, termasuk ketidakadilan ekonomi akibat korupsi.
Sila demokrasi mengharuskan keterlibatan setara dalam pengambilan keputusan.
Sila kemanusiaan menolak kekerasan struktural yang membuat rakyat miskin tetap miskin.
Sila Ketuhanan mengingatkan korupsi adalah pengingkaran terhadap moralitas bangsa.
Itu sebabnya, bicara tentang Indonesia Merdeka tidak bisa dilepaskan dari perlawanan terhadap sistem yang melanggengkan korupsi. Korupsi bukan sekadar soal anggaran atau pasal hukum; ia adalah pencurian mimpi, pembunuhan harapan, dan perampasan masa depan. Ia menumbuhkan ketidakadilan, memperdalam kemiskinan, menghancurkan rasa percaya rakyat pada negara, dan seperti banyak struktur kekuasaan yang timpang, wajahnya jelas: Patriarki.
Perempuan muda, bersama laki-laki yang berpihak pada keadilan tidak boleh lagi diam. Kita memiliki ruang digital, komunitas, kelas, hingga parlemen untuk menegaskan budaya permisif terhadap korupsi harus diakhiri.
Politik yang benar-benar ber-Pancasila tidak memberi tempat pada budaya bungkam, impunitas, atau kekuasaan yang hanya melayani segelintir orang. Sebaliknya, ia memberi ruang pada suara rakyat, berpihak pada yang rentan, dan berani menolak korupsi sampai ke akarnya.
Kita sadar, sistem antikorupsi kita hari ini masih maskulin, legalistik, dan minim perspektif keadilan sosial. Karena itu, kita memerlukan gerakan kolektif yang mengedepankan integritas, kesetaraan, dan keberanian—nilai-nilai yang sejatinya dijunjung tinggi Pancasila dan diperjuangkan banyak perempuan muda hari ini.
Di ulang tahun ke-80 Republik ini, pertanyaannya sederhana: Kemerdekaan macam apa yang ingin kita wariskan? Apakah kita akan terus membiarkan negeri ini dikuasai budaya korup berwajah patriarki? Atau kita memilih untuk memimpin, membersihkan, dan memulihkan Indonesia?
Dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI 2025, Magdalene meluncurkan series artikel #MerdekainThisEconomy dari berbagai POV penulis WNI. Baca artikel lain di sini.
Ilustrasi oleh Karina Tungari