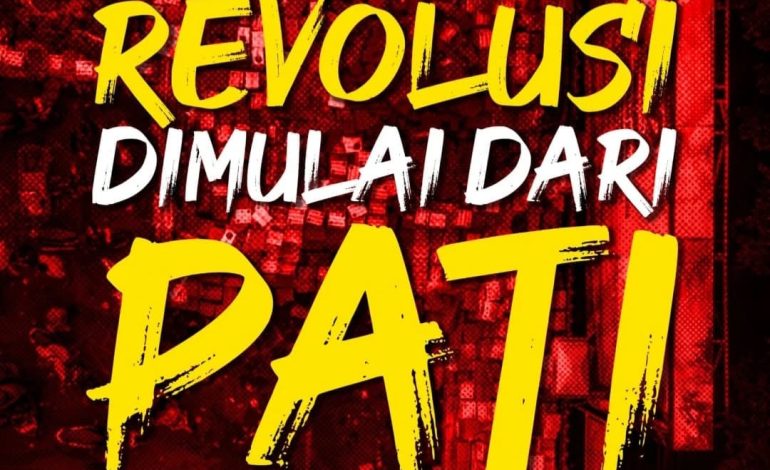#MerdekainThisEconomy: Berjalan Kaki dengan ‘Happy’, Kemewahan Terakhir Kelas Pekerja

Ketika akhirnya resmi menyandang status sebagai kelas pekerja di Jakarta, saya pikir hidup akan sederhana. Bisa punya penghasilan tetap, bisa mengatur ritme harian, dan menjalani rutinitas dengan tenang. Namun ternyata, impian yang sesederhana itu terasa muluk.
Contoh paling remeh adalah berjalan kaki ke kantor. Aktivitas yang harusnya mudah dan gratis ini justru kerap berubah menjadi perjuangan (jihad) sehari-hari. Trotoar yang rusak, becek, penuh lubang, kadang dijajah pengendara motor atau pedagang kaki lima, sering membuat saya lebih mawas.
Pernah suatu kali di Tendean, Jakarta Selatan, saya salah menginjak tepian trotoar yang tak rata. Tubuh saya terjungkal ke depan, lutut tergores aspal, luka persis seperti masa SMP dulu ketika jatuh dari sepeda.
Sakitnya memang tak seberapa. Namun rasa malunya cukup membekas, apalagi saat itu, orang-orang menoleh dengan tatapan heran. Di momen tersebut, saya sadar di kota besar ini, trotoar yang buruk ternyata memang sangat berbahaya.
Saya yakin, ratusan ribu pekerja di Jakarta atau kota besar lainnya pernah merasakan hal yang sama saat berjalan kaki. Kita mendengar riset Stanford University pada 2017 yang menyebut orang Indonesia malas jalan kaki. Kita bahkan di peringkat paling rendah dalam daftar negara dengan rata-rata langkah harian hanya 3.513 langkah per hari, jauh di bawah rata-rata global 4.961 langkah.
Bagaimana orang bisa senang berjalan kaki jika trotoarnya tidak ramah, jalannya semrawut, dan udaranya penuh polusi? Bagaimana mereka bisa menikmati langkah-langkahnya jika setiap saat harus waspada terserempet motor yang menyerobot trotoar, atau terperosok ke galian yang tidak ditutup rapat?
Saya teringat satu sore di kawasan Kuningan. Di sepanjang jalur trotoar, ada galian besar yang dipagari seadanya. Orang-orang yang berjalan terpaksa melipir ke jalan raya. Truk-truk besar melintas, klakson meraung, dan setiap langkah terasa seperti taruhan antara selamat atau celaka. Dalam kondisi seperti itu, siapa yang bisa bilang jalan kaki adalah kegiatan sehat dan menyenangkan?
Realitas ini membantah mitos “orang Indonesia malas jalan kaki”. Malas bukan akar masalahnya. Infrastruktur kota yang buruklah yang membuat berjalan kaki terasa mustahil.
Baca juga: #MerdekainThisEconomy: Dari ‘Survival Mode’ ke ‘Survivor Mode’, Sulitnya Jadi Perempuan Penulis
Berjalan Kaki dan Filosofi Kehidupan
Saya sendiri sebenarnya pecinta jalan kaki. Pulang-pergi ke kantor, rata-rata saya menempuh sekitar empat kilometer. Di tengah kemacetan Jakarta, langkah kaki saya justru sering jadi jalan keluar paling rasional.
Kegemaran ini membuat saya jatuh cinta pada buku A Philosophy of Walking (2020) karya filsuf Prancis, Frédéric Gros. Dalam bukunya, Gros menulis jalan kaki bukan hanya aktivitas fisik, tapi juga filsafat hidup. Berjalan kaki adalah cara kita membebaskan diri dari kegelisahan, ritme kerja yang serba tergesa, bahkan dari obsesi identitas dan jabatan.
Berjalan kaki, kata Gros, juga momen “melepas diri dari godaan memiliki nama”. Kita kembali menjadi manusia biasa yang hanya bergerak, menarik napas, dan menyadari langkah. Ada kualitas mindfulness yang lahir ketika tubuh kita bergerak seirama dengan waktu yang melambat.
Tak heran, banyak pemikir besar menjadikan jalan kaki sebagai ritual. Friedrich Nietzsche, misalnya, menulis gagasan-gagasan filosofisnya sambil berjalan di pegunungan Swiss. Penyair Arthur Rimbaud menempuh perjalanan panjang dengan kaki telanjangnya, menemukan inspirasi di setiap jengkal tanah yang dilalui. Bahkan Immanuel Kant dikenal punya kebiasaan jalan kaki rutin di Königsberg pada jam yang nyaris selalu sama, seolah langkahnya bagian dari sistem filsafat itu sendiri.
Bagi mereka, jalan kaki adalah kemewahan intelektual. Pertanyaannya: Mengapa di Jakarta, sesuatu yang dulu jadi ruang refleksi bagi para filsuf, justru terasa terlalu mahal bagi kelas pekerja?
Baca juga: #MerdekainThisEconomy: Dear Sri Mulyani, Semoga di Kehidupan Selanjutnya Anda Jadi Anak Guru
Kemewahan yang Terampas dari Kelas Pekerja
Tan Malaka pernah berkata, “Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki pemuda.” Jika saya boleh menyitir sedikit, berjalan kaki dengan nyaman adalah kemewahan terakhir yang dimiliki kelas pekerja.
Bagi kami, tubuh adalah modal utama. Kami menjual tenaga, menjual waktu, menjual pikiran. Namun bahkan untuk menjaga tubuh tetap sehat lewat aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, ruang itu kian tercerabut.
Trotoar dirampas motor yang melintas seenaknya. Ruang pejalan diserobot pedagang tanpa ada penataan yang memadai. Pembangunan gedung-gedung tinggi menjulang, tapi ruang antara bangunan justru penuh beton tanpa ruang teduh untuk orang berjalan. Polusi udara semakin menyesakkan, seakan paru-paru kami tak punya hak untuk bernapas lega.
Yang lebih ironis, narasi “kemajuan kota” justru sering menyingkirkan pejalan kaki. Kota seolah hanya dibangun untuk mobil, motor, dan tol, sementara manusia yang berjalan dianggap sisa ruang, bukan prioritas. Padahal, menurut World Health Organization (WHO), kota yang sehat adalah kota yang memfasilitasi warganya berjalan kaki. Ini termasuk menyediakan jalur yang aman, aksesibel, teduh, dan menyenangkan. Jalan kaki bukan sekadar pilihan, tapi hak dasar setiap warga.
WHO bahkan menyebutkan, berjalan kaki minimal 30 menit sehari bisa menurunkan risiko penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, hingga depresi. Artinya, setiap trotoar yang buruk bukan hanya masalah estetika, tapi juga kesehatan publik. Ketika ruang berjalan kaki tidak layak, kita sebenarnya sedang menyiapkan ledakan masalah kesehatan masyarakat di masa depan.
Namun di Jakarta, berjalan kaki justru berubah menjadi perjuangan kelas. Kami yang bergantung pada transportasi umum sering harus melanjutkan perjalanan dengan kaki, berpindah dari halte ke kantor, dari stasiun ke rumah kontrakan. Setiap meter langkah terasa seperti ujian: Apakah akan selamat, atau harus menanggung risiko luka, bahkan nyawa.
Ketika Hari Kemerdekaan tiba, kita merayakan dengan lomba, karnaval, dan pidato. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari, apa arti merdeka?
Bagi saya, jawabannya sederhana: Bisa berjalan kaki dengan nyaman dan happy. Enggak lagi was-was diserempet motor. Tidak lagi malu jatuh karena trotoar yang amburadul. Tidak lagi harus menutup hidung karena polusi.
Baca juga: Konten ‘Jakarta Keras’: Potret Wajah Kota yang Tak Setara
Kemerdekaan itu tidak mewah. Ia sederhana, tapi bermakna. Sayangnya, kesederhanaan itu kini terasa seperti kemewahan terakhir.
Merdeka sejati bukan hanya soal bebas dari penjajahan bangsa lain, tapi juga bebas bergerak dengan aman di kota yang kita tinggali. Merdeka berarti bisa berjalan tanpa rasa takut. Merdeka berarti tubuh pekerja yang sudah lelah oleh jam kerja panjang tetap diberi ruang untuk bernapas, melangkah, dan menikmati hidup.
Saya tidak ingin berjalan kaki hanya menjadi nostalgia atau romantisme kelas pekerja. Jalan kaki harus dikembalikan pada hakikatnya: Aktivitas sederhana yang bisa dinikmati siapa saja, bukan hanya mereka yang mampu tinggal di kompleks elit dengan jalur pedestrian rapi.
Kita, kelas pekerja, berhak menuntut ruang kota yang lebih ramah manusia. Pemerintah punya kewajiban menghadirkan trotoar yang aman. Pengembang kota harus memikirkan ruang teduh di antara gedung. Warga kota pun perlu belajar menghormati hak pejalan kaki.
Kalau Tan Malaka berkata idealisme adalah kemewahan terakhir pemuda, maka mari kita pastikan berjalan kaki dengan nyaman tidak benar-benar menjadi kemewahan terakhir kelas pekerja.
Dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI 2025, Magdalene meluncurkan series artikel #MerdekainThisEconomy dari berbagai POV penulis WNI. Baca artikel lain di sini.
Ilustrasi oleh Karina Tungari