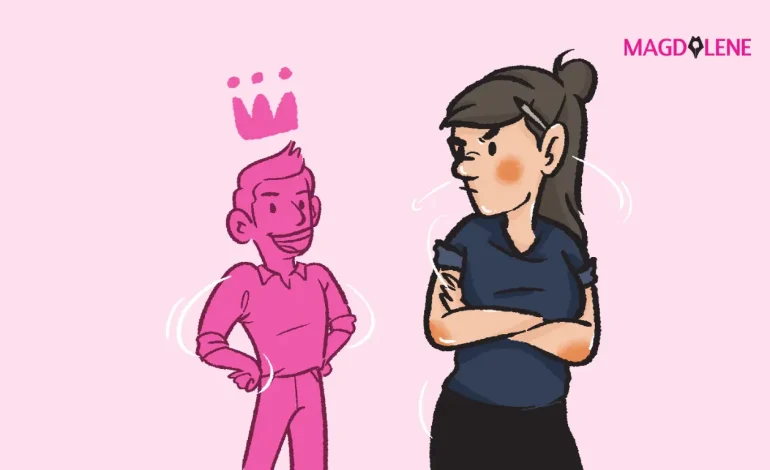Kartu Pers Tak Lagi Cukup Melindungi: Intimidasi Jurnalis dalam Aksi Massa

Ketegangan di depan Mapolda Bali (30/8) tak terhindarkan saat aparat mengeluarkan water canon dan satu unit mobil rantis, untuk menghalau demonstran yang ingin memasuki halaman Polda Bali pada pukul 15.32 WITA.
Saat itu massa beramai-ramai menyampaikan tuntutannya agar kepolisian bertanggung jawab atas kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang dilindas polisi pada demonstrasi di Jakarta (28/8) silam.
Aparat yang dibekali dengan pentungan, tameng, dan gas air mata memukul mundur peserta aksi dan membuat konsentrasi massa bergeser. Aksi yang semula dilakukan di Mapolda Bali berpindah ke Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, dekat Gedung DPRD Bali.
Langkah kaki Fabiola Dianira atau Nia, wartawan Detik Bali, mengikuti pergeseran massa. Nia sampai di Lapangan Renon pada pukul lima sore. Sekitar satu jam meliput, baterai ponsel Nia habis total. Nia lalu memutuskan untuk menepi ke sebuah minimarket yang berada di bagian selatan lapangan.
Setelah baterai ponselnya penuh, Nia berniat kembali ke titik aksi–di utara lapangan. Namun, tanpa Nia sadari massa sudah berpindah ke selatan, tempat ia menepi.
“Waktu masih di selatan itu, saya lihat ternyata massa sudah sampai sini dan ada beberapa massa yang tergeletak, duduk di lapangan, duduk di bawah, ada yang tiduran,” tutur Nia.
Pikir Nia, mereka merupakan massa aksi yang sedang beristirahat. Namun, tiba-tiba pria tidak dikenal menendang mereka. “Salah satu dari mereka itu ada yang ditendang. Jadi posisinya ada orang (massa aksi), tangannya diikat ke belakang, kemudian dia dibaringkan, menyamping,” kisah Nia.
Tak lama kemudian, pria misterius tersebut mengalihkan pandangannya kepada Nia yang tengah memegang ponsel.
“Jangan dokumentasi! Jangan foto!” seru pria itu.
“Saya dari media. Belum foto,” balas Nia.
Pernyataan Nia tak cukup membuat pria itu percaya, sekali pun Nia sudah memakai kartu identitas pers. Ia lalu menginstruksikan dua rekannya untuk memeriksa Nia. Kedua tangan Nia dipegang erat-erat, dan ponselnya diambil paksa.
“Mau enggak mau, akhirnya saya ditekan untuk membuka password pakai sidik jari. Akhirnya saya buka, saya tunjukkan galeri, dan memang belum ada apa-apa,” jelas Nia.
Setelah mengetahui ponsel Nia tidak memuat dokumentasi kekerasan, ketiga pria itu langsung melepas Nia. Tak terima, Nia terlibat cekcok dengan ketiga laki-laki itu.
“Saya di situ bener-bener emosi banget. Saya merasa enggak terima. Kenapa saya diperlakukan seperti itu?”
Nia bertanya berulang kali asal instansi ketiganya. Namun tidak ada jawaban yang didapatkan. Merasa tak puas, Nia terus mencecar ketiganya dengan pertanyaan yang sama. Sampai salah satu di antara mereka kesal dan menunjukkan gestur ingin memukul.
“Buat apa kamu mau tahu saya dari mana?” ujar laki-laki tersebut.
Beruntung, salah satu rekan jurnalis segera datang melerai dan membawa Nia ke tempat aman. “Waktu itu akhirnya nangis. Saya benar-benar nangis. Sampai gemetaran,” kenang Nia.
Nia masih ingat dengan jelas perawakan ketiga pria misterius tersebut: memakai pakaian serba hitam, dan salah satunya berambut gondrong sebahu. Dari amatan Nia, mereka terlihat seperti tengah mengawasi para demonstran.
Trauma akibat peristiwa itu tak hilang begitu saja. Hingga kini Nia masih merasa cemas ketika berada sendirian di kos. Ia memiliki sugesti sedang dibuntuti, dan khawatir keamanannya terancam.
“Ini udah aman belum, ya? Perlu di-sembunyiin enggak ya laptopnya? Mereka bakal ada tindak lanjut (kekerasan) atau enggak, ya?” pikir buruk Nia sampai hari ini.
Baca juga: KBGO pada Jurnalis Tajam ke Perempuan dan Gender Minoritas: Tips Jaga Diri karena Sistem Jelek
Saat Kartu Pers Tak Dapat Melindungi Jurnalis
Kasus yang dialami Nia kerap menimpa jurnalis lainnya. Meskipun sudah memakai kartu identitas pers, jurnalis tetap rentan mengalami kekerasan di lapangan. Nasib yang sama menimpa Bayu Pratama Syahputra atau Ibay, jurnalis foto Antara yang meliput aksi massa 25 Agustus silam.
Ibay ingat saat itu masih tengah hari. Ia tiba pukul 12.00 di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senayan, Jakarta. Akan tetapi, kondisi di lapangan sudah memanas. Polisi terlihat telah memukul mundur demonstran, peristiwa yang biasanya Ibay saksikan di atas jam lima sore.
Massa aksi dipukul hingga ke bawah jembatan penyeberangan orang (JPO) depan DPR. Saat itu posisi Ibay berada di belakang polisi, untuk keamanan selama liputan. Ibay mendokumentasikan momen bentrokan antara massa dan aparat. Setelah mengambil foto tersebut, Ibay bermaksud mengamankan diri lebih jauh ke belakang.
“Ketika saya berbalik melihat ke belakang, pukulan itu sudah mengarah ke muka saya,” cerita Ibay.
Ibay refleks menggunakan kamera untuk melindungi diri. Akibat serangan tersebut, lensa kamera Ibay rusak total dan tidak bisa digunakan kembali. Ibay juga mengalami luka memar di tangannya. “Dan waktu (kamera) dibongkar, ternyata semua kabel tuh putus.”
Estimasi Ibay, kerugian dari kerusakan tersebut mencapai seratus juta rupiah. Setelah peristiwa yang menimpanya tersiarkan, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi mengunjungi kantor Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara untuk meminta maaf, dan mengganti kerugian yang dialami Ibay. Ia berjanji akan mengusut tuntas penganiayaan terhadap Ibay.
Meskipun begitu, Ibay tetap melaporkan kekerasan yang dialaminya ke Polda Metro Jaya. Ia menyerahkan kameranya yang rusak sebagai barang bukti. Begitu pun Nia, ia melapor ke Polda Bali atas delik kekerasan dan penghalangan kerja pers.
Peristiwa yang menimpa Ibay dan Nia hanyalah dua kisah yang naik ke permukaan. Ketua Komisi Keselamatan Jurnalis (KKJ) Erik Tanjung mengaku laporan dan temuan kekerasan terjadi pada jurnalis, serta perusahaan media, begitu masif terjadi.
Setidaknya KKJ mencatat, sepanjang 1 Januari-31 Agustus 2025, telah terjadi 60 kekerasan terhadap jurnalis dan media. Bentuk kekerasan itu beragam, mulai dari intimidasi, teror, serangan digital ke website, akun media sosial, dan ancaman pencabutan iklan.
“Serangan kekerasan ini diduga pelakunya dari institusi militer, politisi, dan kepolisian,” ujarnya kepada Magdalene.
Kasus teranyar salah satu jurnalis media CNN Indonesia dicabut kartu khusus pers oleh pihak istana, akibat menanyakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden.
Baca juga: Jurnalis Perempuan Rentan Alami KBGO
Jurnalis Rentan Diintimidasi, Sulit Dapat Keadilan
Perlindungan pers telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Namun, penegakannya masih jauh dari harapan. Chikita Edrini Marpaung, Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, menilai problem utama bukan pada regulasi, melainkan pada penegakan hukum yang tak berpihak.
Menurut Chikita, pasal 18 UU Pers sudah mengatur ancaman pidana bagi pelaku penghalangan kerja jurnalistik. Namun, dalam praktiknya, kasus kekerasan terhadap jurnalis hampir tidak pernah berujung pada penghukuman pelaku—apalagi jika melibatkan aparat.
“Praktik penyelesaian terhadap kasus serangan jurnalis itu sangat minim preseden baik. Misalnya kasus serangan, itu hanya satu-satunya (yang masuk ke pengadilan) setelah sekian puluh tahun UU Pers berlaku yang kemudian menjerat aparat,” jelas Chikita.
Kasus yang dimaksud adalah kekerasan terhadap jurnalis Tempo Nurhadi oleh dua polisi saat tengah meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji di acara pernikahan anaknya, 2021 silam. Pengadilan Negeri Surabaya kemudian menjatuhi dua penganiaya Nurhadi yang merupakan polisi aktif hukuman penjara selama sepuluh bulan.
Berdasarkan penuturan Chikita, sulitnya penghukuman terhadap pelaku salah satunya disebabkan banyak korban enggan melapor karena takut berhadapan langsung dengan pihak berwenang. Proses hukum yang panjang dan berbelit juga membuat mereka mundur sebelum perkara berjalan jauh.
“Nah, di proses itu sering kali jurnalis sudah paham yang akan dia hadapi di depan, dan cenderung enggan (melanjutkan) karena akan memakan waktu, sedangkan dia juga harus bekerja.”
Kondisi tersebut, sebut Chikita, disebabkan oleh sistem hukum yang tidak proaktif melindungi jurnalis. Alih-alih aparat yang bergerak cepat, tanggung jawab justru dibebankan kepada jurnalis korban kekerasan.
“Harusnya yang proaktif kan aparat, karena ini ada dimensi publik,” imbuh Chikita.
Dengan situasi seperti ini, jurnalis tak hanya rentan direpresi, tapi juga sulit mendapat keadilan ketika menjadi korban kekerasan. Struktur hukum yang tidak berpihak membuat perlindungan pers hanya berhenti di atas kertas.
Baca juga: Pelir, Perek, dan Kekerasan Gender di Media Kita
Penghalangan Kerja Jurnalistik, ‘Framing’, dan Gugatan ke Media
Tantangan dunia pers semakin terasa saat perusahaan media mengalami pelarangan dan pembatasan informasi saat demonstrasi pada 25-31 Agustus lalu. Salah satu lembaga negara mengimbau dan “melarang” media menayangkan liputan demo, dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta melalui edaran surat resmi. KPID Jakarta sendiri membantah tudingan melarang penayangan media.
“Enggak. Kami tidak pernah mengeluarkan surat sebagaimana dimaksud,” kata Ketua KPID Jakarta Puji Hartoyo, seperti dikutip dari Tempo (29/8).
Tantangan bagi media bertambah ketika muncul framing “antek asing”. Beredar klaim di sejumlah media Indonesia bahwa aksi demonstrasi didanai George Soros, filantropis Amerika yang dituding menjadi dalang krisis moneter 1998, untuk memprovokasi massa.
Erik mengatakan media seharusnya bisa bekerja tanpa tekanan pihak manapun. Kerja jurnalistik dibutuhkan untuk menjaga alam demokrasi dan menegakkan kebebasan berekspresi.
Laporan Komisi Kebebasan Pers (KKJ) menceritakan pengalaman salah satu pimpinan perusahaan media. Menurut laporan, pimpinan DPR meminta perusahaan televisi untuk tidak menayangkan aksi demonstrasi Agustus lalu.
“Negara harus hadir menjamin pers, Presiden Prabowo Subianto juga wajib menghormati kemerdekaan pers, karena itu adalah mandat undang-undang,” ujarnya.
Erik, yang juga Ketua Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), menambahkan jika pemerintah keberatan dengan pemberitaan, hak jawab bisa dilakukan sesuai UU Pers. Pemerintah atau pihak yang keberatan harus menempuh mekanisme konstitusi, seperti mengadukan media melalui Dewan Pers.
“Bukan dengan cara intimidasi, pembungkaman, intervensi sampai kekerasan fisik, dan kekerasan digital,” katanya.
Salah satu dugaan pembungkaman dilami media Tempo akhir September lalu. Tempo menghadapi gugatan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penyebabnya, Amran merasa keberatan dengan cover artikel edisi 16 Mei 2025 berjudul “Poles-poles Beras Busuk”. Artikel itu menyoroti kebijakan Bulog yang tidak memilah kualitas beras karena membeli 6.500 per kilogram dari petani.
Akibatnya, petani mencampur gabah kualitas bagus dan buruk, bahkan beberapa daerah mencampur gabah dengan air untuk menambah berat. Kondisi ini membuat beras di gudang Bulog rusak, meski stok mencapai empat juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Amran menuntut ganti rugi 200 miliar kepada Tempo.
Cara Media Bertahan
Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika atau Komang, mengatakan banyak perusahaan media menghadapi tantangan besar selama periode Prabowo-Gibran. AMSI melakukan advokasi non-litigasi bagi media yang menghadapi persoalan.
Komang menyoroti praktik kekerasan terhadap media dan jurnalis yang sering terjadi. “Ini memprihatinkan karena tugas media memang melakukan kritik sosial. Itu bahkan disebut UU Pers, jadi melarang pers mengkritik sama dengan melanggar UU Pers,” ujarnya.
AMSI menantikan tindakan Dewan Pers untuk melindungi kebebasan pers. Jika media atau jurnalis bersalah, sanksinya seharusnya bukan kriminalisasi, sensor, atau pembungkaman. “Melainkan sanksi yang fair jika ada kesalahan etik yang ditemukan Dewan Pers,” tambahnya.
Dewan Pers juga perlu memikirkan keberlangsungan bisnis media dengan memastikan ekosistem di Indonesia memadai bagi media independen untuk hidup dan berkembang. Chikita menambahkan pentingnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menjamin perlindungan jurnalis saat menjalankan kerja jurnalistik.
PKS yang sudah ada saat ini hanya mengatur perihal prosedur koordinasi yang memastikan laporan terkait karya jurnalistik diselesaikan melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi, atau diserahkan kepada Dewan Pers, sebelum diteruskan ke penegakan hukum. Namun, belum spesifik kepada penghalang-halangan kerja jurnalistik seperti kekerasan aparat.
Chikita juga menekankan pentingnya perubahan kultur aparat, agar lebih menjunjung tinggi kemerdekaan pers.
“Memang kultur dan keengganan dari lembaga atau aparatnya yang ternyata menjadi tantangan paling utama,” pungkasnya.
Ilustrasi oleh Karina Tungari