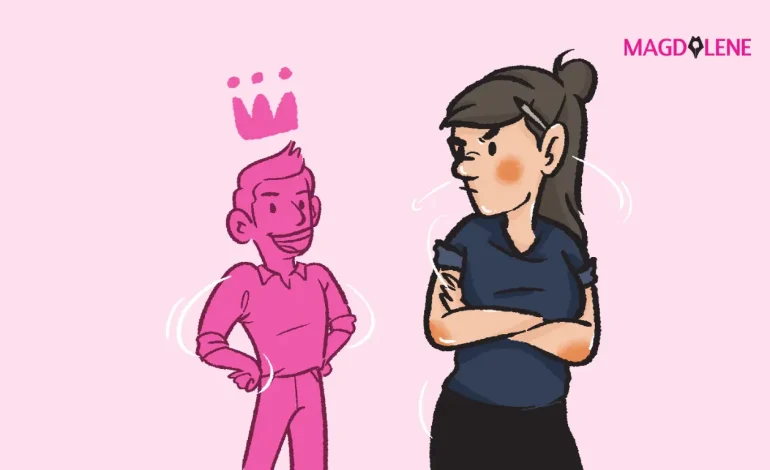
“Kamu di rumah aja, biar aku yang cari uang.”
Kalimat ini sering terdengar begitu romantis—seolah menjadi bukti cinta dan tanggung jawab seorang lelaki. Tapi di balik janji manis untuk “menafkahi sepenuhnya”, ada bahaya yang jarang disadari: perempuan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Ketika uang hanya dimiliki satu pihak dalam hubungan, relasi bisa dengan mudah berubah menjadi ruang kontrol, dominasi, bahkan kekerasan.
Dalam masyarakat patriarkal, lelaki yang mengambil peran sebagai pencari nafkah utama dianggap sebagai simbol kemapanan sekaligus kejantanan. Sebaliknya, perempuan yang tidak bekerja atau didorong untuk menjadi ibu rumah tangga dianggap “beruntung” karena tak perlu memikirkan urusan ekonomi. Padahal, relasi semacam ini menyimpan potensi ketimpangan kuasa yang besar.
Tanpa akses terhadap penghasilan sendiri, perempuan bisa kehilangan kebebasan dalam mengambil Keputusan, mulai dari urusan rumah tangga, pendidikan anak, hingga kebutuhan pribadi sekecil apa pun. Inilah yang disebut sebagai kekerasan finansial—bentuk kekerasan berbasis gender yang sering luput dikenali karena dibungkus dalam narasi pengorbanan dan cinta.
Baca juga: Mimpi Perempuan Jadi ‘Tradwife’: Berikut Penjelasannya
Di balik romantisme lelaki penafkah
Kekerasan finansial bisa hadir dalam berbagai bentuk. Ada yang melarang pasangannya bekerja dengan dalih “anak-anak butuh ibunya”. Ada pula yang memberikan uang bulanan tapi menuntut pertanggungjawaban sampai ke setiap detail pengeluaran. Ada yang menyembunyikan aset, menutup akses rekening bersama, bahkan berutang atas nama pasangan tanpa izin. Dalam banyak kasus, perempuan dipaksa bergantung secara ekonomi dan dibuat percaya bahwa itu adalah bentuk perlindungan.
Ini bukan kasus personal belaka, melainkan pola struktural yang merugikan perempuan. Fenomena ini disebut kekerasan finansial, bentuk kekerasan yang kerap tak terlihat karena dibungkus rapi dengan dalih “aturan rumah tangga.”
Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 dari Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa dari 56.189 kasus kekerasan terhadap perempuan, sekitar 9,84 persen (5.531 kasus) tergolong sebagai kekerasan ekonomi. Angka ini kemungkinan besar jauh lebih besar dari yang terlaporkan, mengingat banyak perempuan tidak sadar bahwa mereka sedang mengalami kekerasan, atau tidak merasa berhak menggugat karena telah “dinafkahi.”
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat, National Network to End Domestic Violence (NNEDV) melaporkan bahwa 99 persen korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga mengalami kekerasan finansial. Uang digunakan sebagai alat kontrol utama dalam relasi yang timpang. Maka, tak mengherankan jika banyak perempuan memilih bertahan dalam hubungan beracun karena tak punya kuasa atas ekonomi mereka sendiri. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan untuk melarikan diri saja, mereka tak punya ongkos.
Padahal, menurut laporan Bank Dunia (2021), perempuan yang mandiri secara finansial memiliki kemungkinan lebih besar untuk keluar dari hubungan kekerasan. Kemandirian ini bukan hanya soal kemampuan membeli kebutuhan sendiri, tapi juga soal otonomi atas keputusan hidup. Ketika akses terhadap sumber daya ekonomi berada di tangan satu pihak, maka relasi yang dibangun bukanlah kemitraan, melainkan dominasi.
Sayangnya, romantisasi peran lelaki sebagai “provider sejati” masih kuat berakar dalam budaya populer. Dalam banyak film, lagu, bahkan obrolan sehari-hari, laki-laki yang menanggung semua beban ekonomi dianggap lebih “lelaki”, sementara perempuan yang menggantungkan hidupnya padanya dianggap ideal, patuh, dan layak dicintai.
Jarang sekali kita melihat narasi yang merayakan relasi finansial yang setara—di mana dua orang berbagi tanggung jawab ekonomi dan saling menghormati kontribusi masing-masing, baik di ranah publik maupun domestik.
Baca juga: Kenapa ‘Performative Male’ yang ‘Red Flag’ Bisa Viral?
Menujur relasi finansial yang setara
Menjadi “provider” sebenarnya bukan masalah, selama itu dilandasi kesepakatan yang setara dan tidak disalahgunakan untuk mengontrol. Relasi finansial yang sehat harus dibangun atas dasar transparansi, kepercayaan, dan penghargaan atas kontribusi masing-masing. Diskusi terbuka tentang pengeluaran rumah tangga, pengambilan keputusan bersama dalam pengelolaan uang, serta saling menghormati pilihan kerja atau karier adalah beberapa hal yang perlu terus dilatih dalam hubungan.
Penting juga untuk menegaskan bahwa perempuan berhak punya penghasilan sendiri, bahkan jika pasangannya memiliki penghasilan berlebih. Kemandirian finansial memberi ruang bagi perempuan untuk merasa aman, percaya diri, dan berdaya dalam relasi. Lagipula, apa artinya rumah besar dan mobil mewah jika semua keputusan ditentukan satu pihak? Banyak perempuan yang hidup dalam “sangkar emas”—terlihat sejahtera, tapi tak bisa mengambil keputusan sendiri, apalagi pergi tanpa izin.
Pada akhirnya, relasi yang sehat bukan tentang siapa yang membayar lebih banyak, melainkan siapa yang menghargai lebih banyak. Cinta bukan soal perlindungan sepihak, melainkan soal kerja sama yang setara. Jadi, ketika seseorang berkata, “Laki-laki itu tugasnya jadi provider,” mungkin kita bisa balik bertanya, “Untuk siapa? Dan dengan syarat apa?” Jika jawabannya adalah untuk mengendalikan, maka itu bukan cinta—itu patriarki yang menyamar sebagai kasih sayang.
Ilustrasi cover artikel oleh Jelita. A. Rembulan






















