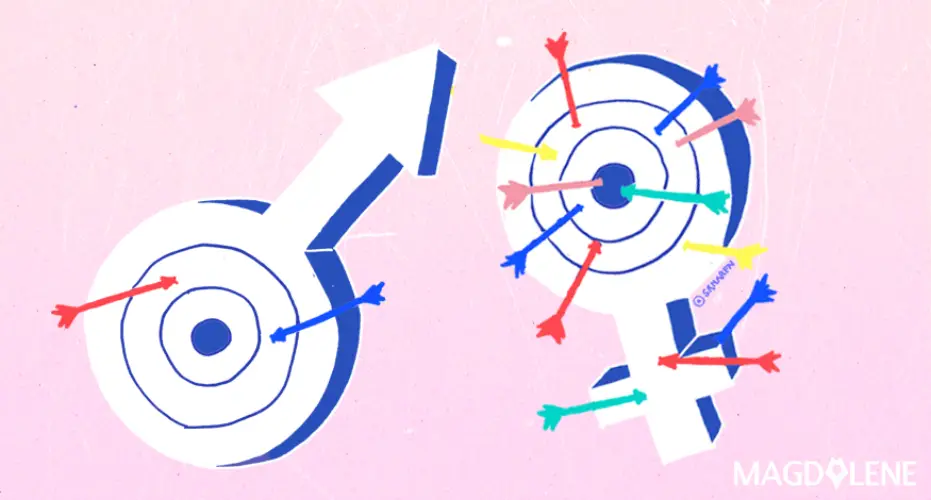Poligami dan Janji Palsu Kesetaraan di Mata Hukum

Poligami bukan sekadar isu rumah tangga atau tafsir agama, melainkan cerminan nyata dari ketimpangan yang dilegalkan. Di Indonesia, poligami hidup bukan hanya dalam budaya, tapi juga dalam sistem hukum. Padahal, kalau kita sepakat bahwa kesetaraan adalah nilai dasar dalam negara demokratis, mestinya poligami tak lagi punya tempat dalam aturan negara.
Tulisan ini tidak hendak menghakimi keyakinan siapa pun. Justru sebaliknya, ini adalah ajakan untuk menempatkan hukum negara pada posisi yang netral, tidak memihak tafsir agama tertentu, dan berpihak sepenuhnya pada prinsip keadilan antarwarga. Tujuannya bukan menghukum pelaku poligami, melainkan menghentikan peran negara dalam memfasilitasi praktik yang melanggengkan ketidaksetaraan gender.
Sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, ruang untuk poligami dilegalkan secara formal. Dalam praktiknya, ini membuka celah diskriminasi yang berpihak pada satu kelompok: laki-laki. Hanya mereka yang diakui secara hukum bisa mengambil istri lebih dari satu, sementara perempuan menjadi penanggung dari konsekuensi diskriminasinya.
Pasal-pasal hukum kita, meski terlihat “mengatur ketat”, justru memberi justifikasi. Izin dari pengadilan agama, persetujuan istri pertama, hingga syarat keuangan, semuanya bisa dinegosiasikan, sering kali dalam posisi kuasa yang tidak seimbang. Banyak istri menyetujui poligami bukan karena rela, tapi karena tak punya pilihan. Tekanan ekonomi, stigma sosial, dan minimnya perlindungan hukum membuat “persetujuan” itu jadi formalitas semata.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa negara yang memfasilitasi poligami ikut memperbesar risiko kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Dalam studi Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), dari 107 perempuan korban poligami, mayoritas mengalami pengabaian nafkah, konflik rumah tangga, dan beban psikologis yang berat.
Lalu, untuk apa kita mempertahankan poligami dalam hukum Indonesia?
Baca juga: Pengalamanku Seminggu Kepo Akun-akun Poligami: Bikin Ngelus Dada dan Emosi
Realitas sosial sudah berubah
Argumen bahwa hukum harus menyesuaikan dengan realitas sosial tak bisa dipakai untuk mempertahankan poligami. Sebab, realitas masyarakat kita pun sudah bergeser. Perempuan Indonesia hari ini adalah penggerak ekonomi, penentu pendidikan anak, bahkan penopang keluarga. Dalam banyak rumah, justru perempuan yang lebih stabil secara finansial dan emosi.
Nilai-nilai kesetaraan semakin menjadi standar etis masyarakat urban maupun desa. Sekali lagi, negara yang konstitusinya mengakui persamaan derajat warga negara seharusnya tidak membiarkan hukum yang mendasarkan hak seseorang pada gender. Poligami melanggar prinsip itu secara terang-terangan.
Jika hukum masih melegalkan poligami, artinya negara membiarkan sistem yang mendiskriminasi warganya hanya karena gender. Ini bertentangan dengan konstitusi kita sendiri, Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 28D Undang ayat (1) menjamin kesetaraan dan keadilan di mata hukum; Pasal 28I ayat (2) melarang diskriminasi dalam bentuk apa pun.
Ada pula anggapan bahwa menghapus poligami dari hukum negara sama saja dengan menghalangi ajaran agama. Tapi sesungguhnya, justru itulah bentuk perlindungan keyakinan. Negara tidak semestinya ikut campur terlalu dalam dalam ranah keyakinan warganya. Jika pun ada yang tetap ingin menjalani bentuk perkawinan tertentu, itu bisa jadi pilihan personal yang tak perlu dilegitimasi atau disubsidi oleh hukum negara. Penghapusan poligami pada ranah hukum negara bukanlah pelarangan ajaran teologis, tetapi penentuan standar keadilan dalam ruang publik.
Hukum negara bukanlah alat untuk mengatur iman, tapi instrumen untuk menjamin keadilan dalam ruang publik. Dalam ranah itulah, negara harus memastikan bahwa semua warga—terlepas dari gender, keyakinan, atau status sosialnya—memiliki hak dan perlindungan yang setara.
Baca juga: Regulasi Poligami dan Dominasi Lelaki: Dari Tafsir Agama hingga Kontroversi Pergub DKI
Dampak sosial poligami
Kita juga tak bisa menutup mata dari konsekuensi sosial poligami. Berbagai studi mengaitkannya dengan konflik rumah tangga, ketidakstabilan psikologis anak, serta kemiskinan struktural. Ketika perempuan tak diberi jaminan hak dan kesejahteraan dalam pernikahan, beban itu bukan hanya ditanggung keluarga, tapi juga masyarakat dan negara. Di tengah tantangan ekonomi dan kualitas pembangunan manusia, mempertahankan mekanisme legal yang berpotensi menghasilkan kerentanan struktural adalah langkah yang kontraproduktif.
Menghapus poligami dari hukum negara tak harus dilakukan dengan gegabah. Negara bisa memulai dari membekukan izin baru untuk poligami, memperkuat perlindungan hukum bagi istri dan anak, serta membuka ruang dialog publik tentang pentingnya keadilan dalam relasi rumah tangga. Perubahan bisa dilakukan secara bertahap, tapi arah tujuannya harus tegas: hukum kita tidak boleh lagi melanggengkan ketimpangan.
Masyarakat Indonesia telah bergerak semakin berdaya, termasuk perempuan. Dalam aspek kapasitas, independensi ekonomi, dan peran sosial, sudah banyak perempuan yang tidak berada pada posisi sekunder. Yang tertinggal justru adalah hukum yang masih memandang mereka sebagai pihak yang dapat dibagi, dipoligami, atau dinegosiasikan atas nama kepentingan lelaki.
Menutup pintu poligami dari sistem hukum bukan tindakan melawan budaya atau agama. Itu adalah langkah menuju kesetaraan yang dijanjikan konstitusi. Kalau benar kita ingin membangun keluarga yang adil dan setara, hukum pun harus berdiri tegak di atas prinsip yang sama.
Usep Hasan Sadikin adalah pemerhati hukum, gender, dan demokrasi. Ia juga seorang peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).