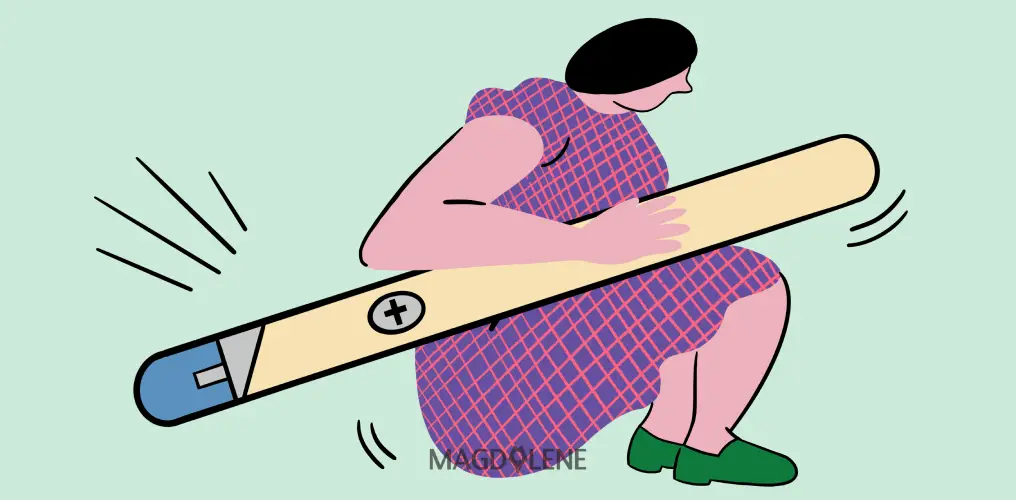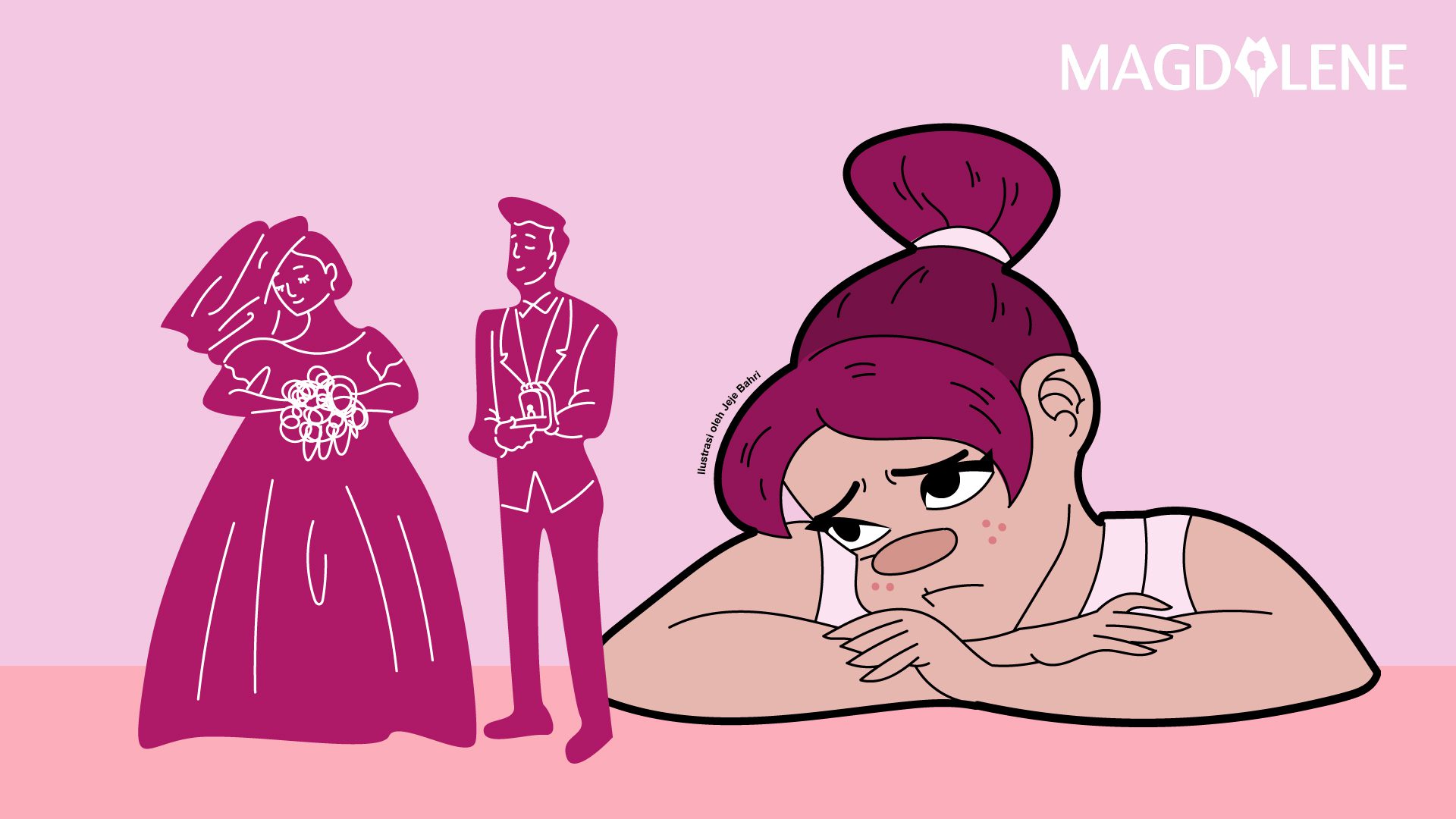Sebagai seseorang yang bekerja di sektor pembangunan, saya kerap menjadi tempat cerita diluapkan. Dari curhatan seputar pekerjaan hingga laporan kasus kekerasan, dari kisah pencarian jati diri hingga luka masa kanak-kanak yang belum sempat sembuh.
Saya merasa terhormat ketika beberapa orang mempercayakan saya sebagai ruang aman untuk melela—bukan hanya tentang seksualitas, tapi juga soal-soal lain yang kerap distigma oleh masyarakat. Sebisa mungkin, saya hadir sebagai pendengar yang utuh. Jika diminta, saya mencoba mencarikan solusi, tentu sesuai dengan kapasitas saya.
Baca juga: Yunus Prasetyo dan Yayasan Lentera: Rawat Anak-anak dengan HIV di Tengah Abainya Negara
Namun tak jarang, cerita-cerita itu meninggalkan jejak dan beban berat. Ada hari-hari ketika saya kewalahan. Ada percakapan yang membuat saya merasa sangat tidak berdaya, bahkan patah hati. Seperti cerita dari dua teman saya, yang kisahnya terpatri di kepala terutama setiap kali memasuki 1 Desember, Hari AIDS Sedunia.
Keduanya adalah lelaki gay, yang satu berusia akhir 20an, yang satu awal 40. Teman pertama, sebut saja Devri, mengajak bertemu usai pandemi mereda. Saya terkejut melihat fisiknya yang menyusut dan kulit wajah yang tadinya glowing jadi kusam dengan koreng dan noda-noda seperti bekas jerawat. Saya pikir, itu efek pasca-COVID. Tapi mendadak saya teringat film Tom Hanks, Philadelphia (1993), yang mengisahkan orang dengan HIV (ODHA) dengan kondisi kulit yang mirip.
Saya menegur diri sendiri dalam hati, “Stereotip amat, sih. Tahu sendiri, kan, kalau mayoritas ODHA itu heteroseksual, bapak-bapak yang kemudian menulari istri dan anak. Lagian itu kan film lama, sekarang beda, HIV bukan sesuatu yang fatal lagi, bisa dikelola seperti penyakit lain.”
Saya terhenyak ketika dugaan saya ternyata benar: Devri sekarang hidup dengan HIV. Meski penasaran, saya tahu saya tidak boleh bertanya soal dari mana infeksi berasal karena itu hanya akan memperparah stigma. Tapi ia sendiri mengalirkan kisahnya, karena tidak tahu harus bercerita kepada siapa yang tidak akan panik atau menghakimi.
“Gue gak promiscuous sama sekali, Mbak. Cuma pacar gue yang om-om itu udah ke sana ke mari dan gak mau pake kondom. Dia sendiri gak sadar udah terinfeksi,” ujarnya.
Hidup Devri adalah kisah klasik banyak anak di Indonesia, the fatherless nation. Dia telah melewati banyak hal: ayah yang absen, trauma kekerasan di masa kecil, ditambah kompleksitas soal seksualitas di masyarakat yang semakin konservatif. Pendidikan seks boro-boro tersedia secara luas, dan dengan aplikasi kencan, Devri dengan mudah mencari pasangan tanpa dasar pengetahuan dan konsep diri yang kuat. Hubungannya dengan si pacar yang jauh lebih tua diwarnai relasi kuasa yang memanfaatkan anak muda rapuh dengan banyak isu.
Syukurnya, di Jakarta tersedia klinik-klinik yang lebih ramah LGBT dan tidak menempelkan stigma soal penyakit ini. Devri pun mendapatkan informasi, pendampingan, dan obat gratis yang harus diminum secara teratur—sepanjang hidupnya. Tapi ia sempat depresi hingga ada keinginan bunuh diri saat pandemi, karena terisolasi di kamar kos sendirian.
“Tapi hubungan gue sama Ibu jadi membaik. Aku cerita sama dia, dan walaupun histeris, dia menerima,” katanya.
Baca juga: Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Kerentanan Berlapis Transpuan Pekerja Seks dengan HIV
Kampanye HIV tak seperti dulu
Teman kedua, “Bima”, bercerita baru-baru ini. Kami mengobrol santai sambil membahas kondisi medis usia paruh baya, dan sama-sama mengaku rajin minum obat sekarang ini. Saya pikir dia makan obat anti-kolesterol, tapi ternyata antiretroviral (ARV). Saya terperangah. Ingin bilang ‘how?’ ‘why?’, tapi saya tahan.
“Makasih, ya, sudah terbuka,” saya cuma bisa bilang demikian.
“Lo pasti heran ya, soalnya gue kan termasuk paham isu ini dan suka advokasi juga. Yah, namanya lagi kesepian waktu pandemi, kesiagaan jadi luntur,” Bima meringis dan tertawa kecil.
Dia dan saya pernah terlibat dalam kampanye HIV pada dekade pertama tahun 2000. Bima mengatakan, keadaan jauh berbeda sekarang. Kampanye bukan hanya tidak segencar dulu, tapi jauh menurun. Tidak ada lagi perbincangan dan diskusi aktif, padahal risiko masih tinggi. Akses layanan dan pendampingan tidak didapatkan semua orang, atau kalau ada pun kualitasnya berbeda-beda.
“Banyak ODHA yang setelah virus dalam tubuhnya tidak terdeteksi lagi, mereka langsung berhenti minum obat. Gak ada yang ngasih tau juga kalau itu harus dimakan seumur hidup,” ujar Bima.
Masyarakat yang tambah bergeser ke kanan dan stigma terhadap LGBT yang menguat memperparah situasi ini. Belum lagi karena Amerika Serikat menutup operasi lembaga donornya, USAID, hal ini juga berpengaruh pada bantuan dana layanan kesehatan dan ketersediaan obat.
“Gue sekarang cuma dapet obat buat stok sebulan. Padahal biasanya per tiga bulan,” ia mengangkat bahu.
Baca juga: Trump Tutup Keran Bantuan Obat HIV: Apa Dampaknya buat ODHIV di Indonesia?
Terus bicara soal HIV
Data menunjukkan bahwa situasi terkait infeksi HIV secara global dan di Indonesia mengkhawatirkan. Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 2024 melaporkan bagaimana penanggulangan HIV secara global memasuki fase genting.
WHO mencatat sekitar 40,8 juta orang di seluruh dunia hidup dengan HIV. Di banyak negara, layanan dan pendanaan terkait HIV mengalami disrupsi—anggaran menurun, layanan di wilayah konflik terganggu, dan program berbasis komunitas yang menjangkau kelompok marginal makin terpinggirkan. Padahal tanpa pencegahan yang kuat, pengikisan stigma, integrasi layanan HIV ke sistem kesehatan umum, serta peningkatan pendanaan domestik, akan sulit mengatasi AIDS.
Di Indonesia, seperti dilaporkan Kompas (3/12), ada tren kenaikan kasus HIV dan infeksi menular seksual (IMS) lainnya. Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 564.000 penduduk hidup dengan HIV, menempatkan Indonesia di peringkat ke-9 dunia untuk jumlah kasus tertinggi. Badan PBB terkait AIDS, UNAIDS, memasukkan Indonesia ke dalam tiga negara dengan pertumbuhan epidemi HIV tercepat di Asia-Pasifik.
Kasus IMS di Indonesia, menurut laporan Kompas, meningkat lebih dari 21 persen, terutama pada Gen Z usia 15–24 tahun, yang didorong praktik seks tanpa pelindung. WHO pada 2024 juga melaporkan bahwa penggunaan kondom di kalangan remaja secara global rendah dan justru menurun dari waktu ke waktu. Ini mengkhawatirkan karena remaja adalah kelompok yang paling mungkin terlibat dalam perilaku seksual berisiko dengan banyak pasangan, dan pola ini kerap terbawa hingga dewasa.
Banyak yang mengatakan, “asal tidak berhubungan seks dan taat agama, semua akan baik-baik saja”, dan bahwa “remaja memang tidak seharusnya berhubungan seks.” Tapi nyatanya, mereka melakukannya. Remaja melakukan hubungan seks, dan seperti Devri, mengakses aplikasi kencan tanpa tahu risiko. Bahkan orang dewasa seperti Bima yang sudah tahu bahaya HIV pun tetap rentan terinfeksi.
Devri beruntung bisa pindah ke negara yang menjamin kesehatan universal, di mana infeksi HIV dipandang sebagai penyakit kronis umum, dan pengobatannya gratis untuk semua, termasuk warga asing. Bima pun masih punya akses terhadap pengobatan meski sering diliputi kekhawatiran soal ketersediaan obat. Tapi banyak orang di luar sana yang bahkan tidak sadar telah terinfeksi. WHO memperkirakan lebih dari 70 persen IMS tidak bergejala, sehingga penularan sering terjadi tanpa disadari.
Inilah pentingnya menggencarkan lagi kampanye HIV dan akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan. Untuk remaja yang tak punya akses ke pendidikan seks komprehensif, untuk komunitas queer yang terus distigma, dan untuk para perempuan yang tak tahu suami mereka “jajan” di luar.
Kita tak bisa berharap perubahan terjadi hanya lewat moralitas atau nasihat lama. Kita butuh informasi yang berbasis bukti, layanan yang mudah diakses, dan keberanian untuk bicara jujur soal seks, risiko, dan hak atas kesehatan.
Nina Marlina adalah kuli pembangunan yang bermimpi jadi pengrajin bordir dan petani.