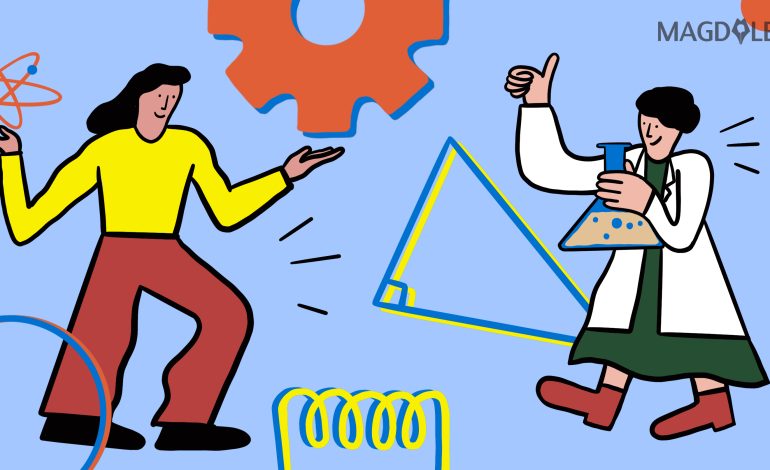Dua Alasan Kenapa Orang Pintar Sentimen pada Kelompok LGTBQ+

Media sosial Twitter sempat diramaikan dengan konten yang diunggah peneliti post-doktoral bidang genetik yang menyebutkan “bahaya” minoritas seksual dari perspektif sains. Ia berargumen, perilaku minoritas tidak dibentuk oleh genetika, hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan.
Argumen tersebut didasarkan pada asumsi pribadinya setelah membaca jurnal ilmiah terkait.
Sang pengunggah kemudian menghapus unggahannya setelah Andrea Ganna – peneliti yang jurnalnya ia kutip – menerbitkan klarifikasi di Twitter. Andrea menganggap argumen peneliti post-doktoral tersebut tidak sesuai tujuan penelitiannya. Riset Andrea juga tidak sepatutnya digunakan untuk menyebarkan sentimen anti-LGBTQ+.
Tuduhan serupa terhadap kelompok minoritas seksual juga pernah dilakukan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin dalam debat publik yang disiarkan di televisi swasta. Sang dokter mengklaim kelompok minoritas seksual berbahaya dan merupakan pembawa penyakit menular, seperti human immunodeficiency virus (HIV) dan cacar monyet.
Padahal, UNAIDS – program PBB untuk penanganan AIDS – telah menghimbau untuk berhati-hati dalam mengaitkan wabah penyakit dengan kelompok rentan tertentu.
Fenomena ini kemudian menimbulkan pertanyaan: Bukankah seharusnya seseorang dengan pengetahuan luas, seperti ilmuwan dan tenaga kesehatan profesional, memiliki sikap yang lebih kritis dalam mengolah bukti ilmiah serta tidak mudah menunjukkan prasangka antarkelompok?
Riset psikologi yang saya lakukan, bersama dengan kolega dari Universitas Persada Indonesia dan Jaringan Rakyat Bhinneka, menunjukkan pengetahuan sains yang dimiliki seseorang memang dapat memunculkan sentimen yang lebih positif terhadap kelompok minoritas seksual.
Sayangnya, pola ini amat tergantung dengan emosi negatif yang dirasakan setiap individu.
Survei dalam riset ini dilakukan pada 2019 dan melibatkan 1.149 orang partisipan berusia 18 sampai 58 tahun dengan orientasi heteroseksual.
Paling tidak ada dua alasan mengapa para ilmuwan masih terjebak dalam sentimen negatif anti-LGTBQ+.
Baca juga: Kepanikan Moral dan Persekusi atas Minoritas Seksual di Indonesia
1. Mengutamakan Keyakinan Pribadi
Sejak lama, manusia digambarkan sebagai makhluk dengan kapasitas akal budi yang luhur. Bahkan, kapasitas rasional manusia sering dianggap sebagai kekuatan terbesar yang dimiliki mereka.
Namun, asumsi tersebut telah dibantah oleh anggapan bahwa manusia sebetulnya tidak didorong sepenuhnya oleh akal, melainkan insting dan kepentingan pribadi.
Riset-riset terkini dalam bidang psikologi sosial menunjukkan, manusia tidak selalu bisa memproses informasi secara objektif. Ahli psikologi sosial Jonathan Haidt dari New York University, Amerika Serikat, bahkan menyebutkan manusia – termasuk ilmuwan sekalipun – seringkali berpikir tidak dengan menggunakan cara-cara ilmiah.
Dalam sains, pengetahuan diperoleh dengan mempertanyakan keyakinan atau asumsi kita sebelumnya. Jika temuan empiris yang objektif menyatakan keyakinan kita salah, maka kita perlu merevisi keyakinan sebelumnya. Itulah cara berpikir ilmiah.
Namun, manusia seringkali berpikir seperti pengacara yang memiliki misi untuk memenangkan kasus.
Kita biasanya sudah tahu apa yang ingin kita yakini dan percayai. Namun, alih-alih menggunakan pengetahuan kita untuk memahami informasi sebenarnya dengan pemikiran terbuka, dan merevisi keyakinan kita jika terbukti salah, kita justru mencari cara untuk menjustifikasi keyakinan itu.
Banyak ilmuwan yang menggunakan pengetahuannya justru untuk memberikan pembenaran terhadap keyakinan pribadi mereka.
Dalam contoh tuduhan terhadap kelompok minoritas seksual seperti yang disebutkan di atas, para ilmuwan dan profesional, seperti dokter, merasa keyakinan yang dimilikinya seputar “kelompok minoritas seksual itu bahaya” perlu dijustifikasi.
Pada akhirnya, mereka hanya memetik bagian-bagian kecil dari temuan atau riset ilmiah sebelumnya yang kiranya bisa mendukung keyakinannya.
Padahal kenyataannya, temuan maupun riset tersebut tidak menunjukkan apapun tentang bahaya kelompok minoritas seksual, bahkan sampai dibantah oleh penulis risetnya sendiri.
Cara berpikir layaknya pengacara yang dilakukan para ilmuwan mendorong mereka memilah-milah mana konten dari artikel yang bisa diterima untuk membenarkan sikapnya terhadap homoseksualitas.
Contoh lain, ada kolom berita yang dipublikasikan oleh jurnal ternama Nature berjudul “No ‘gay gene’: Massive study homes in on genetic basis of human sexuality”. Alih-alih mendalami lebih jauh, banyak ilmuwan terpukau dengan jargon ‘No gay gene’ yang lebih sesuai dengan keyakinannya: bahwa homoseksualitas sama sekali tidak dipengaruhi komponen genetik.
Padahal, maksud riset itu adalah tidak ada gen tunggal yang dapat menentukan homoseksualitas. Artinya, ada banyak komponen gen lain dengan proses yang lebih kompleks dan belum sepenuhnya dipahami.
Ilmuwan dan dokter bukan orang awam dalam memahami artikel ilmiah. Latar belakang pendidikan mereka pastinya sangat memadai.
Namun, banyak dari mereka yang seakan tidak bisa menggunakan kepakaran atau pengetahuannya sebagai ilmuwan dengan baik. Sikap-sikap sosial seringkali lebih dipengaruhi oleh keyakinan individual ketimbang pengetahuan.
Para ahli psikologi sosial menyebut fenomena ini sebagai motivated reasoning atau penalaran yang termotivasi.
Baca juga: Diskriminasi LGBT di Dunia Kerja: Tidak Melela Pun Dicerca
2. Minoritas Dicap Bahaya
Keyakinan kelompok minoritas itu berbahaya merupakan produk adaptasi manusia di Bumi selama ribuan bahkan puluhan ribu tahun lalu. Jauh di masa lampau, kehadiran kelompok asing atau minoritas dianggap rentan membawa wabah penyakit.
Sampai sekarang pun, kelompok minoritas seperti imigran masih dipandang negatif. Selain dianggap membawa wabah penyakit, mereka juga diyakini membawa nilai-nilai yang merusak tatanan dan kemurnian suatu bangsa atau masyarakat.
Kelompok minoritas seksual juga mengalami diskriminasi serupa. Mereka seringkali distigma sebagai pembawa wabah, seperti virus HIV, dan dianggap menularkan orientasi seksual yang “menyimpang” kepada anak-anak.
Penyebaran HIV memang didominasi lewat hubungan seksual. Namun, penyebarannya pada kelompok minoritas seksual di Indonesia hanya sepertiga, apabila dibandingkan dengan kelompok heteroseksual.
Mayoritas penyebaran HIV adalah lewat hubungan seksual dengan pekerja seks – yang merupakan hubungan heteroseksual – dan melalui jarum suntik.
Selain itu, bukti empiris juga menunjukkan bahwa prevalensi homoseksualitas sangat kecil. Bukti ini konsisten dari waktu ke waktu. Artinya, sulit untuk dikatakan bahwa homoseksualitas merupakan penyebab utama penyebaran HIV.
Keyakinan bahwa kelompok minoritas itu berbahaya menciptakan perasaan jijik, cemas, dan takut. Seringkali, emosi-emosi itu sangat kuat dalam membentuk sikap kita. Pengaruh emosi negatif menjadi begitu kuat karena sejak zaman dahulu dianggap berperan menyelamatkan manusia dari bahaya.
Ini menjelaskan mengapa kita seringkali lebih mendengarkan keyakinan kita daripada pengetahuan atau informasi objektif.
Kesimpulannya, tidak selamanya ilmuwan berpikir dengan cara-cara ilmiah. Apalagi, jika ilmuwan tersebut lebih memilih keyakinan pribadinya dibandingkan keinginan untuk memahami lingkungan dan individu yang berbeda-beda.
Pengetahuan yang luas dalam bidang sains memang sering kali membawa sikap yang lebih positif dan toleran terhadap minoritas seksual.
Namun, saat para ilmuwan merasa terancam dengan potensi-potensi bahaya, pengetahuan itu seakan tidak berarti lagi. Mereka menjadi lebih terbawa oleh perasaan dibandingkan pengetahuan ilmiah.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.
Opini yang dinyatakan di artikel tidak mewakili pandangan Magdalene.co dan adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis.