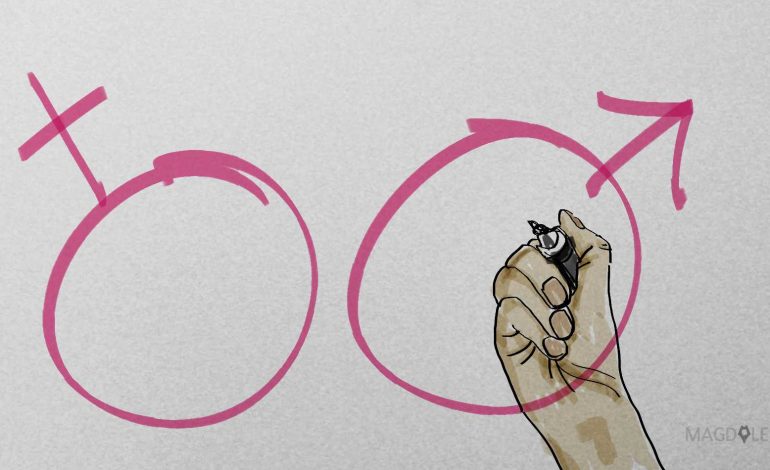20 Tahun Pasca-Reformasi: Diskriminasi Sistemis dan Dihidupkan Lagi Kebijakan Orde Baru

Telah dua puluh tahun Indonesia lepas dari cengkeraman rezim Orde Baru, namun penegakan hak asasi manusia masih belum merata dan menyeluruh. Diskriminasi sistemis masih banyak terjadi dan kebijakan afirmatif masih belum rata dilakukan untuk mencegahnya, demikian kesimpulan dialog nasional Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) yang diadakan pada 18 September.
Para pembicara mengatakan bahwa diskriminasi masa lalu seperti yang terjadi di Timor Leste, Tanjung Priok, dan lainnya tidak ditindaklanjuti secara jelas yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan atas isu tersebut. Walaupun beberapa lembaga sudah berupaya keras untuk membantu pemulihan korban diskriminasi (fisik, psikologi, dan psikosial), masih banyak kebijakan yang perlu dilakukan demi upaya mencegah dan memberantas diskriminasi sistemis.
Aktivis Usman Hamid dari Amnesty Internasional Indonesia menjelaskan keadaan politik saat ini dengan menggunakan dua buah teori. Teori pertama berasal dari Eve Warburton, ilmuwan politik dari Australia National University, yang menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kala telah menghidupkan apa yang disebut neo-developmentalism Orde Baru. Hal itu berarti memprioritaskan pembangunan dan mengesampingkan agenda penting reformasi, yaitu janji pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia. Pembangunan infrastruktur besar besaran yang sedang dilakukan seperti pembangunan jalan, jalan tol, kereta cepat massal MRT, dan sejumlah pembaruan dan perbaikan fisik untuk Asian Games 2018 lalu menunjukkan prioritas pemerintah pada saat ini, ujar Usman.
Teori kedua, menurutnya, berasal dari Vedi Hadiz, ilmuwan politik Indonesia yang mengajar di University of Melbourne di Australia, yang menyatakan bahwa 2017 merupakan tahun kemunduran demokrasi Indonesia.
“Kemunduran tersebut diakibatkan oleh dinamika pertarungan oligarki dan kaum konservatif dalam pemilihan kepala daerah yang memanfaatkan sentimen moralitas, menguatkan kecenderungan negara yang berbau idiom nasionalis yang berlebihan (hypernationalism), dan lemahnya pengorganisasian gerakan sipil. Minoritas yang mengganggu pembangunan dianggap pelaku kejahatan,” ujar Usman.
Salah satu contohnya adalah Budi Pego, seorang petani di Banyuwangi, Jawa Timur. Pada April 2017, Budi dikenakan pasal anti-komunisme karena protesnya terhadap tambang emas di daerah tersebut dianggap sebagai pergerakan komunis. Sidang peradilannya didatangi oleh massa anti-komunis yang mendukung penuntutan.
Setelah itu ada peristiwa penyerangan anti-komunis oleh sekitar 2.000 orang pada September 2017 terhadap seminar sejarah 1965 di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Seminar tersebut dianggap tidak meminta izin dari polisi dan para penyerang tidak dikenakan hukuman.
Media sosial pun ikut merasakan pengucilan terhadap kaum minoritas dengan adanya #2019TetapAntiKomunis. Komunis tetap menjadi kelompok yang dibenci Indonesia dan banyaknya pihak-pihak yang asal menuduh seseorang itu komunis tanpa bukti yang konkret dan jelas menghasilkan isu diskriminasi sistemis yang berkelanjutan.
“Sudah ada 12 orang yang dipenjarakan karena penodaan ataupun penistaan agama dan sekitar 20 orang karena mengekspresikan pandangan mereka mengenai politik dan kepercayaan secara damai,” ujar Usman.
“Retorika adu domba digunakan dalam pemilihan DKI Jakarta tahun 2017 lalu yang memecah kelompok non-muslim dan non-pribumi dengan muslim dan pribumi. Kelompok yang dianggap bukan mayoritas digolongkan sebagai anti-Islam, anti-nasionalis, radikal Islam, komunis, dan separatis. Politik diskriminasi ataupun kebencian tersebut dapat memicu jenis pelanggaran HAM baru dan berpotensi menjadi senjata pada pemilu 2019,” lanjutnya.
Menurut Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara, ada beberapa hambatan dalam menangani kasus ketidakadilan HAM. Belum adanya lembaga atau kementerian yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatasi kasus HAM terutama kasus berat HAM masa lalu merupakan faktor penting. Penanganan korban pun menjadi sulit karena pengadilan berorientasi kepada setiap kasusnya, bukan akar masalahnya.
Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar menyatakan, pelanggaran HAM terus meningkat sementara kasus pada masa lalu belum dapat terselesaikan, termasuk adanya pembatalan Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
“Kebijakan baru yang mencegah ataupun menyelesaikan kasus tersebut juga belum ada. Ketidakadilan tersebut lama kelamaan dilupakan oleh negara dan menyisakan rasa ketidakadilan bagi korban dan penurunnya baik keluarga maupun kelompok,” ujar Wahyudi.
Korban dari pelanggaran HAM yang berat sebetulnya berhak mendapatkan kompensasi dengan mengajukan permohonan bantuan yang bila disetujui hukum akan diajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun keputusan penyelesaian dari sebuah pelanggaran yang tidak kurun selesai terutama bagi kasus berat, menjadi peran penting dalam tidak berlakunya hak tersebut. Informasi yang kurang didapatkan korban atau pun saksi mengenai hak mereka pun juga menjadi faktor penting.
“Saat ini dana masih terbatas jadi tidak semua korban kami layani. Jadi kami prioritaskan yang mengalami pelanggaran HAM berat,” ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.
ELSAM merekomendasikan tiga metode pendekatan untuk mencapai penyelesaian yang menyeluruh dalam pelanggaran HAM, yakni kebijakan afirmatif yang meliputi bantuan medis yang diberikan oleh LPSK khususnya korban yang telah diselidiki Komnas HAM; kebijakan tiap daerah untuk mengakui korban mengalami pelanggaran HAM dan membantu upaya pemulihan; dan akses layanan seperti pemberian hak identitas agar korban mendapatkan layanan dasar dari negara.
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menegaskan pentingnya penerapan kebijakan afirmatif untuk melawan diskriminasi sistemis di Indonesia. Demi mencapai kesetaraan defacto bagi laki-laki maupun perempuan dan kelompok-kelompok yang kurang beruntung, beberapa penerapan khusus yang bersifat temporer diterapkan dan tidak dianggap sebagai pelanggaran atas hak non diskriminasi. Perlindungan hak perempuan demi mencapai persamaan substantif seperti akses dan manfaat yang sama juga diperlukan tindakan khusus agar mendapatkan lingkungan yang kondusif dalam pelaksanaannya. Tindakan khusus juga diperlukan untuk menjamin tujuan yang layak bagi tiap ras, suku bangsa, dan perorangan tertentu seperti jaminan kesamaan dalam menikmati kemudahan atau menggunakan hak asasi sebagai manusia dan kebebasan dasarnya.
Kebijakan afirmatif sudah mendapatkan ranah dalam undang-undang namun sering kali penerapannya belum optimal.
“Kebijakan afirmatif itu perlu untuk perlakuan khusus kelompok tertentu, jika tidak bisa jadi justru lebih lebar ketidakadilannya atau berlanjut ke diskriminasi,” ujar Wahyudi.
Angesti Citra Asih adalah reporter intern di Magdalene dan pejuang tugas akhir di Universitas Multimedia Nusantara. Kemanusiaan dan budaya pop merupakan topik perbincangan favoritnya. Dia sangat menyukai musik terutama RnB kontemporer seperti Teza Sumendra dan Honne dan hobi memainkan ukulele atau gitar.