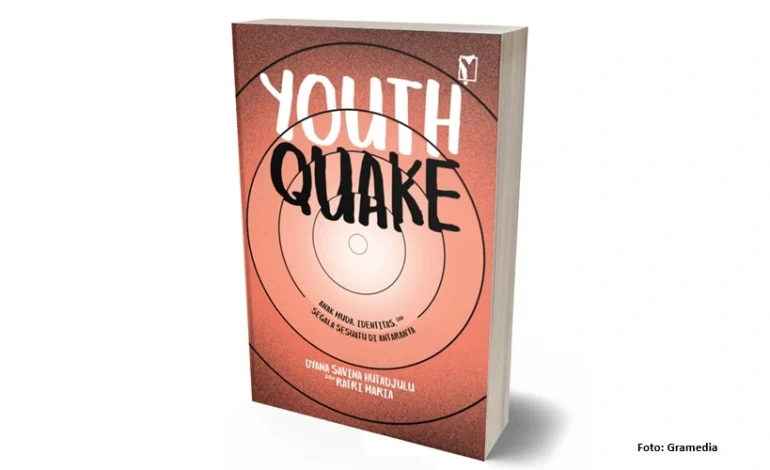#MerdekainThisEconomy: Agustus dan Tubuh Perempuan yang Merdeka Sehari

Ada satu momen yang masih membekas di kepala, dan lebih penting lagi, di hati saya. Bukan soal kerupuk apalagi balap karung. Ini tentang tubuh, tawa, dan keberanian seorang perempuan di kampung saya: Mak Diyah.
Lomba, Yel-Yel, dan Daster Merah
Waktu itu, saya pulang kampung dan bergabung dengan komunitas ibu yang pernah saya dampingi. Mereka bukan ibu-ibu biasa. Jangan bilang “ibu-ibu cuma di dapur”—dapur mereka bisa mengguncang negeri.
Lomba favorit saya: Tebak Kata. Tiap kelompok lima orang. Salah satunya langsung bikin semua orang bungkam: Kelompok Merdeka, dengan yel-yel “MERDEKA!”
Ketua kelompok? Mak Diyah.
Usianya 50-an. Tubuh besar, tampak berat. Kolesterol tinggi. Guru ngaji anak-anak di kampung kami. Selama ini dikenal “perempuan baik-baik”: Ia jarang keluar, tak suka gosip, selalu sopan. Kami selalu segan padanya.
Namun hari itu, Mak Diyah keluar rumah.
Kata rahasia pertama: ‘Burung Menari.’ Dengan daster merah longgar dan jilbab putih, dia merentang tangan seperti sayap, menggoyangkan badan, dan—iya—pinggulnya ikut goyang. Lucu. Jenaka. Mengena.
Penonton terbahak-bahak. Para bapak ikut bertepuk tangan. Mak Diyah jadi bintang. Kelompoknya menang, membawa pulang setengah lusin cangkir plastik warna-warni.
Baca Juga: #MerdekainThisEconomy: Korupsi itu Patriarkal, Pancasila itu Emansipatoris
“Aku Muak Nonton Tipi”
Saya mendekat, masih terkekeh.
“Mak Diyah, mantap kali tadi. Semua kata bisa ditebak karena gerakan yang pas. Kok bisa?”
Dia tersenyum tipis.
Lalu kalimatnya jatuh seperti palu:
“Aku muak nonton tipi di rumah. Katanya merdeka tapi kok kita dijajah terus? Presiden, menteri, DPR—omongannya nyakitin hati rakyat.”
Saya terdiam.
Hari itu tubuh Mak Diyah menari tapi yang bergerak bukan cuma tubuh. Ada kemarahan. Ada harapan. Ada kemerdekaan kecil yang lahir dari pinggul, daster merah dan tawa yang menolak dibungkam.
Tubuh yang Merdeka Sehari
Mak Diyah ingin merdeka—sehari saja cukup.
Merdeka dari kata-kata pejabat yang menyakitkan.
Merdeka dari label “perempuan baik-baik” yang membungkam tawa dan tubuh.
Merdeka dari ruang tamu yang saban hari menyuguhkan berita luka.
Tubuh perempuan, yang biasanya hanya bergerak di dalam rumah, hari itu hadir utuh di ruang publik. Bukan sekadar lomba tapi perayaan kemerdekaan versi perempuan.
Baca Juga: #MerdekainThisEconomy: Pesan untuk Putraku: Merdekalah dari Negaramu
Joget Pejabat, Gaji Puluhan Juta
Sementara itu, di Jakarta, panggung lain viral.
Anggota DPR berjoget usai Sidang Tahunan MPR. Publik marah karena aksi itu dianggap tak peka di tengah hidup yang makin mahal. Ketua MPR menyebutnya “sekadar mencairkan suasana”, menurut pemberitaan media nasional.
Bersamaan itu, tunjangan rumah anggota DPR jadi sorotan: Rp50 juta per bulan sebagai pengganti rumah jabatan. Total penghasilan disebut bisa sekitar Rp69–70 juta per bulan. Klarifikasi resmi menyebut bukan gaji pokok yang naik, melainkan tunjangan rumah. Namun tetap saja, publik misuh—angka dan momennya terasa menampar, sebagaimana ramai diberitakan.
Kontrasnya telanjang.
Yang satu menari karena akhirnya bebas dari domestik.
Yang lain menari karena kebal rasa lapar rakyat.
Baca Juga: #MerdekaInThisEconomy: 80 Tahun Merdeka, Ancaman Otoritarianisme Makin Nyata
Remisi yang Menyayat
Ada ironi lain setiap Agustus: Remisi. Secara hukum, remisi adalah hak semua narapidana yang memenuhi syarat—korupsi pun termasuk; pengecualian hanya untuk hukuman mati dan seumur hidup. Dasarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10.
Tahun ini pemerintah menyebut ratusan ribu warga binaan menerima remisi HUT RI, baik remisi umum maupun remisi dasawarsa (kebetulan 2025 juga siklus sepuluh tahunan). Secara prosedural ini “benar”, tetapi pemberitaan menyoroti betapa publik melihat remisi koruptor menggores rasa keadilan.
Peneliti antikorupsi menilai remisi bagi koruptor justru mengaburkan efek jera, apalagi ketika diumumkan bertepatan dengan Kari kemerdekaan.
Kasus yang paling menyayat perasaan: Setya Novanto. Dirjen Pemasyarakatan mengungkap Setnov menerima remisi 28 bulan 15 hari sebelum bebas bersyarat pada 16 Agustus 2025. Secara aturan mungkin rapi. Namun secara rasa, publik memandangnya sebagai “kado kemerdekaan” yang pahit, sebagaimana ramai dilaporkan media.
Negara berkata, “remisi adalah hak.”
Rakyat menjawab, “lalu kapan giliran keadilan jadi hak kami?”
Hoaks yang Tetap Menyakiti
Di tengah amarah itu, beredar pula video “Menteri Keuangan bilang guru beban negara.” Belakangan terbukti hoaks, hasil manipulasi digital, sebagaimana ditegaskan pemerintah dan diberitakan luas.
Namun perdebatan soal gaji guru tetap menyisakan luka. Cara bertanya pejabat pun dikritik. Rakyat sudah terlalu sering merasa diremehkan. Kalimat bohong boleh dibantah, tapi rasa sakit hati tidak bisa segera hilang.
Guru-guru tetap teringat, betapa kontribusi mereka sering dianggap biaya, bukan investasi. Dan di bulan kemerdekaan, luka semacam itu terasa makin pedih.
Membaca Merdeka dari Tubuh
Feminis Simone de Beauvoir menulis, “Seseorang tidak dilahirkan sebagai perempuan, melainkan menjadi perempuan.” Di kampung, “menjadi perempuan” sering berarti selesai di dapur.
Sampai suatu hari Agustus memberi celah: Panggung reyot, musik dangdut, pengeras suara serak, tawa yang pecah, dan tubuh perempuan yang akhirnya berani menari—tanpa celaan.
Di Senayan, “menjadi wakil rakyat” entah kenapa sering berarti menjadi kebal rasa—joget di panggung megah, tunjangan melangit, remisi yang melunak, sementara rakyat menghitung receh.
Baca Juga: #MerdekainThisEconomy: 5 Bukti Perempuan Pekerja Belum Benar-benar Merdeka
Penutup
Maka saya bertanya:
Kepada siapa kemerdekaan ini diberikan?
Kepada Mak Diyah yang menari sehari, pulang dengan cangkir plastik?
Atau kepada pejabat yang menari saban waktu, pulang dengan puluhan juta, dan koruptor dapat remisi?
Apakah perempuan harus menunggu Agustus untuk merdeka?
Apa gunanya bendera dan pidato, jika merdeka hanya milik mereka yang sudah kenyang?
Mungkin kemerdekaan sejati justru ada di panggung reyot di kampung, ketika daster merah Mak Diyah bergoyang. Karena di sana, tubuh perempuan akhirnya merdeka—walau hanya sehari.
Sehari itu, lebih jujur daripada seribu pidato pejabat.
Lely adalah fasilitator pemberdayaan perempuan, pendiri HAPSARI dan Rumah Kata. Ashoka Fellow (2000), serta penulis yang percaya bahwa cerita adalah alat perubahan.