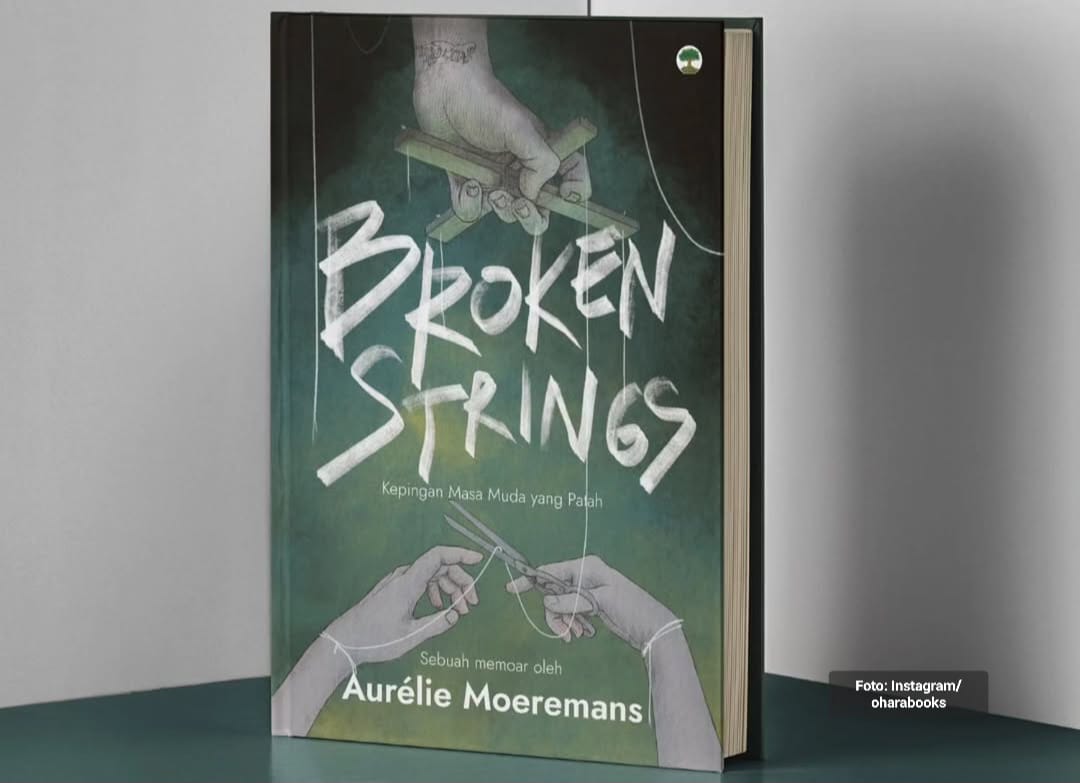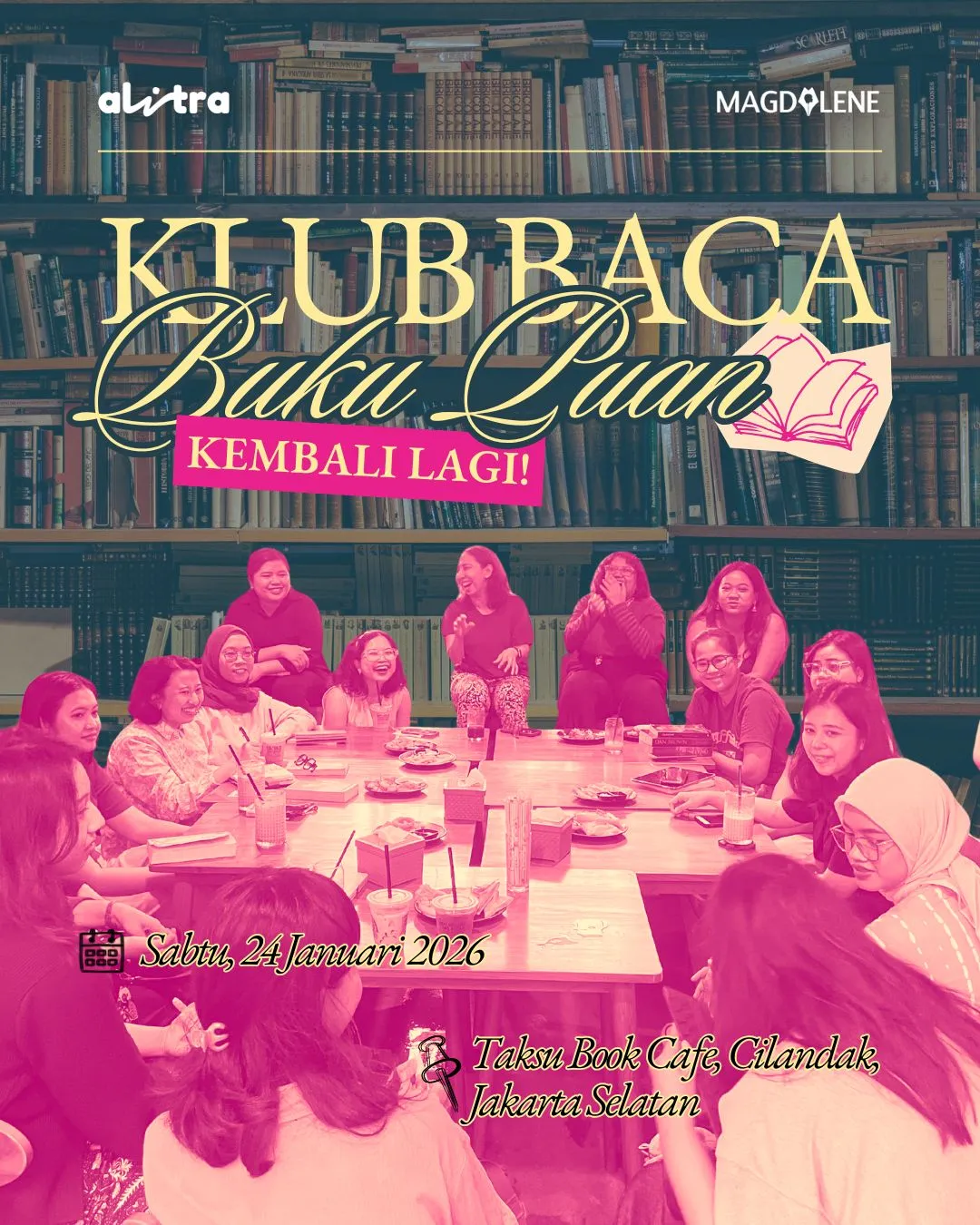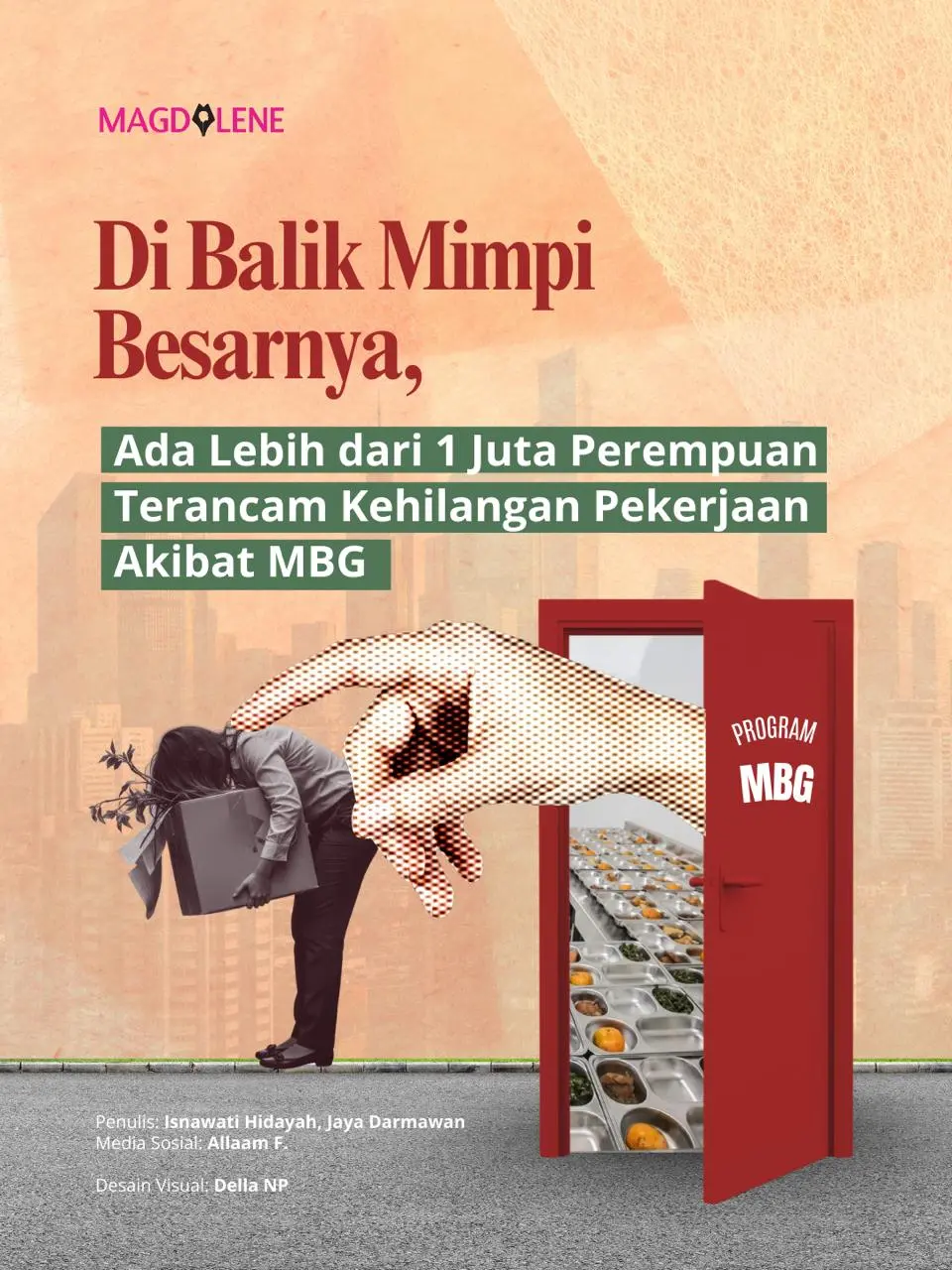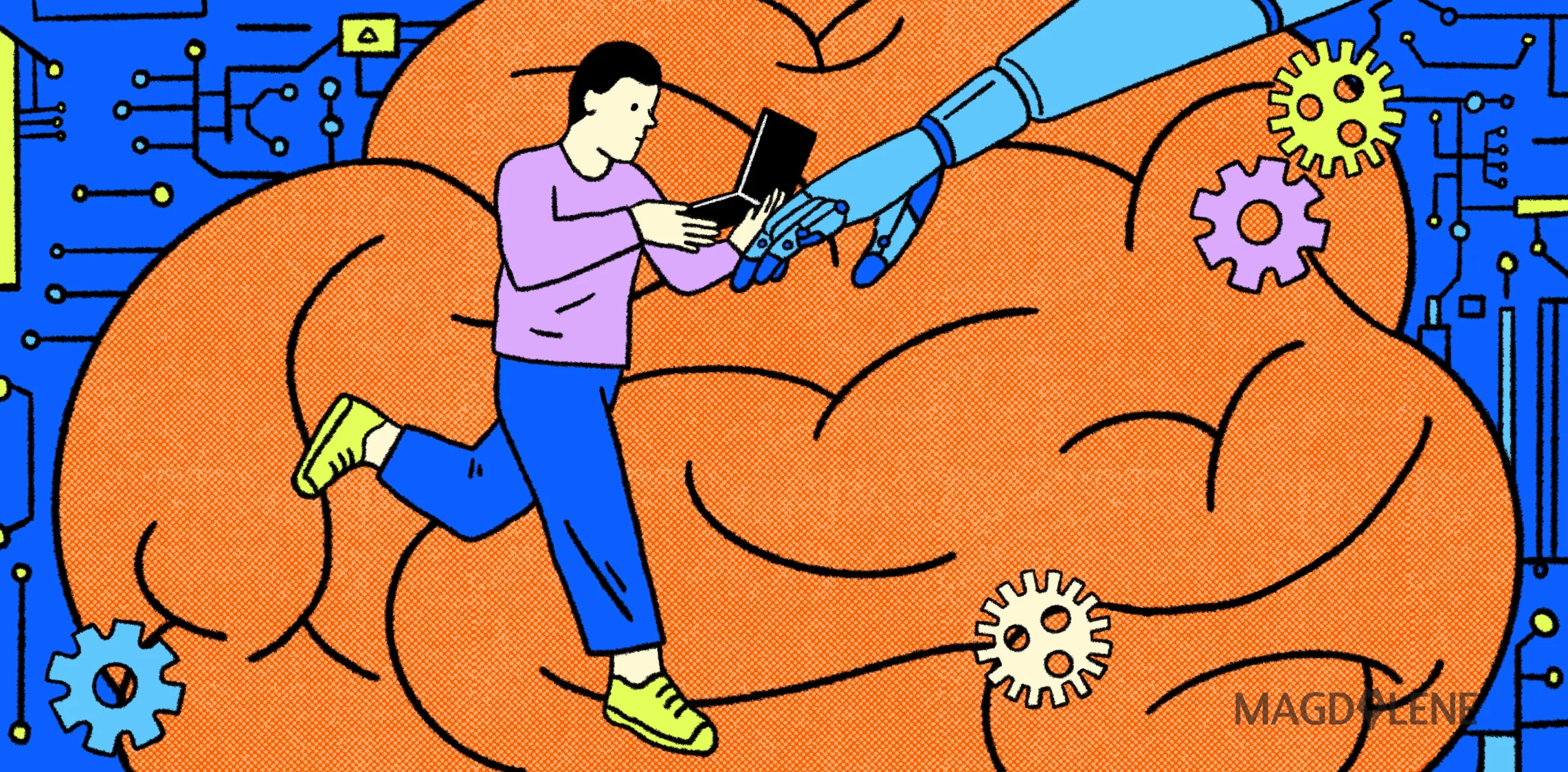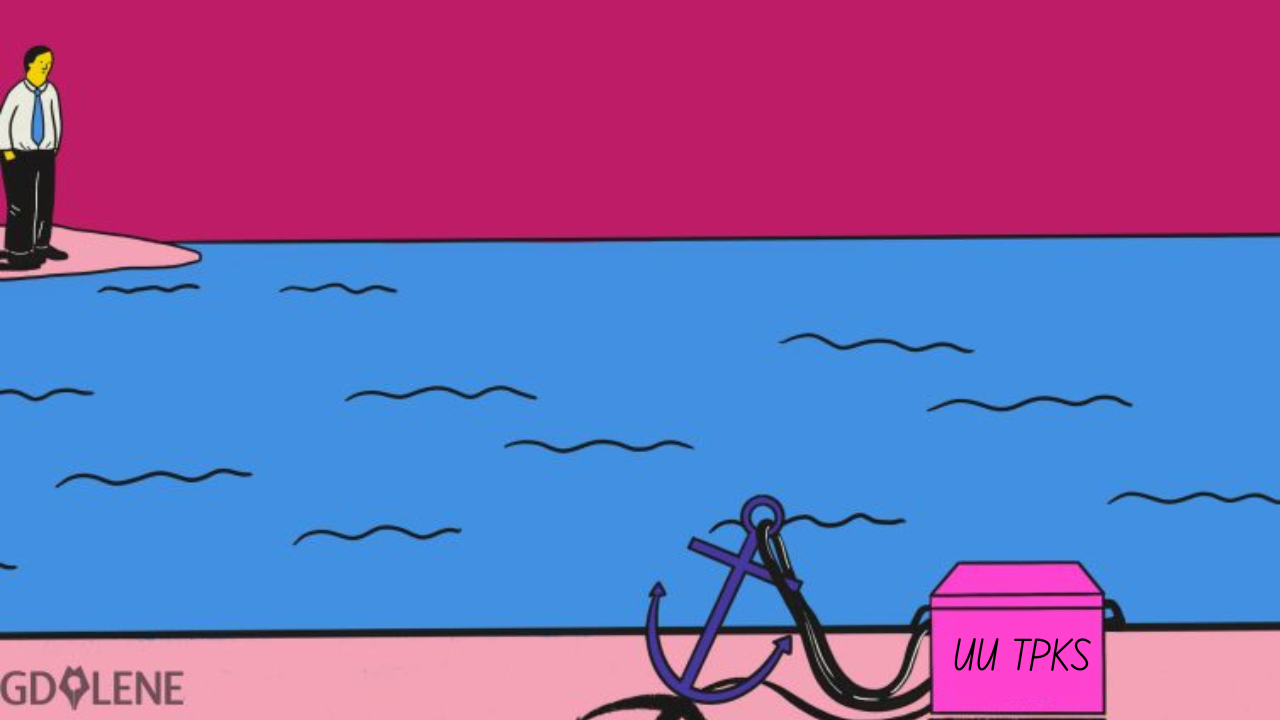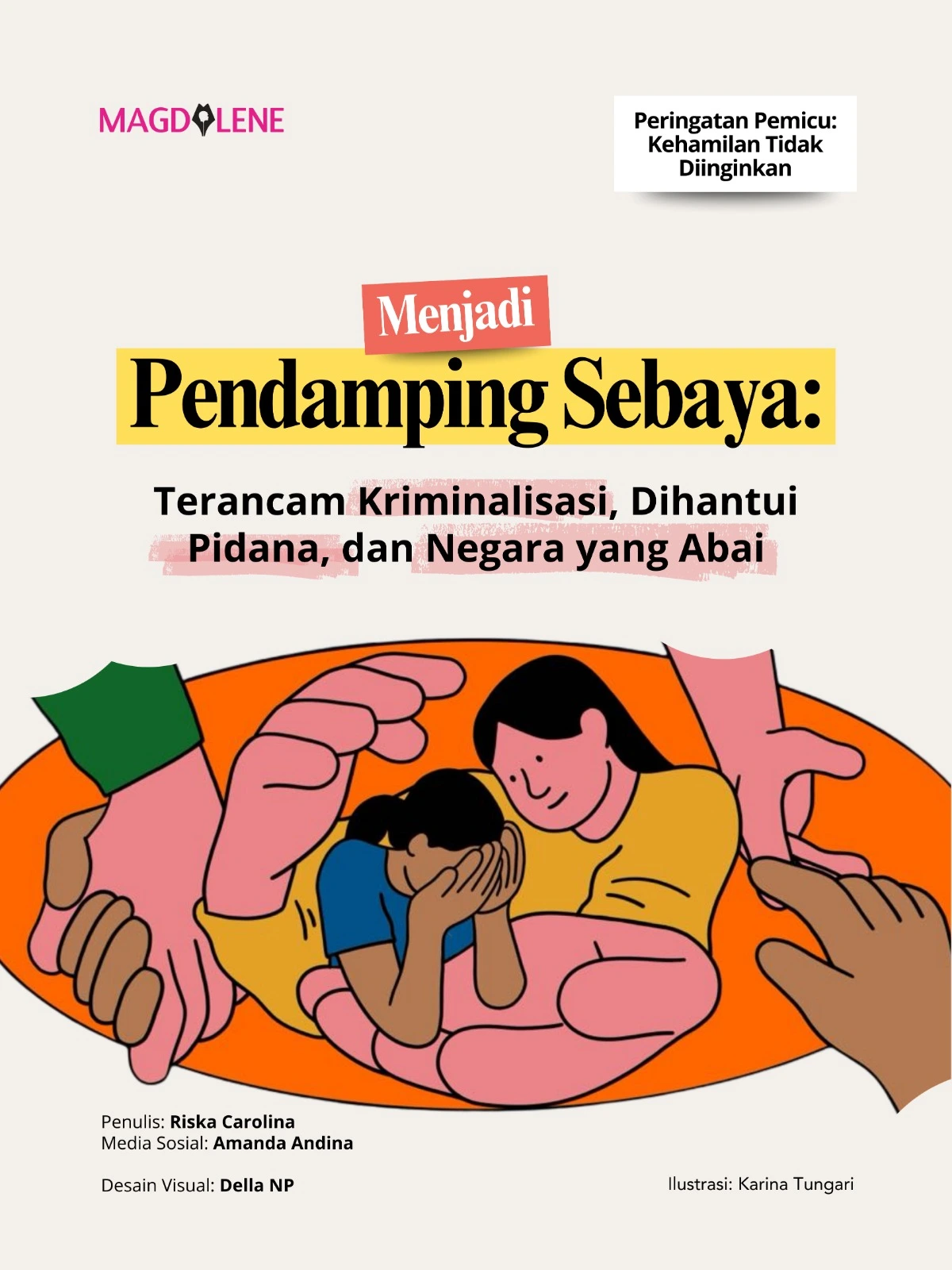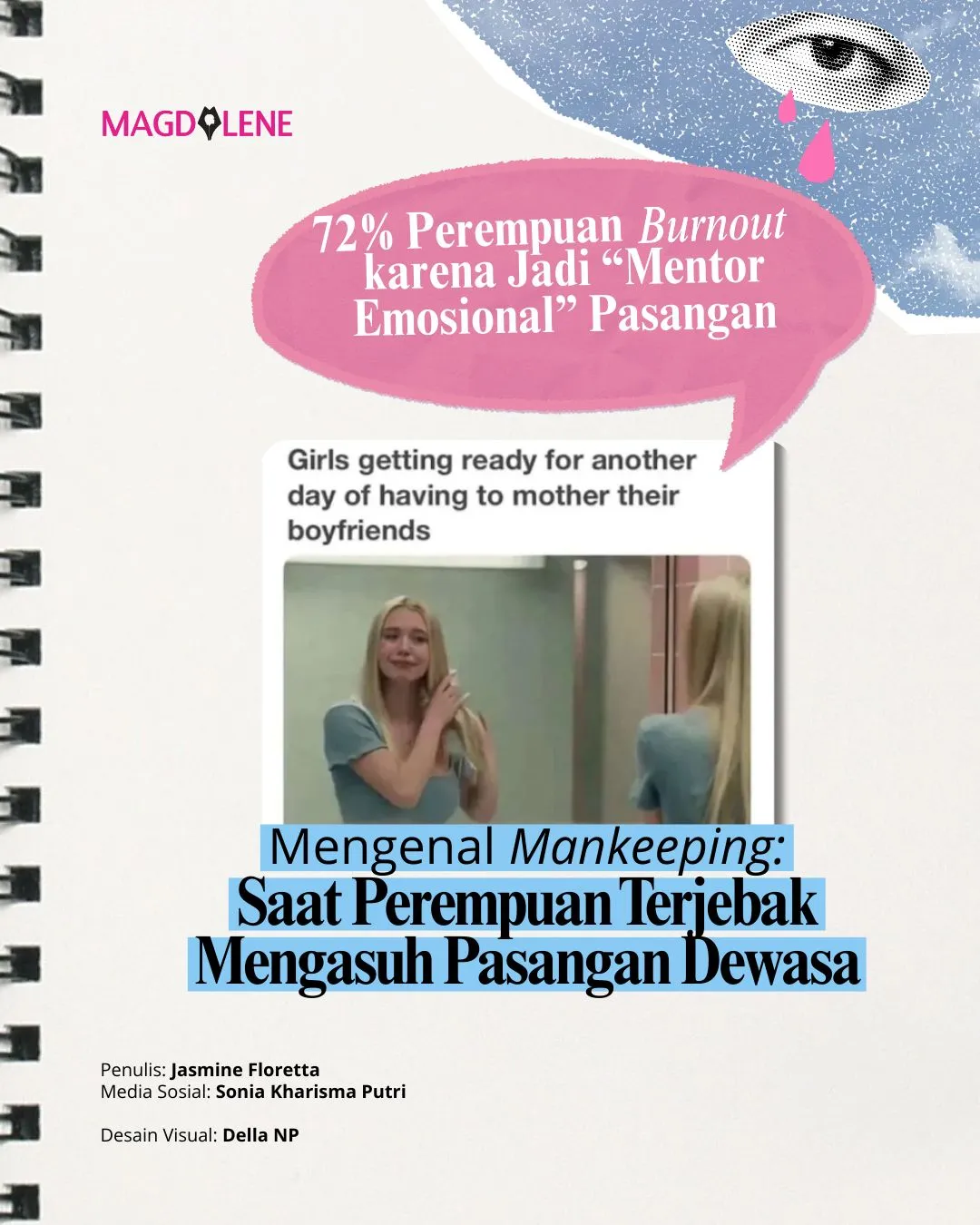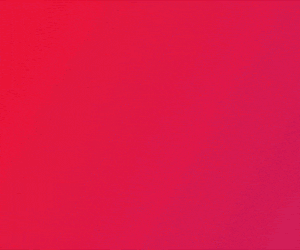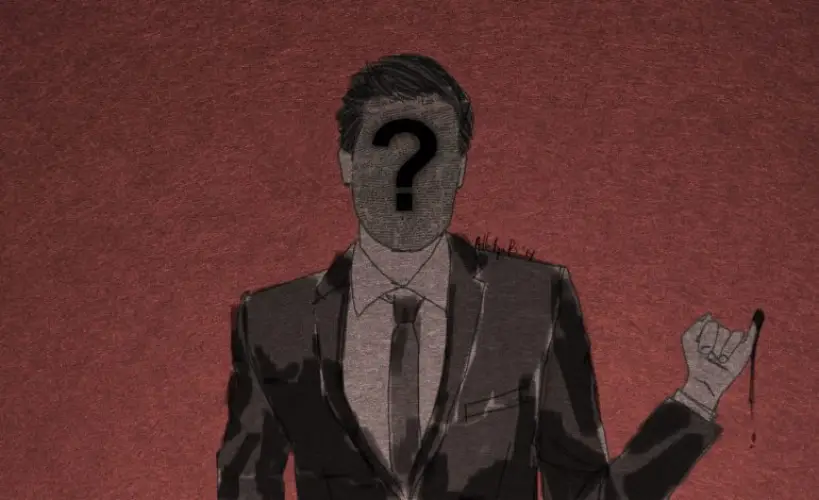Krisis Air dan Sanitasi Buruk, Perempuan dan Kelompok Disabilitas Penting Dilibatkan

Pemerintah jarang melibatkan perempuan dan orang dengan disabilitas dalam menangani permasalahan Water, Sanitation, and Hygiene (WASH). Hal itu diungkapkan pekerja sosial Yayasan Plan International Indonesia Herning Tyas Ekaristi, dalam konferensi pers yang diselenggarakan ABC International Development, (19/5), di Seminyak, Bali.
Padahal, kelompok minoritas inilah yang paling terdampak krisis air—termasuk yang disebabkan oleh bencana. Misalnya pada 2021, saat Badai Seroja melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Waktu itu, terjadi intensitas hujan ekstrem, angin kencang, hingga tanah longsor yang dipicu oleh siklon tropis Seroja. Atau banjir besar di Bima, NTT pada 2016, yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik, lahan pertanian, dan hewan ternak.
Dua peristiwa tersebut hanyalah segelintir dari berbagai bencana di NTT dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut Water for Women, kedua provinsi ini sangat rentan terhadap perubahan iklim: Banjir, tanah longsor, kenaikan suhu dan permukaan air laut, angin topan, serta kekeringan. Ini mengakibatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi terhambat, seperti masyarakat yang tidak dapat menggunakan jamban.
Baca Juga: Ketidakadilan Gender Dapat Bermula dari Toilet
Pada akhirnya, yang terdampak adalah perempuan, anak-anak, dan kelompok disabilitas: Perempuan akan sulit menjaga kebersihan menstruasi dan reproduksi. Anak-anak ikut berupaya memenuhi kebutuhan air dengan berjalan kaki berkilo-kilo meter. Dan orang dengan disabilitas yang terhambat mengakses sanitasi dan fasilitas air.
Sebagai salah satu solusi, warga membeli air demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena mengandalkan subsidi air dari pemerintah saja tak cukup. Di sisi lain, cara ini justru semakin membebankan ekonomi.
Melansir Kumparan, pada 2020 warga Kupang mengeluarkan uang sebanyak Rp60 ribu hingga Rp70 ribu setiap satu sampai dua minggu, untuk membeli air dalam tangki berukuran lima ribu liter. Kondisi ini menggambarkan, krisis iklim semakin merentankan masyarakat. Terutama dari kelas sosial menengah ke bawah, perempuan, dan orang dengan disabilitas. Karena itu, kebijakan pemerintah perlu mencakup aksesibilitas sanitasi dan air bersih, bagi kelompok minoritas.
Baca Juga: Sejarah Toilet: Bias Kelas dan Ketidakadilan Gender

Mendorong Fasilitas Publik yang Inklusif
Berdasarkan data Yayasan Plan International Indonesia, secara keseluruhan terdapat 25 desa di Manggarai, NTT dan Sumbawa, NTB, yang mengalokasikan anggaran dana desa untuk program kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI). Dana itu digunakan untuk merenovasi toilet inklusif, reboisasi mata air, pemasangan hand railing di toilet kantor lurah, puskesmas, dan sekolah. Kemudian perbaikan lantai dan jalan menuju toilet, serta pelatihan dan penguatan penyandang disabilitas.
Novika Noerdiyanti, Water for Women Project Manager dari Yayasan Plan International Indonesia mengatakan, kesadaran akan pentingnya pentingnya GEDSI dilatarbelakangi oleh keterlibatan kelompok disabilitas dalam berbagai kegiatan desa. Dari situ pemerintah desa melihat, mereka membutuhkan dukungan supaya dapat mengakses fasilitas sanitasi. Alhasil, sampai saat ini terdapat 16 desa, yang merenovasi toilet di kantor desa.
Namun, masih ada desa yang belum memprioritaskan program GEDSI, karena fokus pada pembangunan infrastruktur. “Masalahnya ya itu, masuk ke prioritas desa atau enggak. Jadi kami dorong supaya isu GEDSI diprioritaskan,” terang Novika pada Magdalene.
Lain halnya dengan ketersediaan pembalut yang kerap dikesampingkan, termasuk dalam situasi bencana. Awalnya, siswa perempuan memilih pulang ke rumah atau pergi ke warung saat sedang menstruasi, untuk mendapatkan pembalut. Namun, kini sekolah menyuplai dan turut disosialisasikan oleh peer educator.
“Peer educator ini termasuk siswa laki-laki,” tutur Tyas. “Mereka membicarakan manajemen kebersihan dan menstruasi, supaya siswa perempuan nyaman di sekolah ketika sedang menstruasi.”
Baca Juga: Period Poverty dan Maraknya Pembalut Reject
Perlunya Kepemimpinan Transformatif
Situasi serupa terjadi di Nepal, yang wilayahnya pegunungan. Kondisi ini merupakan tantangan dalam pembangunan toilet agar bisa diakses oleh siapa pun, termasuk orang dengan disabilitas. Terlebih karena infrastruktur lainnya masih kurang memadai.
Di samping itu, perihal kasta, gender, dan perempuan yang cenderung memisahkan diri saat menstruasi, menjadi hambatan lain. Karenanya, GEDSI Advisor International Water Management (IWMI) Darshan Karki menyebutkan, ketersediaan infrastruktur bukan berarti mengarah pada penerimaan dan penggunaan fasilitas secara otomatis.
Sementara di Bhutan, baru membebaskan perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada 2022. Sebelumnya, akses sanitasi yang baik tergolong baik hanya 50 persen. Dan tak semua rumah memiliki toilet, sehingga warga menggunakan jamban bersama yang juga belum tentu higienis. Belum lagi ketergantungan warga pada mata air, sedangkan BABS dapat mencemari air.
Dalam pembangunan toiletnya, Gender Officer SNV Bhutan, Jigme Choden mengatakan, perlu dipastikan tidak membahayakan pengguna—terutama ibu dan anak. Ini dikarenakan struktur tanah di area pedesaan yang berlumpur. Aspek tersebut awalnya tak cukup diperhatikan saat membangun toilet. Padahal menghambat aksesibilitas perempuan, anak, lansia, dan orang dengan disabilitas.
Karena itu, para pemimpin dan komunitas—termasuk SNV—menghadiri workshop tentang kepemimpinan transformatif, dengan pembahasan seputar GEDSI. Dalam pembuatan kebijakan pun, SNV Bhutan bekerja sama dengan berbagai stakeholder. Di antaranya pemimpin lokal, asisten tenaga kesehatan, insinyur, dan member komunitas.
“Butuh usaha besar dari pemimpin dalam mengimplementasikan kebijakan,” ujar Choden dalam konferensi pers yang sama. “Makanya pemimpin itu bukan sekadar jabatan yang berkuasa, tapi orang yang memahami bahwa permasalahan perlu disampaikan.”
Choden menggarisbawahi, keberhasilan Bhutan mengatasi BABS didukung oleh kepemimpinan transformatif, yang bekerja sama dengan individu dari berbagai area dalam menciptakan perubahan.
Sedangkan menurut Novika, untuk membuat perubahan di sektor WASH, dapat dimulai dari individu. Contohnya dengan mengampanyekan pentingnya WASH, seperti dilakukan oleh peer educator Yayasan Plan International Indonesia. Kemudian, dibutuhkan komitmen pembuat kebijakan, untuk memberikan dampak lebih besar dan pembuatan program. Diikuti komunitas, yang dapat menyosialisasikan permasalahan ini lewat platform apa pun, secara lebih luas.