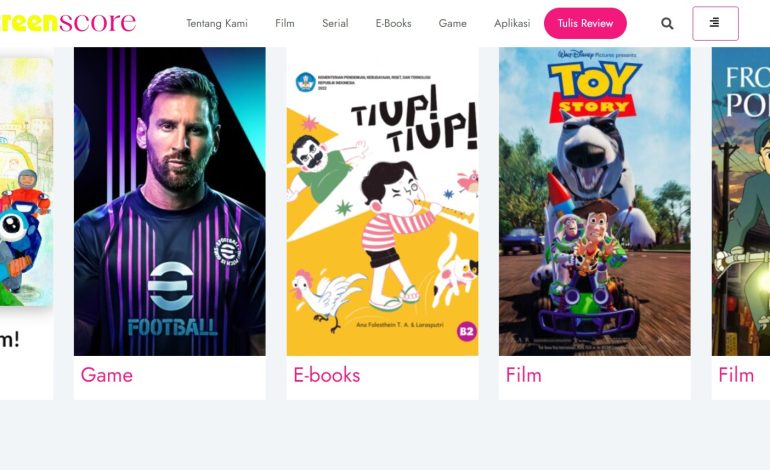#BasaBasiReformasiPolri: Ambisi Polisi Jadi Lembaga ‘Superbody’

Di tengah transisi estafet kekuasaan Jokowi ke Prabowo Subianto, DPR mendadak menginisiasi Rancangan Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri) Nomor 2 Tahun 2002. Dalam Rapat Paripurna DPR, (28/5) dikatakan, UU ini perlu perbaikan karena lembaga lain seperti Kejaksaan, telah lebih dulu mengalami perubahan aturan.
Revisi RUU Polri diharapkan juga mampu memenuhi agenda reformasi kepolisian, yang sudah digulirkan pada 2000. Sejak saat itu, wacana membuat Polri jadi institusi yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat, terus digaungkan. Asa reformasi ini juga dipengaruhi tingginya kepercayaan publik pada Polri, yang kala itu baru dilepas dari ABRI guna mengawal Reformasi 1998.
Sayangnya, Polri gagal menjawab ekspektasi publik. Hal ini terbukti dari rendahnya tingkat kepercayaan publik pada lembaga tersebut. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2023 menempatkan Polri sebagai institusi paling tak dipercaya, dengan angka 64 persen. Dalam urusan pemberantasan korupsi pun, kepolisian menduduki urutan buncit sebesar 61 persen.
Menurut Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andi Muhammad Rezaldy, ada tiga faktor yang membuat kepercayaan publik pada Polri ambles. Di antaranya, kultur kekerasan dan militerisme yang sudah mendarah daging; minimnya pengawasan pro justicia (demi hukum) pada kepolisian; dan tendensi persaingan antarlembaga, terutama TNI yang jadi “sepupunya”.
Alih-alih menyelesaikan persoalan, menumbuhkan kepercayaan publik, dan mereformasi kepolisian, pemerintah justru menyisipkan pasal problematis dalam RUU Polri. “Ke depannya, situasi kebebasan sipil tentu bakal menyempit, kritik dibungkam dengan ancaman pidana, bersuara di media sosial dihadang UU ITE, demonstrasi juga direpresi polisi,” ujarnya dalam diskusi “RUU Polri Melenggang, Impunitas Melanggeng”, (3/7).
Baca juga: Kekerasan Polisi: Slogan Melindungi, Mengayomi, Melayani Cuma di Atas Kertas?
Reformasi Polri yang Seharusnya
Dilansir dari buku “Democratic Policing” (2017) karya Tito Karnavian dan Hermawan Sulistyo, reformasi Polri muncul sejak pengesahan TAP MPR Nomor VI tentang pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri. Ketetapan ini diikuti dengan pembentukan UU Polri yang memberikan Polri tiga tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas-tugas ini mengharuskan Polri mendekatkan diri pada masyarakat. Ide ini sendiri terinspirasi dari gagasan kepolisian negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.
Tak cukup sampai di situ saja. Tim Litbang Kompas menguraikan, reformasi Polri, baik instrumental, struktural, maupun kultural terus dicita-citakan di tiap suksesi Kapolri dengan berbagai format kebijakan. Hanya saja di tiap periode, Polri selalu kesulitan membangun pendekatan dengan masyarakat agar lebih disegani dan dicintai. Di awal Reformasi 1998, reformasi Polri terganjal rentetan pelanggaran HAM yang harus dibereskan, seperti pembunuhan jurnalis Bernas Udin hingga kasus Marsinah. Reformasi Polri di masa itu juga diwarnai berbagai konflik kepentingan kelompok elit.
Meski terseok-seok, pejabat Kapolri dari saat itu hingga kini terus berusaha mendekatkan diri pada masyarakat. Mulai dari pembaruan perilaku dan etika di lembaga kepolisian, di era Kapolri Sutanto pada 2005. Lalu di era Timur Pradopo, Sutarman, dan Badrodin Haiti, catat Kompas, polisi berbenah dengan pemberian akses informasi kepada publik yang lebih transparan terkait penanganan perkara. Di era Sutarman, ditugaskan satu polisi dan satu anggota Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) dalam satu desa. Pun, di era Tito Karnavian dan Idham Aziz, masyarakat juga dilibatkan aktif dalam agenda kepolisian.
Meski begitu, upaya mereka tak cukup “mendobrak”. Bahkan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan oknum kepolisian tetap terjadi hingga sekarang. Di mana-mana kita cenderung mudah menemukan kultur polisi lawas yang arogan dan represif. Yang terbaru kita menyaksikan represi yang berujung pada kematian anak Afif Maulana oleh 17 polisi di Sumatra Barat. Setahun sebelumnya, pada 2022, kekerasan polisi juga tampak di Stadion Kanjuruhan, Malang yang memakan korban hingga 135 orang. Sementara pada 2021, kekerasan di mana oknum Polri membanting demonstran mahasiswa dalam aksi massa di Tangerang juga tersorot media.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (selanjutnya disebut Koalisi Masyarakat Sipil. Red) dalam rilis resminya, (2/6), mengutip dokumentasi KontraS dari 2020-2024 tentang praktik kekerasan yang melibatkan Polri. Sepanjang Juli 2020-Juni 2021, setidaknya terdapat 651 kasus kekerasan polisi. Juli 2021-Juni 2022 mengalami peningkatan hingga 677 kasus. Juli 2022-Juni 2023 mencapai 622 kasus. Lalu, sepanjang Januari-April 2024, telah terjadi 198 peristiwa kekerasan yang melibatkan kepolisian.
Adapun kategori pelanggaran kepolisian berupa penembakan, penganiayaan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, pembubaran paksa, tindakan tidak manusiawi, penculikan, pembunuhan, penembakan gas air mata, water cannon, salah tangkap, intimidasi, bentrokan, kejahatan seksual, kriminalitas, hingga extrajudicial killing.
Karena rekam jejak itulah, Koalisi Masyarakat Sipil melabeli Polri sebagai “aktor pemegang monopoli” kekerasan, pelanggaran HAM, maladministrasi, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), hingga praktik-praktik korupsi.
Jika RUU Polri disahkan, kepolisian semakin potensial dijadikan alat politik untuk memfasilitasi kejahatan penguasa negara. Bahkan menjelma alat kekerasan untuk menciptakan ketakutan di tengah masyarakat guna melanggengkan kekuasaan. Yang tak kalah membahayakan, RUU Polri secara simultan juga dapat memfasilitasi kebangkitan dwi fungsi ABRI dalam tubuh kepolisian, komentar Koalisi Masyarakat Sipil.
Baca Juga: Tingkah Laku Polri-TNI: Dari Flexing sampai Narsistik
RUU Polri Ingkari Asa Reformasi
Sejumlah pakar sepakat, RUU Polri tak ada hubungannya dengan cita-cita reformasi kepolisian. Bahkan RUU Polri dinilai sarat dengan kepentingan politik aktor-aktor tertentu.
Pakar hukum tata negara yang juga Dosen STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti bilang, “Kita berdiri di atas premis bahwa Polri butuh reformasi, tapi UU Polri tak ada kaitannya dengan premis itu.”
Kenapa demikian? Sebab, ditemukan sejumlah indikasi dalam RUU Polri di mana Polri justru fokus menambah wewenang dan kekuatan, alih-alih berorientasi pada kepentingan publik. Celakanya, penambahan wewenang itu tak dibarengi dengan pengaturan yang ketat tentang mekanisme pengawasan pro justicia seperti disinggung di awal tulisan.
Muhammad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menuturkan kepada Magdalene, (3/7), polisi punya ego sektoral sehingga terlibat dalam kompetisi kewenangan dan anggaran dengan lembaga lain.
“Begitu kewenangan Kejaksaan diperkuat oleh DPR, Polri sebagai pihak yang me-lead urusan hukum pidana, ingin nambah (kekuasaan) juga gitu. Mereka ingin ada perluasan kewenangan hingga jadi superbody,” ujarnya.
Lebih lanjut, dalam rilis Koalisi Masyarakat Sipil dijelaskan sembilan alasan kenapa RUU Polri ini berpotensi membuat kepolisian jadi superbody dan berbahaya untuk masyarakat.
Pertama, RUU Polri berpotensi memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak untuk memperoleh informasi; serta hak warga negara atas privasi terutama yang dinikmati di media sosial dan ruang digital. Hal ini tertuang dalam Pasal 16 Ayat 1 Huruf (q) RUU Polri yang membolehkan Polri melakukan pengamanan, pembinaan, dan pengawasan terhadap ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri.
“Ini berarti Polri bisa semaunya sendiri, karena definisi keamanan dalam negeri ini subjektif, sehingga berpotensi ada penyalahgunaan wewenang. Karena mekanismenya sesederhana Polri cukup berkoordinasi saja, maka pasal ini akan semakin menargetkan kelompok masyarakat yang kritis atas kebijakan pemerintah,” ungkap Andi dalam diskusi, (3/7).
Kedua, dalam Pasal 16A, Polri bakal memperluas kewenangan Intelkam melampaui lembaga lain yang mengurus soal intelijen. Di Pasal 16B dipertegas lagi, di mana Intelkam boleh melakukan penangkalan dan pencegahan terhadap kegiatan tertentu guna mengamankan kepentingan nasional, termasuk memeriksa aliran dana dan data dari lembaga kementerian lainnya. Selain berpotensi tumpang tindih dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), definisi “kepentingan nasional” lagi-lagi tak jelas tafsirnya.
Menurut Bivitri, frasa seperti kepentingan nasional, keamanan dalam negeri merupakan contoh newspeak yang pernah dilontarkan George Orwell dalam novel 1984. Istilah ini menyiratkan ada kepentingan politik di dalamnya, ujar Bibip dalam diskusi serupa.
Ketiga, Polri berhak melakukan penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf o. Selain membahayakan privasi rakyat macam kita, kewenangan ini juga bertentangan dengan UU KPK. Dalam UU KPK diatur, penyadapan cuma bisa dilakukan usai mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK. Sebaliknya, dalam RUU Polri, anggota bebas menyadap tanpa izin.
“Memang penyadapan perlu dilakukan dalam konteks penegakan hukum. Akan tetapi kita tak punya UU khusus yang mengatur soal penyadapan ini. Jika RUU Polri disahkan, lalu merujuk pada peraturan mana. Nanti Polri akan subjektif seenaknya melakukan penyadapan tanpa pengaturan jelas,” ucap Andi lagi.
Baca Juga: Mau Jadi PNS atau Pasangan Tentara/Polisi? Pikir Lagi Baik–baik
Keempat, Polri berpotensi menjadi superbody investigator. Ini terkait dengan wewenang pengawasan dan pembinaan teknis kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan penyidik lainnya termasuk penyidik KPK, seperti diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 (g) RUU Polri. Polri bahkan bisa mengintervensi pengangkatan untuk penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lain yang ditetapkan oleh UU sebelum diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam rilis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian disebutkan, hal ini bertentangan dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), yang proses pembahasannya masih menggantung sejak 2014 dan memengaruhi independensi penyidik.
Kelima, RUU Polri memberi wewenang polisi untuk membina Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa. Sebagai informasi, lembaga ini merupakan inisiatif untuk membekali masyarakat dengan kekuasaan pengamanan yang notabene punya rekam sejarah kelam di 1998, termasuk pelanggaran HAM dan jual beli “bisnis keamanan”.
Keenam, RUU Polri menaikkan batas usia pensiun menjadi 60-62 tahun bagi anggota dan 65 tahun bagi pejabat fungsional Polri, tanpa urgensi jelas. Hal ini dikhawatirkan berpengaruh pada proses regenerasi dalam internal Polri. Ketentuan ini juga harus dilihat secara sistematis dan menyeluruh berkaitan dengan pengesahan RUU ASN maupun RUU Kementerian Negara yang diduga bakal memberikan legalisasi praktik “dwifungsi ABRI”.
Ketujuh, tumpang tindih kewenangan di Pasal 14 ayat 1 huruf (e) dan Pasal 14 ayat 2 huruf (c). Misalnya terkait kewenangan pembinaan hukum nasional yang tumpang tindih dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Demikian juga menyelenggarakan sistem kota cerdas (smart city).
Kedelapan, tak diatur tegas mekanisme pengawasan (oversight) bagi institusi Polri dan anggotanya. Tak seperti di Inggris misalnya, mayoritas anggota kepolisian di Indonesia yang melanggar hukum, kata Andi, cuma akan diproses secara etik. Padahal di Indonesia ada berbagai lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman, Profesi dan Pengamanan Kepolisian (Propam), hingga Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). “Ini berarti cuma akan mempertebal impunitas kepolisian saja,” tuturnya.
Kesembilan, pembahasan revisi RUU Polri tampak buru-buru dan mengabaikan partisipasi publik. Terkait ini, Bibip angkat suara dalam diskusi (3/7). Idealnya jika mengikuti UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, RUU Polri tak bisa dibahas sekarang.
“Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dikatakan, proses penyusunan UU harus dimulai dari perencanaan sampai pengundangan. Sementara kita tahu, RUU Polri menyela di ujung rezim Jokowi atau di masa lame duck. Seperti halnya UU Mahkamah Konstitusi, juga UU Kementerian negara, UU TNI, dan UU Penyiaran (meski sekarang pembahasannya ditunda),” kata Bibip.
Intinya, imbuhnya, UU Polri dan semua UU tersebut sengaja didesain untuk meminimkan pengawasan kekuasaan terhadap lembaga negara. “Proses legislasi ini sudah dimanipulasi sedemikian rupa. Saya pernah berdebat dengan DPR, kalian enggak bisa bikin kebijakan yg berpengaruh signifikan terhadap ketatanegaraan di masa lame duck, tapi malah di-gaslight menyebut saya melarang mereka bekerja. Padahal kan prosedur legislasi sudah jelas tertuang dalam UU. Dalam hal ini, RUU Polri tak pernah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas,” lanjutnya.
Berbagai hal inilah yang membuat publik perlu menolak draf RUU Polri saat ini. “Kita harusnya mendorong ada titik nol kepolisian, artinya reformasi yang benar-benar menyeluruh. Polri tak bisa dibiarkan memperluas wewenang tanpa ada pengawasan tanpa ada penyeimbang,” tutup Bibip.
Dalam rangka HUT Bhayangkara, Magdalene merilis series liputan bertajuk #BasaBasiReformasiPolri yang akan tayang sepanjang Juli 2024.