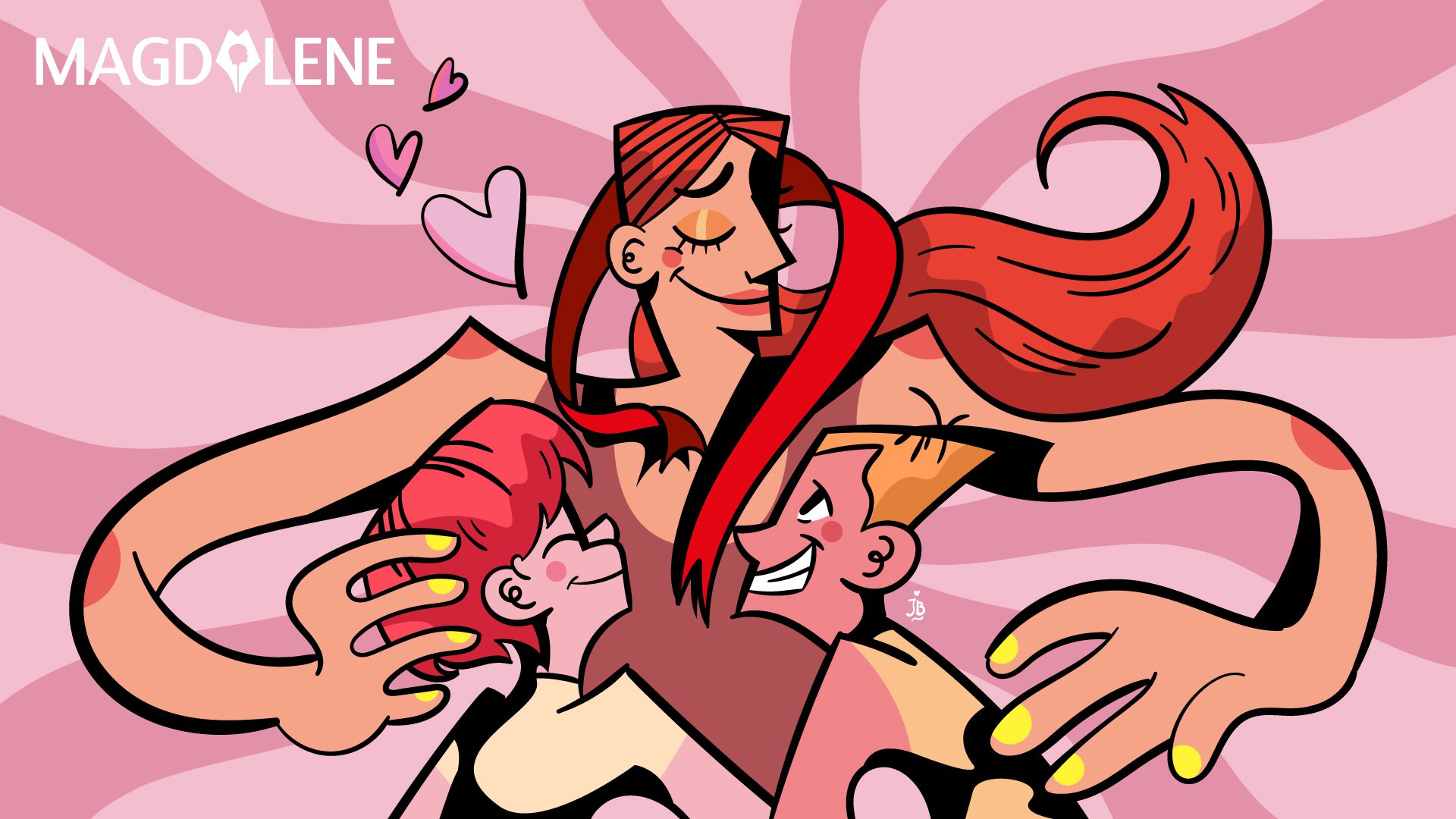Perempuan dalam Perisakan: Pertarungan Panjang Seorang Diri
Perempuan rentan menghadapi perisakan, namun sering kali pelaku dan masyarakat menganggap tragedi itu sebagai candaan.

Saya tidak percaya bahwa perisakan bisa berhenti hanya dengan cara didiamkan. Beberapa dari kita percaya bahwa salah satu bentuk kedewasaan adalah dengan cara mengabaikan segala bentuk perisakan yang ditujukan kepada kita. Ya, kita memang tidak boleh hidup dalam dendam. Kita harus melangkahi kejadian itu sebagai simbol pencerahan dan berkembangnya akal pikiran. Tetapi kita tidak boleh melupakannya begitu saja. Kita harus bicara dengan lantang tentang ini, bukan untuk meluapkan amarah, tapi untuk menghentikan pelaku mencari korban yang baru dan menumbuhkan kesadaran bersama.
Saya pertama kali menjadi korban perisakan ketika saya berusia delapan tahun. Hal itu bukan berawal dari perisakan personal disebabkan rasa iri atau rasialis dan fasis yang dilakukan dengan sengaja sebagaimana sering terjadi pada remaja dan dewasa, tetapi merupakan dampak dari lambatnya reaksi sistem terhadap ciri-ciri dan isu perisakan, atau bahkan murni akibat kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pengertian perisakan itu sendiri.
Saya yakin anak kecil tidak memelihara rasa benci dengan sadar sebagaimana orang dewasa mampu untuk memilih membenci atau tidak. Ketika itu, kami hanya bergerak sejauh mana kami melihat dan mendengar, dan mayoritas kita tumbuh dengan meneladani budaya patriarki dalam aktivitas sehari-hari, di mana sangat mudah bagi laki-laki untuk dimaafkan dan semua titik mati langkah perempuan adalah dipermalukan. Rangkaian kejadian perisakan ini bermula ketika anak-anak lelaki mulai menempelkan sisi cermin dari sebuah rautan pensil di ujung sepatu mereka. Mereka mempergunakan itu untuk mengintip ragam celana dalam di balik rok murid perempuan.
Diolok-olok soal warna, bentuk, bahkan kadang kekurangan kualitas celana dalam, para korban yang murid-murid perempuan ini merasa malu. Namun tidak ada yang bersuara sebab takut akan dipukul. Anak-anak perempuan hanya bisa meringis sambil berlari, di bawah ancaman genggam para anak laki-laki.
Berhari-hari saya menjadi saksi kejadian itu, yang sebetulnya bisa dikategorikan pelecehan seksual. Berhari-hari juga saya pergi ke sekolah dengan perasaan waswas. Saya bahkan terpaksa memakai celana rangkap yang panas untuk berjaga-jaga. Ketika itu, sebagai anak kecil, saya tidak bisa mengatakan dengan jelas tentang perisakan kepada para guru; tentang ketakutan saya, atau rasa malu dan kesedihan yang saya lihat telah ditimbulkannya. Saya bahkan tidak tahu bahwa kala itu kami tengah mengalami perisakan. Namun hati dan pikiran kecil saya terus terusik dan merasa bahwa lelucon demikian tidak benar dan tidak seharusnya terjadi.
Saya mencoba menyelesaikan kegelisahan saya dengan mengadu pada seorang guru agama. Respons guru tersebut hanyalah menegur anak-anak lelaki itu sambil berlalu, “Hayo, jangan nakal ya, simpan rautannya.”
Teguran demikian tentu saja tidak berdampak apa-apa, selain predikat saya yang naik dari anak perempuan yang bukan siapa-siapa menjadi anak perempuan tukang mengadu. Predikat itu membuat hari-hari di sekolah semakin mencekam, dan para anak lelaki mulai menyasar saya sebagai korban. Mereka begitu menikmati ketakutan saya dengan cara berpura-pura mendekati saya sambil membawa kaca. Saya biasanya menjerit cukup nyaring dan itu cukup berhasil menjauhkan mereka sambil tertawa-tawa.
Baca juga: Celana Rangkap di Balik Seragam Tanda Mengakarnya Pelecehan Seksual
Ketakutan saya berubah menjadi amarah ketika teman sebangku saya menjadi korban dan menangis. Saya mulai berteriak pada anak-anak lelaki, meminta mereka untuk menghentikannya. Mereka tidak mengindahkan justru mendekat. Saya merebut kaca dari salah seorang murid laki-laki perisak lalu saya buang. Dalam sekejap setelah perebutan itu, saya dikerumuni beberapa orang perisak yang lain. Mereka mendorong saya jatuh ke kursi dan menabrakkan ujung meja ke dada saya. Seluruh murid yang lain melihat tanpa berani bereaksi apalagi membela, bahkan para korban yang telah saya suarakan penderitaannya.
Dada saya sakit, tapi saya bangkit dan tidak menangis. Ketika itu saya hanya memikirkan untuk pulang. Tidak ada yang bisa saya percaya di sekolah ini; tidak teman-teman dan tidak juga para guru. Saya hanya ingin pulang mencari ibu saya. Saya kemasi semua buku-buku dan saya berlari pulang ke rumah. Dalam perjalanan, saya menangis sendirian.
Menerima ketidakadilan bukan opsi
Ibu saya segera bertindak. Ia mengompres dada saya, memberi saya obat anti demam dan menginterogasi saya, setiap detailnya. Setelah mendengarkan seluruh cerita saya dan mendapatkan nama-nama murid yang mengeroyok saya, bersama kami segera kembali ke sekolah, tanpa tedeng aling-aling masuk ke dalam kelas dan menuding. Ibu saya langsung menghakimi mereka dengan amarah, tanpa mengindahkan keberadaan guru di dalam kelas. Beberapa dewan guru datang menengahi, dan mengatakan bahwa ibu saya telah melanggar aturan sekolah. Seharusnya ibu saya datang secara sopan dan baik untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan dewan guru terkait perisakan yang terjadi.
Ibu saya mengatakan, yang hingga kini saya masih ingat perkataannya, “Jangan kalian terlalu bangga pada otoritas kalian di lingkungan ini. Jika seandainya kalian berfungsi dengan baik, dari awal anak saya mengatakannya, kalian harusnya merespons dengan benar dan kejadian demikian tidak perlu terjadi. Kalau kalian diintip orang lain celana dalamnya, apa kalian masih bisa berpikir itu bercanda? Kalau memang bercanda, ayo sini saya intip celana dalam kalian, kalian bisa terima tidak? Sini, ayo sini buka celana dalam kalian!”
Dalam perjalanan pulang, ibu saya mengatakan bahwa saya boleh pindah sekolah jika saya ingin. Tapi saya pikir tidak, sebab kejadian itu telah menyadarkan saya pentingnya melawan perisakan, bukan menghindarinya. Tentu waktu itu dengan keterbatasan pikiran anak-anak saya, saya tidak bisa menyimpulkan serupa demikian dengan begitu teratur, hanya saja keberanian untuk pergi ke sekolah dan menghadapinya seorang diri itu telah muncul sangat kuat: ibu saya baru saja mengajari saya untuk melawan.
Baca juga: Perisakan Anak Betul-betul Merusak
Keesokan harinya, saya pergi sekolah dengan tatapan semua orang menjauhi saya: Guru-guru yang acuh tak acuh, murid-murid pelaku perisakan yang sadar bahwa kini saya adalah musuh mereka, hingga para korban yang menganggap bahwa saya adalah biang masalah yang sudah membuat mereka malu sebab nama mereka telah muncul ke permukaan sebagai korban. Teman sebangku saya yang saya bela bahkan menolak berbicara dengan saya. Ketika istirahat siang, kegiatan menggunakan kaca untuk mengintip rok memang sudah tiada, tetapi semua pelaku berbaris di lorong menunggu saya pergi ke kantin.
Saya yang tidak punya teman, mau tidak mau harus berjalan sendirian ke kantin. Saya tidak boleh terus berada sendirian di dalam kelas yang kosong, karena Ibu berpesan, itu sangat berbahaya. Ketika saya berjalan, perisakan verbal pun dilontarkan. Mereka mulai mengata-ngatai nama orang tua saya, menyebut diri saya goblok dan cengeng. Saya sabar tidak membalas. Hingga akhirnya satu dari sekelompok mereka yang menabrakkan meja ke dada saya maju ke depan dengan sebilah ranting. Dengan ranting itu, dia menyingkap rok sekolah saya.
Di sana saya betul-betul marah. Saya menendangnya. Ia membalas. Kami adu jotos. Keributan terjadi. Para guru turun tangan. Dalam pergumulan itu, saya yang kalah besar tentu saja tidak menang meskipun saya yakin saya berhasil mencakar wajahnya. Saya pulang dengan bibir bengkak. Keluarga saya bersiaga masing-masing dengan sebilah parang jika saja keluarga musuh saya datang menyerang. Ternyata tidak terjadi. Adu jotos itu adalah akhir segalanya.
Ketika saya kembali bersekolah beberapa hari kemudian, tidak ada seorang pun lagi yang berani merisak saya. Di sana saya mendapat pelajaran kedua meskipun lagi-lagi otak kecil saya ketika itu saya tidak bisa menjelaskannya dalam kata-kata bijak seperti bahwa dalam melawan perisakan, kita tidak bertarung untuk menjadi pemenang atau kalah, melainkan sebuah proses tentang keberanian menghormati diri sendiri. Tubuh kecil saya hanya sanggup menerjemahkannya dalam bentuk keberanian bersuara ketika menemukan ketidakadilan. Saya tidak lagi melihat diam menerima ketidakadilan sebagai opsi.
Perisakan dan/atau pelecehan seksual
Pengalaman perisakan saya tidak berhenti sampai di situ. Di sekolah menengah pertama, saya pernah mengunci seorang penjaga sekolah dalam toilet dan mematikan lampunya, sebab ia berpapasan dengan teman saya seorang perempuan dan saya sendiri, dan dengan sadarnya penjaga sekolah itu menggoda teman saya yang kebetulan memiliki payudara besar. Penjaga sekolah itu berkata, “Aduh-aduh dadanya ranum sekali, sering diremas ya?”.
Melawan perisakan harus menjadi kesadaran kita bersama, harus terus digaungkan agar pelaku sadar bahwa kebebasan tertawa mereka dibatasi oleh hak hidup orang lain.
Teman saya membeku, dia malu. Tapi saya tidak mau diam. Kami menunggu penjaga sekolah itu masuk ke dalam toilet, kemudian saya menguncinya dari luar dan mematikan lampunya. Kejadian itu seharusnya membuat saya dipanggil dewan guru, tapi ternyata tidak. Entah tidak diketahui, atau diketahui tapi dibiarkan saja sebab dianggap hanya keisengan murid. Namun setelahnya, penjaga sekolah itu tampak malas dan selalu menghindar jika bertemu kami.
Dewasa ini, saya juga beberapa kali menjadi korban pelucahan atau catcalling, yang selalu saya lawan dengan berhenti, mengeluarkan ponsel saya lalu memotret orangnya. Tindakan ini cukup untuk memberikan tekanan serupa pada pelaku seperti yang diterima korban: Rasa dipermalukan dan ketakutan. Jika saya sedikit sedang iseng, saya berpura-pura menelepon kepolisian di hadapan mereka. Setelah dilawan dengan cara demikian, mereka biasanya menyingkir dengan dalam ketakutan dan kebingungan.
Terakhir, saya mengalaminya di bandara di kampung halaman saya sendiri, Kalimantan, dan yang menyedihkannya, justru dilakukan oleh dua petugas bandara. Sekian detik setelah mereka melakukan catcalling ketika saya melintas, saya berhenti dan menatap mereka, membaca nama dan divisi kerja yang dibordir di pakaian mereka keras-keras hingga orang melihat ke arah kami lalu saya bertanya, “Kamu mau kita sama-sama pergi ke atasan kamu dan laporin kejadian ini?”. Mereka meminta maaf, dan saya kira itu pelajaran cukup bagi mereka untuk menjaga perilaku mereka.
Perisakan di media sosial juga beberapa kali saya alami. Kebanyakan berupa body shaming. Dibandingkan dengan jalan memutar memberikan alasan ini dan itu agar kondisi tubuh saya menjadi masuk akal bagi pelaku body shaming, saya lebih suka memberikan jawaban langsung pada intinya seperti, “Apakah kamu paham bahwa yang baru saja kamu lakukan pada saya itu body shaming? Apakah kamu sengaja atau tidak sengaja melakukan perisakan ini?”.
Dengan semua perisakan di atas yang terjadi pada saya, dapat dipastikan bahwa saya adalah korban perisakan berbasis gender. Di sebuah negara yang masih menggunakan paham patriarki sebagai rujukan nilai hidup keseharian, kita sebagai perempuan sangat rentan menjadi korban. Begitu rentannya hingga membudaya, atau bisa saja dibenarkan, atau tidak bisa dilihat sebagai kesalahan. Lalu bagaimana dengan perisakan termotivasi oleh bias dan dilakukan oleh gender yang sama? Tenang, saya juga pernah mengalaminya.
Perisakan oleh sesama perempuan
Ya, saya juga mengalami perisakan oleh sekelompok orang yang mendaku sebagai sastrawan dan pemangku kebudayaan. Lingkup profesi mereka tentu seharusnya menjadikan mereka orang-orang yang peka terhadap isu sosial, kemanusiaan, dan kesehatan mental. Sekitar empat tahun lalu, dalam satu percakapan di media sosial, beberapa perempuan dari kelompok sastra dan budaya terkemuka dari daerah asal saya melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada saya dan mengarah ke fitnah yang dibungkus dalam seloroh olok-olok.
Baca juga: Apa yang Lucu dengan Tubuh Perempuan?
Saya mengatakan keberatan saya seketika itu juga di laman yang sama. Pengalaman saya melalui hal demikian mengharuskan saya segera membuat tangkapan layar sebagai bukti perisakan. Tak cukup, saya segera menautkan kejadian itu ke akun seorang pengacara kenalan saya untuk memberikan pandangan hukum baik bagi saya sebagai korban maupun pelaku perisakan.
Seorang yang dianggap tokoh dari kelompok itu menengahi dengan memberikan alasan bahwa itu bukanlah perisakan, melainkan hanyalah candaan sebagai ungkapan keakraban. Saya tidak mengerti bagaimana kata-kata seperti idiot, goblok, dan fitnah yang dilakukan secara berkelompok dan mengarah jelas pada satu orang bisa dikategorikan sebagai candaan. Di sinilah ingatan saya kembali melayang pada kejadian puluhan tahun lalu ketika ibu saya berhadapan dengan para guru SD saya yang kecolongan: Bahwa seseorang bisa saja mendapat predikat sebagai tokoh atau pemikir dalam satu bidang, namun sekaligus juga juru bungkam tanpa berpikir dalam lingkup kemanusiaan.
Kejadian itu tidak lantas membuat saya menempuh jalur hukum meskipun bisa. Kami sesama perempuan dan mereka memiliki anak dan keluarga yang akan ikut menderita jika saya menyeret ibunya ke dalam perkara hukum. Bagi saya, menunjukkan bahwa mereka telah bersikap memalukan dan patut dipertanyakan kedudukannya sebagai orang dewasa yang dengan percaya diri mendaku predikat sebagai pemikir, itu sudah cukup.
Saya percaya setelah kejadian itu, jika mereka memiliki kapasitas untuk berpikir maka mereka akan melakukannya. Sebagai orang yang telah memutuskan untuk berdiri melawan perisakan, saya tidak lagi merasa luka. Namun yang perlu digarisbawahi, meskipun korban telah mampu memandang bahwa perisakan yang dialaminya merupakan satu fase lompatan langkah besar bagi dirinya yang tidak patut untuk ratapi melainkan hanya berguna untuk dipelajari, kita tetap perlu mendudukkan setiap perkaranya dalam pandangan keadilan.
Mengapa pelaku bisa tertawa dengan cara mempermalukan orang lain, sementara sistem melindunginya dan hanya menandainya sebagai candaan? Meskipun tidak membawanya ke jalur hukum, saya merasa perlu membuat surat terbuka yang dengan terang saya tautkan pada akun perisak saya, juga pada orang-orang yang berada di sana tetapi tidak bersuara apa pun juga atas nama kebenaran, kecuali menginginkan ini hanya dianggap sebagai kesalahpahaman gurauan tanpa adanya tanda hitam untuk sebuah kesalahan.
Surat itu berisikan betapa saya menyayangkan bahwa dalam lingkungan orang-orang yang mengaku bahwa mereka intelektual, namun pada kenyataannya masih saja tidak mampu bersikap benar. Surat itu tidak mendapatkan tanggapan dari para pelaku perisakan ataupun pernyataan benar dan salah yang berarti dari para tokoh yang berada di sana ketika terjadi. Semua seperti cuci tangan, namun cukup membuat kotak pesan saya penuh, kebanyakan datang dari korban oleh orang yang sama yang melakukan perisakan terhadap saya. Sebagian lagi memberikan semangat dan dukungan atas keberanian saya mengambil langkah, namun di kehidupan nyata orang-orang itu juga tidak mengambil jarak pada pelaku perisakan itu: Mereka sebenarnya sama sekali tidak peduli terhadap suatu kasus, mereka hanyalah oportunis.
Orang-orang bisa kehilangan kepercayaan diri ketika para perisak bercanda. Orang-orang bisa diperkosa ketika para perisak bercanda. Orang-orang juga bisa mati ketika para perisak bercanda.
Tahun berganti, sesekali saya mendengar lagi sebagian perempuan dari kelompok yang sama masih melakukan perisakan dengan cara yang sama, dan masih dengan leluasa bergerak dilindungi oleh sistem yang sama. Sebagian yang lain menunjukkan penyesalannya dengan cara mencoba berteman dengan saya tanpa menunjukkan lagi gelagat banyak bicara.
Saya tidak pernah lagi bertemu dengan pelaku catcalling di bandara dan saya harap ini tidak perlu dialami oleh perempuan lainnya di bandara yang sama. Ketika saya kembali ke sekolah menengah pertama saya untuk memberikan kelas menulis setahun yang lalu, penjaga sekolah yang saya kunci di toilet masih bekerja di sana. Sementara murid pelaku perisakan di sekolah dasar yang dulu beradu jotos dengan saya kini menjadi seorang petugas pemadam kebakaran. Untuk yang satu ini saya bangga padanya dan kini kami berteman baik.
Hanya ada satu kata: Lawan!
Ada banyak faktor yang menjadikan seseorang menjadi pelaku perisakan, mulai dari kurangnya pengetahuan akan hal terkait, keterampilan sosial yang buruk, cerminan emosi negatif atau rasa rendah diri, hingga trauma masa kecil dan banyak lagi. Keseluruhan yang saya alami akibat semua faktor itu tidak lagi mengacu pada bahwa perisakan hanya bisa terjadi dalam wilayah basis gender, namun telah sampai kerusakannya ke dalam tatanan antar gender itu sendiri. Seorang perempuan bisa menjadi perisak sesamanya akibat tekanan atau trauma atas sistem berbasis gender. Atau bisa saja sebab mereka melihat peluang kepuasan atau kuasa pada orang lain melalui pengamatan mereka yang pasti pernah melihat atau mengalami perisakan berbasis gender, kemudian mencontohnya, mendapatkan manfaat dan kesenangannya hingga kecanduan olehnya.
Namun apa pun itu tidak boleh dijadikan alasan untuk kita menjadi permisif atau kesempatan bagi siapa saja untuk merisak orang lain. Alih-alih memberi kelonggaran pada perilaku buruk untuk berkembang dengan cara mendiamkan, kita harus belajar pada kasus penyintas. Ya, mereka menjadi korban tetapi tak lantas menjadikan mereka pelaku atau tunduk pada bias hingga menerima bahwa mereka pantas diperlakukan demikian. Tidak, mereka memilih melawannya dengan segala risiko.
Baca juga: ‘Tocil’, Pasar: Selalu Ada yang Salah dengan Bentuk Tubuh Perempuan
Masih berkaca pada kasus perisakan yang saya alami, kita harus mempersiapkan diri bahwa ketika mengalami perisakan, kita tidak hanya melawan satu orang pelaku, tetapi juga melawan sistem yang melindunginya dengan dalih bias. Banyaknya orang yang memilih hanya diam menonton tanpa angkat suara ketika perisakan terjadi, tokoh yang mengatasnamakan kedamaian dan lelucon sebagai senjata pembungkam korban, korban yang justru memihak pelaku agar tidak menanggung malu, atau sebagian manusia oportunis yang menyatakan empati tapi tidak mau bergerak untuk memberikan sangsi sosial pada pelaku, memberikan gambaran bahwa melawan para perisak memang harus dimulai dengan sikap berani mati berperang seorang diri.
Keadilan bagi para korban perisakan di negara ini bukanlah hal yang mudah didapatkan, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kebanyakan dari kita pernah mengalaminya dan dengan sadar mengetahui bahwa hal demikian sangat merugikan. Tetapi pepatah tidak ada asap kalau tidak ada api memang sudah mendarah daging pada masyarakat kita. Kita gemar mencurigai korban. Kita lebih suka menuduh bahwa para korbanlah pemilik kertas berisi api itu, padahal bisa saja pelaku yang menyulut kertas di tangan kita tanpa kita melakukan kesalahan apa-apa.
Penting bagi kita untuk melawan perisakan seketika dengan lantang dan saat itu juga, ketika bukti masih panas, ketika jejak belum hilang. Ayo bersuara. Ayo berani menuding pelaku secara terbuka. Melawan perisakan harus menjadi kesadaran kita bersama, harus terus digaungkan agar pelaku sadar bahwa kebebasan tertawa mereka dibatasi oleh hak hidup orang lain.
Ini harus terus digaungkan agar para korban berani bersuara untuk dirinya sendiri dan melanjutkan langkah dalam pandangan kebebasan yang cerah. Harus digaungkan agar para orang tua memberikan pengetahuan dan teladan kepada anak mereka untuk tidak menjadi perisak, agar para tokoh peka terhadap isu perisakan dan mau menyuarakan bahwa tindakan demikian tidak dibenarkan, agar kita sendiri mampu mengedukasi diri kita sendiri tentang betapa bahayanya tidak mampu membedakan yang antara guyonan dan perisakan dan bagaimana cara melawan pelaku. Ini bukan perkara menang atau kalah. Ini perkara berani berkata benar. Perkara jiwa yang tidak akan tunduk pada ketidakadilan standar ganda yang masih berpegang teguh pada kalimat, “Santai, mereka cuma bercanda”.
Orang-orang bisa kehilangan kepercayaan diri ketika para perisak bercanda. Orang-orang bisa diperkosa ketika para perisak bercanda. Orang-orang juga bisa mati ketika para perisak bercanda. Jika sudah demikian, dan telah ribuan kasus dari seluruh dunia yang menjadi bukti bahwa kerusakan yang disebabkan lelucon para perisak ini benar adanya, apakah kita tetap bisa santai dan tertawa sebab berpikir bahwa tragedi kemanusiaan ini barangkali juga hanya sebuah candaan?