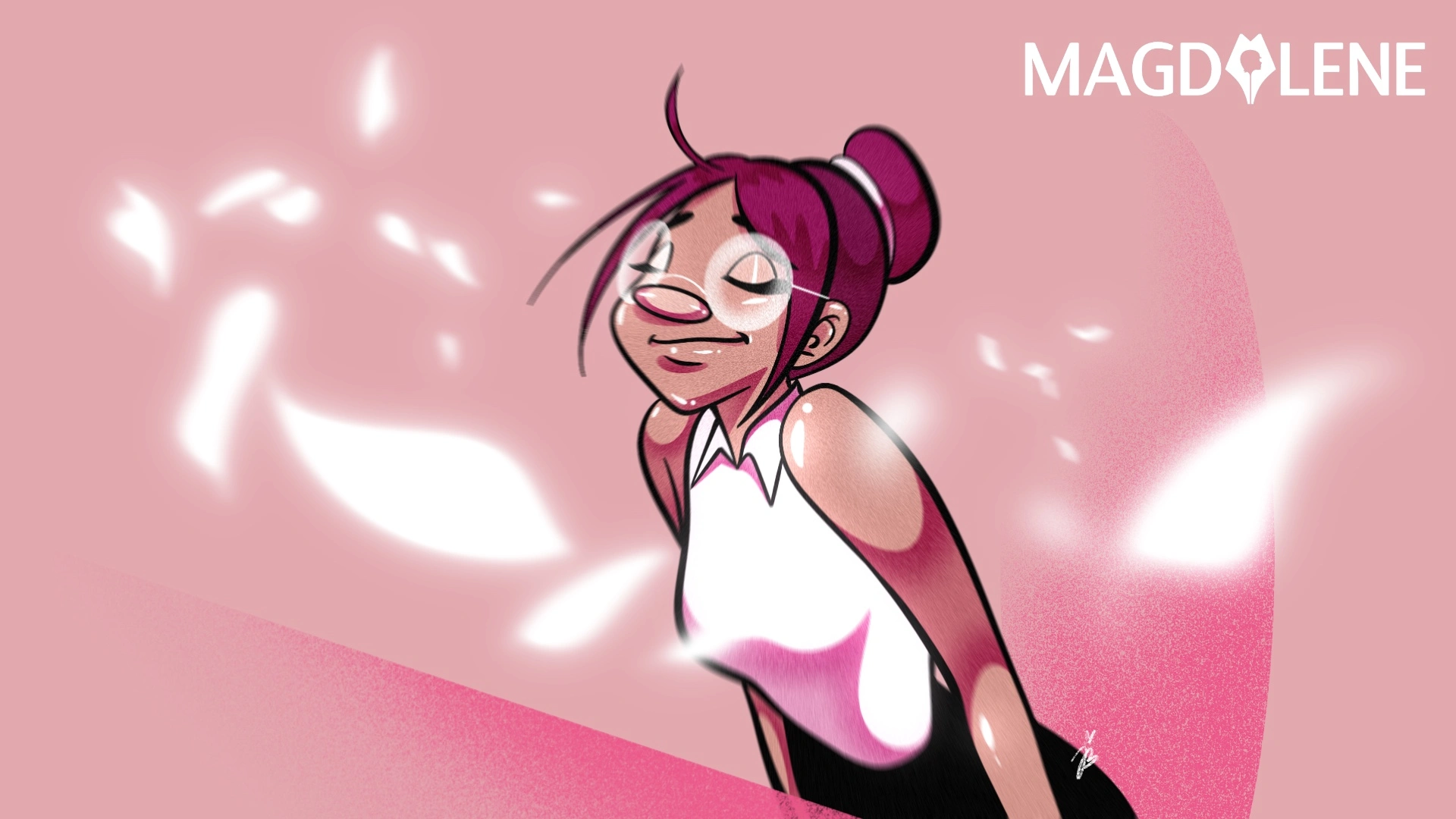Pil Pahit Penyintas Kekerasan Mentawai: Apa Pun Kejahatannya, Denda Adat Jawabannya
Perempuan korban kekerasan seksual di Mentawai tak berhak atas hak pemulihan. Sebab, semua terpaksa diselesaikan dengan ‘tulou’ atau denda adat.

Peringatan Pemicu: Penggambaran kekerasan seksual.
Jumat, (23/3) menjadi malam paling nahas untuk “Dinda”. Anak perempuan 16 tahun itu mengalami kekerasan seksual bertubi-tubi oleh empat laki-laki di kampungnya, Kecamatan Siberut Barat, Mentawai.
Kekerasan itu bermula saat Dinda pergi sendirian ke SD Fransiskus Sikabaluan. Sama seperti banyak warga di Mentawai yang sulit mendapatkan jaringan internet seluler, tujuan Dinda adalah menggunakan jaringan wifi yang dipasang di sekolah. Tak peduli meski ia harus berjalan kaki dari kos ke sekolah dengan penerangan minim. Ia cuma mau bertukar kabar dengan keluarga, teman, dan doom scrolling media sosial.
Keasyikan berselancar di internet, Dinda tak sadar ternyata sudah larut malam. Karena tak berani melintasi jembatan simpang empat desa yang ramai pemuda, Dinda urung pulang ke kosnya. Ia memilih menginap di kos teman yang dekat dengan lokasi sekolah. Saat berjalan ke kosan teman, Dinda melewati warung makanan tanpa penerangan.
Mendadak, ada empat laki-laki yang menahan Dinda untuk diajak ngobrol bersama. Ia menolak dan berusaha lari dari tempat itu. Namun, keempat lelaki tersebut justru mengejar dan membawa Dinda kembali ke lingkungan sekolah. Di tempat itu, salah satu lelaki yang ia kenal sebagai kakak kelas melakukan kekerasan seksual padanya, diikuti oleh kawan-kawannya yang lain. Mereka menggerayangi payudara, mencium paksa, bahkan memaksa Dinda melakukan seks oral.
Kekerasan ini terjadi berulang kali, dari pukul 23:00 hingga 05.00 WIB saat para pelaku akhirnya melepaskan Dinda. Usai kejadian itu, Dinda sempat divisum dan melaporkan kekerasan seksual ini ke Polsek Sikabaluan bersama sang ayah. Namun, bukannya segera diusut, polisi bilang penyintas tak mengalami kekerasan seksual. Sehingga, sudah sepatutnya jika kasus ini diselesaikan lewat peraturan adat.
“Tidak ada jejak (kekerasan). Korban tidak mengalami ‘kerusakan’, selaput daranya tidak robek, tidak ada bersetubuhan. Karena itu tidak ada kekerasan, kata polisi. Maka dilakukanlah mediasi, pelaku disuruh bayar tulou (denda adat) Rp30 juta. Tapi itu pun baru dibayar 11,5 juta, 5 jutanya diminta sama polisi, dan korban cuma dapat 6,5 juta,” jelas Direktur Nurani Perempuan-Woman Crisis Center (WCC) Rahmi Meri Yanti, yang mendampingi korban.
Baca Juga: Kepanikan Moral, Dalih Basi Persekusi Dua Perempuan di Sumbar
Kasus Kekerasan yang Dibayar oleh Denda Adat
Dinda dan ayahnya tak tinggal diam. Mereka kukuh meneruskan kasus ini ke ranah hukum pidana, dengan didampingi Nurani Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. Kasus Dinda sendiri ramai dibincangkan. Bahkan masuk ke media lokal dan disorot gerakan masyarakat sipil, seperti Forum Mahasiswa Mentawai Sumatera Barat (Formma Sumbar) dan Kelompok Muda Padang dari Solidaritas Perempuan.
Kini kasus Dinda sudah mulai memperlihatkan titik terang. Sesuai dengan keterangan LBH Padang yang dihubungi Magdalene, (18/7), laporan kekerasan seksual sudah dilimpahkan pada Kejaksaan dan dalam tahap penyerahan tersangka.
Sayangnya, tidak semua korban kekerasan seksual di Mentawai punya nasib sama dengan Dinda. Banyak perempuan korban kekerasan seksual di Mentawai harus puas dengan penjatuhan denda adat atas kasus kekerasan seksual yang menimpa mereka, alih-alih pemulihan korban. Tulou ini tentu saja tidak menimbulkan efek jera pada pelaku.
“Mekar”, 25 dan “Tifa”, 17 adalah dua di antara korban yang menceritakan kisahnya pada Magdalene. Mekar, perempuan Tuli dan disabilitas sensorik bicara mengalami kekerasan seksual oleh sepupunya sendiri saat ia masih berusia 16 tahun. Tangan dan kaki Mekar diikat, mulutnya dibekap oleh pelaku, sehingga membuatnya tidak bisa memberontak atau mengeluarkan suara. Kejadian ini membuat Mekar hamil dan melahirkan seorang anak perempuan bernama “Melati”.
Dengan trauma sebesar ini, Mekar nyatanya tidak mendapatkan keadilan sama sekali. Lewat tulou, pelaku menyerahkan dua babi jantan, dua kubik kayu, dan gergaji mesin, lalu simsalabim kasusnya dianggap selesai begitu saja.
“Dia masih bebas (berkeliaran) di desa. Tiap berpapasan sama dia, saya masih takut,” kata Mekar dalam bahasa tubuh yang diterjemahkan oleh ibunya.
Pelaku pun sama sekali tidak andil menghidupi anaknya. Mekar terpaksa pontang-panting sendirian menghidupi anak perempuannya dengan bekal berladang di lahan milik sang ayah.
“Dia (pelaku) lepas tanggung jawab. Dia tidak memberikan apapun, Melati tidak dibiayai sama sekali,” keluh ibu Mekar ketika ditanyai tentang pelaku.
Sebelas dua belas dengan Mekar, Tifa juga mengalami kekerasan seksual pada usia 16 tahun. Kejadian bermula saat Tifa diajak singgah ke kos pacar yang berusia satu tahun lebih tua dengannya. Di kos itu, sang pacar memaksa Tifa berhubungan seksual, jika tak ingin hubungannya diputuskan. Berhubungan seksual, kata pacar Tifa, adalah satu-satunya cara pembuktian cinta.
Kekerasan dalam pacaran (KDP) yang dialami oleh Tifa terendus oleh pihak sekolah. Sayang, bukannya berpihak pada Tifa, sekolah justru mengeluarkan anak perempuan itu. Orang tua Tifa yang sudah terlanjur malu dengan kejadian yang menimpa anaknya pun, memutuskan menyelesaikan kasus lewat peraturan adat. Pelaku dikenai tulou dan Tifa dipaksa oleh orang tua untuk menikah.
“Saya enggak mau nikah, masih muda. Masih mau sekolah. Sempat ada pikiran mau ke polisi, tapi kakek bilang apa yang terjadi sama saya itu suka sama suka jadi diselesaikan secara adat saja. Tapi saya merasa penyelesaian ini (tulou) tidak adil. Saya tidak puas,” cerita Tifa saat ditemui Magdalene awal Juli 2023 lalu.

Baca Juga: Resesi Seks di Jepang dan Korea Selatan, Benarkah Salah Perempuan?
Tulou yang Tak Berpihak pada Korban
Tulou atau denda adat adalah bagian dari mekanisme hukum masyarakat Mentawai yang sudah eksis secara turun temurun. Tarida Hernawati, antropolog dan Project Manager Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) dalam wawancaranya bersama Magdalene bilang, tulou dalam hukum masyarakat Mentawai berlaku umum untuk setiap kasus yang dinilai melanggar secara adat.
Besaran tulou pun juga disesuaikan dengan besarnya tindak pidana yang dibagi menjadi tiga, yakni tindak pidana ringan, menengah atau sedang, dan berat. Kasus-kasus seperti pembunuhan, pelecehan dan/atau kekerasan seksual masuk dalam tindak pidana berat. Tulou yang dijatuhkan pada pelaku berupa harta seperti ternak babi, ladang, bahkan tanah leluhur.
Tarida melanjutkan, tulou sebenarnya dibangun dengan niat yang baik. Tulou tidak hanya berfungsi sebagai sanksi dan kontrol sosial bagi pelaku, tetapi juga jadi bagian penting dalam hak pemulihan korban, yang dalam hukum pidana modern dikenal sebagai hak restitusi.
“Tanah misalnya punya peran penting bagi adat istiadat. Silsilah atau asal usul tanah itu penting untuk masyarakat adat, sehingga jika pelaku kena tulou jadi ini akan diingat abadi oleh masyarakat Mentawai. Jadi secara adat, tulou dibuat untuk korban dalam rangka memiskinkan dan membuat malu pelaku. Pelaku akan kehilangan harta-harta berharga sebagai ganti kerugian pada korban,” jelas Tarida.
Sayangnya, niat baik dari penerapan tulou di Mentawai telah bergeser. Dalam peradilan adat Mentawai, sebelum pelaku dijatuhkan tulou, sidang biasanya akan digelar. Korban dan pelaku tak dihadirkan demi meminimalisasi konflik terbuka. Sebagai gantinya, parapihak akan diwakili sipatalaga atau mediator.
“Dia adalah seseorang yang dianggap bijaksana di masyarakat dan paham hukum adat. Dia juga tidak boleh punya kedekatan kepada korban, keluarga, pelaku, maupun keluarga pelak. Ini agar konflik yang ia tangani bisa terhindar dari berbagai kepentingan,” jelasnya.
Sipatala akan menanyakan kasus langsung ke korban, menanyakan apa keinginan korban, menyampaikan, serta menegosiasikannya ke pelaku. Dalam persidangan adat, sipatalaga kemudian akan hadir mempertimbangkan tulou serta menjatuhkan besaran tulou yang seharusnya dibayar oleh pelaku. Dengan perannya yang sangat besar, maka sipatalaga haruslah individu yang independen. Tidak boleh punya afiliasi dengan siapa pun.
Namun, sejak 1980-an dengan penyeragaman dan dibentuknya susunan dan kedudukan Pemerintah Desa oleh Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, peran sipatalaga di masyarakat Mentawai mulai berubah. Dalam perkembangannya, kepala desa atau kepala dusun akhirnya berperan ganda menjadi sipatalaga.
“Ketika diadopsi ke sistem pemerintahan, hukum adat ini berbenturan. Sehingga, kalau kepala desa ini punya kepentingan atau punya kedekatan dengan pelaku timbulah konflik kepentingan. Akhirnya semenjak peralihan fungsi ini, banyak ditemukan kasus kekerasan yang ditutupi oleh kepala desa. Kasus kekerasan dianggap jadi bagian aib desa apalagi ketika desa sedang berlomba-lomba membuktikan ke pemerintah pusat bahwa desanya ramah perempuan dan anak,” jelasnya.
Di sisi lain, imbuhnya, penyeragaman dan pembentukan susunan dan kedudukan pemerintah desa juga membuat tulou kehilangan esensinya. Banyak dari aparatur pemerintah desa menganggap tulou dalam kasus kekerasan seksual sebagai formalitas saja. Enggak jeran jika tulou berubah menjadi harta benda bersifat konsumtif.
“Tulou jadi diuangkan, dijadikan emas, bahkan sekarang tulou bisa berupa mesin atau kendaraan bermotor. Akibatnya yang menggunakan juga bukan korban, tapi pihak laki-laki dari keluarganya. Tidak ada efek jera dan pemulihan korbannya,” ucapnya.
Baca juga: Kasus Pemerkosaan di Aceh dan Dukungan Lingkungan Sekitar
Perlunya Dorong Hukum Pidana
Pengalihan fungsi sipatalaga dan hilangnya esensi tulou, membuat para perempuan korban di Mentawai jadi semakin rentan. Meri mengatakan, ketika masyarakat Mentawai masih mengandalkan tulou sebagai satu-satunya penyelesaian kasus, maka hak korban atas pemulihan takkan pernah bisa tercapai. Korban akan mengalami trauma berkepanjangan, apalagi ketika lingkungan sosial punya kecenderungan menyalakan korban.
Ketika hukum adat sudah tidak bisa berpihak pada korban, maka hukum pidana pun, kata Meri, jadi sangat penting. Ironisnya, cuma sedikit sekali kasus kekerasan seksual di Mentawai yang dilaporkan sebagai kasus pidana, menurut Edi Surya, Kepala Polsek Sikabaluan.
“Tahun 2022 itu pencapaian terbesar polsek kami yang berhasil memidanakan lima kasus kekerasan seksual. Tahun-tahun sebelumnya kami tidak punya catatan atas itu. Memang kendala terbesarnya itu karena hukum adat. Kalau ada laporan masuk pasti kami usut sampai tuntas. Itu udah tanggung jawab saya. Tapi kalau enggak ada laporan masuk dan keluarga mau damai ya kita harus bagaimana. Masa kami harus menangkap semua orang di desa,” kata Edi yang ditemui di Magdalene di kantornya, (5/7).
Pernyataan Edi direspons Dechtree Ranti Putri, Advokat Publik LBH Padang. Dalam wawancaranya bersama Magdalene (17/7), Ranti justru kecewa terhadap sikap kepolisian. Menurutnya, polisi punya tanggung jawab untuk mengusut dan melakukan penyidikan pada kasus kekerasan seksual, terlepas kasus itu dilaporkan atau tidak oleh korban atau keluarga korban. Ini mengingat kasus kekerasan seksual masuk ke dalam delik biasa bukan delik aduan.
“Dalam delik biasa, walau enggak ada yang lapor tapi informasi itu sampai ke polsek, ya ini wajib diusut tuntas. Di kasus-kasus kekerasan seksual kan banyak pelakunya orang terdekat, walinya sendiri apakah harus menunggu dari orang tuanya? Siapa pun yang sudah mengetahui berhak menyampaikan ke polisi, dan ketika polisi tahu, mereka harus menindaklanjuti ini. Harusnya kepolisian tau tentang ini, apalagi kasus kekerasan di Mentawai juga bersangkutan dengan (korban) anak,” tegasnya.
Kewajiban polisi mengusut kasus kekerasan seksual tanpa menunggu laporan penting, imbuhnya, mengingat korban sulit mengakses layanan bantuan hukum atau pendampingan.
“Di Mentawai kalau melapor kasus kekerasan seksual, paling ke Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat). Selain paling dekat, tidak ada lembaga layanan seperti di Padang. Jika orang-orang di Puskesmas punya perspektif korban, akan disambungkan ke dinas pemberdayaan perempuan atau dinsos (dinas sosial). Tapi masalahnya tidak setiap pulau punya puskesmas,” kata Meri.
Kalau pun korban atau keluarganya melapor, biaya dan waktu yang dikeluarkan relatif besar. Sebagai informasi, tak ada pengadilan di Mentawai, jadi mereka perlu pergi ke Padang jika sidang dilangsungkan. Menurut Meri sekali jalan biaya perjalanan dari dusun ke Padang, bisa menghabiskan Rp1-2 juta per orang.
“Kalau ada saksi, tiga misalnya maka tinggal kalikan saja biaya perjalanan itu ditambah biaya penginapan kalau tidak ada sanak saudara di Padang ditambah biaya konsumsi. Sidang juga kan tidak hanya sekali saja, bayangkan biaya dan waktu yang harus dikeluarkan korban. Jadilah keluarga korban atau korban sendiri memilih tidak melapor,” jelas Meri.
Agar korban bisa melapor dan terpenuhi hak pemulihannya, Meri mengungkapkan, akses terhadap layanan bantuan di Mentawai perlu diadakan. Pemerintah desa sudah seharusnya melihat ini sebagai permasalahan serius yang bisa berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) desa. Salah satu pengadaan akses layanan bantuan bisa dilakukan lewat pengembangan layanan berbasis komunitas di dusun dan desa yang gampang diakses masyarakat.
“Posko pengaduan dan prosedur ks seperti apa itu harus mulai dikembangkan. Bidan di beri tugas, rekrut masyarakat menjadi relawan dengan catatan perlu dilatih lewat peningkatan kapasitas. Layanan berbasis komunitas juga bisa jadi wadah untuk pemerintah dan tokoh adat untuk duduk bersama. Bisa kita diskusikan terkait tulou misalnya dan pertimbangan soal adat yang merugikan perempuan,” katanya.
Selain mengembangkan layanan berbasis komunitas, imbuhnya, penting bagi Dinas Pendidikan membuat program khusus bagi tenaga pengajar. Sebab, sebagai pendamping, Meri kerap menemukan stigma dan penghakiman korban kekerasan seksual anak dan remaja yang justru datang dari guru. Dengan demikian, melatih dan memberikan pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender harus jadi prioritas.
“Ini harusnya jadi program dinas pendidikan. Tidak hanya satu pertemuan atau dua kali. Perspektif gender perlu dipahami guru agar mereka tau ks terjadi karena relasi kuasa, korban tidak bisa menolak,” jelasnya.
Selain itu, sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi masyarakat perlu dilakukan. Ia menilai, hukum pidana di masyarakat Mentawai masih dilihat menakutkan dan merepotkan.
“Perlu ada penanaman pemahaman soal hukum pidana. Tulou tidak serta merta menghapuskan pidana. Karena jika mengaminkan tulou tanpa memberikan perspektif, maka orang kaya akan seenaknya melakukan pelecehan atau kekerasan. Kasih duit selesai. Maka ini (hukum pidana) harus disosialisasikan, karena ini penting juga buat korban,” tutup Ranti.
Ilustrasi oleh: Karina Tungari