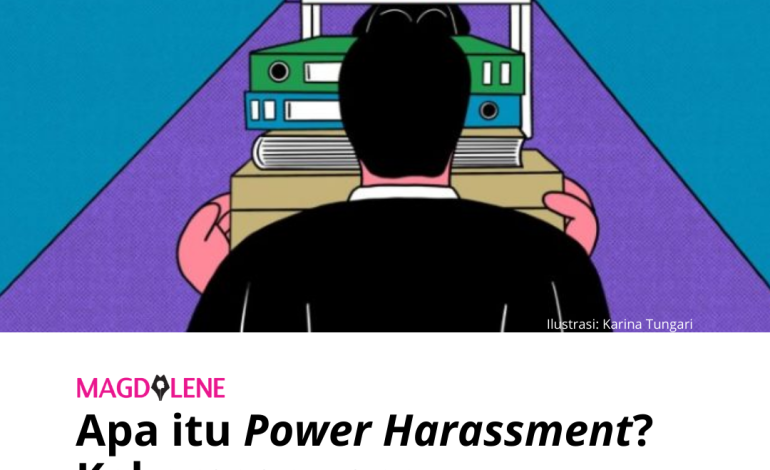Jokowisme, Trumpisme, dan Dinasti Politik: Nafsu Kekuasaan yang Kikis Demokrasi
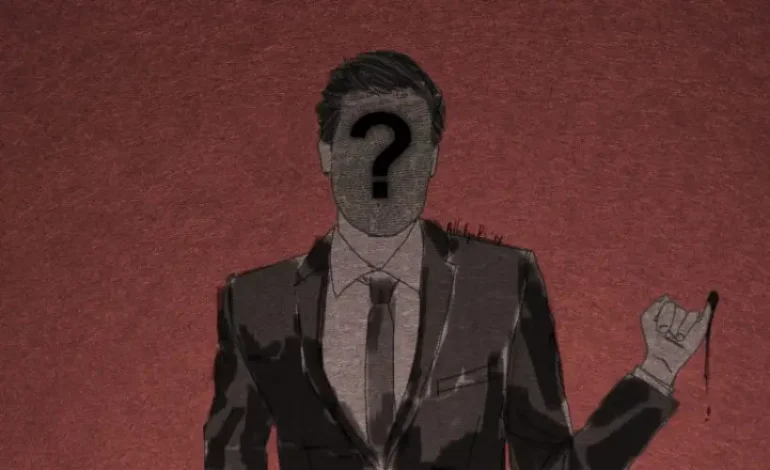
Hari-hari ini kita disuguhi berita tentang keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan kepala daerah di bawah usia 40 tahun bisa maju dalam Pemilu. Tak lama kemudian, sesuai tebakan, anak Presiden Joko “Jokowi” Widodo melenggang ke Komisi Pemilihan Umum, berpasangan dengan Prabowo Subianto. Hal ini membuat publik mengritik Jokowi memang dari awal berniat melebarkan jalan dinasti politiknya.
Saat ini Gibran tengah menjabat Wali Kota Solo. Sebelumnya, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), hal yang kemudian turut memantik kontroversi karena Kaesang hampir nihil pengalaman politik.
Yang menarik adalah PSI memunculkan dan mempopulerkan terminologi Jokowisme, terminologi yang mengagungkan figur tertentu. Metafora semu semacam ini akan turut berperan mendangkalkan praktik demokrasi. Kedaulatan rakyat kini menjadi arena pertaruhan sekelompok elit politik demi mempertahankan maupun merebut kekuasaan.
Namun, pada kenyataannya, pendangkalan demokrasi semacam ini telah menjadi tren global yang terjadi di negara-negara pelopor demokrasi seperti Amerika Serikat (AS) dan Australia. Ini menunjukkan, ternyata praktik demokrasi di dunia tengah menghadapi tantangan yang makin meningkat, yang membuat kita mempertanyakan kembali definisi demokrasi itu sendiri.
Baca juga: Andai Kaesang Jadi Wali Kota Depok, Sebuah Curhatan Akamsi
Jokowisme dan Dinasti Politik di Indonesia
PSI mengklaim istilah Jokowisme sebagai metafora pemimpin yang bekerja keras memajukan rakyat serta memiliki paham progresivitas pembangunan negara yang berkeadilan dan berdaulat. Penjelasan ini kemudian memunculkan anggapan bahwa Jokowisme telah melampaui sekat ideologi.
Ini sekilas memberi angin sejuk bagi platform (prinsip atau kebijakan yang didukung) pergerakan partai politik di Indonesia yang kebanyakan saat ini susah dibedakan–hampir semuanya menganut platform nasionalis religius, atau sebaliknya, religius nasionalis.
PSI dan para loyalisnya menjustifikasi, mereka yang mengritik maupun menolak Jokowisme telah gagal memahami cara kerja kekuasaan. Padahal, metafora Jokowisme itu sulit dipisahkan dari kesan proses pembentukan dinasti politik bagi anak-anak Jokowi.
Dengan kata lain, secara tidak langsung ini menunjukkan cara kerja kekuasaan dalam metafora Jokowisme sendiri ternyata tidak berbasis sistem meritokrasi yang mendasarkan pada kapabilitas, melainkan tidak lebih dari sekadar fanatisme terhadap tokoh tertentu. Ini akan sangat mendorong terbangunnya dinasti politik.
Di Indonesia fenomena dinasti politik memang tidak hanya dilakukan oleh keluarga Jokowi. Di tingkat nasional, dengan skala yang berbeda, beberapa yang masih terlihat di antaranya adalah Puan Maharani (keluarga Megawati Soekarnoputri), Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono (keluarga Susilo Bambang Yudhoyono), dan mungkin belakangan muncul Yenny Wahid (keluarga Abdurrahman Wahid).
Baca juga: Perempuan sebagai ‘Vote-Getters’: Kompetensi, Popularitas, atau Politik Dinasti?
Trumpisme dan Ancaman terhadap Demokrasi AS
Pendangkalan demokrasi melalui terminologi semu juga menjalar di AS. Polarisasi antara dua partai besar di AS–Partai Republik dan Partai Demokrat–terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ada istilah Trumpisme yang muncul ketika mantan Presiden AS Donald Trump maju sebagai kandidat presiden dari Partai Republik dalam Pemilu Presiden AS 2016.
Trumpisme kemudian kerap digunakan untuk menyebut arah kebijakan dan sikap Trump terhadap berbagai kebijakan, baik domestik maupun luar negeri, serta gerakan yang mendukung atau sejalan dengan pandangan Trump. Sejumlah pengamat politik AS menyebut Trump sebagai presiden yang mempromosikan autokrasi yang akan mengancam demokrasi AS.
Peter J. Katzenstein, profesor politik dari Cornell University, mendefinisikan bahwa Trumpisme terdiri dari tiga pilar yaitu etnonasionalisme, agama, dan ras. Etnonasionalisme berfokus pada loyalitas kaum kulit putih AS. Sementara, pilar agama berpusat pada kelompok Kristen sayap kanan dan isu ras meminggirkan kelompok kulit hitam, hispanik, Muslim, dan kelompok minoritas lain.
Politik yang Trump lakukan lebih berfokus kepada dirinya sendiri sebagai tokoh. Ketika kalah dalam Pemilu AS 2020, Trump memprovokasi pendukungnya hingga menciptakan kerusuhan di Gedung Capitol, bahkan sempat melontarkan wacana untuk membuat partai baru.
Arah politik yang dibawa Trump tidak selalu mewakili ideologi partai yang mendukungnya. Bahkan muncul gerakan Never Trump oleh tokoh-tokoh Partai Republik yang lebih moderat karena mereka tidak mendukung kebijakan Trump.
Menjelang Pemilu AS 2024, narasi Trumpisme masih kembali muncul dalam debat kandidat presiden Partai Republik, padahal Trump sendiri sedang berkutat dengan berbagai dakwaan hukum.
Bagaimanapun, sistem demokrasi AS yang telah dibangun berdasarkan meritokrasi sejak abad ke-18 mampu bertahan meski sempat menghadapi berbagai ancaman. Peran dan pembagian kekuasaan yang dimiliki kongres serta pemerintah negara bagian, independensi lembaga yudikatif, serta kebebasan pers menjadi pengawal dan penjamin utama berjalannya sistem demokrasi di AS.
Baca juga: Putusan MK Soal Batas Umur Capres-Cawapres dan Potensi Dinasti Politik Jokowi
Referendum dan Prospek Demokrasi Australia
Tren pendangkalan demokrasi menjadi tantangan bagi Australia sejak satu dekade terakhir. Terbaru, hasil referendum Australia yang dilaksanakan 14 Oktober 2023 menunjukkan bahwa 60,6 persen rakyat Australia menolak usulan untuk mengubah konstitusi agar mengakui penduduk asli (Aborigin dan Pribumi Selat Torres). Padahal, penyelenggaraan referendum ini sendiri awalnya merupakan indikasi demokrasi Australia yang kian progresif.
Sekilas, hasil referendum ini menunjukkan kedaulatan rakyat karena adanya proses pemungutan suara yang demokratis. Namun, dalam konteks praktik demokrasi, ini mencerminkan kebangkitan tren demokrasi reaksioner.
Demokrasi reaksioner adalah gambaran kebangkitan rasisme dan populisme yang sekilas tampak sebagai cerminan tuntuan masyarakat, meski sebenarnya kebangkitan tersebut adalah hasil manipulasi yang dilakukan secara sadar oleh elit untuk mendorong kemunculan ide-ide reaksioner.
Dari definisi tersebut, boleh jadi, antiklimaks hasil referendum Australia ini muncul akibat ide-ide reaksioner yang menggagalkan dukungan pengakuan penduduk asli.
Pemimpin oposisi, Peter Dutton dan politikus populis Pauline Hanson menjadi yang terdepan dalam menolak pengakuan penduduk asli dalam konstitusi.
Menurut Hanson, dukungan terhadap perubahan konstitusi hanya akan menambah kekuasaan yang dimiliki oleh penduduk asli. Pandangan ini dinilai rasis dan kian menguatkan istilah Hansonism yang dilekatkan padanya sebagai metafora antiglobalisasi. Hanson juga dikenal sebagai politikus demagog–yang menarik dukungan dengan memanfaatkan isu populer, bukan dengan menggunakan argumen rasional.
Selain antiklimaks hasil referendum, ancaman pendangkalan demokrasi Australia juga sempat marak dengan terjadinya instabilitas politik dalam pemerintahan federal, seperti pergantian perdana menteri yang sengaja dirancang oleh kolega kabinet sendiri, menyimpangi hasil Pemilu.
Baca juga: Dari AHY hingga Kaesang: Politikus Muda Didominasi Dinasti Politik, Kaderisasi Partai Gagal?
Ujian Demokrasi Reaksioner: Dinasti dan Demagogi
Tren politik dunia yang tengah menghadapi ancaman pendangkalan demokrasi memberikan tanda bahwa perjuangan negara merawat demokrasi tidak hanya terjadi di Indonesia.
Meski Indonesia, Australia, dan AS menghadapi konteks masalah berbeda dalam melawan erosi demokrasi, ketiganya tampak menghadapi ujian yang sama: Demokrasi reaksioner yang ditunjukkan dari praktik politik demagogi dan politik dinasti.
Di Australia dan AS, ujian ini lebih terlihat dari pergerakan demagog yang menyebarkan isu-isu reaksioner seperti etnonasionalisme, agama, dan ras. Isu ini dijadikan komoditas politik demi mendulang popularitas dan merebut kekuasaan. Untungnya, kejelasan peran oposisi dalam badan legislatif pada kedua negara tersebut sedikit banyak menangkal kampanye demagogi yang kian memprihatinkan.
Di Indonesia, tidak mudah mengidentifikasi politik demagogi. Di atas permukaan, lebih banyak muncul fenomena dinasti politik yang bertujuan melanggengkan kekuasaan dengan sokongan fanatisme dari para pendukung yang mengidolakan patron.
Demagog dari luar terlihat sebagai seorang yang seolah memperjuangkan rakyat, padahal semua itu sekadar hasutan yang dilakukan demi kekuasaan untuk dirinya. Jika demagog sering diidentikan sebagai suara oposan yang menebar ketakutan demi meraih kekuasaan, hal ini sulit ditemukan di Indonesia.
Pada beberapa hal, ketiadaan oposisi formal dalam sistem pemerintahan Indonesia berpotensi membuka kemungkinan politik demagogi justru dapat muncul dari pucuk penguasa.
Demi keberlangsungan nilai-nilai demokrasi di Indonesia, sikap Jokowi yang selama ini tidak netral dalam kontestasi pemilihan presiden 2024, jika memang harus diteruskan, perlu disajikan dengan pendekatan yang lebih bermartabat guna menghindari kemungkinan kebangkitan politik demagogi dari penguasa.
Hangga Fathana, Dosen Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Karina Utami Dewi, Dosen Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.