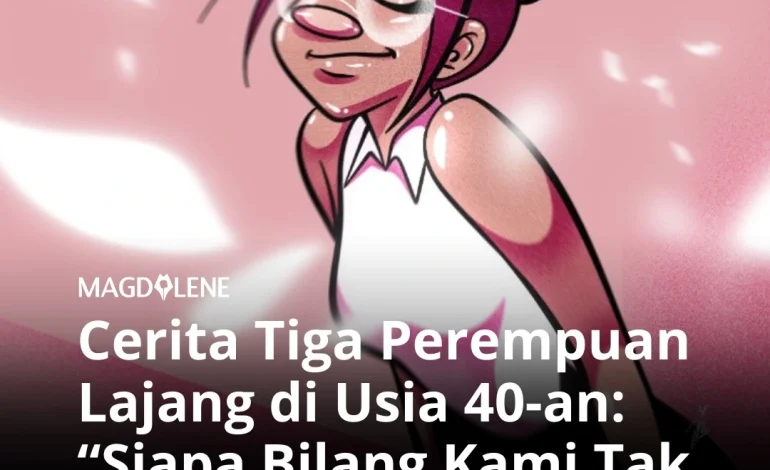Elitisida, Kematian Refaat Alareer, dan Pembunuhan Orang Penting di Palestina

“Jika aku harus mati, kamu harus hidup untuk menceritakan kisahku.”
Penggalan puisi di atas adalah warisan terakhir Refaat Alareer pada dunia. Sebelum mati dibom tentara okupasi Israel (IOF) pada (8/12), puisi yang diunggah di X itu viral di berbagai platform media sosial. Puisinya diterjemahkan ke banyak bahasa dan menghiasi aksi solidaritas pro-Palestina di seluruh dunia.
Orang-orang turun ke jalan membawa poster berisi penggalan puisi Alareer. Ada pula yang menuliskannya di atas layang-layang putih sebagai tanda duka mendalam. Brian Cox, aktor Skotlandia baru-baru ini juga terlihat membacakan kembali puisi Alareer untuk menghormati keguguran dan merawat api perjuangannya.
Alareer sendiri adalah aktivis, penulis, penerjemah, dan profesor sastra di Universitas Islam Gaza yang menginspirasi generasi penulis Palestina di Gaza. Ia menjadi editor Gaza Writes Back (2014), kumpulan cerita pendek dari para penulis muda di Gaza. Dia ikut menyunting Gaza Unsilenced (2015) dan berkontribusi dalam koleksi Light in Gaza: Writings Born of Fire (2022).
Dia juga salah satu pendiri “We Are Not Numbers”, platform yang membimbing para penulis muda untuk menceritakan kisah-kisah warga Palestina yang selama ini hanya dilihat sebagai angka.
Sejak Israel melancarkan agresi militernya di Gaza pada (7/10 ), Alareer merupakan salah satu dari sekian banyak suara dari Gaza yang secara rutin menulis kabar terbaru di media sosial, tampil dalam wawancara, dan menerbitkan puisi. Semua ini lakukan sebagai caranya melawan pendudukan, seraya memberikan gambaran penting dari kehidupan warga Gaza yang terisolasi.
Baca Juga: Ulasan ‘Minor Detail’: Kami Orang Palestina Dianggap Setengah Binatang
Mengenal Elitisida
Tak cukup menargetkan rumah penduduk, perpustakaan, rumah sakit, hingga kamp pengungsian. Dengan dalih memberantas Hamas, Israel rupanya juga menargetkan orang-orang berpengaruh di Gaza, Palestina. Alareer adalah salah satu dari banyak intelektual dan orang-orang berpengaruh di Gaza yang dibunuh oleh IOF.
Sebelumnya dunia kehilangan Dr. Hammam Alloh, spesialis ginjal dari Gaza yang bekerja di Rumah Sakit Al-Shifa–Israel mengklaimnya sebagai sarang Hamas. Ia terbunuh saat serangan udara yang menargetkan rumah keluarga istrinya. Kebetulan rumah tersebut berdekatan dengan rumah sakit Al-Shifa dan kompleks medis, di mana ia sedang beristirahat.
Dunia juga kehilangan Dr. Sufyan Tayeh, Kepala Universitas Islam di Gaza dan anggota terkemuka dalam komunitas Fisika Teoretis dan Matematika Terapan, yang termasuk dalam dua persen peneliti sains teratas di seluruh dunia pada 2021. Serangan udara di daerah Al-Falouja, Jabalia, Gaza Utara menewaskan Tayeh bersama keluarganya.
Sedari awal, terbunuhnya sosok-sosok hebat ini memang kebetulan. Mereka bukanlah korban kerusakan yang selalu diklaim otoritas Israel untuk lepas dari tanggung jawab kejahatan HAM berat. Sebaliknya, Israel memang sengaja menargetkan mereka, dan ini adalah contoh dari elitisida.
Mengutip penelitian yang diterbitkan jurnal Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity (2014), elitisida mengacu pada pembunuhan sistematis pada tokoh-tokoh terkemuka dan berpengaruh dari kelompok etnis, ras, kebangsaan, atau agama tertentu. Tujuan dari elitisida adalah untuk mencegah komunitas yang ditargetkan untuk beregenerasi atau membangun kembali komunitasnya.
Kelompok yang berkuasa dalam hal ini secara sistematis akan menargetkan para intelektual, termasuk dokter, seniman, penulis, jurnalis, akademisi, aktivis, dan pemimpin agama. Pembunuhan terhadap orang-orang yang paling dikenal dan berpengaruh di komunitas dilakukan untuk membuat kita ingat, tidak ada yang aman di sana. Kita dipaksa kehilangan harapan, sehingga enggan melawan atau mengorganisasi diri.
Elitisida adalah istilah yang pertama kali digunakan pada 1992 oleh jurnalis Inggris Michael Nicholson. Istilah itu dipakai untuk menggambarkan pembantaian puluhan orang berpengaruh dan terkemuka di Bijeljina, kota di timur laut Bosnia dan Herzegovina. Setelah kota tersebut diambil alih, unit-unit paramiliter yang didatangkan dari Serbia, dikenal dengan sebutan Harimau Arkan, membawa daftar identifikasi untuk menangkap lalu membunuh anggota-anggota non-Serbia yang merupakan elit politik, intelektual, dan pengusaha setempat.
Tujuh belas tahun kemudian, opini publik terutama dari para sarjana Hukum dan Sosiologi menafsirkan elitisida ini di Bosnia dan Herzegovina sebagai cara untuk memuluskan kebijakan pembersihan etnis. Maka tak heran, Dennis Gratz, anggota Dewan Perwakilan Federasi Bosnia dan Herzegovina yang menulis penelitian ini mengatakan, elitisida merupakan penghancurkan dari atas ke bawah dengan tujuan untuk menguasai komunitas tersebut.
Dalam sejarah manusia, elitisida bukan lagi barang langka. Sudah banyak catatan sejarah–walau tak semuanya secara eksplisit ditulis sebagai elitisida–terjadi di berbagai belahan dunia. Genosida Armenia, misalnya, jika mengacu pada karakteristiknya masuk dalam elitisida. Ini karena menurut Gratz, genosida Armenia secara efektif dilancarkan dengan penangkapan dan deportasi sistematis para elit Armenia di Konstantinopel. Tragedi Holokaus juga terindikasi sebagai elitisida karena banyak intelektual di Jerman pada 1930-an dimasukan ke kamp konsentrasi dan dibunuh. Genosida di Kamboja (1979), Burundi (1972), Bangladesh (1971), atau Rwanda (1994) juga memasuki unsur elitisida.
Salah satu elitisida paling menonjol dan masih terjadi hingga saat ini adalah yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Tiongkok (RRC) kepada Suku Uyghur. Dalam laporan pelanggaran HAM Uyghur Tribunal, setidaknya tercatat 341 kasus penahanan, pemenjaraan, dan penghilangan paksa terhadap warga Uighur dan intelektual Turki lainnya dari 2017 hingga Maret 2021. Angka ini diklaim Uyghur Tribunal lebih besar, mengingat bagaimana RRC dengan rapi menyembunyikan kejahatan HAM berat mereka.
Baca Juga: Magdalene Primer: Yang Perlu Diketahui tentang Isu Palestina-Israel
Elitisida Palestina
Committee to Protect Journalists (CPJ) dalam laporan investigasi mereka mencatat, sejak 7 Oktober hingga 11 Desember, 63 jurnalis dan pekerja media telah terbunuh. Angka ini disusul dengan sebelas jurnalis yang dilaporkan terluka, tiga jurnalis dilaporkan hilang, dan 19 jurnalis dilaporkan ditangkap oleh otoritas Israel.
Hari paling mematikan dalam agresi militer militer ini adalah hari pertama, 7 Oktober, dengan enam jurnalis terbunuh dan hari paling mematikan kedua terjadi pada 18 November, dengan lima orang terbunuh. Ini membuat IOF bertanggung jawab atas 80 persen pembunuhan jurnalis dan pekerja media di wilayah Palestina dalam database CPJ.
Sebagai perbandingan, 63 jurnalis terbunuh dalam Perang Vietnam yang berlangsung selama dua dekade, dan total 69 jurnalis terbunuh dalam Perang Dunia II (1939-1945). Dalam pembelaannya, Israel selalu mengatakan jurnalis terbunuh oleh kelompok militan, bagian dari kerusakan kolateral dalam situasi konflik, atau bahkan dicap sebagai teroris. Salah satu retorika ini terjadi pada narasi pembunuhan jurnalis Amerika Palestina Shireen Abu Akleh pada 2022 yang menurut keterangan IOF terbunuh karena tidak sengaja terkena tembakan IOF yang dilepaskan ke arah tersangka–yang diidentifikasi sebagai orang-orang bersenjata Palestina.
Beberapa minggu setelah pernyataan akhir IOF, Arsitektur Forensik dan organisasi HAM Palestina, Al-Haq, menerbitkan laporan bersama yang merekonstruksi keadaan pembunuhan tersebut. Berdasarkan rekonstruksi digital dan optik dari penglihatan penembak, rompi pers para jurnalis akan terlihat jelas selama kejadian, sehingga IOF memang secara sengaja meloloskan pelurunya kepada Shireen Abu Akleh.
Kematian demi kematian jurnalis Palestina oleh IOF ini, kata CPJ, punya pola pembunuhan berbahaya. Dalam hukum internasional, menargetkan dengan sengaja dianggap sebagai kejahatan perang. Media tidak dapat dianggap sebagai target militer bahkan ketika mereka digunakan untuk tujuan propaganda kecuali jika mereka memberikan “kontribusi yang efektif terhadap aksi militer” atau “menghasut kejahatan perang, genosida, atau tindakan kekerasan,” menurut Komite Palang Merah Internasional. Karena itu, jurnalis seharusnya mendapatkan kebebasan dan perlindungan untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa terancam keselamatannya.
Walaupun dalam hukum dan kesepakatan internasional sudah diatur, Israel nyatanya tetap kebal hukum. Selama lebih dari 22 tahun, CPJ mencatat Israel tidak pernah mengadili seorang tentara atas pembunuhan yang disengaja atau tidak disengaja terhadap jurnalis. Sampai saat ini belum ada pengadilan internasional yang mampu menghadirkan Israel sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan. Hal yang menurut media Vox, terjadi karena Israel memiliki sekutu kunci Internasional yang akan terus menjaganya.
Tak hanya jurnalis, tenaga medis dan pengusaha Palestina juga jadi target pembunuhan Israel. Per 16 November lalu sudah tercatat 200 petugas kesehatan yang terbunuh di Gaza sejak dimulainya agresi militer Israel, menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Angka ini terus bertambah tiap harinya mengingat serangan Israel meningkat pasca-gencatan sementara.
Sama kasusnya dengan para jurnalis, pembunuhan tertarget ini tidak terjadi setelah 7 oktober saja. Al Jazeera pada 2021 melaporkan dua dokter senior, seorang ahli saraf dan kepala bagian penyakit dalam di rumah sakit terbesar di Gaza terbunuh dalam serangan Israel. Pada 2022, Dr Abdullah al-Ahmad di Kota Jenin, Wilayah Pendudukan Palestina (OPT) kata kementerian kesehatan Palestina. Dr Abdullah al-Ahmad meninggal dunia akibat luka tembak di kepalanya yang ditembakkan oleh IOF.
Pengusaha Palestina punya nasib sama. Hal ini dikonfirmasi dalam laporan terbaru Al Jazeera pada 3 Desember lalu. Tercatat sejak 7 Oktober lalu Israel telah membunuh pengusaha terkenal di Gaza. Tiga di antaranya adalah Tariq Thabet, Abdelhamid al-Fayoumi, dan Yasser al-Alam.
Baca Juga: Epistemisida: Saat Israel Bakar Buku, Bom Sekolah, dan Hapus Sejarah Palestina
Thabet adalah pimpinan inkubator bisnis di University College of Applied Sciences di Gaza, al-Fayoumi adalah pendiri Sanabel, perusahaan yang memproduksi perangkat lunak dan sumber daya multimedia untuk pasar lokal dan regional Arab. Sedangkan, al-Alam disebut-sebut sebagai bapak kewirausahaan di Gaza karena dikenal pandai menemukan solusi yang tidak terduga dan menciptakan strategi pemasaran yang inovatif.
Terbunuhnya para pengusaha sangat berdampak bagi masyarakat Palestina. Mereka adalah sosok di balik peningkatan prospek lulusan baru di Gaza. Mereka membuka lapangan kerja di saat Gaza tercatat menempati salah satu tingkat pengangguran yang tertinggi di dunia karena mencapai 70 persen di antara para lulusan muda. Dan lewat inovasi-inovasi, mereka berusaha membangun kehidupan yang lebih baik bagi warga Palestina.
Sayangnya, buat dunia, kematian mereka tidak berarti apa-apa. Hingga hari ini gencatan senjata permanen tidak pernah terjadi. Sebaliknya, Israel yang disokong penuh oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Barat lainnya terus meningkatkan agresi militernya.
Bahkan hingga (11/12), Amerika Serikat telah menggunakan hak veto untuk menolak resolusi gencatan senjata di Gaza. Sampai pada titik pemerintah dunia yang punya tanggung jawab dan kekuasaan menolak mengambil tindakan tegas untuk meminta pertanggungjawaban Israel, maka sesuai apa yang dikatakan Amnesty International, Israel akan terus melakukan kekerasan terhadap Palestina.
llustrasi oleh Karina Tungari