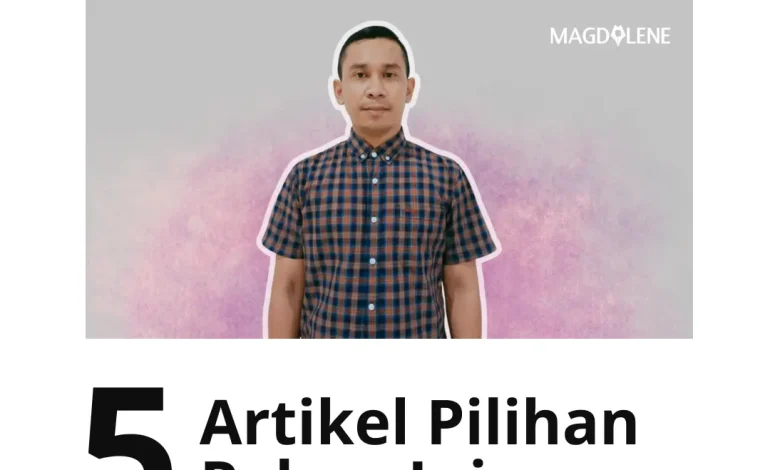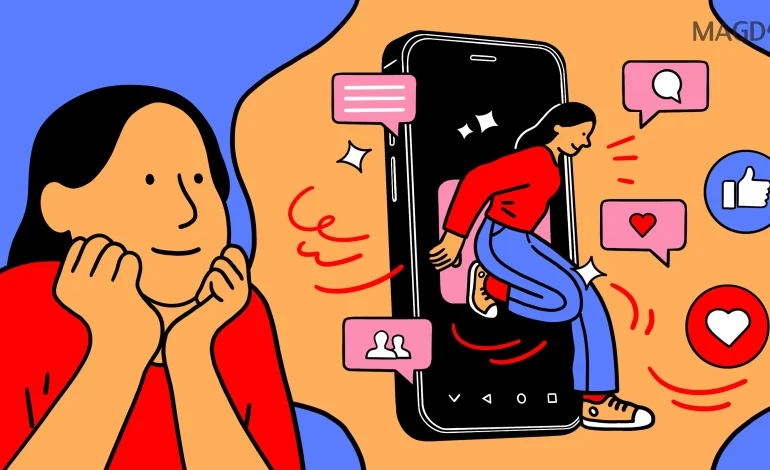Menonton ‘Aftersun’, Menonton Depresi dalam Wujud Mentahnya

Sophie (Frankie Coiro), remaja 11 tahun, pergi liburan dengan ayahnya Callum (Paul Mescal), yang masih 31 tahun. Mereka berlibur ke Turki: berenang, bercanda, makan malam, karaoke, dan hal-hal lain yang wajar dilakukan saat berlibur. Namun di bawah terik matahari dan di antara tiap canda yang mereka bagi, sesuatu terasa ganjil.
Melalui potongan-potongan rekaman MiniDV yang kemudian ditonton oleh Sophie dewasa, kita perlahan memahami bahwa perjalanan itu adalah yang terakhir. Setelah liburan usai, film memberi insinuasi, bahwa Calum mengakhiri hidupnya.
Tragedi itu tak pernah tampil secara eksplisit. Charlotte Wells, sutradara Aftersun, piawai memperlihatkan yang akan amat mudah terlewat: kegelisahan yang samar di balik tawa dan kemurungan mendalam yang disembunyikan di balik obrolan santai.
Sebagai seseorang yang didiagnosis depresi, buat saya, representasi Callum terasa begitu tepat—nyaris terlalu akurat. Bukan karena ia berbicara tentang depresi secara terbuka, tetapi karena Wells mengartikulasikannya lewat momen kecil yang mencekik: tangan yang gemetar, pandangan kosong di tengah tawa, atau saat ia menghela napas di ujung kalimat yang diucap.
Baca juga: ‘A Poet’: Kemalangan Lulusan Humaniora yang (Sayangnya) Lucu
Depresi dalam Aftersun hadir sebagai pergeseran waktu dan persepsi. Wells sering menahan kameranya sedikit lebih lama dari umumnya, membuat kita duduk di antara dua perasaan: cinta dan kehilangan.
Callum sering dipotret melalui cermin, dari belakang, atau di luar bingkai—seolah ada jarak tak kasatmata antara dia dan dunia. Persis cara depresi bekerja: menciptakan kabut antara diri dan realitas.
Ketika Callum bilang, “surprised I made it to 30,” kalimat itu tak terdengar seperti pengakuan. Ia lebih terdengar seperti permintaan maaf.
Simbol air hadir prominen. Adegan Sophie menyelam di kolam, ombak yang menelan suara, warna biru yang menyelimuti kamar hotel; semua seolah menandai perasaan tenggelam yang dialami Callum, tempat waktu melambat, dunia teredam, dan segalanya terasa jauh. Dalam level naratif, Aftersun tidak pernah secara gamblang “mengumumkan” tema soal depresi.
Alih-alih, ia memperlihatkan bagaimana kesedihan mendalam yang kadang tak terdefinisikan itu menenggelamkan Callum secara perlahan.
Musik, Memori, dan Upaya untuk Bertahan
Aftersun adalah film tentang ingatan; tentang bagaimana seseorang mencoba menggenggam kenangan yang seiring waktu terus meregang.
Sophie dewasa menonton rekaman liburannya bukan semata-mata hanya untuk bernostalgia, tetapi untuk mencari makna: siapa ayahnya sebenarnya, dan apa yang ia lewatkan saat kecil. Dalam proses itu, kita ikut berada di posisinya: menafsirkan potongan gambar, menebak apa yang saat itu Callum coba sembunyikan.
Wells menjadikan kamera bukan hanya alat dokumentasi, tapi juga alat bertahan hidup. Bagi Callum, kamera memberi jarak dari realitas pedih yang menggerogotinya; bagi Sophie, kamera adalah satu-satunya cara untuk mendekatinya lagi.
Film ini menolak gaya penceritaan linear. Ia bergerak seperti kenangan itu sendiri: loncat, kabur, dan hadir di antara waktu. Di sela-sela scene, ruang dan masa bercampur dalam cuplikan adegan rave: Sophie dewasa menari di tengah lampu strobo, mencoba meraih ayahnya yang hilang di kerumunan. Mereka saling mencari, lalu saling memeluk sebelum ia menghilang.
Rave ini adalah ruang duka, tempat Sophie memproyeksikan kerinduan yang tak pernah selesai. Di sanalah Callum hidup untuk terakhir kalinya. Bukan di dunia nyata, tapi di ingatan anak yang terus mencintainya.
Wells memperkuat seluruh perjalanan emosional ini melalui pilihan lagu yang nyaris berfungsi sebagai narasi tersendiri.
Baca juga: ‘It Was Just An Accident’: Saat Penyintas Tahanan Politik Tergoda Jadi Algojo
Setiap lagu dalam soundtrack—dari Tender oleh Blur hingga Losing My Religion oleh R.E.M.—memikul beban emosional yang semakin berat saat kita sudah tahu akhir ceritanya. Lirik “I thought that I heard you laughing, I thought that I heard you sing, I think I thought I saw you try” yang dinyanyikan Sophie dalam sebuah sesi karaoke, secara tidak langsung adalah pembacaannya atas situasi sang ayah. Lagu itu mengungkapkan apa yang tidak pernah diucapkan Calum: bahwa ia telah berusaha, bahkan ketika usahanya nyaris tak terlihat dan berdampak.
Puncak emosional film hadir dalam bentuk adegan lantai dansa yang diiringi Under Pressure oleh Queen dan David Bowie. Lagu ini, yang memang mengandung kemurungan dalam kemasan beat bersemangat, justru bekerja memperdalam lapisan makna naratif adegannya. Refrain: “Why can’t we give love, give love?” yang diulang-ulang, membuat gerakan dansa bebas yang dilakukan Callum di bawah gemerlap cahaya lampu terasa begitu menyayat dan memilukan.
Lirik itu mengkomunikasikan dengan begitu jelas, tentang penyadaran bahwa memberi cinta pada seseorang tidak serta merta akan menyembuhkan mereka.
Dan ketika Bowie menyanyikan “Love dares you to care for people on the edge of the night,” di shot yang memperlihatkan Sophie kecil, menyadarkan kita tentang bagaimana Sophie mencoba memahami ayahnya yang berada di tepi gelap itu, meskipun di saat yang sama, sebagai anak kecil, ia belum benar-benar tahu apa yang ia lihat.
Di satu scene, Sophie berkata, “It’s nice we all share the same sky”. Kalimat polos ini, yang pada awalnya terdengar hangat, akhirnya memiliki interpretasi yang memilukan di akhir: mereka memang berbagi langit, tapi tidak bisa berbagi cahaya yang sama. Calum berjuang untuk hidup, sementara Sophie perlahan belajar tentang kehilangan.
Dan mungkin inilah mengapa setelah film berakhir, penonton di studio tempat saya menonton terdiam lama. Beberapa tepuk tangan kecil, tapi kebanyakan yang terdengar adalah kesunyian panjang, seolah setiap orang baru saja menyaksikan seseorang yang sudah tiada.
Film ini sudah tayang 2022 lalu, tapi karena reputasinya sebagai film kultus, ia diputar lagi di bioskop Indonesia melalui program Matinee Screening—sebuah inisiatif menghidupkan kembali budaya menonton di pagi hari; waktu yang tepat untuk film yang membicarakan senja di dalam diri.
Aftersun menunjukkan bahwa mencintai seseorang dengan depresi tidak selalu berarti menyelamatkannya; terkadang, cinta hadir dalam bentuk keberanian untuk tetap duduk di samping mereka, meski kita tahu, sebanyak apa pun kata-kata baik yang diucapkan belum tentu bakal sanggup menarik mereka dari lubang kegelapan.