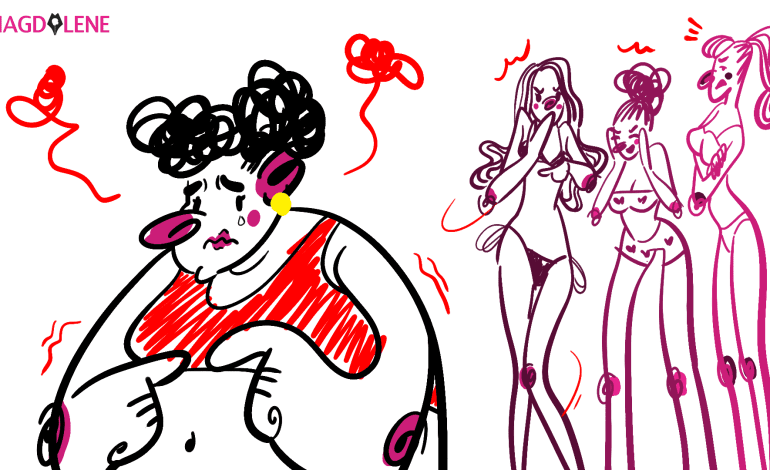Restitusi Korban Kekerasan Seksual dan Victim Trust Fund Masih Hadapi Tantangan

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang ustaz dan pemilik Madani Boarding School, Herry Wirawan sempat jadi headline nasional. Vonis hukuman mati yang diberikan Makhkamah Agung sempat menimbulkan perdebatan tentang hukuman buat pelaku perkosaan.
Selain hukuman mati, hakim juga memutuskan restitusi atas 13 korban dibebankan sepenuhnya pada Herry, bukan pada negara. Vonis ini menganulir putusan PN Bandung, yang sebelumnya membebaskan Herry dari pembayaran restitusi korban.
Kini Herry diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp331.527.186 kepada korban. Tiap korban mendapat restitusi dengan nominal beragam, lewat penjualan dan penyitaan aset pribadinya.
Restitusi korban yang ditanggung pelaku juga kembali jadi obrolan, karena penetapannya yang ditanggung oleh pelaku. Tapi, apa sebenarnya hak restitusi?
Apa Itu Restitusi dan Kenapa ini Penting?
Menurut Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mekanisme pelaksanaan restitusi yang bahkan belum banyak dikenal baik oleh aparat penegak hukum sendiri.
Mengacu Jurnal Risalah Hukum Vol. 17 No. 1 (2021), kompensasi dan restitusi adalah upaya pemenuhan hak atas korban dalam suatu perkara pidana. Keduanya dibikin berdasarkan konsep ganti rugi, tapi memiliki perbedaan signfikan.
Pertama, kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau negara. Karena itu kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman berikut efek jera atas tindak pidana yang pelaku lakukan.
Sebaliknya, tuntutan ganti rugi dalam restitusi dilakukan melalui putusan pengadilan dan sepenuhnya dibayar oleh pelaku tindak pidana. Restitusi diharapkan bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku. Tak hanya itu, berbeda dengan kompensasi, restitusi lebih mengedepankan pemenuhan hak korban.
Rainy Maryke Hutabarat, Komisioner Komnas Perempuan mengatakan, dalam kasus kekerasan seksual sering kali korban harus menanggung biaya materil dan non materil seorang diri. Korban tak hanya harus menggelontorkan biaya yang tak murah untuk melakukan visum et repertum atau tes DNA. Tetapi, mereka juga rentan mengalami hambatan fisik, psikis, sosial maupun pemenuhan hak-hak asasi lainnya seperti hambatan atas pendidikan, karier, dan hak politik.
Pengabaian penanganan kekerasan seksual secara hukum serta dampak yang korban alami bisa mengakibatkan perempuan korban mengalami trauma berkelanjutan bahkan disabilitas psikososial (gangguan kesehatan jiwa).
“Dalam pemantauan panti rehabilitas dan rumah sakit jiwa di berbagai wilayah di Indonesia, misalnya Komnas Perempuan mendapati bahwa banyak perempuan disabilitas psikososial yang dirawat, merupakan korban kekerasan seksual,” kata Rainy pada Magdalene.
Itu sebabnya, korban memerlukan pemulihan komprehensif. Artinya, diperlukan biaya sekurangnya untuk pemulihan fisik berupa pengobatan medis dan psikis seperti konseling hingga korban pulih dan dapat melanjutkan kehidupannya dan menjalankan peran-peran sosialnya secara penuh.
“Restitusi yang diberikan kepada korban juga bertujuan untuk membiayai proses pemulihan berbagai dampak kekerasan seksual yang dialami termasuk waktu, transportasi dan dan lain-lainnya. Restitusi perlu diberikan kepada korban dengan memastikan jumlah yang diberikan dapat membiayai seluruh proses pemulihan yang optimal agar hak-haknya terpenuhi,” jelas Rainy.
Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara yang juga diwawancarai oleh Magdalene kemudian menjelaskan pelaksanaan restitusi sendiri harus sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula atau restitutio in integrum. Hal ini karena restitusi merupakan upaya pengembalian keadaan korban pada kondisi semula sebelum terjadinya tindak pidana lewat pemenuhan keadilan yang maksimal.
Meskipun praktiknya korban tidak mungkin kembali ke kondisi semula karena sudah banyak kehilangan haknya, menurut Bivitri, restitusi adalah bentuk pemulihan yang harus dicapai dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
“Korban kan mendapatkan kerugian besar. Mereka butuh pendampingan, enggak bisa kerja karena kondisi psikologis, dapet stigma, makanya lewat restitusi ini korban dapat dipulihkan hak-hak hukum dan ekonominya, hak dan status sosialnya, dipulihkan juga traumanya,” ungkap Bivitri.
Jumlah nominal biaya restitusi yang diterima setiap korban juga berbeda. Hal ini karena menurut Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK, korban memiliki kebutuhan yang berbeda. Apalagi dalam mekanisme pengajuan restitusi, pengajuan nilai kerugian awal berasal dari korban yang selanjutnya baru dinilai kewajarannya oleh LPSK.
“Kebutuhannya kan beda-beda. Mulai dari harta benda yang hilang akibat peristiwa, biaya transportasi dalam proses hukum, biaya medis, psikologis, sampai biaya bersalin, tentu setiap korban berbeda-beda jadi enggak bisa disamaratakan.”
Tantangan Pemenuhan Hak Restitusi
Sebelum UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disahkan April 2022 lalu, mekanisme pengajuan restitusi telah diatur dalam UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah (PP) No 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban.
Kendati sudah diatur dalam perundang-undangan, pemenuhan hak korban melalui restitusi masih menghadapi tantangan.
Dikutip dari Laporan Tahunan LPSK Tahun 2021, masih terdapat perbedaan persepsi dalam pemenuhan hak restitusi. Misalnya, nilai yang diajukan LPSK kepada hakim dengan besaran nilai restitusi yang diputuskan hakim berbeda. Korban tak jarang dianggap “menikmati eksploitasi seksual” yang dialaminya. Ini terjadi karena perspektif korban masih sangat minim dimiliki aparat penegak hukum.
Kedua, terdapat argumen dari aparat yang menangani perkara bahwa dia belum punya pengalaman dalam mekanisme restitusi. Dengan ini, hakim akhirnya hanya memutuskan nilai materiil dan tidak dapat menerima penilaian immaterial yang dimohonkan korban. Kerugiannya hanya disandingkan dengan bukti pengeluaran yang sah.
Ketiga, dalam laporan Tahunan LPSK pada 2020, pencapaian eksekusi restitusi untuk korban kurang dari 10 persen dari yang dijatuhkan pengadilan, yaitu hanya di angka sekitar Rp101 juta.
Padahal penilaian restitusi yang dilakukan oleh LPSK berada di angka sekitar Rp7 miliar, sedangkan angka yang dikabulkan oleh putusan pengadilan hanya Rp1,3 Milyar. Satu tahun berlalu, pencapaian eksekusi restitusi untuk korban pun tetap sama. Dari total putusan pengadilan yaitu Rp3,7 miliar, pelaku hanya membayar sebesar Rp279 juta.
Edwin mengatakan minimnya pencapaian eksekusi restitusi ini sering tersandung kesediaan dan kemampuan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban. Jika tidak diikuti dengan langkah-langkah dan upaya tertentu (“memaksa” pelaku) untuk membayar restitusi, sudah dapat dipastikan sebagian besar pelaku akan memilih untuk menyatakan ketidakmampuan dan ketidakbersediaan membayarkan restitusi.
Dalam UU TPKS sendiri, restitusi dinilai lebih progresif karena dijadikan sebagai pidana pokok. Berbeda dari peraturan sebelumnya, yang menempatkan restitusi sebagai pidana tambahan.
Namun, UU TPKS hadir bukan tanpa cela. Edwin mengeluhkan UU TPKS masih membuka ruang hukuman subsider atau hukuman pengganti pada pelaku. Dalam pasal 33 ayat 35 dinyatakan bahwa terpidana yang harta kekayaannya tidak mencukupi biaya restitusi, bisa dikenai pidana penjara pengganti.
“Masih adanya hukuman subsider yang bahkan rata-rata hanya berkisar tiga bulan saja, pelaku jadi tidak menerima efek jera,” keluh Edwin.
Baik Bivitri maupun Rainy kemudian menambahkan, perkara ini diperparah dengan belum adanya Dana Bantuan Korban atau Victim Trust Fund. Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, sebagaimana dimaksud dalam UU TPKS Pasal 33 ayat 71, negara wajib memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada korban lewat Dana Bantuan Korban.
Dana Bantuan Korban ini dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sayangnya hingga saat ini, Dana Bantuan Korban berikut dengan aturan-aturan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan oleh UU TPKS berupa peraturan pemerintah dan peraturan presiden masih dalam proses pematangan.
“Dari bulan Juli kita sudah melakukan rapat koordinasi penyusunan aturan turunan UU TPKS. Ngerjainnya bareng pemerintah, Kemenkumham, KemenPPPA. Ada sepuluh aturan yang diminta, salah satunya mengenai kompensasi negara untuk restitusi. Tapi, sampai sekarang pemerintah belum bisa mengakomodasi. Mereka terkunci dengan sistem mereka sendiri,” jelas Bivitri.
Seraya terus mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden, Rainy menegaskan ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan pemerintah dalam menjamin terpenuhi hak korban secara menyeluruh.
Pertama, pemerintah harus memperkuat LPSK dalam anggaran, agar restitusi dibayarkan seturut pemenuhan hak-hak korban. Kedua, melakukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar berperspektif korban.
Terakhir, pemerintah juga perlu menggandeng dan memperkuat lembaga-lembaga layanan korban berbasis masyarakat sipil selain berbasis pemerintah dalam mengimplementasikan amanat UU TPKS.