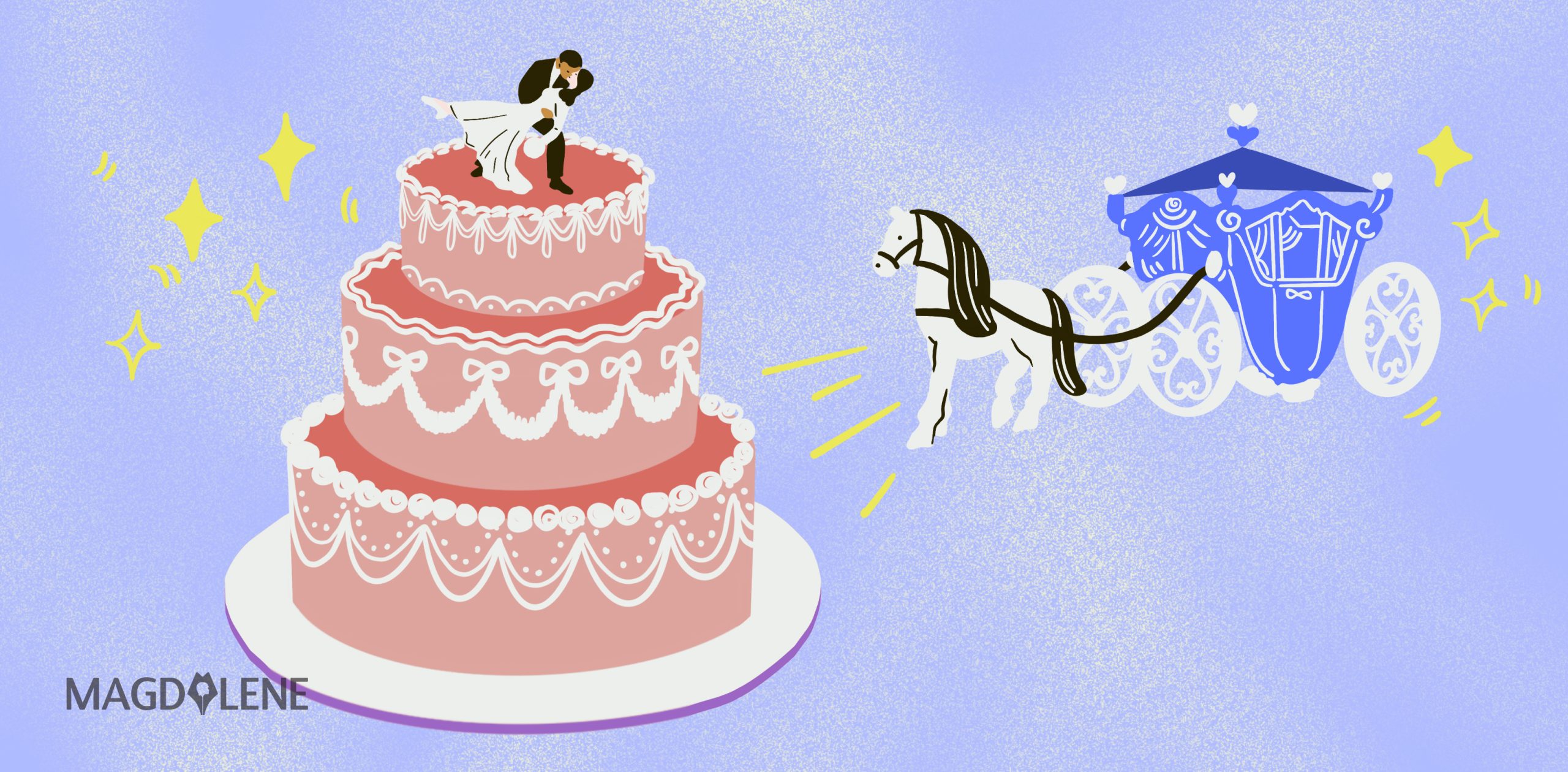Jangan Takut Disebut ‘Baper’
Masalahnya bukan hanya tentang asumsi yang salah bahwa perempuan selalu emosional, tapi juga bagaimana kita menganggap emosi sebagai sesuatu yang buruk karena "terlalu perempuan."

Saya dan teman-teman selalu mencoba menciptakan suasana dimana kami bisa bicara blak-blakan tentang pikiran, pendapat dan hubungan kami satu sama lain. Kami sepakat bahwa bicara apa adanya itu perlu. Teman-teman percaya saling terbuka itu produktif, meskipun tingkatnya berbeda-beda. Mereka ini orang-orang yang sangat berpengetahuan, progresif dan cerdas yang bisa berargumen secara logis dan jelas. Tapi mereka tidak sempurna.
Suatu kali dalam pembicaraan kami, saya merasa beberapa di antara mereka bersikap meremehkan saya. Saat suasana memanas, nada suara saya menjadi emosional, dan saya merasa itu wajar. Beberapa waktu kemudian, ketika kami membicarakan hal itu kembali, saya mengatakan kepada mereka bahwa saya merasa diremehkan dan tidak dihormati. Hal itu saya ungkapkan dengan semangat keterbukaan dan juga untuk menjelaskan kenapa saya bersikap emosional. Sebagai perempuan yang blak-blakan, saya berbicara dengan semangat dan menunjukkan emosi saya.
Setelah menjelaskan panjang lebar, saya merasa nyaman karena jujur pada diri sendiri, tidak seolah-olah “tangguh” dan berpura-pura mereka tidak membuat saya jengkel. Dan salah satu dari mereka kemudian bilang bahwa saya “Baper” dan yang lainnya mengangguk mengiyakan. Baper, alias bawa perasaan, menjadikan sesuatu personal, atau terlalu emosional.
Saya terdiam, sambil menahan tangis, dan saya menyerah setelah dua teman laki-laki saya mengalihkan fokus ke kondisi emosional saya. Mereka mengecewakan saya. Saya pikir, orang-orang yang dihormati dan cerdas seperti mereka tahu pentingnya memperlakukan manusia lain dengan baik. Tapi saya terutama paling kecewa dengan diri saya sendiri karena membiarkan pernyataan yang seksis itu.
Seksisme halus di balik pernyataan tersebut tidak saya sadari sampai saya renungkan sedikit. Ini karena sebagai seseorang dengan hak istimewa untuk berada dalam sekelompok orang-orang intelek, saya menjadi korban sebuah ideologi yang menempatkan logika dan rationalitas di atas segalanya. Dua hal itu bukan segalanya. Tapi lebih penting lagi, narasi itu terlalu sering digunakan untuk menyalahkan perempuan, sama seperti orang-orang mengatur nada suara perempuan Afrika-Amerika untuk membuat mereka diam.
Perempuan telah melakukan perjalanan panjang demi kemajuan, tapi tidak berarti masyarakat berhenti memberi gambaran yang salah tentang perempuan, bahwa mereka makhluk emosional dan irasional. Pemikiran ini meluas sampai bagaimana masyarakat mendiskreditkan konsep emosi hanya karena hal itu diasosiasikan dengan perempuan. Masalahnya bukan cuma asumsi yang salah bahwa perempuan selalu emosional, tapi juga bagaimana kita menganggap emosi itu buruk karena dianggap “terlalu perempuan” – sesuatu yang tidak seharusnya didukung atau ditonjolkan.
Ada dilema di sini. Kita mungkin berpikir bahwa untuk melawan stereotip perempuan harus menunjukkan bahwa kita bisa rasional dan logis, karena kita memang bisa. Itu sama sekali tidak salah. Yang saya ingin katakan di sini adalah kita harus terbuka dengan ide bahwa kita bisa logis sambil tetap punya sentimen. Kita tidak perlu mendiskreditkan sentimen agar dianggap rasional atau logis. Kita menolak ide bahwa sentimen itu buruk, bukan sentimen itu sendiri.
Kita tidak seharusnya dianggap kurang intelek karena memiliki emosi. Sebaliknya, kita jauh lebih intelek dengan memasukkan emosi ke dalam berperilaku dan berpikir. Orang-orang yang pintar harus berbicara ketika mereka diserang secara emosional, bukannya menutup emosi mereka. Untuk itu, orang-orang pintar seharusnya tahu bahwa emosi orang lain bukanlah sesuatu yang harus dicemoohkan.
Saya percaya bahwa intelektualitas tidak disertai dengan hak istimewa untuk mendikte orang lain mengenai apa yang harus mereka lakukan, perasaan mereka, atau perilaku mereka. Intelektualitas adalah hak istimewa yang mewajibkan orang-orang untuk beradaptasi dengan orang lain, karena mereka bisa mengkalkulasi manfaat menjadi adaptif di dalam masyarakat secara umum. Intelektualitas seharusnya berarti bahwa kita tidak boleh membuat orang lain diam dengan menanamkan standar perilaku sosial yang patriarkal.
Jika perasaanmu disakiti, berbicaralah. Tidak ada yang boleh menjadikan perasaan kita tidak valid. Karena hal itu seksis.
Rachel Diercie sedang belajar Bahasa Perancis di Universitas Indonesia. Ia seorang introvert yang aneh, sangat gemar literature, seorang aktivis pencegahan bunuh diri, dan seorang perempuan dengan sikap progresif dan feminis yang digugahkan oleh debat.