Kekeliruan Logika Revina VT: Tanggapan Atas Tulisan ‘Feminisme Garis Logis’
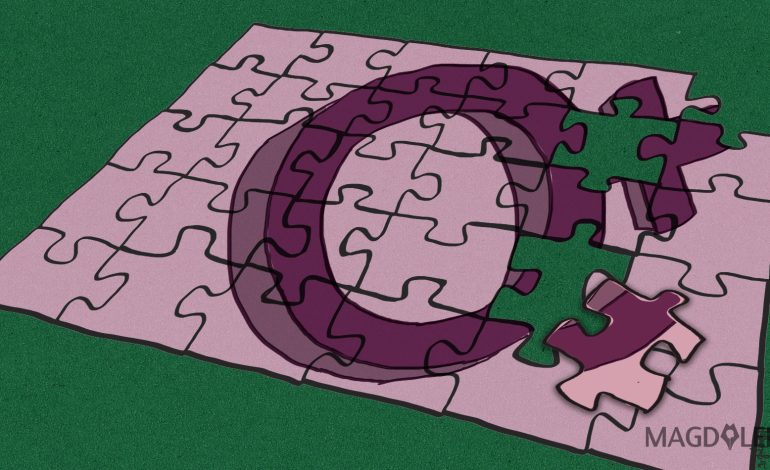
Baru-baru ini, jagat media sosial memanas akibat perdebatan yang diinisiasi oleh tulisan Revina VT dalam laman Geolive.id yang berjudul “Feminisme Garis Logis”. Tulisan itu dibagikan warganet di media sosial dan menuai banyak dukungan maupun kritikan.
Pada awal tulisan, Revina mengkritik kelompok yang ia sebut sebagai “feminis media sosial”. Secara tersirat, ia mengecap kelompok feminis media sosial tersebut sebagai orang-orang yang tidak mampu berpikir lurus dan tidak berpengetahuan dasar.
Revina kemudian mempertanyakan integritas feminis media sosial yang menurutnya terlalu vokal melindungi perempuan ketika ia menuntut laki-laki untuk bertanggung jawab atas kehamilan yang tidak diinginkan, ketimbang mengajari perempuan agar mampu berpikir logis dan lebih sadar atas risiko dari perbuatannya sendiri. Bertolak dari radikalisasi slogan “tubuhku adalah otoritasku”, ia menegaskan bahwa sebenarnya perempuan sendirilah yang harus dituntut untuk berani bertanggung jawab atas perbuatannya.
Ia mengatakan, “Menurut saya, otoritas tubuh manusia berjalan seiring dengan tanggung jawab manusia itu sendiri terhadap tubuhnya. Logis saja”.
Memang benar bahwa jika manusia memiliki otoritas penuh atas tubuhnya sendiri, maka ia sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan apa yang dilakukan. Pemikiran yang serupa itu bisa ditemukan dalam banyak pemikir eksistensialis. Tetapi, apakah kemudian illogical jika feminis berperan aktif dalam membantu perempuan untuk menuntut laki-laki supaya bertanggung jawab dalam sebuah kasus kehamilan yang tak diinginkan (KTD)? Dan apakah benar pandangan bahwa kehamilan itu adalah kecerobohan dari perempuan sendiri sehingga ia harus siap dengan risikonya?
Terlalu parsial
Di sepanjang tulisannya, Revina berfokus pada tindakan perempuan dan keharusannya untuk siap menanggung risiko atas kehamilan sebagai konsekuensi dari tindakan dan consent-nya sendiri. Sebenarnya, perspektif tersebut bukan berarti sepenuhnya salah, hanya saja parsial. Pasalnya, dalam sebuah aktivitas seksual, kehamilan bisa terjadi akibat aktivitas seksual laki-laki dan perempuan. Karena kehamilan sebagai hasil tindakan bebas kedua orang tersebut memiliki konsekuensi bagi mereka, tentu keduanya secara otomatis menanggung beban atas tindakannya itu.
Revina berangkat dari premis bahwa “Ketika pemilik vagina sudah mengizinkan sebuah penis masuk ke dalam liangnya, ketika itulah dia sudah mengatakan ‘iya’ pada segala risiko yang ada dan siap dengan segala konsekuensinya”. Agar kalimat parsial itu menjadi utuh, maka perlu ditambahkan premis yang juga penting: “Begitu pula berlaku pada laki-laki. Ketika pemilik penis sudah memutuskan untuk memasukkan penisnya ke dalam vagina perempuan, ketika itulah dia sudah mengatakan ‘iya’ pada segala risiko yang ada dan siap dengan segala konsekuensi atas tindakannya”. Bukan hanya “kebersediaan perempuan untuk dimasukkan penis ke dalam vaginanya” yang menjadi soal, melainkan juga “kebersediaan laki-laki untuk secara sadar memasukkan penis ke dalam vagina pasangannya”.
Di satu sisi, argumen Revina sangat kritis dan mendorong perempuan agar berani bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Namun di sisi lain, sikap kritisnya itu tumpul terhadap laki-laki atas tindakan bebas yang mereka pilih dan konsekuensinya. Revina menuntut perempuan agar siap menanggung risiko, tetapi pada saat yang sama, ia begitu saja mengesampingkan (dominasi) laki-laki dan keharusannya juga dalam menanggung risiko. Dalam proses penalaran logisnya, ia sepenuhnya tidak konsisten, jika tidak monistik, karena telah mengesampingkan variabel laki-laki (yang merupakan premis penting) di dalam proses reproduksi sebagai subjek yang juga bebas dalam mengambil tindakan, dan dengan demikian, juga memikul beban atas tindakan tersebut.
Baca juga: Feminisme untuk Keadilan, Bukan Feminisme Pengakuan
Katakanlah kita mengikuti jalan pikir Revina itu. Katakanlah bahwa perempuan sebagai sang pemilik tubuh bertanggung jawab atas kehamilan, yaitu proses dan sensasi biologis yang terjadi secara badaniah di dalam dirinya sendiri, karena tubuh perempuan adalah otoritasnya. Namun, begitu sampai pada tahapan kelahiran seorang keturunan (bayi) sebagai sebuah entitas yang eksis, tanggung jawab bayi tersebut tetap dibebankan pada kedua orang tuanya. Pasalnya, secara kausatif, keturunan tersebut merupakan konsekuensi logis dari tindakan bebas keduanya. Tidak logis bila kita melimpahkan tanggung jawab atas KTD kepada perempuan sendiri, atau mengatakan KTD sebagai bentuk kecerobohannya.
Dari penjabaran di atas, maka sebenarnya kritik Revina kepada kelompok “feminis media sosial” menjadi tidak berdasar, karena justru apa yang sesungguhnya dilakukan oleh kelompok tersebut adalah upaya merestorasi kembali tanggung jawab yang seharusnya dipikul bukan hanya oleh pihak perempuan saja, melainkan juga oleh pihak laki-laki.
Teoretikus sosial bukan motivator
Walau demikian, sebenarnya apa yang saya jabarkan tadi sudah dipahami betul oleh Revina sendiri. Ia mengatakan, “Selain itu, ada fakta lain yang juga tak kalah penting: yang hamil adalah pemilik rahim, bukan donatur sperma. Pertanggungjawaban idealnya memang datang dari keduanya, tapi yaaa itu IDEALNYA.”
Sebelumnya, di awal artikel sudah tercantum tentang pandangan humanis Revina, yaitu bahwasannya karena manusia bebas (memiliki otoritas atas tubuhnya), ia bertanggung jawab penuh atas setiap tindakannya sendiri. Tetapi, dalam kutipan di atas, dengan bersembunyi di balik label “ideal” yang ia peyoratifkan, alih-alih menekankan kepada publik bahwa laki-laki juga bertanggung jawab atas tindakan bebasnya, ia justru menyingkirkan variabel penting itu sepenuhnya dan menyuruh perempuan untuk menanggung beban kehamilan sendiri dengan menyebut hal itu sebagai “realistis”.
Revina berkata, “Saya menyadari bahwa sebenarnya yang saya dukung adalah manusia, bukan perempuan.” Lantas, kalau ia benar-benar seorang humanis tulen seperti yang diklaimnya itu, mengapa tidak memilih untuk—sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok “feminis media sosial”―menyuarakan agar setiap manusia yang bebas (yang memiliki otoritas atas tubuhnya), dan dalam kasus ini laki-laki, tidak lari dari tanggung jawabnya?
Revina sibuk pada anjuran agar perempuan sebaiknya mempertimbangkan untuk menjaga dirinya dari risiko kehamilan ketimbang menitikberatkan pada problem ketimpangan sistemik, melihat potret permasalahan gender secara utuh, dan menuntut tanggung jawab yang adil dari setiap pihak, terutama pihak yang dapat kabur, yaitu laki-laki. Tendensi parsial dalam memandang gender yang semacam itu berjalan paralel dengan para pemikir misoginis yang alih-alih mengedukasi publik agar laki-laki berkewajiban untuk tidak memperkosa perempuan, malah menyuruh perempuan menutup pakaiannya saja agar selamat dari pemerkosaan.
Dalam argumennya, Revina tidak mengajak orang untuk berefleksi kepada kondisi sosial yang ada. Ia hanya sibuk berbicara tentang kiat-kiat praktis dalam membuat pertimbangan atas kehamilan seperti “kalkukasi risiko dalam pilihan” atau “membuat pilihan yang tepat untuk tubuh Anda”.
She did not address the real problem. She was just blindly throwing solutions on the table.
Revina bingung mengapa “Para feminis media sosial ini” alih-alih mengedukasi perempuan untuk membuat keputusan cerdas atas tubuhnya, malah menyemangati perempuan untuk berteriak lantang meminta dukungan dan justifikasi atas kelakuan ceroboh mereka. Mengapa feminis media sosial ini justru encourage perempuan-perempuan untuk dengan mudahnya mengeluarkan “kartu korban?”
Jawabannya adalah karena teoritikus sosial bukanlah motivator. Motivator bekerja dalam skala individual mengenai pengembangan diri dan memberikan kiat-kiat guna meningkatkan peluang bertahan hidup dalam iklim sosial tertentu. Motivator tidak memeedulikan struktur kuasa seperti apa yang ada dan hanya berfokus pada cara untuk membuat keputusan cerdas dalam hidup seorang individu.
Sementara, teoretikus sosial bekerja dalam skala makro, berpijak pada kerangka ilmiah dalam melihat masyarakat secara holistik, memeriksa satu per satu rangkaian variabel terkait dalam suatu permasalahan sosial, mengkaji perilaku individu berdasarkan relasinya dengan struktur sosial, membantu menunjukkan persoalan-persoalan yang ada ke permukaan dan merumuskan jalan keluarnya.
Baca juga: Kalau Kamu Begini, Kamu Bukan Feminis: 7 Pandangan Saklek Soal Menjadi Feminis
Teoritikus sosial tidak ada urusannya dengan tugas seorang motivator sebagaimana yang dilakukan oleh Revina. Selain kritiknya salah sasaran, Revina juga tidak mampu membuat distingsi yang jelas, serta gagal memahami sebagai apa suatu teori dan gerakan sosial seharusnya diperlakukan. Ketimbang membahasakan problem yang nyata di masyarakat, Revina secara implisit malah mengajak perempuan untuk permisif dan manut saja pada kondisi ketimpangan yang ada, membeo pada dominasi patriarki yang langgeng, dan menceramahi perempuan agar dapat bertahan di dalamnya.
Alih-alih mengajak publik berpikir logis dan membantu mereka untuk memahami struktur ketimpangan gender, tulisan Revina justru dapat menggiring publik untuk semakin dalam terjerumus dalam perpektif yang misoginis. Selain itu, argumennya juga bisa menyebabkan publik ikut tenggelam dalam kebingungan dan tidak mampu melihat dengan jernih kondisi yang sebenarnya dari status quo relasi kuasa, ketimpangan gender, serta konsep kebebasan dan konsekuensi atas tindakan. Maka, ketimbang diberi judul “Feminisme Garis Logis” yang terdengar seperti pseudo-ilmiah-filosofis, lebih cocok jika judul esai itu diganti saja menjadi “Tips-Tips Jitu Mempertimbangkan Seks dan Kehamilan” layaknya artikel motivasi lain.
Namun sayangnya, Revina buru-buru mem-branding tulisannya dengan embel-embel ilmiah dan membentenginya dengan jargon-jargon filosofis seperti “logika dasar” dan “pengetahuan dasar saja”. Ia secara konsisten mengatasnamakan logika sebagai senjata untuk menyerang feminisme, seolah-olah siapa pun yang tidak bersepaham dengan argumennya, berarti tidak berpengetahuan dasar dan tidak mampu berpikir lurus. Padahal, tulisannya sendiri mengabaikan penalaran logika sederhana dengan cara menyingkirkan premis-premis yang penting dan merumuskan gambaran permasalahan secara utuh.
Revina secara abusif menggunakan jargon “logika”untuk mendukung argumennya yang rancu. Padahal, bukankah agar gagasan feminismenya dapat menjadi utuh dan penarikan simpulannya logis, butuh suatu uraian yang lengkap atas premis-premis yang terkait dan representasi yang adil dari setiap gender yang telah didefinisikan? Namun, sepertinya semua hal itu luput dari kacamata Revina.
Karena telah bersikeras menempatkan logika pada koridor yang tidak semestinya itu,barangkali gelar feminis garis logis yang Revina sematkan untuk dirinya sendiri patut dipertanyakan. Benarkah sudah logis, atau ia justru tengah memopulerkan kekeliruan cara pikir dalam mazhab feminisme yang baru?






















