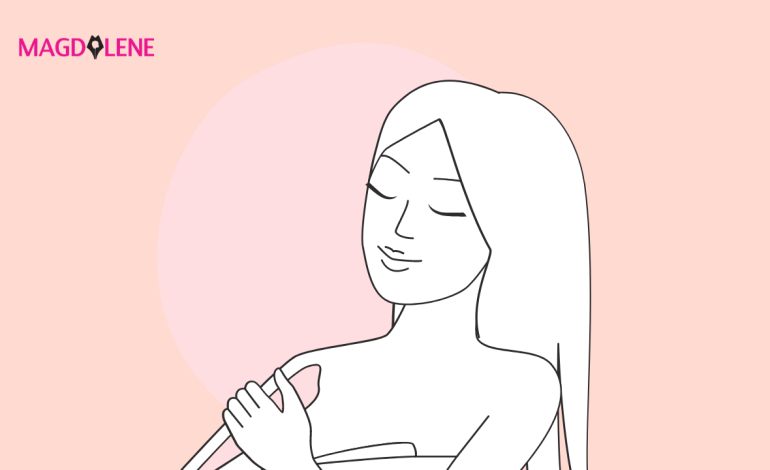Tak Sesuai Agama dan Hukum, Kenapa Tren ‘Kumpul Kebo’ Diminati Anak Muda?

Kamu tentu familier dengan frasa kohabitasi, “kumpul kebo”, atau tinggal bareng pasangan tanpa ikatan perkawinan. Praktik kohaitasi yang kadang diikuti kelahiran anak di luar pernikahan (nonmarital childbearing) menjadi fenomena demografi yang semakin umum di kota-kota besar di Indonesia.
Generasi muda mulai mengalami pergeseran pandangan terhadap relasi dan pernikahan. Pernikahan dianggap sebagai institusi normatif dengan regulasi yang kompleks. Di sisi lain, mereka melihat kohabitasi sebagai hubungan yang murni, refleksi dari cinta dan daya tarik mutualisme.
Dalam teorinya tentang “Second Demographic Transition” (SDT), Ron Lesthaeghe, profesor demografi dan sains sosial dari Belgia, mengajukan pandangan bahwa pernikahan telah kehilangan statusnya sebagai bentuk persatuan konvensional yang berdasar pada norma dan nilai sosial. Sebagai gantinya, kohabitasi telah menjadi bentuk baru pembentukan keluarga.
Bagaimana tren kohabitasi di dunia dan praktiknya di Indonesia?
Baca juga: Kumpul Kebo sampai TTM: Dilema Relasi Tanpa Nama
Tren Kohabitasi
Perbedaan regulasi hukum, budaya, dan struktur ekonomi menyebabkan variasi yang signifikan dalam pola dan tren kohabitasi di berbagai negara. Di sebagian besar negara di Eropa barat dan utara, Amerika Serikat (AS), Kanada, Australia, dan Selandia Baru, kohabitasi telah memperoleh pengakuan hukum.
Di Belanda, misalnya, tingkat kelaziman kohabitasi di Belanda mencapai 50 persen, dengan durasi rata-rata lebih dari empat tahun, dan kurang dari separuh dari pasangan kohabitasi ini melanjutkan ke pernikahan. Sejak 1998, negara ini mengakui berbagai bentuk partnership formation (pembentukan relasi) melalui Civil Solidarity Pact (Pacs).
Pakta ini mengatur kontrak kohabitasi, termasuk kohabitasi yang terdaftar maupun tidak, sekaligus merinci hak dan kewajiban dalam ikatan kohabitasi yang lebih fleksibel daripada pernikahan. Hal ini termasuk dukungan finansial, perumahan, pajak, dan hak-hak sosial lainnya. Adanya pakta ini membantu mengurangi diskriminasi terhadap anak-anak tidak sah (illegitimate children, atau sering disebut sebagai “anak haram” di Indonesia) dan menyediakan dukungan substansial bagi orang tua tunggal.
Sementara, di Asia, kohabitasi tidak mendapatkan pengakuan legal karena pengaruh budaya, tradisi, dan agama. Kohabitasi cenderung terjadi dalam periode singkat dan sering dianggap sebagai tahap awal menuju pernikahan karena tradisi keluarga yang mengharuskan pasangan menikah.
Di Jepang, contohnya, data dari National Fertility Survey menunjukkan bahwa sekitar 25 persen pasangan melakukan kohabitasi dengan rata-rata durasi sekitar dua tahun, dan sekitar 58 persen dari total pasangan kohabitasi melanjutkan ke jenjang pernikahan. Data tersebut juga menunjukkan bahwa kelahiran anak di luar pernikahan hanya sekitar 2 persen atau terendah di antara negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang rata-ratanya sebesar 36,3 persen.
Baca juga: Istri Lempar Kode di Status Media Sosial: Ciri Hubungan Tak Setara
Alasan Kohabitasi di Indonesia
Di Indonesia, studi tahun 2021 yang berjudul “The Untold Story of Cohabitation”, mengungkap bahwa kohabitasi lebih umum terjadi di wilayah Indonesia Timur, yang mayoritas penduduknya non-Muslim.
Hasil analisis saya terhadap data dari Pendataan Keluarga 2021 (PK21) milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), misalnya, menemukan 0,6 persen penduduk kota Manado, Sulawesi Utara, melakukan kohabitasi. Dari total populasi pasangan kohabitasi tersebut, 1,9 persen di antaranya sedang hamil saat survei dilakukan, 24,3 persen berusia kurang dari 30 tahun, 83,7 persen berpendidikan SMA atau lebih rendah, 11,6 persen tidak bekerja, dan 53,5 persen lainnya bekerja secara informal.
Penelitian yang saya lakukan di Manado (belum dipublikasikan) mengungkap tiga alasan mengapa pasangan memilih melakukan kohabitasi.
1. Beban finansial
Di Manado, pasangan cenderung memilih kohabitasi sebagai alternatif karena mereka belum siap secara finansial untuk menanggung biaya pernikahan. Mereka memilih menunda pernikahan guna mengumpulkan biaya untuk membayar mahar yang besarannya ditentukan oleh status sosial, pendidikan, dan level pekerjaan yang lebih tinggi.
Salah satu responden wawancara menyatakan bahwa dia harus menunggu hingga empat tahun agar pasangannya mampu mengumpulkan mahar sebesar Rp50 juta.
2. Rumitnya prosedur perceraian
Faktor lain yang mendorong pasangan memilih kohabitasi adalah karena mereka tidak perlu melalui prosedur birokrasi perceraian yang rumit dan mahal ketika memutuskan berpisah.
Dalam prosesnya, perceraian membutuhkan banyak biaya, mulai dari biaya perkara, jasa pengacara, hingga pembagian harta gana-gini, hak asuh anak, dan lain-lain.
Selain itu, dalam ajaran agama Kristen dan Katolik, yang dianut oleh mayoritas penduduk kota Manado, terdapat ayat: “Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia,” (Markus 10:6-9). Artinya, secara hukum agama, suami istri yang bercerai hanya diperbolehkan menikah lagi ketika pasangannya sudah meninggal.
3. Penerimaan sosial
Adanya penerimaan sosial terhadap pasangan kohabitasi menjadi faktor pendorong kohabitasi di Manado. Penerimaan ini dipengaruhi oleh nilai budaya yang menempatkan hubungan individu di atas formalitas pernikahan, serta faktor ekonomi yang seragam di kalangan masyarakat lokal, yang membuat mereka lebih toleran terhadap praktik kohabitasi.
Selain itu, pasangan kohabitasi di Manado memiliki komitmen serius dan tetap berorientasi pada pernikahan. Rata-rata pasangan di Manado menjalani kohabitasi selama 3-5 tahun. Biasanya, pasangan akan memutuskan untuk menikah setelah mereka memiliki 2-3 anak dan saat mereka memiliki kebutuhan administratif tertentu, semisal pendaftaran anak ke sekolah.
Baca juga: Menikah Itu Tidak Indah
Dampak Kohabitasi
Perempuan dan anak menjadi pihak yang paling terdampak secara negatif oleh kohabitasi. Dalam konteks ekonomi, karena tidak ada peraturan yang mengatur kohabitasi, tidak ada jaminan keamanan finansial bagi anak dan ibu selayaknya dalam hukum terkait perceraian. Ayah tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan dukungan finansial dalam bentuk pemberian nafkah (alimentasi). Ketika pasangan kohabitasi berpisah, tidak ada kerangka regulasi yang mengatur pembagian aset dan finansial, alimentasi, hak waris, penentuan hak asuh anak, dan masalah-masalah lainnya.
Dalam konteks kesehatan, dampak negatif kohabitasi dapat dirasakan melalui penurunan kepuasan hidup dan masalah kesehatan mental. Kurangnya komitmen dan kepercayaan antara pasangan, serta ketidakpastian mengenai masa depan, dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi pada pasangan kohabitasi.
Berdasarkan data PK21, 69,1 persen pasangan kohabitasi mengalami konflik dalam bentuk tegur sapa, 0,62 persen mengalami konflik yang lebih serius seperti pisah ranjang hingga pisah tempat tinggal, dan 0,26 persen lainnya mengalami konflik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, tekanan dari stigma sosial dan harapan yang tidak realistis dari keluarga atau masyarakat, seperti harus mapan finansial dalam waktu singkat agar dapat segera menikah, dapat memperburuk kondisi mental pasangan kohabitasi.
Anak-anak yang lahir dari hubungan kohabitasi juga sering mengalami dampak negatif, termasuk gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, dan emosional. Anak dapat mengalami kebingungan identitas dan memiliki perasaan tidak diakui karena adanya stigma dan diskriminasi terhadap status “anak haram”, bahkan dari anggota keluarga sendiri. Hal ini menyulitkan mereka untuk menempatkan diri dalam struktur keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.
Baca Juga: ‘Influencer’ Dakwah: Wajah Baru ‘Pemimpin Agama’ di Era Medsos
Solusi yang mungkin
Alih-alih “mengkuhum” pasangan kohabitasi, pemerintah dan pembuat kebijakan perlu fokus untuk mengurangi hambatan dalam melangsungkan pernikahan.
Salah satu tindakan intervensi yang dapat dilakukan adalah melalui pembentukan gerakan komunitas yang berkolaborasi dengan pemimpin masyarakat (dalam lingkup komunitas gereja, adat, atau satuan lingkungan setempat), untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait pentingnya menyesuaikan mahar pernikahan dengan kemampuan ekonomi calon pengantin.
Selain itu, edukasi mengenai dampak negatif kohabitasi dan anak di luar pernikahan juga penting, agar generasi muda lebih sadar dan bijak dalam mempersiapkan kehidupan masa depan, termasuk merencanakan pernikahan.
Yulinda Nurul Aini, Peneliti Ahli Muda, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.