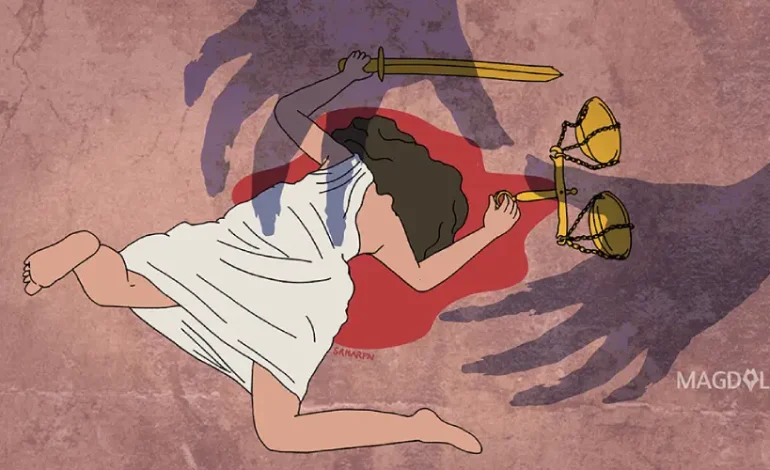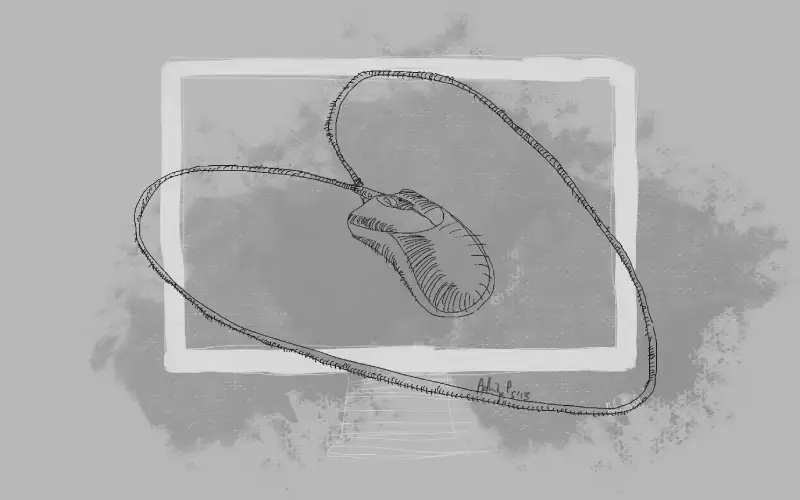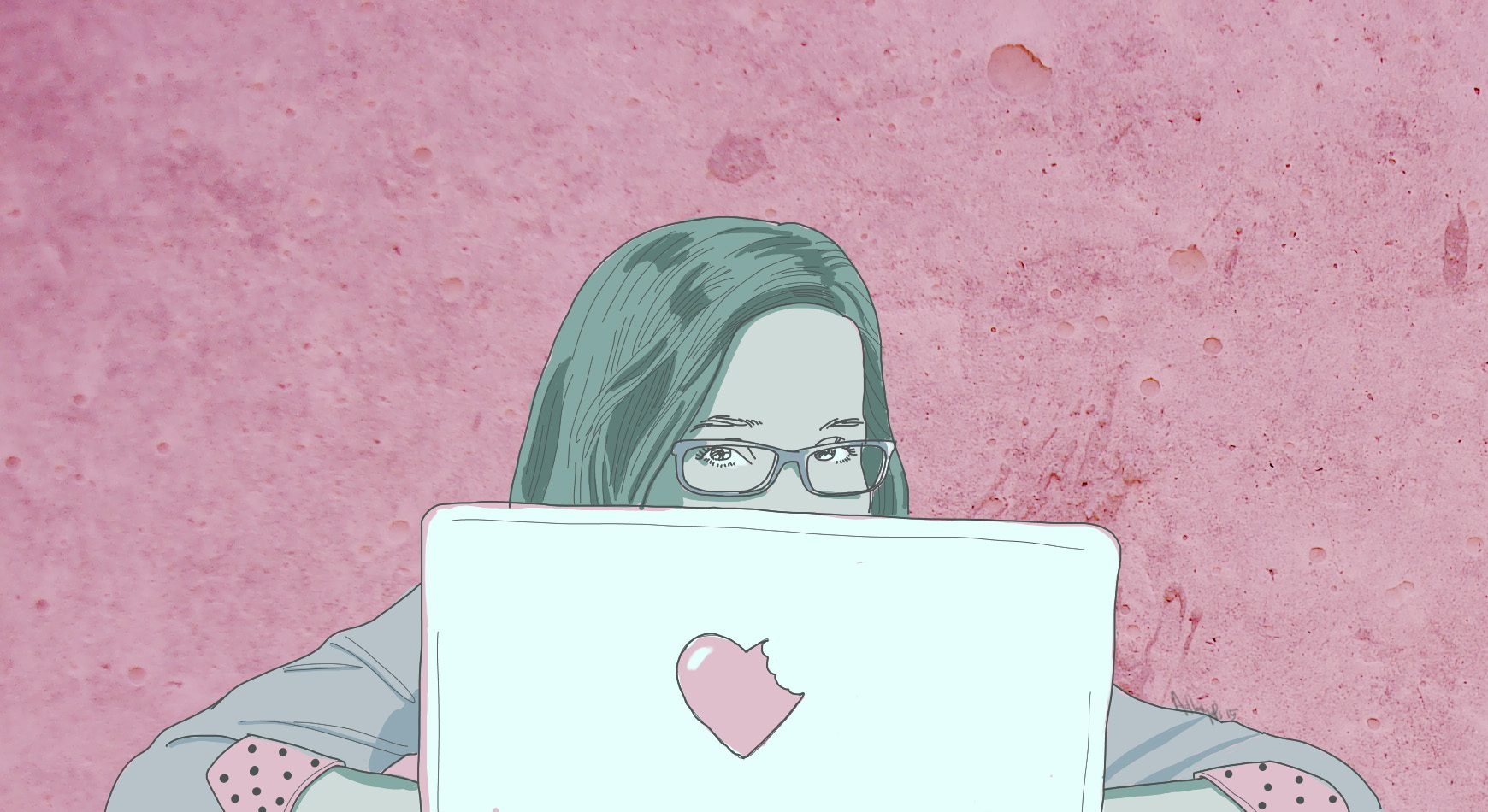Menikah Itu Tidak Indah

Besar dan tumbuh di bumi pertiwi ini menjadikanku perempuan yang memiliki “tujuan hidup” untuk menikah. Besar dengan segudang buaian komik, novel dan drama menjadikan aku pribadi yang mendambakan pernikahan penuh cinta, kesetiaan, dan perlindungan dari sosok laki-laki alias suami.
Sampai pada akhir tahun 2016, kekasih yang sudah kupacari selama tiga tahun dan aku kenal selama 13 tahun mengajak aku untuk menikah. Dengan penuh keraguan dan kesadaran bahwa selama berpacaran hubungan kami (tidak) baik-baik saja, aku menyambut dengan antusias ajakan itu. Bayang-bayang keindahan menjadi istri dengan khayalan memiliki suami yang bisa menjadi teman serta (mengaku) feminis lebih membayangi aku selama menyiapkan pernikahan.
Pada pertengahan 2017, kami melangsungkan pernikahan yang tergolong megah untuk kebanyakan orang Indonesia. Ada tiga kali perayaan, di tiga hari dan tempat yang berbeda. Acara utama berlangsung di kawasan Medan Merdeka dengan rentetan karangan bunga yang memenuhi halaman gedung. Masih teringat jelas baju pengantin adat Bugis berwarna merah, dan bagaimana aku menyalami setiap tamu yang datang tanpa henti selama kurang lebih tiga jam.
Segala kemegahan dan keindahan mimpi tentang bahagianya pernikahan harus berakhir hanya di H+1 pesta, yakni pada acara ngunduh mantu di rumah suami saat itu. Hal itu sesuai kesepakatan kami yang aku kira sudah disampaikan kepada orang tuanya mengenai tinggal terpisah dari mereka. Hari itu aku menangis karena dituduh ingin mengambil aset mereka yang akan kami tinggali. Padahal awalnya aku meminta agar kami mandiri dan mengontrak rumah tapi ditolak.
Tiga bulan setelah menikah dan aku belum juga menunjukkan tanda-tanda kehamilan, penghakiman berhamburan. Mulai dari aku yang bekerja, terlalu sering menggunakan ojek, diet nasi, sampai celana jin disebut sebagai penyebab aku tak kunjung hamil. Tekanan dan dorongan untuk segera punya anak dari berbagai pihak pun bermunculan. Aku pun memutuskan untuk melakukan pemeriksaan dan “program hamil” di bulan ke-4 kami menikah. Hasil dari pemeriksaan menunjukkan bahwa aku mengalami masalah dalam siklus menstruasi, sementara suami memiliki bawaan lahir yang menurut dokter menghambat kami untuk memiliki keturunan sehingga harus melakukan inseminasi buatan.
Baca juga: Suamiku Menjadi Serigala Ketika Malam Tiba
Di bulan ke-4 itu, bukan hanya program memperoleh keturunan yang menerpa rumah tangga baru kami. Pada November 2017, suamiku berencana untuk berhenti bekerja dan mempersiapkan diri untuk maju di panggung legislatif tingkat provinsi. Rencana ini memang sudah dia sampaikan sebelum kami menikah, tapi kami sepakat dia akan maju di tahun 2024, bukan 2019.
Aku yang disebutnya selalu overthinking” ini panik dan memikirkan segala kemungkinan dengan perubahan rencana yang dia putuskan. Mulai dari hitung-hitungan keuangan rumah tangga kecil kami, hingga persiapan kampanye yang akan menyebabkan kami harus tinggal serumah dengan orang tuanya, yang melarang aku menggunakan asisten rumah tangga/binatu/jenis bantuan lainnya, sementara suamiku dilarang membantuku mengerjakan pekerjaan rumah. Padahal rumah mereka dua lantai dan cukup besar sementara aku bekerja.
Di bulan ke-11 di 2017 itulah, pernikahan terasa neraka untuk aku dan dia. Aku yang merasa tertekan dengan jadwal pemeriksaan dokter untuk program hamil dan berbagai vitamin dan obat yang harus kuminum untuk membesarkan sel telur. Dia yang sibuk memilih partai politik dan menyiapkan jaringan untuk ikut serta di pesta demokrasi.
Aku yang “temperamental” dan “dramatis” ini merasa “dikorbankan” untuk mimpi dan rencana suami dan menanggung beban untuk “bertanggung jawab” hamil karena aku yang memiliki janin. Pertengkaran semakin menjadi di antara kami; hampir setiap hari kami beradu argumen dan saling menuntut untuk dipahami.
Maret 2018, akhirnya sel telurku siap untuk dibuahi melalui inseminasi buatan. Dua minggu aku berusaha untuk sehati-hati mungkin (menjauhi tangga, tidak berlari dan tidak menggunakan celana jin) serta beribadah lebih banyak dari biasanya untuk memohon agar segera hamil. Lewat dua minggu, aku belum juga kunjung datang bulan. Sedikit harapan muncul di dada. Sampai tiba hari kedua aku sudah masuk kerja, setelah sebelumnya aku cuti tanpa dibayar selama dua minggu. Tamu bulanan itu pun hadir tepat tengah hari.
Baca juga: Nicky Astria dan Merebut Tafsir Soal Izin Suami
Aku izin pulang dari kantor sambil menahan tangis. Semua kolega kantor yang paham kesulitanku memberikan tatapan prihatin. Aku pulang menangis dan meraung-raung, sementara suamiku sulit untuk dihubungi. Aku pun marah karena merasa diabaikan dan tidak dipahami. Dia pun marah karena aku pun tidak mau mengerti dia yang sedang bekerja. Kami pun bertengkar lagi via gawai.
Setelah kegagalan inseminasi, frekuensi pertengkaran kami makin intens. Dia kerap pulang larut karena harus mempersiapkan pendaftaran pemilihan anggota legislatif dan berjejaring (atau mungkin terlalu lelah menghadapi aku yang masih emosional). Pertengkaran yang dibumbui cibiran, singgungan, dan makian menjadi menu utama kami di rumah.
Sampai akhirnya dia memutuskan untuk berpisah dengan alasan aku yang tidak “patuh” sebagai istri karena menentang rencananya. Hari Buruh di tahun 2018 terasa sebagai kiamat dan langit runtuh bagiku. Dia menjatuhkan talak untukku tanpa mendiskusikan apa pun sebelumnya dan menolak untuk mengunjungi psikolog atau konsultan pernikahan.
Hari itu aku merasa gagal sebagai perempuan. Aku menyalahkan diriku karena terlalu emosional dan tidak mencoba “memahami” dia lebih dalam. Tapi di sisi lain, tuntutan keluarganya agar aku berhenti bekerja dan hidup dibiayai oleh orang tuanya adalah hal yang tidak dapat aku toleransi. Bagiku itu artinya aku dibuat tidak berdaya. Bagiku yang sarjana, berdaya adalah kunci menjadi manusia.
Di tengah keengganan antara tidak ingin bercerai dan tidak ingin berhenti bekerja, aku menghabiskan waktu dengan menangis dan mengemis padanya agar bisa kembali serumah sebagai suami-istri dan tetap bekerja.
Sampai akhirnya pada Lebaran 2018, setelah sebulan kami tidak serumah, aku datang ke rumahnya untuk meminta maaf dan mencoba lagi untuk memperbaiki rumah tangga kami. Tapi takdir berkata lain. Hari itu, di salah satu aplikasi pesan gawainya aku menemukan percakapan dia dengan kekasih barunya. Selama aku menangis dan mengemis kembali, ternyata mereka rutin berjumpa dan menghabiskan waktu bersama. Ketika aku marah membaca percakapan tersebut, jawaban dia adalah “Aku ngelakuin ini setelah aku talak kamu kok”.
Sejak hari itu aku menekan dia untuk melakukan proses perceraian sesuai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Setelah kurang lebih lima bulan menjalani persidangan, aku pun resmi bercerai dengan teman yang sudah aku kenal sejak 15 tahun lalu. Aku pun semakin sadar bahwa pernikahan memang tidak seindah yang digembar-gemborkan banyak orang.
Ilustrasi oleh Adhitya Pattisahusiwa