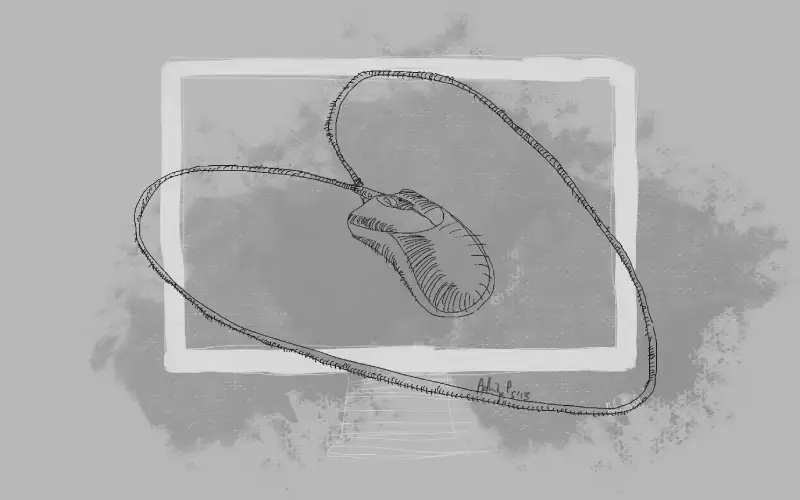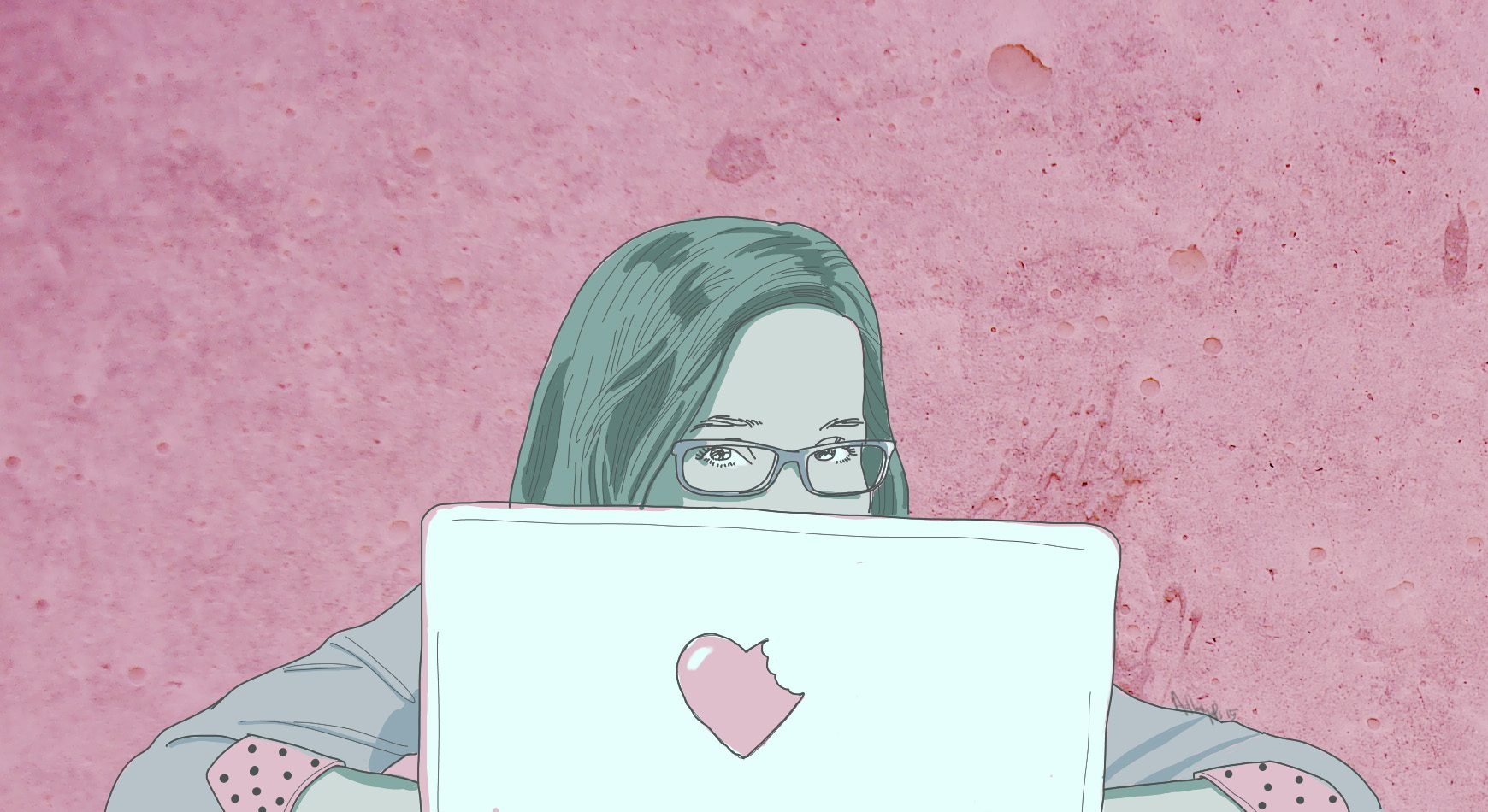Konsekuensi Janji Nikah yang Tidak Kunjung Ditepati

Dalam surat curhat pembaca yang dimuat di Fimela, perempuan bernama “Tata” menceritakan pengalamannya saat dijanjikan akan dinikahi oleh pacar. Sejak awal berpacaran, Tata mengatakan, mereka berdua sudah berencana menikah. Delapan bulan berelasi, Tata bahkan sempat berhubungan seksual dengan pacarnya sampai hamil.
“Awalnya dia mau tanggung jawab, tapi nyatanya sampai aku hamil lima bulan dia enggak mau tanggung jawab, malah ngegantung aku,” demikian petikan cerita Tata.
Kisah pedih seperti yang Tata alami ini ditemukan pula dalam sederet kisah perempuan lainnya yang dimuat dalam pemberitaan lokal. Banyak di antara perempuan yang berhubungan seksual hingga hamil setelah diiming-imingi nikah oleh pacarnya, ternyata masih di bawah umur.
Dalam cerita lain yang dimuat di Detik.com (5/8) lalu, perempuan di Makassar yang menjadi korban janji nikah pacarnya bahkan sempat dipukuli pelaku hingga lebam. Hal ini terjadi setelah ia terus menagih janji nikah pacarnya tersebut, sementara sang pacar menolak dengan menuduh perempuan itu terlibat dalam jaringan prostitusi online.
Baca juga: Manipulasi dalam Pacaran Rentan Lahirkan Kekerasan Seksual
Manipulasi di Balik Janji Nikah Palsu
Dalam kasus-kasus di mana perempuan (tampak) setuju melakukan hubungan seksual dengan pelaku janji nikah palsu, terdapat upaya manipulasi yang sering tidak disadari olehnya. Menurut psikolog dari Yayasan Pulih, Ika Putri Dewi dalam acara Campus Online Talkshow bertajuk “Manipulasi dalam Relasi” yang diselenggarakan Magdalene bersama The Body Shop Indonesia dan Yayasan Pulih Februari lalu, relasi yang manipulatif muncul karena adanya ketimpangan relasi kuasa di dunia yang patriarkal, di mana laki-laki berposisi di atas perempuan. Banyak perempuan yang merasa harus mengikuti kemauan-kemauan pasangannya meskipun sebenarnya ia tidak nyaman.
“Tanda-tanda manipulasi dalam suatu relasi itu ada pihak yang sebenarnya merasa tidak nyaman atau tidak ingin, tapi dia tidak mampu menolaknya. Entah karena dia merasa tertekan secara fisik dan psikis, atau merasa tidak punya pilihan dan tidak bisa keluar,” ujar Ika.
Lebih lanjut Ika menjelaskan, dalam relasi demikian, gabungan rasa cinta korban terhadap pelaku dan manipulasi yang terjadi membuat korban berharap banyak pada pelaku.
Janji nikah yang tidak ditepati juga bisa masuk kategori kekerasan. Dalam perbincangan di Bisik Kamis Magdalene dengan aktivis perempuan founder gerakan #NoRecruit List, Poppy Dihardjo mengambil contoh kasus di mana perempuan sudah memberikan apa yang dia punya, termasuk “keperawanannya”, tetapi kemudian ditinggalkan pacar begitu saja.
“Apakah dia korban kekerasan seksual? Enggak bisa langsung dibilang begitu karena konsensual hubungannya. Apakah dia bukan korban? Enggak, dia tetap korban, yaitu korban perasaan [kekerasan emosional],” kata Poppy.
Baca juga: Dari Pelecehan Seksual sampai Kawin Paksa, RUU PKS Jamin Hak Penyintas
Dampak bagi Korban Janji Nikah Palsu
Janji nikah yang tidak ditepati kerap dianggap sebagai suatu kejadian apes yang mau tidak mau ditelan sendiri oleh korban dan rasa sakit akibat hal tersebut akan mudah hilang seiring waktu. Sebagian orang bahkan menganggap ini bukanlah suatu hal yang bisa diperkarakan secara serius dan malah menyalahkan korban dengan kata-kata seperti, “Ya kamu juga sih, mau-maunya makan janji palsu dia” alih-alih berempati kepadanya.
Nyatanya, dampak yang dialami korban janji nikah palsu ini besar dan bisa mempengaruhi kehidupannya dalam jangka panjang. Berkaca dari peristiwa yang menimpa Tata, bila ia sampai hamil hingga akhirnya melahirkan, tentu saja beban berat sebagai ibu juga perempuan yang pernah ditipu seorang laki-laki tidak terelakkan. Tidak hanya beban fisik karena mengandung dan melahirkan, ia juga dapat merasakan beban psikis berupa kekecewaan besar yang bisa mengarahkannya pada masalah kepercayaan dalam relasi berikutnya, depresi, ditambah beban mental mengurus seorang anak sebagai ibu tunggal karena bapaknya tidak mau bertanggung jawab atas dirinya.
Beban secara psikis bagi korban janji nikah yang terlanjur berhubungan seksual dengan pelaku juga bisa hadir karena adanya budaya patriarki yang mengagungkan keperawanan. Setelah pertama kali berhubungan dengan seorang laki-laki dan ternyata laki-laki tersebut tidak merealisasikan janji nikahnya, perempuan korban akan cenderung memandang dirinya hina atau tidak berharga lagi karena “sudah rusak”.
Dalam penelitian Santy Pranawati yang dimuat di The Conversation bahkan disebutkan, ketidakperawanan menjadi salah satu faktor pendorong remaja putri melacurkan dirinya. Penelitian Santy ini dilakukan terhadap delapan perempuan usia 18-24 tahun dan informan-informannya itu sudah menjadi pekerja seks sejak remaja, tanpa ada latar masalah ekonomi atau paksaan dari pihak lain.
Selain dampak-dampak tersebut, korban janji nikah palsu juga bisa merasakan imbas ekonomi. Hal ini terlihat dari contoh kasus yang diwartakan Liputan6.com, di mana seorang korban sampai menggelontorkan uang ratusan juta rupiah untuk seorang laki-laki yang mengiming-iminginya pernikahan dan uang lebih besar lagi. Janji nikah palsu tersebut menjadi bagian dari rangkaian aksi penipuan yang dilancarkan lewat Facebook oleh komplotan penjahat, yang salah satunya adalah laki-laki WNA.
Dampak ekonomi juga dapat terjadi ketika janji nikah palsu tersebut sampai memasuki tahap lamaran dan pertemuan keluarga. Dalam tahap ini, biasanya pihak korban juga mengeluarkan sejumlah dana persiapan pernikahan dan telah mengumumkan acara besarnya tersebut kepada kerabat dan teman-temannya.
Bisa Masuk Perbuatan Melawan Hukum
Walau sering dianggap hal yang “abu-abu”, sebenarnya janji nikah palsu ini bisa diperkarakan secara hukum. Dalam tulisannya di HukumOnline.com, Aida Mardatillah menyebutkan satu contoh kasus di mana orang yang tidak menepati janji nikah dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung (MA).
Hal ini bermula saat laki-laki berinisial AS memacari SSL sampai melamarnya pada Februari 2018. Setelah bertunangan, AS meminta SSL untuk berhubungan seksual. Walau sempat menolak, SSL pun mengiyakan permintaan AS itu karena AS berdalih mereka akan segera menikah. Namun, sampai waktu ditentukan, yakni September 2018, AS tidak juga menikahi SSL, bahkan kedapatan mengencani perempuan lain.
Keluarga SSL pun mengadukan kasus ini ke Pengadilan Negeri Banyumas, yang kemudian menetapkan AS melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena merugikan SSL secara moril lewat pembatalan rencana nikahnya. Sempat naik banding hingga kasasi, MA menolak permohonan AS hingga akhirnya laki-laki tersebut dituntut untuk membayar kerugian Rp150 juta.
Akan tetapi, tidak semua kasus janji nikah palsu berujung seperti ini. Masalah pembuktian telah dibuatnya janji menjadi salah satu hal yang menghambat seseorang untuk menuntut pelaku. Biasanya, sesuatu bisa diperkarakan jika ada janji yang terdokumentasi/ tertulis, bukan lisan laiknya iming-iming nikah dilontarkan. Selain itu, menurut Pasal 58 KUH Perdata, janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut untuk dilangsungkannya perkawinan, begitu juga hak untuk menuntut penggantian biaya dan kerugian atas dilanggarnya janji itu.
Walau demikian, bila telah ada pengumuman pernikahan seiring janji nikah tersebut, seseorang bisa melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku, paling lama 18 bulan sejak pengumuman pernikahan.
Dalam pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), sebenarnya janji nikah palsu juga diperkarakan. Hal ini disinggung dalam naskah akademik RUU PKS yang disusun Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Forum Pengada Layanan (FPL), khususnya pada bagian eksploitasi seksual. Di sana dikatakan, praktik eksploitasi seksual bisa dilakukan dengan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan. Iming-iming ini memanfaatkan cara pikir dalam masyarakat, di mana perempuan menjadi sosok yang tidak memiliki daya tawar dan mau tidak mau mengikuti kehendak pelaku agar ia dinikahi.
Pembahasan secara khusus tentang pengingkaran janji nikah juga terdapat dalam buku berjudul “Perempuan Menggugat Atas Integritas Tubuh Dirinya Tidak Terpenuhinya Janji Kawin”(2017) tulisan Dr. Lusiana Margareth Tijow S.H., M.H. dan Prof. Dr Sudarsono S.H., M.S. Dalam tulisannya, mereka mendukung dibentuknya perlindungan atas perempuan-perempuan yang menjadi korban janji nikah palsu karena selama ini hukum yang ada belum cukup melingkupi itu.
Mereka mendasarkan argumennya pada teori-teori seperti teori hak asasi manusia, keadilan, perlindungan hukum, dan hukum berperspektif feminis, serta keadaan ketimpangan gender yang ada di masyarakat. Salah satu argumen mereka terkait perempuan sebagai korban dilandaskan pada pasal 1 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana korban merupakan seseorang yang menderita secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi.
“Dengan demikian, bisa juga dikatakan bahwa perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dari laki-laki yang berakibat pada penderitaan fisik, psikis, seksual, sosial, diartikan sebagai tindakan atau sikap yang dilakukan dengan menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan dan sebagai akibat langsung dari pengabaian dan pelanggaran hak asasi manusia,” tulis mereka.