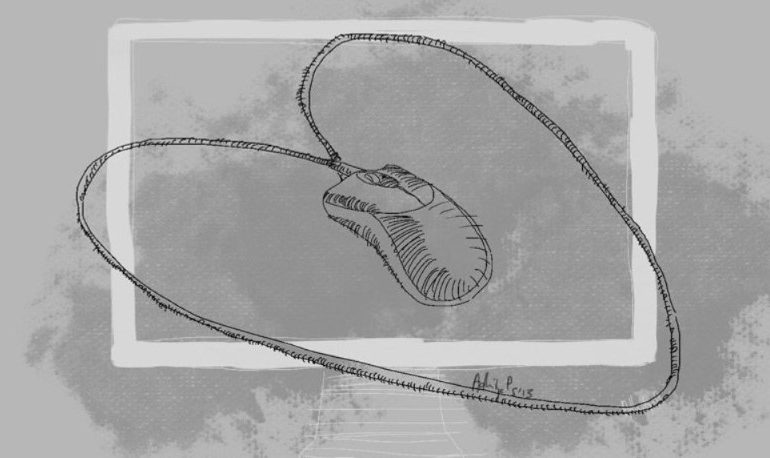Berita Pemilu 2024: Banjir Gimik, Kering Substansi

Ada yang berbeda dari Pemilu 2024. Karena mayoritas konstituen adalah milenial dan Gen Z, mencakup 56 persen, strategi kampanye kandidat pun digeser sedemikian rupa. Sudah jarang ditemui kampanye konvensional macam pidato atau kunjungan ke pemuka agama. Sebaliknya, kandidat lebih menitikberatkan pada gimik nir-substansi. Makanya tahun ini kita mengenal joget gemoy Prabowo-Gibran, fenomena kpopisasi Anies-Cak Imin, dan tim Penguin Ganjar-Mahfud.
Walau termasuk ampuh menjaring suara anak muda, strategi ini bukan tanpa cela. Itu justru mengaburkan substansi yang lebih penting. Parahnya lagi, riset terbaru watchdog media Remotivi bertajuk Tolak Basa Basi Politik menunjukkan, media-media di Indonesia justru andil mengamplifikasi gimik “murahan” itu, alih-alih mengkritisinya.
Dengan mengajak 100 orang anak muda di sembilan kota di Indonesia, Remotivi melakukan pemantauan berita Pemilihan Presiden (Pilpres) di 18 media daring nasional dan enam media daring lokal. Selama Desember 2023 hingga Februari 2024, Remotivi menemukan sebanyak 3.136 berita non-substansial. Berita-berita ini menekankan pada narasi berbasis emosi dan sentimen.
“Kita dicemari pemberitaan sentimental emosional. Kita punya ekspektasi dengan ekosistem tercemar ini, banyaknya buzzer dan gimmick, media justru bisa jadi entitas yang waras. Tapi nyatanya media gagal sebagai pilar keempat demokrasi dan kemakan gimmick kandidat. Media belum melaksanakan tugas yang baik dalam membuat pemilih memilih secara rasional,” jelas peneliti Remotivi Surya Putra, (12/2).
Baca Juga: Masalah Lain Baliho Politik: Bahayakan Pengguna Jalan dan Jadi Sampah Baru
Pemberitaan Rasa Pertandingan Olahraga dan Infotainment
Dalam pemberitaan media terkait Pemilu, Remotivi melihat dua praktik pembingkaian berita politik. Praktik pertama mengacu pada game frame. Surya mengatakan dalam kajian komunikasi dan jurnalisme politik, berita politik dibingkai seolah-olah seperti pertandingan olahraga. Dalam praktik game frame, berita-berita politik berfokus pada narasi drama dan konflik antar-elite, tafsir atas gestur politik, hingga siapa yang sedang unggul dan tertinggal dalam “balapan” politik.
Maka tak heran, praktik game frame informasi terkait saling sindir antar-politikus, siapa yang sedang menang atau kalah dalam kontes politik elektoral, hingga spekulasi tentang hasil pemilihan atau koalisi elit politik jadi jualan utama media. Coba kita lihat dari beberapa tajuk berita di bawah ini yang dikutip dari temuan Remotivi.
1. Sentilan Adian Napitupulu Sebut Projo Panik hingga Deklarasi Dukung Prabowo
2. Fahri Hamzah Vs Rommy PPP Debat Panas soal Pengkhianatan
3. Tanda Jokowi Dukung Prabowo Semakin Terlihat
4. Beragam Hasil Survei Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, Berpotensi Melejit?
Beberapa berita tersebut akrab kita temui dan terkesan normal-normal saja. Namun, menurut Remotivi ini justru jadi titik permasalahannya. Berita (1), misalnya, bercerita tentang para elite yang sedang mengklaim dukungan Jokowi terhadap capresnya masing-masing. Klaim yang sebenarnya didasarkan pada perdebatan tafsir atas jumlah pukulan gong Jokowi saat membuka Rakernas Projo.
Lalu pada berita (4), kita melihat bagaimana wacana pencalonan Gibran Rakabuming sebagai bacawapres dikaitkan dengan peningkatan/penurunan elektabilitas kandidat. Cara ini sampai banyak dilakukan media. Lihat saja bagaimana survei elektabilitas paslon selalu jadi dagangan paling laris semasa Pemilu. Jarang ada media yang membicarakannya dalam kerangka lebih substansial, seperti potensi konflik kepentingan dan dampak jangka panjang terhadap demokrasi.
Praktik kedua politaiment atau politic infotainment. Dalam politaiment, logika entertainment diterapkan pada wacana politik. Kehidupan personal para tokoh publik dalam pemberitaan macam ini lebih sering diangkat yang merujuk pada fenomena kultural dan politis di mana batas antara politik dan entertainment akhirnya menjadi kabur.
Sama halnya dengan game frame, pemberitaan politaiment justru mengalihkan publik dari informasi-informasi penting yang substansial. Ia sebaliknya justru berguna menutupi bobroknya gagasan, kebijakan, rekam jejak, serta kualitas kepemimpinan kandidat.
“Keduanya (game frame dan politaiment) sama-sama mengonstruksi politik sebagai kompetisi atau permainan strategi antara lawan. Jadi tidak menyasar pada substansi, proses, gagasan, dampak kebijakan publik, hingga bagaimana mereka mewujudkan visi kebijakan,” tutur Surya.
Dalam pemberitaan politaiment, imbuhnya, renik-renik peristiwa atau serba-serbi kejadian selama kampanye, kehidupan personal paslon, dan keluarga paslon adalah tiga di antara sembilan topik yang paling banyak dibicarakan. Renik-renik peristiwa ini misalnya mencakup momen lucu dan momen-momen “merakyat” para kandidat paslon.
Baca juga: Sedang Ramai Istilah ‘Quick Count’, ‘Real Count’, dan ‘Exit Poll’: Apa Bedanya?
“Momen Gibran main futsal bareng anak Kiai, momen Prabowo masak bareng Youtuber Bobon di Cilincing ini contohnya. Pemberitaan macam ini sebenarnya mengkonstruksi kandidat dengan cara-cara tertentu. 02 dibingkai sebagai masyarakat biasa suka masak kaya kita so sweet sama anak atau cucunya. Gibran dekat dengan anak muda karena main sama anak muda,” tutur Surya.
Dalam pemberitaan terkait kehidupan personal, Remotivi juga menemukan berita remeh temeh seperti musik atau serial kesukaan paslon. Bahkan ada media yang secara khusus memberitakan pergantian avatar atau profile picture Gibran. Keluarga kandidat juga tak luput dari pemberitaan. Kini berkat media, publik jadi mengenal sosok Alam Ganjar dan Mutiara Baswedan.
“Padahal yang mau kita coblos kandidatnya, enggak ada relevansi gagasan, visi misi kandidat. Ketika keluarga kandidat dapat exposure, ini justru bisa menyuburkan kultur politik dinasti. (Keluarga) bisa dicalonkan lebih gampang, elektabilitasnya kemungkinan tinggi karena popularitas yang dibangun duluan oleh Media. Bisa dilihat dari Gibran yang mana pada 2014 media banyak menyorot dia,” tutur Surya.
Praktik kedua politaiment atau politic infotainment. Dalam politaiment, logika entertainment diterapkan pada wacana politik. Kehidupan personal para tokoh publik dalam pemberitaan macam ini lebih sering diangkat yang merujuk pada fenomena kultural dan politis di mana batas antara politik dan entertainment akhirnya menjadi kabur.
Mirisnya lagi, imbuh Surya pemberitaan seperti ini juga hadir dalam format logis sekalipun. Ia memberikan contoh Desak Anies dan Debat Capres Cawapres. Bukannya memberitakan tentang isu apa yang dibahas dalam Desak Anies, media justru memberitakan soal lightsick Owl yang dibuat para K-Popers untuk Anies. Lalu di adu gagasan seperti debat Capres Cawapres, media justru memberitakan hal remeh temeh seperti gestur, atribut, atau outfit pada kandidat.
“Di tengah kultur media seperti ini, cara politisi mencitrakan sendiri sebagai sosok yang peduli lingkungan hanya sebatas dengan pakai baju eco-friendly. Saya kemudian teringat dengan apa yang dikatakan Thomas E. Patterson (Ilmuwan politik Amerika) bahwa di kultur jurnalisme politik remeh temeh yang diuntungkan ya pada akhirnya paslon yang ber-gimmick ria,” kata Surya.
Baca Juga: Ekonomi Ekstraktif: Bayang Kepunahan Perempuan Indonesia
Komersialisasi Industri Media
Budaya jurnalisme seperti ini sebenarnya bukan barang baru, kata Surya. Dalam konteks Indonesia, kita bisa melihatnya lewat pemberitaan media jelang pemilu 2014. Pada tahun itu, pemberitaan didominasi oleh topik-topik yang hanya merefleksikan kepentingan elite, seperti dinamika koalisi partai politik, aktivitas kampanye kandidat, dan deklarasi dukungan terhadap kandidat tertentu. Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019 juga diwarnai dengan berita-berita serupa.
Surya lalu menjelaskan menurut sejumlah ilmuwan komunikasi dan jurnalisme politik, budaya jurnalisme ini lahir karena kombinasi antara pergeseran budaya kampanye politik dan semakin komersilnya industri media. Di era menjamurnya media daring, model bisnis media saat ini bergantung pada jumlah klik atau page views. Jurnalis dituntut untuk memproduksi berita sebanyak-banyak dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Dalam laporan Magdalene pada 2022, “Dirla”, jurnalis perempuan yang bekerja di media daring arus utama menuturkan, kendati dia sekarang tengah duduk di posisi editor, ia masih dibebani tujuh artikel setiap harinya. Ia bahkan sempat mendengar curhatan teman sesama jurnalis perempuan yang harus menulis belasan artikel per-hari.
“Mereka itu nyari-nyari angle yang mudah karena kuota, karena satu orang bisa sampai menulis belasan artikel setiap hari. Temanku bahkan ada yang menulis 17-18 artikel per-hari. Dengan kuota kaya gini, jelas saja jurnalis sudah terlanjur lelah untuk mikirin angle berita bahkan netral sekali pun,” katanya.
Citra Dyah Prastuti, Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) menambahkan, dengan model bisnis ini, persaingan media daring kini cenderung lebih sengit. Segala caranya pun dilakukan media untuk mengambil atensi pembaca. Jika ditarik pada pemberitaan politik, maka memproduksi berita lewat praktik game frame dan politainment jelas membutuhkan sumber daya dan waktu yang lebih sedikit ketimbang meriset gagasan, visi, dan kebijakan kandidat pemimpin. Pemberitaan ini lebih menguntungkan secara komersial dan efisien dari segi tenaga dan waktu.
Suburnya budaya jurnalisme macam ini pada prosesnya berdampak pada demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Ia bisa mengikis minat dan kapasitas warga untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Akibatnya jelas. Basis pemilih rasional jadi tak terbangun yang malah menyuburkan polarisasi tidak produktif. Parahnya lagi, ini bisa menimbulkan semacam sinisme politik yang mengalienasi publik.
“Respons ‘Gue males ah ngomongin politik. Males ah baca politik’ lahir dan ini karena warga hanya diposisikan sebagai penonton aja. Politik dibingkai enggak ada sangkut pautnya sama kehidupan warga,” kata Surya.
Kunto Adi Wibowo, Ketua Pusat Studi Komunikasi, Media, dan Budaya Universitas Padjajaran mengatakan untuk mengatasi permasalahan ini tidak bisa mengandalkan perubahan ekosistem di media. Hal ini lantaran adanya konglomerasi media juga terjadi di Indonesia yang menimbulkan ketimpangan frekuensi pemberitaan capres dan cawapres di media-media yang pemiliknya menjadi bagian dari kubu-kubu politik pilpres.
Pemilik MNC group Hary Tanoesoedibjo mendukung Ganjar Pranowo dan pemilik Media Indonesia, Surya Paloh, mendukung Anies Baswedan. Dalam temuan Remotivi, konglomerasi media misalnya menunjukkan kecenderungan frekuensi pemberitaan Anies yang lebih tinggi di Metrotvnews.com dan Ganjar di Okezone dan Sindonews dan tentunya dengan tone pemberitaan yang lebih bias memihak pada paslon tersebut.
Karena faktor inilah, kata Kunto, yang perlu dilakukan bukan lewat solusi taktis tapi solusi strategis. Platform Bijak Memilih bisa jadi contohnya. Afutami, co-founder Bijak Memilih menjelaskan dalam acara Remotivi bagaimana Bijak Memilih berfokus menciptakan demand akan informasi politik yang substansial. Pertama-tama dan paling utama adalah dengan mengubah kerangka berpikir para pemilih muda.
“Saat ini kita melihat pertarungan capres cawapres sebagai kontestasi idola dan fans club. Kami mau ubah itu. Ini bukan kontestasi idola, kita ini recruiter HRD kantor bernama Indonesia. Maka sebagai recruiter, kita harus peduli dan mau terbaik dari kandidat yang ada. Kita baca CV, prestasi, rekam jejak sebelumnya secara rasional,” kata Afutami.
Mengubah kerangka berpikir ini tentu enggak mudah. Afutami bilang banyak kendala yang ia dan timnya hadapi. Untuk mengakalinya, Bijak Memilih menjadi bunglon. Mereka menyesuaikan interest anak muda misal lewat budaya populer dalam menyampaikan isi substansial dalam konten-kontennya. Tujuannya tak lain adalah agar informasi-informasi politik yang substansial jadi mudah dicerna.
Kendati demikian, Bijak Memilih bukan satu-satunya jalan keluar. Untuk memaksimalkan Solusi strategis, Kunto bilang NGO, aktivis, dan media alternatif juga harus urun tangan. Pertama, ia mendorong NGO, aktivis, dan media alternatif juga harus aktif riding the wave dan tidak terjebak tokenism.
“Reluctant to jump in to conversation. Sekalinya diangkat udah keburu telat. Harusnya NGO, aktivis, media alternatif ini menciptakan sebuah gelombang. Secara tidak sadar terutama NGO dan aktivis juga itu masih bikin tokenisme pada pemuda yang akhirnya terjebak seasonality. Posting di sosmed enggak sustain padahal isunya penting,” tutur Kunto.
Baca Juga: Baliho ‘Mama Semok’ dan ‘Mama Muda’: Benarkah Ini Objektifikasi dan Seksualisasi Diri?
Kedua, Kunto menyarankan pada ketiga elemen ini untuk berbenah dan mulai melakukan non-persuasive communication. Ia bilang terkadang NGO, aktivis, dan media alternatif terlalu “bersemangat” melakukan edukasi persuasif ke masyarakat. Padahal cara ini menurut Kunto tak cocok dengan anak muda.
“Anak muda sekarang lebih suka dikasih informasi aja, biar mereka yang mikir. Kasih aja informasi lumayan lengkap dari perspektif lo, gue akan cari yang lain biar dia yang memutuskan. Kaya menggiring itu mereka enggak suka. We have to provide them the space, jangan jita jadi hegemonik di space mereka juga kan, bahwa kita juru selamat, messiah complex-nya masih besar,” kata Kunto.
Terakhir dan yang paling penting adalah kolaborasi. Dengan ekosistem informasi yang bisa dibilang cukup berantakan ini, usaha kolektif harus didorong untuk mengubah status quo.
“Jangan merasa satu media alternatif akan punya impact besar dibandingkan dengan influencer yang disuntik steroid iklan, susah. Apalagi wartawan juga jadi “piaraan” para politisi. Setiap penulis dia muat tanpa refleksi kritis sebagai jurnalis. Ini terjadi. Kita menghadapi raksasa-raksasa besar jadi effort-nya harus effort kolektif,” tutupnya.
Ilustrasi oleh: Karina Tungari