Masalah Besar di STEM: Representasi Perempuan dan Produk yang Bias
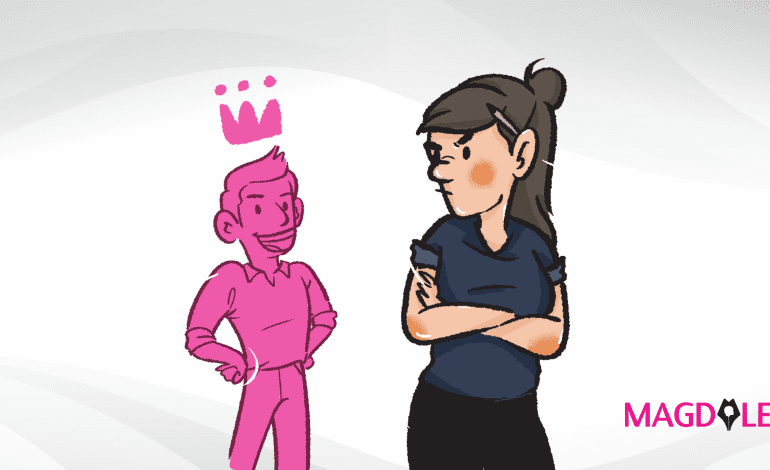
“Buah jatuh tak jauh dari pohonnya” adalah petitih yang cocok menggambarkan hubungan artificial intelligence (AI) alias kecerdasan buatan dengan manusia, sang penciptanya.
November 2017 lalu, Alex Shams, antropolog dari Universitas Chicago mengeluhkan Google Translate yang bias gender. Ia memasukkan sejumlah kata dalam bahasa Turki, dan mencoba menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris.
“Bahasa Turki adalah bahasa yang netral gender. Tak ada “he” [kata ganti orang ketiga pria] atau “she” [kata ganti orang ketiga perempuan]—semuanya disebut “o”. Namun, lihat apa yang terjadi ketika Google menerjemahkannya ke bahasa Inggris,” cuit Alex lewat Twitternya.
Ia melampirkan potongan gambar dari Google. Tukang masak, perawat, dan guru diterjemahkan berkelamin perempuan. Sementara mekanik, dokter, tentara, dan tukang bersih-bersih diterjemahkan berkelamin laki-laki. Tak hanya itu, kata ‘lajang’ dan ‘bahagia’ diasosiasikan dengan laki-laki. Sedangkan, ‘sudah menikah’ dan ‘tidak bahagia’ diasosiasikan dengan perempuan.
Padahal, bahasa Turki tak mengenal kata ganti orang ketiga dengan gender. Pun, ketika diterjemahkan oleh Google, kata-kata itu berubah memiliki gender dan seksis. Twit Alex viral dan Google Translate yang seksis sempat jadi percakapan cukup lama.
“Ingat, teknologi itu dibentuk oleh pembuatnya, dengan bias-bias mereka,” ungkap Alex. “Dan industri teknologi tingkat tinggi ini berisi banyak sekali orang kulit putih muda, para pria kaya raya, yang menghasilkan seksisme merajalela, rasisme, kelas-isasi, dan banyak bentuk ketidaksetaraan sosial lainnya. Inilah orang-orang yang kita biarkan (kini) mengatur hidup kita.”
Baca Juga: Keterasingan Perempuan dalam Transformasi Digital
Ketika kita memakai memakai Google Translate atau fitur autocomplete misalnya, Google Translate atau fitur autocomplete secara otomatis akan menempelkan gender pronoun “he” ke profesi yang “bergengsi” dan dianggap maskulin seperti dokter, teknisi, ilmuwan, atau CEO.
Empat tahun berikutnya, keluhan yang sama muncul di International Women’s Day 2021.
Vuokko Aro, Vice President Monzo Bank Ltd membagikan pengalaman serupa Alex tentang Google Translate. Bahasa Finlandia—bahasa ibu Aro—tidak mengenal gender pronouns, tapi ketika ia menuliskan beberapa kalimat yang mengandung kata kerja, Google Translate menerjemahkannya jadi kata kerja dengan gender.

Misalnya, ketika Aro menuliskan, “Ia berinvestasi. Ia bekerja. Ia mengendarai mobil. Ia melakukan olahraga” Google Translate ternyata otomatis menempelkan gender pronoun “he”. Sedangkan ketika Aro menuliskan, “Ia mencuci baju. Ia merawat anak-anak. “Ia menari”, Google Translate otomatis menempelkan gender pronoun “she”.
Pertanyaannya, apakah dunia teknologi cuma progresif menciptakan teknologi baru, tapi lambat mengatasi problem uzur bernama: seksisme?
Bias Gender karena Minim Representasi
“Teknologi by default tidak pernah netral. Di balik penciptaan dan pengembangannya terdapat developer dan desainer teknologi yang merupakan laki-laki, kulit putih, dan able bodied,” kata Dhyta Caturani, feminis dan aktivis keamanan siber (digital security).
“Karenanya, end product dari pengembangan yang lakukan otomatis akan membawa semua nilai, paradigma, dan cara berpikir mereka (pembuatnya).” Dhyta juga bilang bahwa teknologi tidak akan pernah netral. Bukan cuma ketika dilihat dari lensa gender, tapi juga identitasnya keseluruhan.
Dhyta mencontohkan teknologi period tracker, yang digunakan untuk memonitor siklus menstruasi tapi masih bias patriarkal andosentris.
“Aplikasi untuk memonitor menstruasi oleh perempuan, ini banyak dibuat oleh laki-laki,” kata Dhyta. “Dalam bias mereka, monitor ini ada untuk conceiving, masa ovulasi, mereka mengedepankan ini. Padahal tidak semua perempuan ingin atau bisa hamil. Jadi aplikasi dibuat dengan asumsi bahwa perempuan mau atau tidak mau akan hamil, bukan untuk memonitor kesehatan reproduksi perempuan,” tuturnya.
“Teknologi by default tidak pernah netral. Di balik penciptaan dan pengembangannya terdapat developer dan desainer teknologi yang merupakan laki-laki, kulit putih, dan able bodied,” kata Dhyta Caturani, feminis dan aktivis keamanan siber (digital security).
Produk teknologi yang bias gender, seperti kata Dhyta, tak terlepas dari pembuatnya yang didominasi laki-laki. Ketidaknetralan teknologi yang kita gunakan sekarang adalah akumulasi dari minimnya representasi perempuan dalam bidang Science, Technology, Engineering, and Math (STEM).
Peneliti di Pusat Riset Gender Universitas Indonesia, Andi Misbahul Pratiwi mengatakan kesenjangan gender dalam STEM bisa dilihat dari minimnya perempuan yang mengenyam pendidikan di bidang ini. “Saat di SMK saya misalnya, hanya ada 10 anak perempuan dari total 40 murid. Ketika kuliah pun persentasenya tidak beda jauh padahal TI itu jurusan popular,” kata Andi yang merupakan lulusan Teknik Informatika (TI) dan Teknik komputer dan Jaringan semasa SMK.
Ia juga melihat semakin tinggi jenjang pendidikan, jumlah perempuan semakin sedikit dan hal ini otomatis berpengaruh ke angkatan kerja. “STEM itu fancy, partisipasi di pendidikan STEM aja sudah sedikit. Apalagi di dunia kerja,” jelas Andi pada Magdalene.
Sebenarnya tak ada data terbaru yang spesifik menyebutkan jumlah anak perempuan di jurusan Teknik dan Komputer di Indonesia. Namun, dalam laporan UN Women 2015, jumlah perempuan dalam STEM dari sekolah menengah, kuliah, sampai laboratorium terus menurun.
Di Indonesia, dalam dokumenter Indonesian Women and Technology (2015), siswi di SMK yang berbasis STEM hanya berjumlah 2 persen berdasarkan data dari Pusat Data Dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara laporan Strait Times 2015 menyebut, dari 10 siswa SMK di Indonesia, hanya 4 murid yang perempuan.
Baca Juga: Sejarah ‘Computer Girls’ Sebelum Industri IT Berparas Lelaki
Di tingkat global, representasi angkatan kerja perempuan di bidang STEM juga tidak kalah mengkhawatirkan. Merujuk laporan UNICEF 2020, perempuan hanya mengisi sekitar 40 persen dari angkatan kerja STEM di 68 negara. Masing-masing sangat kurang terwakili dalam pekerjaan teknik dan teknologi di masa depan, karena hanya sekitar 28 persen perempuan profesional yang ada di industri teknologi dunia.
Belum lagi ditambah fakta perempuan juga kurang terwakili dalam kewirausahaan di STEM. Di Amerika Serikat, 26 persen startup teknologi hanya memiliki setidaknya satu pendiri perempuan. Di Eropa, hanya 21 persen pendiri teknologi yang perempuan.
Kurangnya representasi perempuan di angkatan kerja STEM apalagi kepemimpinan perempuan di dalamnya menjadi biang kerok kenapa pengambilan keputusan di level strategis masih dalam kendali penuh laki-laki. Dalam pemahaman patriarkal andosentris inilah peran dan perspektif perempuan dibungkam.Teknologi sebagai end product akhirnya tidak pernah bisa mengakomodir kebutuhan perempuan.
Diperparah Diskriminasi di Tempat Kerja
Kurangnya representasi perempuan di dunia kerja STEM kemudian diperparah dengan bias dan diskriminasi gender yang masih menghantui perempuan. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya memutuskan keluar dari bidang ini. Dalam laporan Pew Research Center 2018, rata-rata perempuan yang bekerja di bidang STEM lebih mungkin mengalami diskriminasi daripada laki-laki.
Setengah alias 50 persen perempuan yang bekerja di bidang STEM mengalami salah satu dari delapan bentuk diskriminasi di tempat kerja karena jenis kelamin mereka. Angka itu lebih banyak daripada perempuan yang punya pekerjaan non-STEM (41 persen) dan jauh lebih banyak daripada laki-laki dalam pekerjaan STEM (19 persen).
Bentuk-bentuk diskriminasi gender yang paling umum mereka alami adalah: upah lebih rendah, dianggap atau diperlakukan seolah tidak kompeten, dan dikritisi berlebihan sekaligus kurang dapat dukungan dari atasan.
Tidak mengherankan kemudian, sesuai dengan laporan dari New View Strategies, sebuah perusahaan manajemen bisnis, sebanyak 38 persen dari 1000 responden perempuan di industri teknologi mengatakan mereka berencana untuk meninggalkan pekerjaan mereka dalam dua tahun pertama.
Industri STEM di Indonesia tak jauh berbeda. Khalilan Lambangsari, dosen di bidang Agroteknologi dan Teknologi Bioproduk di Institut Teknologi Bandung (ITB), bercerita pada kami tentang bias gender dan diskriminasi yang ia alami.
Lilan, panggilan sehari-harinya, pernah sebal betul pada kantornya karena tidak dipilih berangkat pelatihan ke luar negeri. Waktu itu atasannya justru memilih kolega laki-laki Lilan. “Padahal jabatan saya ketika itu adalah principal investigator. Tidak ada alasan yang bisa menjustifikasi kenapa justru yang dipilih itu kolega laki-laki saya bukan saya,” tuturnya.

Saat hamil dan melahirkan pun, Lilan harus mengalami diskriminasi lainnya. Kendati dapat keringanan dan dukungan dari perusahaan untuk cuti, tapi tanpa bayaran alias paid leave. Lilan bahkan diharuskan mencari dan melatih pengganti dirinya selagi ia sedang cuti. STEM yang masih didominasi laki-laki luput mempertimbangkan kebutuhan perempuan yang hamil dan baru melahirkan seperti Lilan.
Baca Juga: Jumlah Perempuan yang Lebih Sedikit di Bidang Teknologi, Apa yang Menyebabkannya?
“Ketika aku bekerja aku tidak mendapatkan fasilitas yang mendukung peran baruku sebagai ibu. Aku tidak mendapatkan paid leave dan aku masih mendapatkan tuntutan peran dari manajer. Tanpa memandang aku sedang hamil, aku dituntut untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kapasitasku sebelum hamil, sesuai dengan timeline kolega laki-lakiku yang lain,” ungkap Lilan. “Ujung-ujungnya pun akhirnya aku memutuskan untuk keluar.”
Perempuan yang Terasing dari Teknologi Sejak Dini
Sebagai seseorang yang bergerak di isu feminisme dan teknologi, Dhyta melihat jarak antara teknologi dan perempuan terjadi sejak mereka masih kecil.
“Sejak kecil perempuan telah teralienasi dengan teknologi,” katanya.
Kurangnya representasi perempuan di angkatan kerja STEM apalagi kepemimpinan perempuan di dalamnya menjadi biang kerok kenapa pengambilan keputusan di level strategis masih dalam kendali penuh laki-laki.
Berbeda dengan laki-laki, perempuan tidak pernah mempunyai relasi baik dengan teknologi. Perempuan memang bisa menggunakannya, karena perempuan dipandang hanya sebagai user semata. Sehingga ketika teknologi yang mereka gunakan rusak, perempuan dibuat kelabakan. Sedangkan relasi laki-laki dengan teknologi dibangun baik sejak mereka kecil yang membuat mereka lebih percaya diri ketika berhubungan dengannya.
“Misal kulkas, mesin cuci, laptop, HP, we can use it but when its broken ada kecenderungan bagi perempuan, like, they will go to men in their lives. Seakan-akan laki-laki akan bisa lebih tahu gimana cara memperbaiki. Padahal belum tentu laki-laki juga bisa memperbaiki, tapi mereka mempunyai kepercayaan diri terhadap teknologi yang lebih besar dibandingkan perempuan,” jelas Dhyta.
Andi menyebut ada istilah technophobia, yang cukup popular di kalangan pekerja STEM untuk menggambarkan fenomena yang dimaksud Dhyta. Technophobia atau ketidaksukaan serta terhadap teknologi terbangun karena budaya patriarki. Perempuan tidak hanya dijauhkan dari teknologi sejak kecil, tapi seiring dewasa mereka dibuat tidak mampu untuk menguasainya.
“Dalam buku-buku pelajaran yang masih bias, anak perempuan tidak melihat bagaimana perempuan ternyata bisa jadi teknisi, astronot. Enggak ada imajinasi itu pada mereka, karena mereka dikondisikan tidak masuk di dunia ini sejak awal,” kata Andi.
Bagaimana perempuan dikondisikan untuk tidak memiliki relasi yang baik dengan teknologi inilah yang kemudian membuat perempuan memiliki kepercayaan diri yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Padahal jika diukur, kemampuan mereka setara.
Dalam penelitian Gender, Performance, and Self-Efficacy: A Quasi-Experimental Field Study, Matthew J. Liberatore dan William Wagner dari Universitas Villanova menemukan tidak ada perbedaan kinerja antara laki-laki dan perempuan dalam menjawab pertanyaan terkait komputasi yang mereka berikan.
Namun, ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam cara laki-laki dan perempuan menilai kinerja mereka sendiri. Perempuan dalam hal ini dinilai kurang percaya diri dengan jawaban mereka di semua skenario, meskipun telah melakukan hal yang sama dengan laki-laki.
Dalam laporan UNICEF 2020, hanya 8 dari 70 negara yang punya 10 persen atau lebih perempuan dengan keterampilan pemrograman.

Perlu Kebijakan Afirmasi dan Transformasi Kurikulum
Problema produk teknologi yang bias dan minimnya representasi perempuan di STEM bak lingkaran setan yang sulit diputus. Tapi, bukan berarti mustahil.
Menurut Andi cara yang baik dan tepat untuk membangun relasi yang baik antara perempuan dan teknologi adalah dengan membumikan bahasa teknologi. Hal ini harus dilakukan sejak dini dalam lingkungan keluarga.
Setelah anak sudah memiliki relasi yang lebih baik dengan teknologi, hal kedua yang bisa dilakukan dalam level keluarga adalah membawa perbincangan soal keberagaman profesi perempuan, kata Andi. Perbincangan ini bisa dilakukan ketika makan bersama keluarga dan dibicarakan dengan ringan dan fleksibel. Dengan menormalisasinya, anak perempuan akan memiliki imajinasi yang sama dengan laki-laki tentang pilihan profesi mereka di masa depan tanpa harus terkotak-kotakan dengan peran gender tradisional.
“Anak perempuan memang harus di-encourage sejak dini agar kepercayaan diri mereka tumbuh dan mereka jadi bisa konsisten untuk berkarya di bidang STEM. Hal ini bermula dari pembangunan imajinasi mereka lewat keberagaman profesi karena selama ini imajinasi itu belum ada di banyak anak perempuan,” kata Andi.
Namun, sayangnya membangun relasi dengan teknologi dan menanamkan imajinasi pada anak melalui perbincangan keberagaman profesi tidak cukup. Sejak awal perempuan sudah berada di garis start yang berbeda dengan laki-laki. Apalagi dalam bidang yang telah dikukuhkan sebagai domain laki-laki. Karenanya, harus ada tindakan afirmasi yang diberikan oleh pemangku kebijakan agar perempuan memiliki kesempatan yang sama.
Andi menganggap tindakan afirmatif berbentuk beasiswa khusus untuk perempuan yang ingin menggeluti bidang STEM jadi amat perlu. Perubahan kurikulum dan metode ajar dalam pendidikan awal yang lebih adil dan setara gender juga jadi tawaran solusi lain darinya.
“Perlu afirmasi, perlu intervensi, enggak bisa tarung bebas. Bentuknya apa? Beasiswa perempuan di bidang STEM, secara eksplisit ngubah kurikulum. Kurikulum di SD kita bias gender, ibu budi masak bapak budi berangkat kerja. Ini kan memunculkan imajinasi anak. Makanya kurikulum, materi ajar, metode pembelajaran itu harus diubah,” jelasnya.
Hal terakhir yang tidak kalah penting untuk menutup kesenjangan gender dalam teknologi adalah dengan mempermudah akses perempuan pada teknologi. Tak lupa dibarengi pembongkaran nilai sosial kultural patriarki mulai dari level komunitas. “Akses pendidikan rata juga perlu, afirmasi ke sistem pendidikan yang luas yang bisa berdampak sangat spesifik ke STEM dan keterwakilan perempuan dalam teknologi,” kata Andi.
Dhyta juga sepakat bahwa pemberian infrastruktur saja tidak cukup. Nilai-nilai misoginis khas patriarki di dunia teknologi juga harus dibongkar.
“Pemberian infrastruktur saja tidak cukup karenanya kita butuh membentuk community-based network yang tentunya dibarengi membongkar nilai-nilai sosial kultural yang patriarkal. Kalau kita enggak membongkar nilai misoginis yang patriarkal.”
Pertanyaan selanjutnya, berapa lama yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan transformatif ini?
Proyek jurnalistik ini didukung oleh Meedan, organisasi non-profit di bidang teknologi yang punya visi memperkuat literasi digital dan jurnalisme global.






















