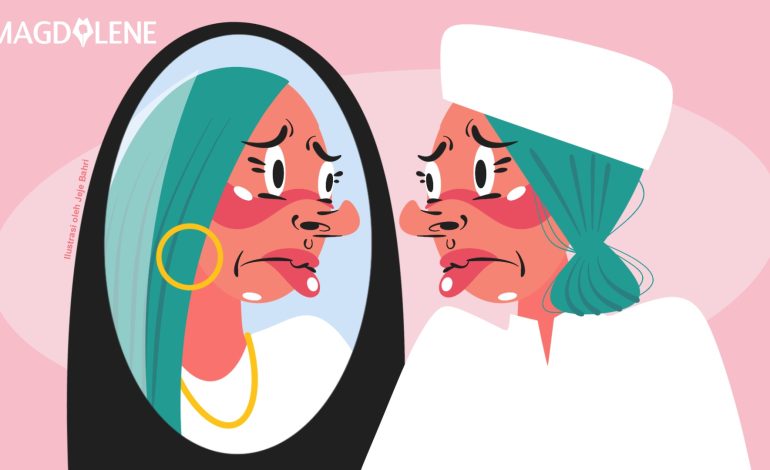Persiapan Menuju Rezim Otoriter, ini yang Bisa Dilakukan Media

Kualitas demokrasi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Sementara, rezim baru Prabowo juga tak bikin kita terlalu optimis bahwa akan ada perbaikan. Beberapa waktu lalu, memburuknya demokrasi di Indonesia diafirmasi dalam laporan lembaga Freedom House, organisasi internasional yang concern dengan isu demokrasi dan perlindungan HAM. Pada 2024, laporan itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan label partly free.
Partly free adalah kondisi yang digunakan untuk menggambarkan Indonesia belum sepenuhnya demokratis karena rendahnya skor-skor yang berkaitan dengan hak berserikat dan berorganisasi (associational and organizational rights), supremasi hukum (rule of law), dan otonomi pribadi serta hak individu (personal autonomy and individual rights). Situasi ini tidak jauh berbeda dengan laporan serupa pada 2023.
Sementara itu, V-Dem Institute, lembaga riset yang menggunakan beberapa indikator demokrasi untuk menilai situasi negara di dunia, pada 2024 mengategorikan Indonesia sebagai negara dengan rezim electoral democracy yang mengarah pada otokratisasi, yang artinya beberapa parameter demokrasi masih berjalan namun ada pola yang cenderung menuju pada kemunduran demokrasi.
Laporan V-Dem itu menyebutkan demokratisasi yang dimulai sejak turunnya Suharto mengarah pada kemunduran. Inti dari kondisi otokratisasi tersebut adalah meningkatnya polarisasi masyarakat dan bangkitnya populisme sejak 2014. Kepemimpinan Presiden Joko “Jokowi” Widodo disebut melemahkan kebebasan sipil dan menghapuskan mekanisme checks and balances pada pemerintah.
Secara umum, parameter yang dipakai oleh Freedom House dan V-Dem mengarah pada runtuhnya pilar-pilar demokrasi yang seharusnya bermuara pada setidaknya dua hal: mekanisme pembatasan atau perimbangan kekuasaan dan penghargaan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Pola ini tampaknya akan terus terjadi, mengingat rezim pemerintahan pasca-Jokowi ini juga sejak awal bermasalah pada aspek penyalahgunaan penggunaan kekuasaan.
Publik agaknya tidak boleh terlalu optimis, atmosfer demokrasi akan semakin baik pada masa-masa mendatang akibat keroposnya pilar eksekutif, yudikatif dan legislatif. Karenanya, media sebagai kekuatan keempat sekaligus bagian penting dari demokrasi perlu selalu menempatkan dirinya sebagai pembela publik.
Namun, di tengah situasi rezim yang menuju otokratisasi, hal ini tentu tidak mudah. Sejumlah praktik jurnalisme yang lebih berpihak kepada publik perlu segera diimplementasikan. Salah satu caranya dengan melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narasumber yang merupakan figur elite.
Baca juga: Kebebasan Pers dan Berekspresi Terancam Pasca-Pemilu 2024?
Lepas dari Ketergantungan Narasumber Elite
Rezim yang cenderung tertutup sering kali ditandai dengan adanya ketidakterbukaan informasi. Informasi sebagai aset yang berharga dalam membangun kecerdasan publik kemudian dipelintir atau bahkan ditutup pihak yang berkuasa sedemikian rupa agar tidak bisa diakses oleh masyarakat.
Sebagai contoh, pada saat sesi debat calon presiden (capres) 2024, Prabowo Subianto menolak membuka data pertahanan Indonesia dengan dalih hal tersebut merupakan rahasia negara. Jokowi bahkan mendukung argumentasi Prabowo tersebut.
Contoh lainnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pernah tidak mau membuka data terkait klaimnya bahwa banyak warganet yang mendukung penundaan Pemilu 2024.
Berkaitan dengan isu rahasia negara dan keamanan nasional, pada tahun 2013 Amnesty International memberikan pernyataan sikap tentang prinsip-prinsip keberimbangan keamanan nasional (national security) dan hak atas informasi (right to information).
Ada lima hal yang menyangkut hal tersebut. Pertama, informasi harus dirahasiakan hanya jika pengungkapannya menimbulkan risiko nyata dan dapat menimbulkan kerugian signifikan terhadap kepentingan nasional yang sah. Kedua, informasi mengenai pelanggaran serius HAM internasional atau hukum humaniter harus selalu diungkapkan.
Ketiga, masyarakat harus mempunyai akses terhadap informasi mengenai program surveilans. Keempat, tidak ada lembaga pemerintah yang boleh dikecualikan dari pengungkapan informasi. Kelima, pejabat publik yang bertindak demi kepentingan publik untuk mengungkap pelanggaran pemerintah harus dilindungi dari pembalasan.
Sementara itu, sejumlah peristiwa yang telah disebutkan di atas menjadi sinyal krusial bagi media akan perlunya mempertimbangkan kembali kredibilitas para narasumber elite ini. Ketergantungan media pada segelintir narasumber pejabat penting, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah, dapat melumpuhkan kegesitan media.
Salah satu riset ilmiah terkait jurnalisme menyoroti bahwa narasumber yang merupakan figur yang dipilih secara demokratis, seperti Presiden, sering kali memberikan label kepada media massa yang melaporkan ketidakbenaran sebagai “palsu” dan “tidak jujur”.
Hal tersebut tentu tidak bisa disikapi dengan penjelasan sesuai standar umum bahwa objektivitas jurnalisme harus mencakup keberimbangan narasumber, termasuk narasumber otoritatif seperti pejabat negara atau pejabat partai.
Pada titik ini, jurnalisme tidak lagi bisa melakukan liputan dengan aturan lazim. Media harus mampu menantang sumber-sumber otoritatif yang selama ini sering digunakan oleh media, termasuk untuk alasan keberimbangan dan menjaga objektivitas.
Posisi sumber-sumber otoritatif yang selalu kuat harus digeser dengan publik yang selama ini tidak pernah mendapatkan tempat yang sentral di media. Publik sebagai pihak yang memiliki pengetahuan dan menjadi pihak yang paling terdampak dari kebijakan pemerintah perlu diberikan ruang yang luas agar opininya mendapatkan sorotan.
Misalnya, dalam konteks Indonesia, masyarakat adat justru lebih sering muncul dalam konteks isu wisata, bukan isu politik yang sering kali meminggirkan peran dan keberadaan mereka. Riset menunjukkan bahwa berita yang membuka ruang partisipasi publik menjadi alternatif untuk menantang sumber-sumber otoritatif. Wacana dan opini alternatif perlu selalu diperlihatkan agar tidak ada dominasi.
Ketergantungan terhadap narasumber elite tidak hanya merusak nalar publik namun juga dapat membuatnya terperosok pada kesalahan pengambilan keputusan-keputusan penting. Informasi yang seharusnya dapat diakses dan dibandingkan dengan informasi lainnya menjadi semakin sulit didapatkan.
Di satu sisi, narasumber elite tidak hanya memiliki kekuasaan dalam mendominasi wacana namun juga alat produksi yang masif untuk menjaga agar produksi informasi sesuai dengan yang mereka inginkan.
Baca juga: Jokowisme, Trumpisme, dan Dinasti Politik: Nafsu Kekuasaan yang Kikis Demokrasi
Alternatif Sumber: Jurnalisme Data
Ketergantungan pada narasumber elite sejatinya bisa dibebaskan melalui satu konsep yang telah lama dikenal pada praktik jurnalisme di Indonesia yakni jurnalisme data.
Jurnalisme data fokus pada pembukaan data kepada publik dan penggunaan input untuk analisis data, visualisasi dan pelaporan. Jurnalisme jenis ini menekankan pada hubungan antara desain visualisasi dan nilai jurnalistik. Tidak hanya itu, ragam jurnalisme ini juga memandang pembaca sebagai co-constructor atas klaim kebenaran dan moral
Sudah saatnya jurnalisme data diletakkan pada aspek-aspek yang tidak saja berkaitan dengan teknologi termasuk keindahan visual infografis semata namun bagaimana dapat menghadirkan praktik quality journalism, yakni tidak hanya memberikan ruang bagi data dan publik namun juga nilai kualitas produk jurnalistik.
Peter J. Anderson dalam tulisannya yang berjudul “Defining and Measuring Quality News Journalism” menyebutkan bahwa quality journalism dapat diukur melalui enam parameter, yakni comprehensibility (pemahaman), context (konteks), causality (kausalitas), comparativeness (komparatif), comprehensiveness (komprehensif) dan accuracy (akurasi).
Comprehensibility berkaitan dengan struktur logis dan kejelasan eksposisi. Context mengacu pada bahwa berita harus memiliki konteks yang memadai, misalnya latar belakang atau konteks umum lainnya yang dapat menambah pemahaman publik. Causality berkaitan dengan penjelasan yang baik dari sebuah peristiwa misalnya penyebab kondisi-kondisi tertentu. Comparativeness adalah permasalahan yang dilaporkan seharusnya berisi multiperspektif sehingga menawarkan cara alternatif bagi publik untuk melihat sebuah permasalahan. Sementara accuracy menyangkut sumber dan metode verifikasi yang tepat, termasuk keberagaman rentang narasumber sehingga berita dapat mewakili sejumlah argumen.
Contoh salah satu produk jurnalistik yang mampu mengurangi ketergantungan dengan narasumber elite dan secara umum memenuhi parameter quality journalism adalah laporan “Semua Bisa Kena” yang berisi kisah-kisah korban kriminalisasi UU ITE. Laporan kolaborasi ini menghadirkan beragam perspektif korban yang memiliki kisah dan latar belakang yang variatif. Kisah-kisah yang berbeda ini mampu memberikan tidak hanya kekayaan argumen narasumber namun juga konteks dan relasi sebab akibat yang lengkap.
Baca juga: Pengguna Internet Meningkat, tapi Kebebasan Pers Terancam: Kita Tetap Butuh Jurnalisme Baik
Laporan “Semua Bisa Kena” juga membuka peluang bagi publik untuk membagikan kisah serupa. Akurasi dijaga dengan data yang lengkap dan kredibel. Selain menggunakan data publik, produk jurnalistik ini juga memakai data putusan MA untuk melihat kasus ITE dari ranah hukum. Dengan banyaknya data, berita seperti ini mampu menunjukkan bahwa permasalahan ini bukan hanya kasus tunggal namun membentuk pola kriminalisasi dan bisa berdampak luas.
Penjelasan dan contoh di atas menunjukkan bahwa keuntungan utama dari praktik jurnalisme data tidak hanya untuk menghindari ketergantungan pada narasumber elite, tetapi juga dapat menantang sumber-sumber otoritatif. Artinya, media dapat menyajikan pengetahuan alternatif sehingga kekuasaan tidak berjalan semena-mena.
Dengan melepaskan diri dari jerat ketergantungan terhadap narasumber elite dan menantang sumber otoritatif, perjuangan kebebasan berekspresi mendapatkan energi dalam bentuk informasi yang beragam dan lengkap. Ini akan dapat membuat publik terhindar dari jebakan seperti logika “rahasia negara” jika liputannya lebih banyak mengeksplorasi permasalahan pertahanan di Indonesia.
Ke depannya, media dan para jurnalis disarankan tidak hanya menitikberatkan pada kutipan atau ucapan tokoh yang diposisikan sebagai “narasumber otoritatif”.
Senja Yustitia, Dosen, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.
Ilustrasi oleh: Karina Tungari