Semua Orang Mau Diakui di Medsos, tapi Tak Semua Berani Tampil Asli
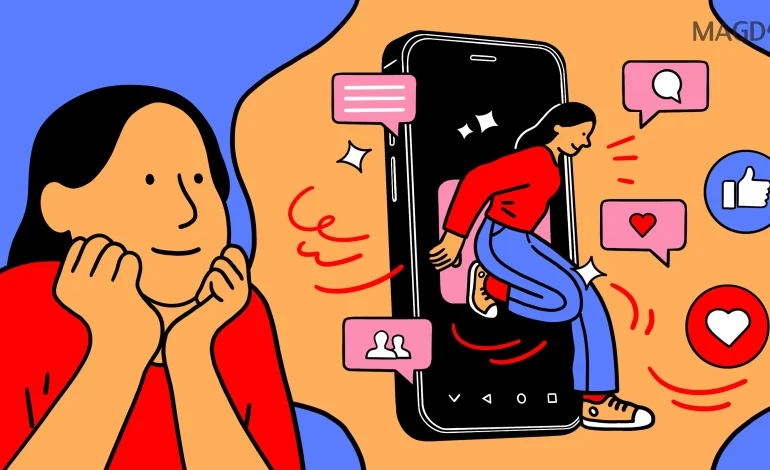
Anggi, 23, cukup aktif di media sosial. Ia kerap mengabadikan momen kecil dalam kesehariannya, terutama saat mengajar di preschool and sensory class. Dalam video terbarunya, anak-anak terlihat bermain tepung warna di atas meja sensorik, tertawa ketika tangan mereka belepotan cat.
Bagi Anggi, momen seperti itu patut dibagikan. “Gue pasti ngepost yang menurut gue bagus buat di-share, buat dilihat orang banyak,” ujarnya pada Magdalene (31/10). Ada kepuasan tersendiri ketika apa yang ia kerjakan dapat terlihat banyak orang. Seolah menjadi penanda bahwa ia hadir dan aktivitasnya berarti.
Media sosial juga menjadi semacam arsip pribadi baginya. Ia senang menonton ulang dokumentasi yang pernah diunggah. Aktivitas posting menjadi cara sederhana untuk merayakan hal-hal yang memberinya rasa hangat dalam hidup.
Baca juga: Yang Perlu Kita Tahu tentang Wacana Tata Kelola Medsos
Kebutuhan untuk Dilihat dan Diterima
Kebutuhan seperti yang dirasakan Anggi tidak tunggal. Menurut Psikolog Ifa Hanifah Misbach, manusia selalu membutuhkan rasa terhubung dan memiliki.
“Sejak awal keberadaannya, manusia adalah makhluk sosial yang bergantung pada koneksi dan penerimaan dari kelompoknya untuk bisa bertahan hidup,” jelas Ifa kepada Magdalene (31/10).
Media sosial kemudian menjadi ruang baru untuk memenuhi kebutuhan keterhubungan ini. Dalam hiruk pikuk aktivitas dan tekanan hidup modern, ruang digital memberi tempat seseorang merasa hadir dan diakui, meski interaksinya serba singkat.
Hal serupa dialami William, 23. Ia dahulu jarang menampilkan dirinya di media sosial, meski sejak remaja senang memotret. Pengalaman diejek teman tentang fisiknya membuat ia menahan diri. Ia khawatir ejekan di ruang sekolah akan terbawa ke ruang digital, sehingga ia memilih hanya menjadi penonton.
“Sosial media gue cuma buat scrolling aja. Dulu yang jadi sasaran guyonan mereka itu kulit gue yang hitam, wajah gue yang enggak simetris, dan gigi gue yang moncong,” kata William kepada Magdalene (31/10).
Keadaannya berubah belakangan. William mulai membagikan potret dirinya, pemandangan, hingga pendapat pendek soal isu sosial politik. Baginya, setiap unggahan menandai keberadaannya. Ia ada dan layak terlihat.
“Gue merasa bebas untuk posting apapun, dalam artian suka-suka gue. Kalau orang gak suka ya tinggal unfollow,” ujarnya.
Perubahan ini menunjukkan ruang digital bisa menjadi tempat pemulihan. Di balik unggahan, ada proses perlahan membangun penghargaan diri.
Riset Rebecca Godard dan Susan Holtzman dari University of British Columbia yang menganalisis 141 penelitian dengan lebih dari 145 ribu partisipan menemukan, semakin aktif seseorang berinteraksi di media sosial, semakin besar dukungan sosial digital yang ia rasakan. Aktivitas ini memperkuat rasa diterima dan terhubung.
Dalam artikel Are Active and Passive Social Media Use Related to Mental Health, Wellbeing, and Social Support Outcomes? (2024), Godard dan Holtzman mencatat keterlibatan aktif di media sosial berkaitan dengan meningkatnya kesejahteraan dan suasana hati positif.
Baca juga: Polaroid AI Bahayakan Perempuan dan Normalisasi Kekerasan Digital
Autentisitas dan Kebahagiaan Hakiki
Di media sosial, seseorang kerap berada di antara dua dorongan: menampilkan diri seideal mungkin atau tampil apa adanya. Keduanya tidak saling meniadakan, tetapi tujuan di balik keduanya memberi dampak berbeda.
Ifa menjelaskan pencarian pengakuan lewat likes memang dapat memicu rasa senang sesaat. “Secara neurologis, ada aktivasi di area tegmental ventral (VTA) di otak yang berkaitan dengan sistem penghargaan. Saat kita menerima likes atau pujian, VTA memicu dopamin sehingga kita merasa bahagia dan tenang,” katanya.
Namun, efek ini mudah menguap. Ketika tidak ada respons sosial baru, dorongan mencari validasi muncul kembali sehingga rasa bahagia menjadi rapuh dan bergantung pada orang lain.
Penelitian Erica R. Bailey dkk. terhadap lebih dari 10.000 pengguna Facebook dalam Authentic Self-Expression on Social Media is Associated with Greater Subjective Well-Being (2020) menemukan, mengekspresikan diri secara autentik berkaitan dengan tingkat kepuasan hidup lebih tinggi. Mereka menyebutnya quantified authenticity, yakni sejauh mana ekspresi daring mencerminkan diri sebenarnya.
Menariknya, efek positif ini konsisten di berbagai tipe kepribadian. Artinya, menjadi diri sendiri tetap memberikan manfaat, apa pun bentuknya.
Ini menunjukkan media sosial bukan sekadar tempat membangun citra. Ia dapat menjadi ruang tumbuh, ketika digunakan untuk mengekspresikan diri secara jujur. Keseimbangan antara menampilkan sisi terbaik dan hadir apa adanya yang pada akhirnya melahirkan kebahagiaan yang bersumber dari penerimaan diri, bukan dari jumlah engagement.
Baca juga: 5 Hal yang Perlu Diketahui Soal Teknologi Deepfake
Tetap Waras di Ruang Digital
Menemukan keseimbangan ini bukan perkara mudah. Di tengah banjir unggahan, seseorang bisa saja terjebak dalam pembandingan tanpa henti.
Menurut psikolog Gisella Tani Pratiwi, kesadaran atas batas dan tujuan penggunaan media sosial penting untuk menjaga kesehatan emosional. “Kalau kita punya hubungan yang baik di dunia nyata dan tahu untuk apa menggunakan media sosial, kita tidak mudah terseret pada pencarian validasi tanpa akhir,” jelas Gisella kepada Magdalene (31/10).
Ia menekankan pentingnya jeda saat lelah serta kembali hadir di ruang-ruang nyata yang memberi dukungan. Dunia digital adalah perpanjangan kehidupan, bukan pengganti diri.
Pada akhirnya, semua orang ingin diakui. Namun kebahagiaan lebih mungkin ditemukan ketika keberanian untuk tampil autentik perlahan tumbuh, dan seseorang menerima dirinya tanpa syarat penilaian orang lain.
Ilustrasi oleh Karina Tungari






















