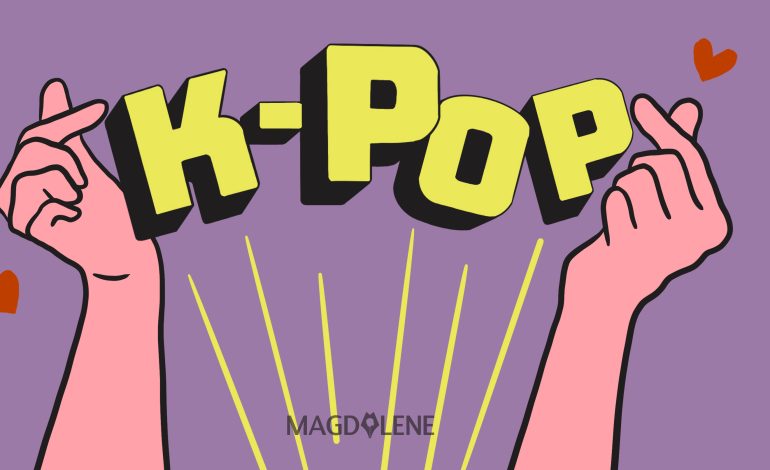Memoar Depok di Mata Saya: Enggan Kembali Meski Banyak Memori

Banyak perantau yang rindu kampung halaman atau kota asal, sehingga mereka bermimpi pulang. Namun, tidak dengan saya. Tumbuh dan tinggal di Depok selama 17 tahun sebelum kuliah ke luar kota pada 2016, saya tetap tak suka kota itu. Bahkan, kendati jarak tempat tinggal sekarang ke Depok hanya terpaut satu jam, saya cuma akan pulang ketika di(ter)paksa orang tua.
Tindakan ini saya ambil bukan tanpa alasan. Orang bilang kita bisa mencintai dan membenci dalam satu waktu. Namun, deretan memori pahit di Depok membuat saya terus berjarak dengan Kota Belimbing ini. Belum lagi, sejumlah problem lain yang membuat keputusan saya makin bulat.
Tentu saja dalam hal ini, saya enggak peduli-peduli amat dengan perundungan orang-orang terhadap Depok. Disebut aneh karena berbagai “spesies” naik daun di Depok, dari babi ngepet, pocong keliling, kolor ijo, hingga keranda terbang. Namun, yang jauh lebih problematik adalah, Depok tak malu-malu menunjukkan betapa amburadulnya ia. yang lebih ironis, Depok punya beragam julukan manis macam “Kota dengan Lingkungan Bersih” dan “Kota Peduli HAM”.
Saya perkenalkan kepada kalian, Kota Depok.
Depok Semrawut dan Panas
Jika melihat kemacetan dan semrawutnya Depok saat ini (halo, Margonda!), mungkin kamu takkan percaya kota itu pernah menjadi kawasan yang tentram dan asri pada masanya.
Dalam buku Depok Tempo Doeloe: Potret Kehidupan Sosial & Budaya Masyarakat (2011), sejarawan Yano Jonathans menggambarkan bagaimana Depok yang rimbun dan tenang menjadi tujuan para petapa untuk bersemedi. Tak heran banyak padepokan di tepian Situ Pancoran Mas serta Kali Ciliwung berdiaspora. Saking tenangnya, oleh penjajah Belanda, Depok kemudian dijadikan tempat pilihan berakhir pekan.
Wajah sejuk Depok mulai pudar sejak pemerintah membangun ribuan rumah penduduk pada 1976. Wilayah itu kian padat seiring kepindahan kampus Universitas Indonesia dari Jakarta Timur pada 1987. Menurut catatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kepadatan penduduk di Kota Depok saja pada 2016 mencapai 10.883 jiwa/km2. Jika begini melulu, kata Bappenas, Depok digadang-gadang jadi kota terpadat setelah Jakarta pada 2045.
Tingginya arus perdagangan serta ambisi pemerintah kota untuk menyulap Depok menjadi zona industri memperburuk situasi. Ditambah lagi ambisi pembangunan pusat perbelanjaan, ruko, jalan layang, serta penghubung tol antar-kota yang berpusat di Jalan Margonda Raya.
Sementara itu, Ruang Terbuka Hijau di Depok baru mencapai 11 persen dari total kewajiban 30 persen, menurut Badan Lingkungan Hidup Kota Depok pada 2019. Tidak heran jika hawa di Depok tidak jauh berbeda dengan kamar sauna.
Ngelekeb adalah kata dalam Bahasa Sunda yang tepat untuk menggambarkan cuaca Kota Depok: Panas, pengap, tanpa aliran udara segar sama sekali. Beberapa kali saya serasa mendapatkan heat stroke selama berjalan kaki di tengah terik dan polusi udara yang pekat. Hal ini juga turut menciptakan kecemasan setiap kali saya harus beraktivitas di ruang terbuka di Depok. Bahkan, udara di Mekkah pun lebih bisa ditoleransi karena masih ada angin yang bertiup sesekali.
Baca juga: Ada Apa dengan Depok dan LGBT?
Depok dan Peraturan Konyol
Tidak hanya lingkungan dan tata kotanya yang berantakan, Depok pun kerap kali mengundang kontroversi akibat peraturan Pemerintah Kota yang terasa konyol, terutama sejak kota itu dikuasai oleh partai Islam tertentu.
Selama dua kali masa jabatan sejak 2006-2016, Wali Kota Depok dari klan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nur Mahmudi Ismail meluncurkan berbagai program yang membuat alis auto-naik. Ia, misalnya, meluncurkan program One Day No Rice, One Day No Car, dan larangan menggunakan elevator pada waktu tertentu untuk para pegawai negeri sipil. Selain itu juga ada “imbauan” untuk makan dan minum dengan tangan kanan, serta memisahkan zona parkir berdasarkan jenis kelamin.
Pejabat penggantinya juga tidak kalah konyol dalam melahirkan kebijakan. Wali Kota Mohammad Idris sempat memberlakukan aturan pemutaran jingle di setiap lampu lalu lintas sebagai solusi kemacetan abadi Kota Depok. Idris mengatakan, lagu yang dia nyanyikan (ya, dia sendiri yang menyanyikannya) berguna untuk mengurangi stres para pengendara. Efektifkah? Tentu tidak. Saya malah makin stres.
Baca juga: Depok dan Perda Anti-LGBT yang Salah Kaprah
Depok Kota [Tidak] Peduli HAM
Pada 2016, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menganugerahi Depok dengan penghargaan sebagai “Kota Peduli HAM”. Pasalnya, Depok dinilai berhasil dalam penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Penghargaan itu menuai kritik karena jauh panggang dari api. Banyak fasilitas umum saja tidak ramah warga, apalagi mereka yang memiliki disabilitas. Saya selalu merasa seram menyeberang di jembatan Margo City Mall karena tangganya yang rusak serta bercelah sampai saat ini.
Di lain waktu, Pemkot Depok kembali mengepakkan sayap ketidakbhinekaan-nya dengan menyegel ulang Masjid Al-Hidayah milik Jemaat Ahmadiyah, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, pada 2021.
Namun, kebijakan buruk yang paling terasa personal bagi saya sebagai seorang queer adalah aturan diskriminatif terhadap kelompok LGBT. Menyusul vonis pada 2020 terhadap warga Depok, Reynhard Sinaga, yang ditangkap Kepolisian Inggris karena memperkosa 200-an laki-laki, Wali Kota Idris menggiatkan razia terhadap LGBT.
Melansir BBC Indonesia lalu, Idris mengerahkan tim Satpol PP dan perangkat pemerintah lain untuk menyisir indekos, apartemen, hotel, bahkan sampai pusat perbelanjaan demi menjaring orang-orang gay, transgender dan anggota LGBT lainnya untuk didata dan “dibina” secara keagamaan.
“Secara kehidupan sosial dan moralitas, semua ajaran agama pasti mengecam perilaku LGBT,” ujarnya.
Ini adalah jurus klasik andalan para homophobes untuk mendiskriminasi kelompok LGBT. Sebagai seorang queer, saya amat terluka karena Idris jelas-jelas menyamaratakan seluruh individu LGBT sama seperti Reynhard—seorang predator seks.
Muhammad Isnur yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menilai kebijakan Idris tersebut sarat akan muatan politik. Ia menganggap Idris memainkan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) demi memungut simpati kelompok tertentu dan mendongkrak popularitas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Di titik ini, saya tidak akan paham jika ada orang yang terang-terangan mengagumi kota tersebut. Gimana bisa menyayangi tempat yang tidak menginginkan kamu? Serius, deh, tidak banyak yang bisa diacungi jempol dari Kota Depok—bahkan belimbingnya sekali pun.