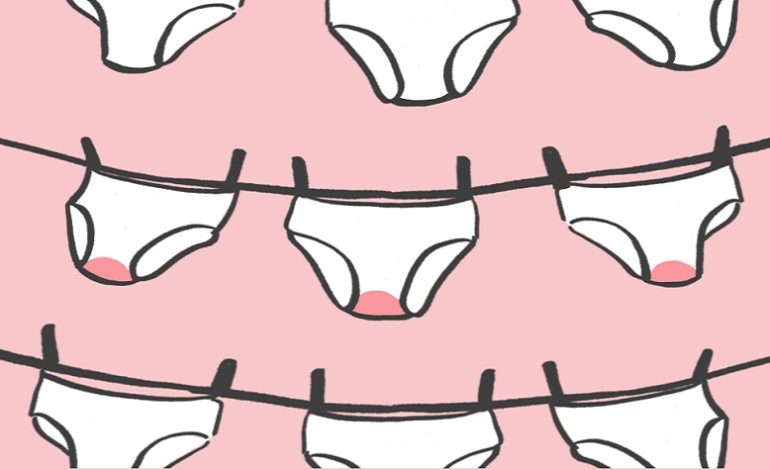
Siang itu panggilan telepon masuk dari anak sulung saya. Dia menangis tersedu-sedu dan terdengar cemas. Sebagai ibu saya segera sigap dan menanyakan apa yang menyebabkannya menangis. Lalu dia menjawab, “aku keluar darah, Bun.” Seketika saya tersenyum.
Saat si sulung mendapati menstruasi pertamanya baru-baru ini, saya tidak ada di sampingnya karena urusan pekerjaan. Namun beberapa waktu sebelumnya, kami sudah membahas tanda-tanda tubuhnya yang belakangan berubah. Dimulai dari adanya vlek di celana dalam beberapa waktu lalu, timbulnya bulu pubis, jerawat, dan reaksi hormonal lainnya seperti sindrom pramenstruasi (PMS).
Satu minggu setelah fase haid, kami melakukan selebrasi kecil-kecilan, semacam selamatan. Hal ini kami buat untuk merayakan otoritas tubuh perempuan saat momen menstruasi mereka alami pertama kali. Jika masyarakat kita begitu fasih pada perayaan puber yang maskulin seperti khitanan atau sunatan (biasanya bahkan dengan pesta, tenda, dan undangan warga), maka tidak berlebihan rasanya jika kami merayakan menarke (menstruasi pertama) anak kami.
Sebagai orang tua, kami mendoakan keselamatan dia. Selamat karena dia sedang dan akan memasuki fase baru yang saya pastikan akan sangat berharga untuk hidupnya. Seiring dengan itu, ada perasaan yang tidak bisa saya gambarkan secara utuh. Serupa keharuan tapi diiringi juga dengan kecemasan. Terharu karena mengingat masa kehamilan serta kelahirannya. Serasa baru saja kemarin dia belajar berjalan, mengucap kata pertamanya, berceloteh, dan semua gejolak haru itu. Di sisi lain, juga ada sedikit kecemasan tentang bagaimana dia akan tumbuh remaja, meninggalkan masa kanak-kanak, dan masuk ke fase yang bisa dikatakan mulai rumit.
Baca juga: Kisah Menstruasi Pertama: Siklus Ketidaktahuan Menahun
Kerumitan itu terjadi pada saat saya remaja dulu. Saya tidak mendapatkan perlakuan seperti apa yang saya sampaikan kepada anak saya sekarang. Saat pertama kali menstruasi, saya ingat ibu saya ada di rumah dan tanpa basa-basi dia mengambil pembalut. Tidak ada pendampingan atau pelatihan manajemen kebersihan menstruasi yang layak dan runut. Dia hanya mengingatkan setidaknya tiga hal saat itu.
Pertama, “Mulai sekarang hati-hati, karena kamu bisa hamil!” Ibu saya bahkan tidak mengawali penjelasan terkait proses pembuahan atau dasar-dasar kesehatan reproduksi yang jelas. Dia hanya ingin menekankan dan tentu meminta saya menurutinya, patuh tanpa kritik yang lebih jauh. Dari petuahnya tersebut, saya yang usia remaja saat itu justru mempelajari kesehatan reproduksi dari sumber yang keliru.
Kedua, “Kamu sudah mulai dewasa. Urus semua sendiri.” Padahal saat itu saya baru berusia 12 tahun dan masih dalam definisi usia anak. Ibu saya justru mulai membangun jarak dan menganggap seolah-olah saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Sikap dan perlakuan yang seperti inilah yang membuat saya tidak diakui, dihargai, atau bahkan tidak valid di hadapannya. Tidak heran jika relasi toksik lebih kental mewarnai hubungan kami.
Baca juga: Lebih Kenal dengan Vagina Lewat Cawan Menstruasi
Ketiga, “Menstruasi itu darah kotor, jadi kamu tidak boleh blablabla…” Ibu membanjiri saya dengan segudang mitos mengenai menstruasi. Dimulai dari tidak boleh memotong rambut, memotong kuku, mengonsumsi makanan atau minuman tertentu, mencuci rambut, dan lain sebagainya yang tentunya sesat pikir. Banyak mitos dan kepercayaan tentang menstruasi yang justru merugikan kesehatan perempuan. Membersihkan diri seperti mencuci rambut justru sangat penting. Konsumsi daging, ikan, dan nutrisi kaya protein serta zat besi justru dibutuhkan untuk mengganti sel-sel darah merah yang hilang saat menstruasi.
Pengenalan kesehatan reproduksi sejak bayi
Sebagai generasi milenial yang dibesarkan oleh generasi baby boomers, pendekatan reward and punishment dalam aturan yang tidak konsisten dan penuh mitos merupakan pola pengasuhan yang saya terima. Saya tentu ingin memutusnya. Langkah yang paling mudah dilakukan adalah saat saya dan pasangan memberlakukan pola pengasuhan yang setara dan memberdayakan kepada ketiga anak perempuan kami.
Pengenalan mengenai kesehatan reproduksi adalah langkah awal. Sejak bayi, kami menggunakan semua istilah dan pembahasaan bagian tubuh manusia tanpa bias, mitos, stigma, dan ketabuan. Contoh, kami tidak mengganti kata vagina dengan “kue apem”,”warung”, “pepe”, “anunya”, dan istilah lain, sehingga anak-anak kami tahu dan memahami bagian tubuh mereka serta fungsinya.
Baca juga: Memikirkan Kembali Menstruasi: Darah dalam Iklan Pembalut
Konsep konsensual juga sangat penting. Otoritas tubuh adalah milik mereka sendiri. Bukan orang lain, bahkan tidak orang tuanya. Tentu ada benturan pemahaman dari generasi sebelumnya seperti kakek nenek mereka, tetapi pemahaman di dalam relasi keluarga inti menurut kami adalah yang terpenting. Proses penyaringan informasi atau konsepsi yang tradisional di luar kami mesti dilakukan secara terbuka di dalam keluarga inti. Peran saya dan pasangan sebagai orang tua adalah kunci.
Membuka ruang diskusi dan siap dikritik sebagai orang tua adalah fase yang terus-menerus kami lakukan. Anak-anak kami lahir di era generasi Z dan Alfa. Sebagai generasi yang disuguhi informasi dengan begitu cepat dan masif, bisa jadi anak-anak tidak memiliki waktu dan energi lebih untuk memilah sumber informasi dan pertemanan. Sehingga penting memastikan bahwa kami sebagai orang tua adalah pihak yang bisa mereka percaya untuk berbagi cerita dan keluh kesah, salah satunya mengenai tubuh, diri, dan kesehatan reproduksi.
Saya ingin kami sebagai orang tua dan keluarga bisa memutus mitos dan ketabuan seputar tubuh perempuan dan menstruasi. Kami terus mengedukasi diri, keluarga, dan orang lain mengenai pentingnya kesehatan reproduksi bagi remaja dan generasi masa depan.






















