Menjadi Subjek dalam Feminisme
Praktik penjajahan membawa banyak penyakit pascakolonial di tubuh masyarakat yang dijajah, termasuk dalam tubuh feminisme.
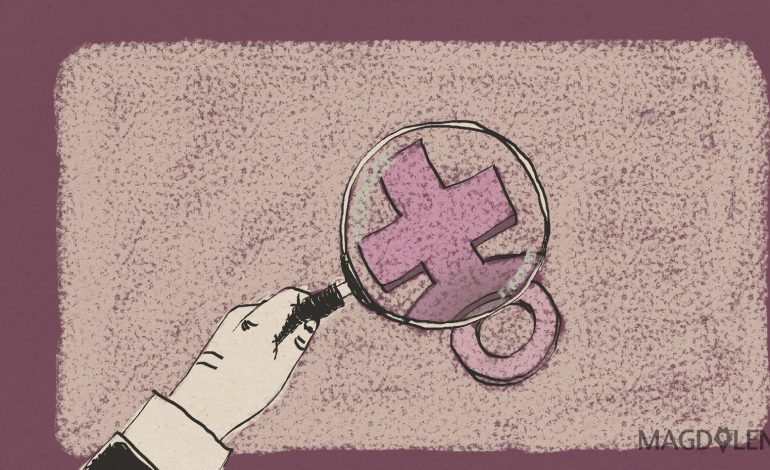
Salah satu pertanyaan inti, kalau bukan pertanyaan paling mendasar, dari feminisme (sebagai gerakan maupun sebagai laras intelektual) adalah tentang bagaimana untuk menjadi subjek. Subjek di sini dimaknai sebagai pelaku yang diasumsikan berdasarkan keutuhan otonomi diri dibandingkan mereka yang umumnya dipandang sebagai “yang dikenai tingkah laku” atau objek.
Mengapa penting sekali untuk menjadi subjek? Asumsinya ada dua. Pertama, secara ontologis, kesubjekan dipandang sebagai inti dari kemanusiaan. Maka bukanlah manusia seutuhnya jika seseorang hanya menjadi objek. Kedua, secara epistemologis, ketika mereka yang umumnya berposisi sebagai objek kemudian berubah menjadi subjek maka upaya kemanusiaan untuk mencapai “kebenaran” akan menjadi lebih “sah” adanya.
Maka kemudian lahirlah beragam warna feminisme yang dengan metodenya masing-masing berusaha untuk menjadikan mereka yang tertindas, terutama perempuan, sebagai subjek. Dalam catatan ini saya menyederhanakannya menjadi dua arus utama feminisme (yang tentunya tidak eksklusif terpecah-belah satu sama lain). Feminisme berbasis sekularisme (feminisme liberal, feminisme sosialis, feminisme Marxis, feminisme radikal, feminisme kulit hitam, dsb) meyakini bahwa jalan perubahan dari objek menjadi subjek terletak pada ideologi-ideologi sosial-politik-ekonomi-budaya itu sendiri yang harus dibebaskan dari dominasi patriarki.
Sedangkan feminisme berbasis agama (feminisme Islam, feminisme Kristiani, feminisme Yahudi, feminisme Hinduisme, dll) meyakini bahwa metode perubahan itu tidak cukup hanya berasal dari ideologi-ideologi sosial-politik-ekonomi-budaya itu tadi, melainkan juga harus berasal dari intuisi keagamaan yang dipegang teguh oleh banyak kelompok marginal di seluruh dunia.
Tentu saja deskripsi kedua arus utama feminisme ini terlihat telanjang saja tanpa nilai-nilai kepentingan sampai kita melihat bahwa penjelasan secara definisi seperti ini tidak menjawab elemen epistemologis dari kerangka feminisme yang tersebut di atas. Pendek kata, kebenaran seperti apa dan oleh siapa yang dihasilkan oleh feminisme berbasis sekuler? Dan kebenaran seperti apa dan oleh siapa yang dihasilkan oleh feminisme berbasis agama?
Dalam elemen epistemologis itulah pertanyaan apa artinya menjadi subjek sangat penting adanya. Dan di sini penting bagi kita untuk menilik lebih jauh dari mana datangnya sekularisme.
Pendek kata, sekularisme merupakan produk ideologis yang lahir dari keengganan Eropa atas hadirnya agama (terutama Katolik dalam bentuk Tahta Suci Romawinya) yang mereka anggap merupakan akar utama dari Perang 30 Tahun (1618-1648). Perang ini sangat mematikan bagi Eropa. Tercatat secara resmi kurang lebih 8 juta orang meninggal dunia. Pada tahun 1648 pihak-pihak yang berperang menyatakan untuk berdamai di Kota Westphalia dan lahirlah konsep negara-bangsa dengan prinsip inti transfer kuasa dari Gereja menuju pemerintahan non-agamis.
Tentunya sebagai sebuah ideologi, perkembangan sekularisme tidak berhenti di situ saja. Terdapat kesadaran kawasan yang berkembang tentang betapa kuatnya landasan ‘sekularisme’ sebagai prinsip kuasa. Dominasi kontrol negara atas kekerasan yang sah (dengan kata lain militer) yang sebelumnya dilegitimasi melalui narasi-narasi Kristiani, kemudian disahkan dengan narasi-narasi yang menempatkan agama sebagai musuh utama. Kekerasan yang sah digunakan untuk menjaga agama supaya tetap pada tempatnya, yakni ranah pribadi saja. Kuasa dan kekerasannya tetap sama, narasinya saja yang berbeda.
Anehnya, ketika era pelayaran kolonialisme bermula, agama (Kristiani dalam berbagai bentuknya) diekspor oleh Eropa kepada wilayah jajahannya untuk melegitimasi kekuasaan mereka di sana. Permainan standar ganda ini tidak bermula dari Amerika Serikat saja, melainkan sudah menjadi prinsip utama dari kolonialisme sejak semula.
Praktik alienasi yang bekerja di atas prinsip biner (saya baik, mereka buruk) pun diterapkan di wilayah koloni. Agama tradisional itu primitif, agama penjajah itu modern; perempuan masyarakat asli itu terkekang, perempuan penjajah itu bebas; masyarakat kulit berwarna di daerah koloni itu barbar, masyarakat kulit putih itu beradab; dan seterusnya. Di sinilah kosmologi (alam pikir) hitam-putih yang tidak mengenal kekayaan ragam lahir.
Setelah Perang Dunia II, cengkeraman narasi penjajahan itu masih terus digalakkan oleh negara-negara penjajah Eropa dan Amerika Serikat melalui kontrol budaya dan pemikiran, walaupun sebagian besar wilayah koloni secara de jure telah memerdekakan diri. Narasinya sedikit banyak berubah.
Sekularisme yang dahulu hanya dipegang teguh di wilayah penguasa kolonial, di masa ini diekspor menuju wilayah jajahan budaya. Negara yang “beradab” adalah negara yang sepenuhnya sekuler seperti di Eropa (walaupun negara yang sepenuhnya sekuler itu sendiri pada tataran praksisnya hanya mitos belaka). Kekuatan agamis di wilayah jajahan budaya ditakuti oleh pihak penjajah karena potensinya untuk membangkitkan revolusi dan perlawanan. Dalam tatanan hegemonis macam begini, setiap tatanan alternatif adalah ancaman bagi pihak penguasa.
Praktik penjajahan yang berlangsung berabad-abad lamanya membawa banyak penyakit pascakolonial di tubuh masyarakat yang dijajah. Berbagai paradigma dan gerakan feminisme di wilayah bekas jajahan termasuk salah satu yang menderita penyakit pascakolonial paling parah.
Ada tiga gejala utama yang bisa dilihat dari gerakan dan pemikiran feminisme yang sedang menderita penyakit pascakolonial. Pertama, permusuhan terhadap tatanan-tatanan alternatif yang disodorkan oleh agama. Feminisme sekuler yang melakukan invalidasi terhadap kehadiran konsep-konsep kedirian, ketubuhan, dan agensi non-sekuler adalah feminisme yang sedang menderita penyakit penjajahan, dan sebaliknya.
Kedua, ketidakmampuan untuk berpikir di luar kerangka oposisi biner. Seperti yang sudah disebutkan, berhubung logika penjajahan berjalan di atas prinsip alienasi biner, maka logika feminisme yang berlaku juga didasarkan pada prinsip serupa (contoh, kalau kau beragama, tidak mungkin kau bisa bertindak kritis. Kalau kau mampu menjadi kritis, tak mungkin kau beragama) merupakan logika feminisme penjajahan.
Dan ketiga, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan ideologis gerakan. Feminisme dengan logika penjajahan tidak mampu berimajinasi di luar kerangka pikir kolonial. Dengan demikian, setiap denyut kebutuhan, ancaman, dan metode gerakan dari feminisme macam ini akan selalu membeo “tuan-tuan kolonialnya”. Apa yang menjadi kebutuhan narasi imperialis di Eropa dan Amerika Serikat menjadi kebutuhan para feminis dalam gerakan ini. Demikian pula dengan ancaman dan laku gerakan yang sedang trendi di Eropa dan Amerika Serikat, akan menjadi trendi dalam pandangan feminisme macam ini.
Hasilnya? Gerakan feminisme yang menderita penyakit pascakolonial menjadi gerakan feminisme yang tidak relevan bagi kehidupan banyak perempuan di wilayahnya sendiri.
Parahnya, proses penyembuhan dari penyakit pascakolonial ini rumit dan sulit sekali untuk dilakukan karena penderita umumnya merasa bahwa ia sehat-sehat saja.
Kerangka pikir hitam-putih ala kolonial menyodorkan kenyamanan moral yang sulit untuk ditolak. Siapa yang tidak mau tinggal dalam perbedaan biner di mana diri selalu benar dan liyan selalu salah? Siapa yang punya waktu untuk memikirkan berbagai bentuk ekspresi identitas diri yang jauh dari label kebebasan seksual? Mengapa susah-susah mencari setan patriarki dalam diri sendiri jika dapat dengan mudah menunjuk jari kepada setan patriarki dalam tubuh agama atau budaya tradisional? Mengapa ribut mempertanyakan diri jika berbagai kebutuhan dan ancaman dapat dengan mudah diperoleh dari mimpi-mimpi perempuan penguasa koloni macam Margaret Atwood? Mengapa sibuk berimajinasi jika bisa memilih untuk disuapi?
Terlepas dari narasi umum feminisme imperial, sebenarnya menjadi subjek itu tidak mudah karena kerumitan berpikir yang merupakan bagian dari kewajibannya. Menjadi subjek berarti melawan arus dominasi berpikir, dan dengan demikian tidak pernah menjadi trendi. Menjadi subjek berarti terus-menerus mempertanyakan diri akan seberapa bebaskah kita dari pola pikir tuan-tuan kolonial.
Lailatul Fitriyah adalah mahasiswi doktoral Program Studi Agama-agama Dunia dan Gereja Global di University of Notre Dame, AS.












