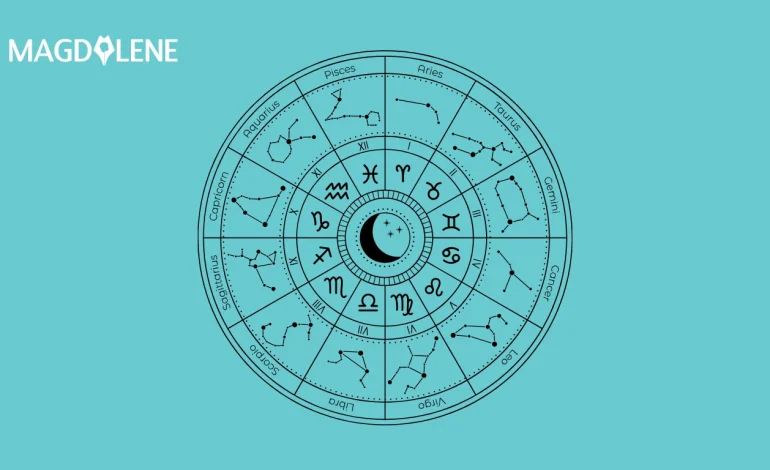Tren Fotografi Lari: Ada Peluang Ekonomi, Ada Pelanggaran Privasi

Selain bangun Subuh, buatku, hambatan lari pagi setiap Minggu adalah menjumpai para fotografer olahraga. Mereka berjajar di trotoar Jalan Sudirman-Thamrin, area car free day Jakarta. Dengan kamera di tangan, para fotografer siap membidik subjek yang berolahraga.
Respons orang-orang beragam. Ada yang dengan sengaja berpose di depan kamera, tapi tak sedikit yang cuek dan tetap fokus pada aktivitasnya. Aku termasuk yang kedua. Bukan karena ingin terlihat cool atau anti-mainstream, tapi karena merasa tidak nyaman membayangkan berapa banyak jepretan yang diambil puluhan fotografer di lokasi.
Sebagai “subjek foto” yang tak pernah memberikan consent, aku merasa waswas sekaligus mempertanyakan: Ke mana sebenarnya foto-foto itu akan berakhir? Selain kemungkinan besar dijual lewat platform dokumentasi bernama FotoYu, tentu.
Yang jadi persoalan, platform ini juga tidak sepenuhnya menjamin keamanan. FotoYu mengumpulkan data biometrik wajah dan lokasi pengguna lewat fitur facial recognition—dengan alasan untuk memudahkan pencarian foto. Saat registrasi, pengguna diminta merekam wajah dari depan dan samping, sebelum menerima email konfirmasi dan bisa mulai mengakses akun.
Sistem ini membuatku mengurungkan niat mencari dokumentasi saat ikut lomba lari beberapa waktu lalu. Memang, dari sisi regulasi, FotoYu cukup transparan. Mereka menjelaskan penggunaan data dan komitmen terhadap keamanan digital. Namun tetap saja, ada celah penyalahgunaan, baik dari sisi sistem platform maupun dari fotografer yang menyuplai foto.
Baca Juga: Ancaman Deepfake: KBGO dan Gerak Perempuan yang Makin Rentan
Privasi di Ruang Publik dan Ancaman KBGO
Jika dilihat dari segi keamanan digital, fenomena ini memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan: Consent, privasi, dan fitur facial recognition. Sayangnya, fotografer olahraga sering kali melupakan ketiga hal tersebut. Asumsinya, selama berada di ruang publik, siapa pun berhak difoto.
“Menurutku bebas aja (untuk memfoto). Kalau fotonya disalahgunakan, baru yang difoto berhak menegur,” ujar Radit, 29, fotografer olahraga.
Teguran itu tak hanya berlaku jika foto disalahgunakan. Bagi Radit, ia akan menghapus dan tidak mengunggah foto-foto, jika subjek yang bersangkutan tak berkenan. Ini untuk menghargai orang lain dan menghindari perselisihan dengan pembeli.
Yang tak disadari adalah, pentingnya meminta consent sebelum memotret seseorang. Selain tidak semua orang nyaman difoto, setiap wajah merupakan identitas dan bisa mengidentifikasi setiap orang yang dipotret. Karenanya, setiap orang berhak menentukan bagaimana dirinya direpresentasikan, sehingga meminta consent adalah bentuk menghargai orang lain. Apalagi, foto-foto tersebut akan diunggah di platform digital.
Hal ini termasuk privasi, seperti dijelaskan Profesor Ilmu Informasi dari Cornell Tech Helen Nissenbaum dalam Privacy in Context (2010). Sebab, itu menyangkut bagaimana foto seseorang digunakan dan dibagikan. Dalam konteks foto-foto olahraga, fotografer akan mengunggah hasil fotonya di FotoYu dan media sosial. Jika dipotret diambil tanpa consent, subjek foto pun tak tahu pasti ke mana identitasnya disebarkan. Dan ini termasuk pelanggaran privasi.
“Kenapa pelanggaran privasi? Soalnya fotografer bukan memfoto suasana car free day sebagai ruang publik, tapi individu atau grup yang terdiri dari beberapa orang,” tutur Direktur SAFEnet Nenden Sekar Arum pada Magdalene.
Artinya, berada di ruang publik tidak otomatis berarti seseorang memberikan consent untuk dipotret, apalagi disebarluaskan. Keberadaan di ruang umum bukan “risiko bawaan” untuk direkam. Situasi ini berbeda dengan lomba lari atau acara formal, di mana panitia biasanya memberi informasi sejak awal bahwa peserta akan didokumentasikan, baik untuk kebutuhan promosi maupun unggahan di FotoYu. Dalam konteks ini, setidaknya ada transparansi dan pemahaman bahwa dokumentasi akan dilakukan.
Namun begitu, consent bukan berarti aman sepenuhnya. Subjek foto tetap berada dalam posisi rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan, baik oleh fotografer maupun platform yang mengarsipkan ribuan data visual.
Nenden bilang, penyimpanan ini membuat subjek foto rentan dimanipulasi, diseksualisasi, hingga menjadi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Dalam sistem seperti ini, tubuh bukan lagi sekadar terekam tapi dikomodifikasi. Ia dipindahkan dari ruang publik ke ranah digital yang jauh lebih sulit dilacak dan dipertanggungjawabkan.
Bahkan, kasus KBGO dari foto olahraga pun pernah terjadi di media sosial. Beberapa waktu lalu, akun Instagram dengan handle @ukhti.berlegging—kini akunnya sudah hilang—mengunggah foto-foto perempuan berhijab sedang berolahraga. Memiliki 55 ribu followers, akun tersebut menyeksualisasi perempuan berhijab yang memakai celana legging.
Kejadian ini mengingatkan kita pada pentingnya menghargai privasi. Salah satunya dengan mempertimbangkan consent seseorang sebelum memotret. Seksualisasi hanyalah salah satu isu, di ruang digital, foto yang beredar juga rentan dimanipulasi melalui teknologi seperti deepfake.
Masalah kedua muncul dari penggunaan teknologi facial recognition di platform FotoYu. Fitur ini memang memudahkan pengguna mencari dokumentasi foto secara cepat dan akurat. Setelah melakukan verifikasi wajah berbasis biometrik dan mengisi data lokasi, pengguna bisa mengakses foto-foto mereka—bahkan foto orang lain yang memiliki kemiripan wajah.
Meskipun FotoYu melarang pengguna membeli dokumentasi orang lain jika mereka tidak ada dalam foto tersebut, tetap ada potensi pelanggaran.
Di balik kemudahan ini, risiko keamanan tidak bisa diabaikan. Melalui data biometrik, sistem dapat mengidentifikasi banyak hal, termasuk gender, ras, usia, hingga ekspresi wajah yang dapat mencerminkan kondisi mental seseorang. Penggunaan teknologi ini pun rentan terhadap kebocoran data dan pencurian identitas, bahkan dengan penerapan sistem Anti Spoofing Liveness seperti yang digunakan FotoYu—yakni teknologi pencegah penipuan saat proses verifikasi wajah.
Yang menjadi perhatian lain adalah penyimpanan dokumentasi. Sesuai ketentuan platform, FotoYu menyatakan, hanya fotografer—sebagai kreator—yang dapat menghapus foto, dan itu pun hanya untuk dokumentasi yang belum terjual.
Radit cenderung memilih objek berdasarkan momen, estetika, dan ekspresi ketimbang sekadar memperlihatkan aksi olahraga. Namun, ia mengakui belum mempertimbangkan soal consent subjek saat memotret—terlebih di ruang publik. Ia juga menyebut di kalangan fotografer olahraga, belum ada kode etik yang mengatur pengambilan gambar.
Sementara pengguna dapat menghapus data identitas seperti lokasi, biometrik, profil, hingga unggahan, baik saat menghapus akun maupun atas permintaan. Namun, mekanismenya tidak dijelaskan secara rinci. Padahal, pengguna berhak tahu dan memastikan data mereka benar-benar sudah dihapus dari sistem.
Kerentanan-kerentanan ini menggambarkan adanya relasi kuasa yang melekat dalam praktik fotografi. Dalam On Photography (1977), Susan Sontag menulis memotret bukan hanya merekam, tapi juga memberi kesan kepemilikan atas subjek. Proses ini menimbulkan relasi kuasa yang kuat, di mana fotografer sebagai pemegang kamera memiliki kendali atas bagaimana subjek direpresentasikan.
Situasi ini juga terjadi dalam dunia fotografi olahraga. Ketika fotografer memotret tanpa izin, mereka otomatis menjadi pemilik gambar. Sementara subjek—meski wajahnya terpampang jelas—tidak tahu kapan foto itu diambil, digunakan untuk apa, dan diunggah ke mana. Ketimpangan ini diperparah oleh keberadaan platform marketplace seperti FotoYu, yang semakin menjauhkan subjek dari kendali atas data pribadinya.
Namun di sisi lain, pekerjaan sebagai fotografer olahraga juga menjadi sumber penghidupan.
Baca Juga: Menghindari Kebocoran Data: Tips Melindungi Data Pribadi
Antara Cuan dan Minimnya Literasi Privasi di Kalangan Fotografer
Dalam seminggu, Radit bisa memotret lebih dari dua acara olahraga, baik event besar maupun kegiatan komunitas. Cabang olahraga yang ia dokumentasikan beragam: dari Pilates, lari, hingga padel dan yoga.
Ia biasa mendapat klien dari agensi, sehingga gaya fotonya disesuaikan dengan permintaan. Misalnya menampilkan latar Jakarta, mengikuti pelari elite, atau menangkap momen pelari yang tos dengan penyorak.
Saat ditanya Magdalene, Radit enggan menyebut jumlah penghasilan. Baginya, menjadi fotografer olahraga cukup untuk memenuhi kebutuhan harian.
Sebelum bekerja sama dengan agensi, Radit sempat menjadi fotografer ngamen—istilah untuk mereka yang memotret acara publik seperti car free day dan mengunggah hasilnya ke FotoYu atau Google Drive. Pada 2022, ia mengamen di Mozia Loop, Tangerang Selatan. Karena saat itu belum ada platform seperti FotoYu, Radit menjual foto lewat tautan Google Drive yang ia sematkan di bio Instagram atau tawarkan langsung ke subjek fotonya.
“Lama-lama enggak enak, karena memaksakan orang untuk beli foto. Rasanya ganggu privasi juga,” ucap Radit.
Setelah FotoYu beroperasi, Radit sempat menjual hasil fotonya di sana, meski hanya sebentar. Ia merasa lelah harus membawa laptop untuk langsung mengunggah foto. Dari hasil ngamen di car free day untuk FotoYu, ia pernah mengantongi lebih dari Rp3 juta, terutama jika ada acara besar. Sementara jika hanya lewat Google Drive, penghasilannya berkisar Rp1 juta–Rp2 juta.
Radit cenderung memilih objek berdasarkan momen, estetika, dan ekspresi ketimbang sekadar memperlihatkan aksi olahraga. Namun, ia mengakui belum mempertimbangkan soal consent subjek saat memotret—terlebih di ruang publik. Ia juga menyebut di kalangan fotografer olahraga, belum ada kode etik yang mengatur pengambilan gambar.
Ketiadaan kesadaran soal consent ini merupakan dampak dari minimnya regulasi dan rendahnya literasi publik terhadap visual consent—bahwa setiap orang berhak menentukan apakah dirinya ingin didokumentasikan atau tidak. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi lebih menyoroti peran pengendali dan subjek data pribadi—dalam hal ini FotoYu dan penggunanya.
UU tersebut mengharuskan platform menetapkan masa penyimpanan data (data retention), namun FotoYu belum mengikuti ketentuan ini. Mereka menyerahkan penghapusan dokumentasi kepada fotografer dan pengguna.
Di sisi lain, belum ada hukum yang spesifik mengatur pengambilan foto.
Nenden menekankan, seharusnya ada aturan yang menegaskan untuk tidak mengambil gambar secara berlebihan sehingga merugikan subjek foto. Sebab, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), hanya bisa digunakan untuk kasus penyalahgunaan foto.
“Tapi kalau dilihat per kasus pun, (kedua UU) itu nggak bisa menyelesaikan masalah privasi. Soalnya spektrumnya sangat luas,” ungkap Nenden.
Jika praktik memotret tanpa consent dan menyimpan jejak digital orang lain terus dinormalisasi, kelompok rentan akan semakin terekspos terhadap penyalahgunaan foto—mulai dari perundungan, seksualisasi, hingga eksploitasi data untuk melatih sistem AI diskriminatif atau dijual ke pihak ketiga.
Sayangnya, kekosongan hukum dan rendahnya kesadaran publik membuat beban perlindungan identitas jatuh pada individu yang sudah lebih sadar akan isu ini.
Baca Juga: #VampirData: Bagaimana Teknologi AI Mengisap Sumber Daya
Apa yang Bisa Dilakukan?
Perlindungan privasi seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan meningkatkan literasi publik. Platform seperti FotoYu bisa memperketat jenis konten yang diunggah fotografer, serta menghindari angle yang mengeksploitasi subjek.
Fotografer juga perlu memahami isu privasi dan menyusun kode etik pengambilan gambar agar lebih bertanggung jawab.
Namun, karena perubahan struktural butuh waktu, ada langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan individu.
“Menempelkan stiker di pakaian, atau kaos bertuliskan ‘do not photograph’, bisa jadi cara agar fotografer tidak mengambil gambar,” terang Nenden.
“Ini kompleks dan butuh pemahaman bersama. Bisa dimulai dari konsep privasi, karena orang Indonesia masih awam tentang ini.”