Objektifikasi Festival ‘Breastfeeding’: Gagal Paham Publik tentang Reproduksi Perempuan
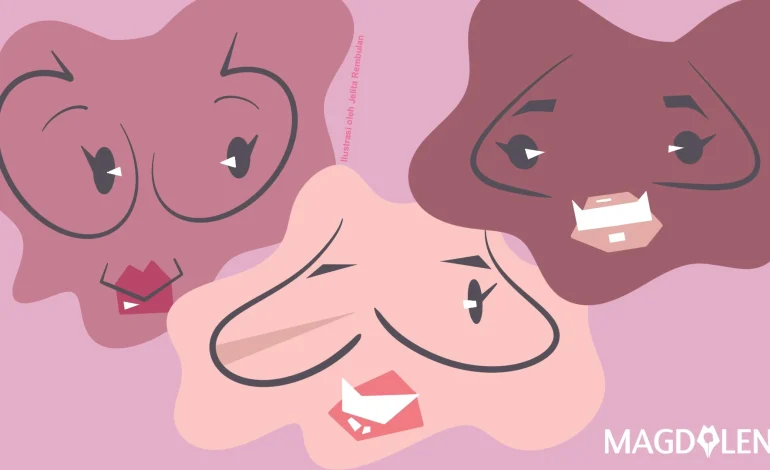
Pada 1–3 Agustus lalu, Komunitas Pejuang ASI Mom Uung mengadakan Breastfeeding Fest 2025 di Jakarta. Festival ini lahir dari niat baik, yakni mendukung perempuan hamil dan menyusui dalam perjalanan panjang menjadi ibu.
Ada banyak kegiatan yang ditawarkan, mulai dari pilates untuk ibu hamil, olahraga dengan seputar menyusui, hingga konser musik yang menghibur. Semua dirancang agar para ibu dan calon ibu merasa punya ruang aman, dikelilingi komunitas yang memahami perjuangan mereka.
Namun, alih-alih mendapat apresiasi, acara ini justru menuai cemoohan di media sosial. Komunitas yang digagas oleh Uung Victoria Finky, konselor ASI, diserang dengan komentar-komentar seksis.
Akun @mood.jakarta pada (5/8) lalu mengunggah ulang berbagai komentar di X (Twitter) yang bernada merendahkan. Ada yang menyebut festival ini sebagai “ajang nenen bareng-bareng,” ada yang bilang “festival payudara,” bahkan ada yang pura-pura antusias ingin mendaftar hanya demi “melihat pemandangan.”
Komentar-komentar ini memperlihatkan betapa tubuh perempuan masih sering diobjektifikasi. Bahkan dalam konteks yang seharusnya sakral dan penuh perjuangan: Menyusui. Ruang aman yang dibangun di festival ini mendadak terasa terancam ketika publikasi acaranya masuk ke ruang maya. Alih-alih dipandang sebagai bagian dari kesehatan ibu dan anak, tubuh perempuan sekali lagi direduksi hanya pada objek seksual.
Objektifikasi itu menguak satu hal penting, yakni minimnya pemahaman masyarakat, khususnya laki-laki, tentang proses reproduksi perempuan. Padahal, pengalaman hamil, melahirkan, dan menyusui bukan hanya urusan medis, tapi juga sarat dengan tantangan fisik, emosional, dan sosial.
Baca juga: Dear Ibu, Jangan Lupa ‘Me Time’ Jadi Kunci ‘Parenting’ Sehat
Anggota Keluarga Perempuan Belum Tentu Bisa Jadi Ruang Aman
Komentar seksis di dunia maya ini sempat direspons oleh para pejuang ASI. Banyak perempuan menegaskan laki-laki perlu tahu: Menyusui bukan hal mudah. Tidak semua ibu bisa langsung memproduksi ASI dengan lancar, dan itu sering menimbulkan rasa bersalah yang besar. Di titik inilah, dukungan seharusnya hadir. Sayangnya, tekanan justru sering datang dari keluarga sendiri.
Saya masih ingat ketika menjenguk teman kuliah yang baru saja melahirkan. Baru 24 jam pasca-persalinan, ia sudah dibombardir oleh ibu dan tantenya dengan berbagai nasihat agar segera memproduksi ASI. Padahal, dokter dan perawat sudah menjelaskan ASI akan keluar seiring waktu, biasanya saat bayi bangun.
Namun suara tenaga medis itu dikesampingkan. Ibu dan tantenya lebih percaya pada mitos dan stigma sosial bahwa “ibu yang baik” harus langsung bisa menyusui. Teman saya hanya terdiam, menahan tekanan dari orang-orang terdekatnya.
Pengalaman lain datang dari sahabat saya yang mendapat bantuan dari kakak perempuan setelah melahirkan. Sang kakak mengatur jadwal pijat laktasi, memberikan banyak tips, hingga menekan agar tidak memberi susu formula. Padahal sahabat saya sudah berencana menambah nutrisi bayinya dengan susu formula agar lebih tenang. Namun karena takut dicap sebagai “ibu buruk,” ia akhirnya menurut saja.
Tekanan itu tidak berhenti di ibu baru. Seorang rekan kerja saya, yang sudah punya dua anak, pernah mengalami mastitis hingga harus operasi. Ia menjalani sakit itu dalam diam, tidak ingin terlihat “lemah” sebagai ibu. Ia mengaku sudah terbiasa menormalkan rasa sakit, karena di masyarakat, beban reproduksi dianggap takdir perempuan yang tak boleh dikeluhkan.
Ketiga cerita itu menunjukkan satu hal: Bahkan sesama perempuan di dalam keluarga pun bisa memperkuat stigma, alih-alih memberi ruang aman. Bukan berarti niat mereka jahat—kebanyakan berasal dari keinginan membantu—tetapi tekanan berlapis inilah yang membuat ibu baru makin rapuh.
Dalam konteks ini, acara seperti Breastfeeding Fest menjadi oase langka, ruang di mana perempuan bisa bertukar pengalaman tanpa dihakimi.
Baca juga: Women and the Moral Imperative of Breastfeeding
Suami Sebagai Ruang Aman dan Pendukung Utama Ibu Hamil dan Menyusui
Ruang aman yang paling krusial justru ada di tangan suami. Ketika ibu baru rentan terkena stres dan Baby Blues Syndrome, peran suami menjadi penentu. Sayangnya, masih banyak laki-laki yang merasa urusan ASI, melahirkan, dan pengasuhan anak hanya tanggung jawab perempuan. Padahal penelitian menunjukkan, keterlibatan ayah berpengaruh langsung pada kualitas kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi.
Aliansi Laki-Laki Baru (ALB) sudah lama mengampanyekan peran ayah dalam proses reproduksi. ALB menekankan pentingnya dukungan laki-laki sejak masa kehamilan, persalinan, hingga menyusui. Suami bukan hanya penonton, melainkan aktor penting yang bisa membantu istri menghadapi tekanan keluarga, stigma sosial, dan tantangan medis.
Breastfeeding Fest 2025 sebenarnya sudah mengakomodasi hal ini. Kegiatan tidak hanya ditujukan untuk ibu, tapi juga ayah. Ada talkshow bersama, kompetisi anak, hingga olahraga keluarga. Kehadiran ayah di ruang seperti ini bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari pendidikan bersama.
Sayangnya, komentar-komentar seksis di media sosial menunjukkan pola pikir ini belum meluas. Masih banyak laki-laki yang lebih cepat mengobjektifikasi tubuh perempuan daripada memahami perjuangan reproduksi. Di sinilah pentingnya melanjutkan edukasi, bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki.
Baca juga: The Truth about Trend of New Mothers Drinking the Breast Milk
Melawan pola pikir masyarakat yang masih merendahkan perempuan memang tidak mudah. Namun prioritas utama harus tetap pada mereka yang benar-benar membutuhkan: Para ibu yang sedang menjalani proses reproduksi. Edukasi lewat talkshow, edutainment, dan festival seperti Breastfeeding Fest perlu dilakukan lebih sering dan lebih luas. Semakin banyak ruang aman yang dibuka, semakin besar pula peluang mengikis stigma yang sudah mengakar.
Objektifikasi terhadap tubuh perempuan tidak boleh lagi menghalangi ibu hamil dan menyusui untuk mendapatkan dukungan. Masyarakat harus belajar reproduksi bukan hanya urusan perempuan, melainkan kerja bersama yang menuntut empati, kesadaran, dan partisipasi laki-laki.
Retno Daru Dewi G. S. Putri adalah pengajar bahasa Inggris di Lembaga Bahasa Internasional, Universitas Indonesia. Topik yang diminati Daru meliputi isu gender, kesehatan mental, filsafat, bahasa, dan sastra.






















