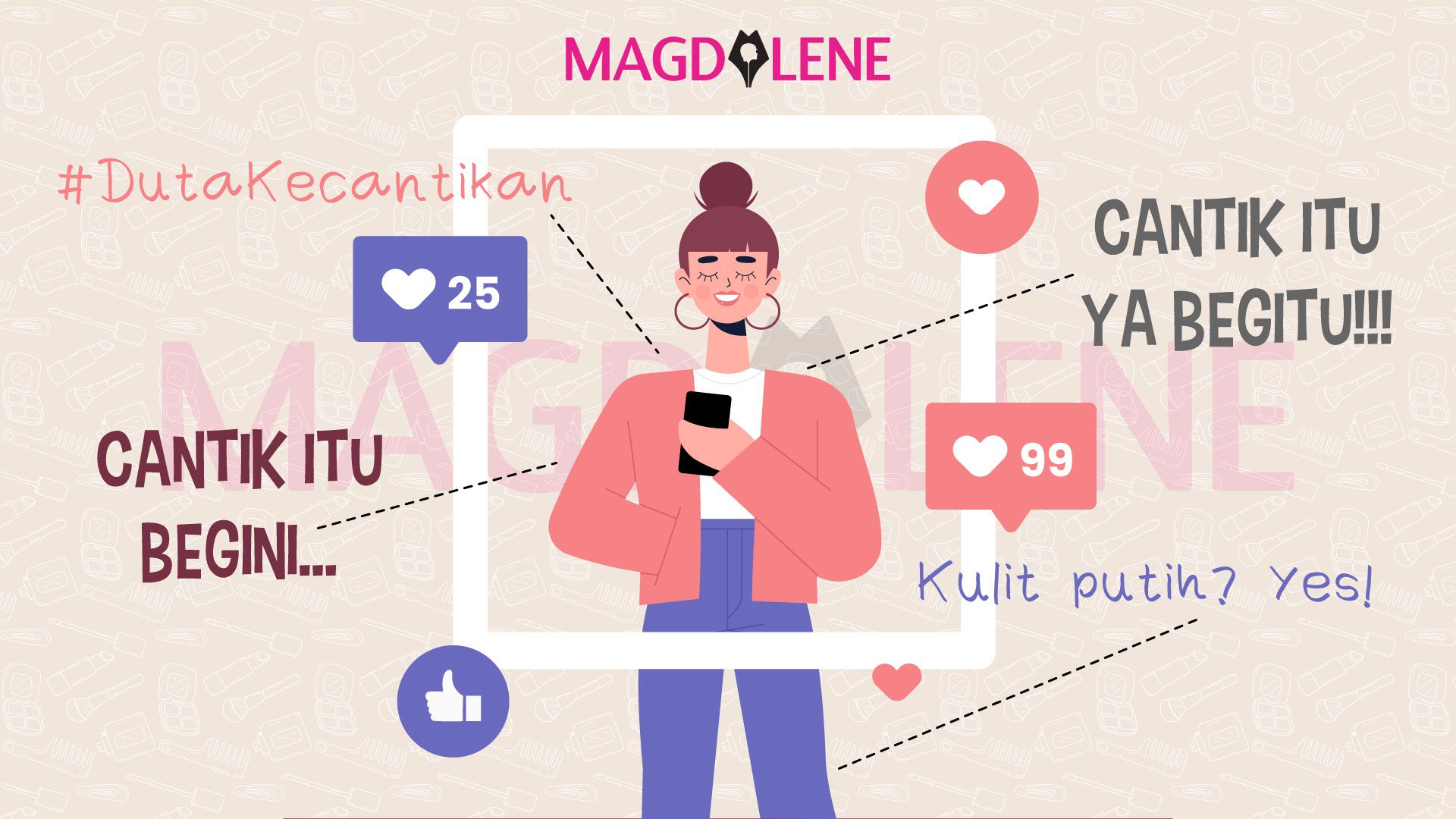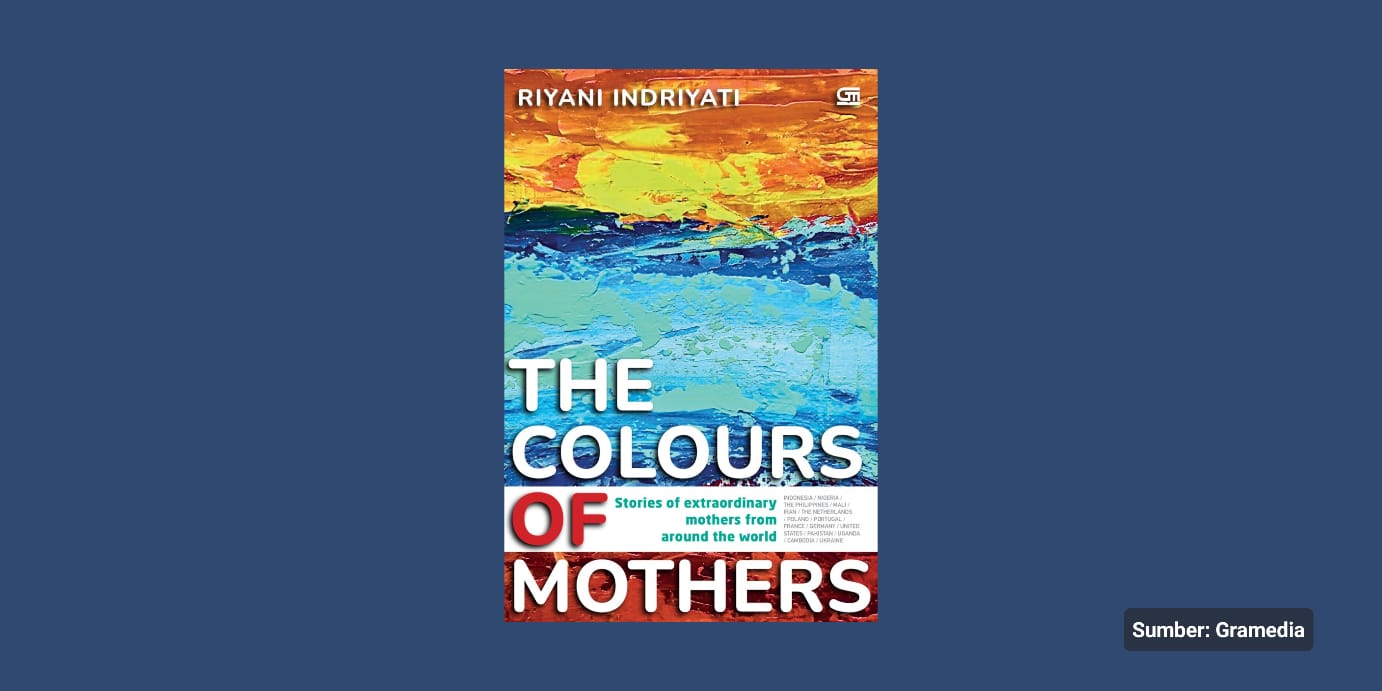Jerat UU ITE: 9 Pasal Karet yang Bisa Kirim Kita ke Penjara
SAFEnet mencatat, ada sembilan pasal UU ITE yang belum berperspektif gender dan hak digital. Hal ini semakin merentankan korban kekerasan, minoritas gender, dan sejumlah profesi.

Ada sembilan pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bermasalah, kata Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). Dalam diskusi berjudul “UU ITE v.3.0: Catatan Masyarakat Sipil untuk Kebijakan yang Peka Gender dan Berperspektif Digital”, (25/4) dijelaskan, pasal-pasal itu rentan mereviktimisasi korban kekerasan atau membungkam ekspresi publik.
Menurut aktivis Fatia Maulidiyanti, UU ITE bahkan membuat perempuan semakin rentan terhadap kekerasan berbasis gender. Dalam hal ini, UU ITE mengabaikan keragaman identitas perempuan, dari suku, ras, agama, identitas gender, kelas, orientasi seksual, hingga pekerjaan. Alhasil, kekerasan berbasis gender jarang dilihat sebagai isu yang setara seperti bentuk kekerasan lainnya.
Berikut penjelasan sembilan pasal yang dimaksud:
Baca Juga: Magdalene Primer: UU ITE Kriminalisasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual
1. Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 terkait Pidana Kesusilaan
Kedua pasal ini mengatur pidana penjara paling lama enam tahun, dan/atau denda paling banyak senilai Rp1 miliar, bagi setiap orang yang sengaja tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, untuk diketahui umum.
Sebenarnya, Pasal 27 Ayat 1 adalah duplikasi dari Pasal 407 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalamnya mengatur perbuatan yang termasuk pidana kesusilaan. Misalnya melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.
Namun, ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam pasal ini. Pertama, kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 1 hanya berdasarkan pada moralitas, dan mengesampingkan isu-isu gender maupun HAM.
Kedua, tak ada tolok ukur yang jelas untuk frasa “untuk diketahui umum”—apakah lebih dari satu orang, atau sekelompok masyarakat. Hal ini multitafsir sehingga tidak dapat menjamin kepastian hukum.
Ketiga, perspektif yang digunakan masih subjektif dan patriarkis, sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pemaknaan kasus. Sebab, pengadilan bisa memaknai unsur “melanggar kesusilaan” secara beragam.
Di samping itu, ada kemungkinan Aparat Penegak Hukum (APH) mengkriminalisasi korban kekerasan seksual. Ini lantaran unsur “menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya” mengakibatkan pengabaian terhadap perspektif korban. Akibatnya, korban rentan dijerat pidana sebagai pelaku.
Misalnya, seperti pemidanaan yang dialami Baiq Nuril, eks guru honorer di SMAN 7 Mataram satu dekade lalu. Saat itu, Mahkamah Agung menyatakan Nuril bersalah, dan menerima hukuman enam bulan penjara serta denda senilai Rp500 juta. Namun, Nuril meminta amnesti ke Presiden Joko Widodo, yang dikabulkan dengan alasan kemanusiaan.
2. Pasal 27A juncto Pasal 45 Ayat 4 UU ITE tentang Penyerangan Kehormatan atau Nama Baik Orang Lain
Dalam pasal ini tertulis, setiap orang yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik, dipidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta.
Yang termasuk menyerang kehormatan atau nama baik, adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain, sehingga merugikan orang tersebut. Termasuk menista dan/atau memfitnah.
Sebenarnya, penjelasan “menyerang kehormatan atau nama baik” masih multitafsir karena tak ada indikator perbuatan yang dimaksud. Sementara dalam prinsip hukum pidana, rumusan delik pidana harus jelas—atau disebut lex carta. Begitu pun dalam Pasal 19 Ayat 3 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Dijelaskan bahwa pasal pencemaran nama baik perlu dirumuskan dengan jelas, dan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan kebenaran atau verifikasi.
Melihat implementasinya, pasal ini sering digunakan oleh penguasa—termasuk lembaga negara—untuk mengkriminalisasi masyarakat yang kritis dan memperjuangkan haknya lewat berpendapat. Bahkan, produk jurnalistik pun rentan terjerat. Padahal, setiap orang bebas berpendapat dalam bentuk apa pun; lisan, tertulis, berupa karya, atau media lain yang dipilih.
Sementara bagi korban kekerasan seksual—termasuk KBGO—yang mencari keadilan dengan spill the tea di medsos, rentan mengalami reviktimisasi. Sebab, pelaku bisa melapor dengan pasal ini. Karena itu, dalam kasus kekerasan seksual, seharusnya tidak diberlakukan pasal penyerangan kehormatan atau nama baik.
Sayangnya, banyak APH belum berperspektif korban maupun gender. Pelaporannya pun seharusnya dialihkan ke Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), supaya korban mendapatkan haknya.
3. Pasal 27B Ayat 2 juncto Pasal 45 Ayat 10 tentang Pemerasan dan Pengancaman
Pasal ini menyebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia dan memaksa orang.
Tujuannya dua: Pertama, memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Kedua, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Sanksinya berupa pidana penjara paling lama enam tahun, dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.
Namun, frasa “ancaman pencemaran” bisa mengakibatkan multitafsir, lantaran tak memiliki indikator yang jelas—perbuatan apa yang bisa menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Karenanya, bisa dimaknai secara subjektif dan munculnya keberagaman putusan hakim—bahkan tindakan sewenang-wenang oleh APH.
Dalam implementasinya, tidak ada penjelasan dan pengaturan yang tepat maupun jelas, terkait jaminan data pribadi nasabah yang memiliki utang piutang. Akibatnya, data pribadi nasabah rentan disebarkan oleh pihak ketiga, seperti debt collector.
Pasal ini pun dapat menjerat nasabah yang berutang, diperlakukan tidak adil dalam proses penagihan. Misalnya lewat serangan massal atau penyebaran data pribadi tanpa consent. Dan membuat APH sulit membedakan tindak pidana yang termasuk dalam pemerasan dan pengancaman, atau perundungan.
Karena itu, dalam pasal perlu dijelaskan jenis utang piutang—bersifat daring atau luring. Tujuannya agar masyarakat memahami prosedur dan kewajiban pembayaran utang, terlepas dari jenis platform yang digunakan.
4. Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45A Ayat 2 terkait Kebencian atau Permusuhan berdasarkan SARA
Pasal yang merupakan duplikasi dari Pasal 243 KUHP 2023 ini menjelaskan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu, dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.
Bagi yang melanggar, dikenakan hukuman pidana penjara paling lama enam tahun, dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.
Ada sejumlah catatan untuk pasal tersebut. Pertama, menggunakan kata “transmisi”, yang artinya mengirimkan informasi elektronik lewat sistem elektronik dari satu individu ke individu lain, atau ke group chat yang tertutup.
Hal itu tidak selaras dengan KUHP, yang yang merumuskan, ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA dilakukan di muka umum. Padahal, tanpa unsur “di muka umum”, percakapan pribadi tidak memenuhi aspek publik bisa dipidana.
Kedua, rumusan UU ITE memuat kata “individu”. Ini membuat perbuatan yang termasuk dalam penghinaan individu dan yang tergolong ujaran kebencian, sulit dibedakan.
Ketiga, disabilitas yang tercakup belum cukup komprehensif, karena hanya menyebutkan disabilitas mental dan fisik. Padahal, ada jenis disabilitas sensorik dan intelektual.
Keempat, UU ITE ini tidak mencakup kelompok minoritas ras, agama, etnis, identitas gender, dan orientasi seksual. Mereka adalah kelompok yang paling rentan mengalami diskriminasi.
Akibatnya, pasal karet ini sering digunakan untuk mengkriminalisasi individu atau kelompok minoritas, yang memiliki keterbatasan dalam mengakses keadilan. Atau orang-orang yang bebas berekspresi, dan jurnalis yang mengkritik pemerintah dan penguasa.
Baca Juga: Isi UU ITE yang Tak Lindungi Korban KBGO
5. Pasal 28 Ayat 3 juncto Pasal 45A Ayat 3 terkait Penyebaran Berita Bohong
Menurut pasal UU ITE ini, setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong, yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun, dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.
Yang perlu diperhatikan, adalah frasa “pemberitahuan tersebut bohong” dan “mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat”. Kedua frasa tersebut tidak memiliki tolok ukur, sejauh mana pemberitahuan dikategorikan sebagai kebohongan—sehingga bisa menimbulkan multitafsir. Dampaknya, informasi atau dokumen elektronik berupa karya seni dan sastra yang satire pun, bisa dipidana.
Begitu pun dengan penggunaan kata “kerusuhan”, yang memerlukan indikator. Meski dijelaskan, kerusuhan yang dimaksud adalah yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan digital.
Dampaknya, profesi seperti jurnalis dan peneliti rentan dikriminalisasi dengan pasal ini. Pasal ini pun membatasi individu maupun kelompok dalam berekspresi—yang menimbulkan kemunduran dalam praktik demokrasi.
6. Pasal 29 juncto Pasal 45B terkait Ancaman Kekerasan
Disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik secara langsung kepada korban, yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti, akan dipidana dengan penjara paling lama empat tahun, dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.
Pasal tersebut tidak memiliki tolok ukur terkait “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti”. Karenanya, makna ancaman kekerasan dapat ditafsirkan secara bebas dan diimplementasikan dengan subjektif, sehingga tidak ada kepastian hukum.
Selain itu, pasal hanya menjelaskan akibat dari kekerasan atau cyber bullying, bukan pengertian dari ancamannya. Padahal, yang diperlukan adalah definisi dari cyber bullying, dan tindakan apa saja yang termasuk di dalamnya.
Melansir catatan SAFEnet, pelaporan kasus cyber bullying dengan pasal tersebut pernah dilakukan oleh Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN). Terdapat 12 mahasiswa yang diskors karena terlambat membayar biaya kuliah. Kemudian, mereka melakukan somasi dan upaya dialog pada pihak rektorat terkait keputusan itu, karena ke-12 mahasiswa juga menerima sanksi penghapusan nilai.
Lantaran Rektor ISTN merasa diancam, ia balik melaporkan ke-12 mahasiswa ke kepolisian dengan pasal ancaman kekerasan. Setelah diselidiki dan melakukan mediasi bersama Kemenristekdikti, laporan tersebut akan dicabut dan nilai yang dihapus akan dikembalikan.
Atas inisiatif tujuh orang advokat, pasal UU ITE itu pun mengalami gelar uji materil pada Juli 2020—dengan dasar tak ada parameter yang jelas dan menyebabkan multitafsir. Sebab, hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum, dan kemungkinan melanggar prinsip negara hukum.
7. Pasal 36 juncto Pasal 51 Ayat 2 terkait Data Pribadi
Pasal ini menyebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian materiel bagi orang lain, dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar.
Sebenarnya, Pasal 32 UU ITE yang tercakup dalam Pasal 36, berpotensi menimbulkan situasi dilematis bagi korban KBGO. Sebab, tak ada kejelasan dalam penggunaan kata “publik”—yang dimaksud adalah publik secara luas atau per orangan. Begitu pun dengan medium transmisi yang dimaksud—pesan pribadi atau yang bisa diakses publik.
Di samping itu, pasal ini cenderung digunakan untuk mengkriminalisasi pihak-pihak yang dinilai merugikan penguasa. Dengan kata lain, itu dapat melanggengkan konflik kepentingan, yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.
Sementara, korban sering kali tidak menerima ganti rugi yang semestinya, lantaran nominal denda cenderung dibayarkan pada negara. Alhasil, korban pun menerima ketidakadilan dalam penegakan hukum.
8. Pasal 40 Ayat 2a, 2b, 2c, adn 2d terkait Pencegahan Penyebarluasan dan Kewenangan Pemerintah Memutus Akses
SAFEnet mencatat, pasal ini memberikan celah bagi pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang. Sebab, tak ada mekanisme kontrol dari lembaga lain, terkait muatan yang bisa dikategorikan melanggar peraturan perundang-undangan.
Dampaknya, adalah penyensoran berlebihan termasuk pada konten yang dianggap mencemarkan nama baik pemerintah. Atau konten-konten hiburan, yang dinilai bertentangan dengan undang-undang multitafsir. Misalnya membuat konten—atau akun—tidak dapat diakses oleh pengguna internet.
Dengan kata lain, ini adalah bentuk otoritarianisme digital, yang berujung pada represi dan penurunan kebebasan berekspresi.
Contohnya adalah pelambatan dan pemutusan internet di Papua dan Papua Barat, oleh Kominfo pada 2019. Kejadian ini tak lama setelah peristiwa rasisme di asrama mahasiswa Papua.
Menurut majelis hakim, tindakan itu melanggar ketentuan UU ITE Pasal 40 Ayat 2a dan 2b. Padahal, pemaknaan pembatasan hak akses internet seharusnya dilakukan terhadap informasi atau dokumen elektronik, yang muatannya mencakup pelanggaran hukum.
Maka itu, diperlukan pasal yang mengatur konten ilegal, yang bertentangan dengan UU—bukan peraturan turunan. Sebab, peraturan turunan hanya mengatur secara teknis, tanpa mendefinisikan ulang perihal konten ilegal.
Baca Juga: Belajar dari Kasus Gilang, Penggunaan UU ITE untuk Kekerasan Seksual Keliru
9. Pasal 43 Ayat 3 dan Ayat 6 terkait Penggeledahan, Penyitaan, Penangkapan, dan Penahanan
Revisi UU ITE pada 2016 hingga saat ini, justru menghapus ketentuan izin dari pengadilan untuk menggeledah dan/atau menyita sistem elektronik, yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana di bidang teknologi informasi. Sama halnya dengan ketentuan, bahwa penyidik wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, untuk melakukan penangkapan dan penahanan.
Penghapusan itu berdampak pada pengambilan keputusan sewenang-wenang oleh penyidik, dalam melakukan upaya paksa. Lagi pula, seharusnya terdapat UU yang mengatur mekanisme upaya paksa dari ketua pengadilan negeri. Ini bertujuan untuk mengontrol penyidik, sekaligus jaminan atas perlindungan HAM.
SAFEnet menggarisbawahi, perlunya perhatian khusus terhadap pelanggaran hak individu yang bisa terjadi karena kemudahan penangkapan dan penahanan. Misalnya dengan mengintegrasikan perlindungan HAM supaya penegakan hukum tidak merugikan hak individu.