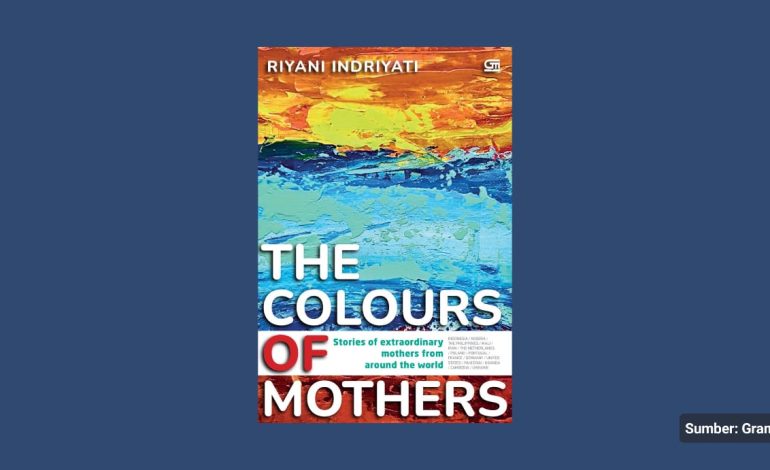Dear Sineas ‘Vina: Sebelum Tujuh Hari’, Filmmu Bukan Sarana Edukasi tapi Eksploitasi
Terang-terangan mengeksploitasi korban femisida, film ini banjir kecaman. Sineasnya dituding memprioritaskan keuntungan semata alih-alih keadilan.

*Peringatan: Gambaran femisida, kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap perempuan.
Sejak pertama kali rilis poster perdana pada Maret lalu, film Vina: Sebelum 7 Hari sudah jadi kontroversi. Film horor garapan Anggy Umbara yang diangkat dari kasus femisida di Cirebon pada 2016, menggambarkan korban, Vina, dalam wujudnya yang berdarah-darah. Dengan kepayahan, ia merangkak berusaha menyelamatkan nyawa dari kerumunan laki-laki yang memerkosanya.
Saat rilis resmi pada 8 Mei 2024, eksploitasi terhadap mendiang Vina semakin diperlihatkan tanpa malu. Dalam cuplikan rekaman layar bioskop yang beredar di X, film ini menampilkan adegan pemerkosaan eksplisit Vina oleh sebelas pelaku geng motor. Adegan ini diluluskan Lembaga Sensor Film (LSF) dengan dalih masih wajar untuk kategori 17 tahun ke atas, dan dibutuhkan sebagai konteks awal film.
“Artinya secara alur film, adegan ini harus ada karena memang itu bagian dari adegan yang kemudian memunculkan sebab-akibat di depan dan di belakangnya,” ungkap Ketua Lembaga Sensor Film (LSF), Rommy Fibri Hardiyanto pada BBC Indonesia.
Tak cuma adegan pemerkosaan eksplisit, film ini juga memutar rekaman suara Linda, sahabat Vina, ketika ia dirasuki arwah almarhum di akhir film. Dalam rekaman itu, Linda mendeskripsikan secara detail apa yang terjadi pada Vina.
Sejumlah warganet, kritikus film, hingga aktivis perempuan dibuat geram. Mereka mengecam Vina: Sebelum 7 Hari dengan memboikot dan tak ikut menonton atau mengulas filmnya. Alasannya, film tersebut mengeksploitasi korban femisida dan tidak memberikan penghormatan pada penyintas kekerasan seksual.
Baca Juga: Selingkuh dan Pernikahan, Kacamata Islam tentang ‘Layangan Putus’
Bukan Sarana Pendidikan tapi Ajang Penghakiman
Kecaman warganet, kritikus film, hingga aktivis perempuan cukup valid. Dari awal, Dee Company memang bertekad memuat adegan kekerasan seksual apa adanya. Tujuannya, penonton bisa memahami kejadian asli dan jadi sarana edukasi agar tak ada Vina-vina lain berikutnya, kata Dheeraj Kalwani, produser sekaligus CEO Dee Company kepada sejumlah media. Namun, pembelaan Dheraaj bak omong kosong. Jika memang film ini jadi sarana edukasi, lalu kenapa ia selalu mereduksi femisida Vina sebatas perundungan semata.
Padahal femisida dan perundungan jelas berbeda. Femisida berdasarkan Sidang Umum Dewan HAM PBB merupakan pembunuhan perempuan yang didorong oleh kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan, penikmatan, dan pandangan bahwa perempuan sekadar objek kepemilikan. Karena itu menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), femisida berbeda dari pembunuhan biasa apalagi bullying. Di dalamnya ada aspek ketidaksetaraan gender, dan terjadi di ranah privat, komunitas, maupun negara.
Pengreduksian femisida menjadi bullying pun berpengaruh pada bagaimana film ini berusaha keras menggambarkan Vina sebagai sosok “lemah dan tidak berdaya”. Penggambaran ini berhasil karena banyak orang di internet yang mengaku menikmati “ketidakberdayaan” Vina saat diperkosa.
Terkait ini, Şehriban Kaya, profesor feminis dari Dokuz Eylül University bilang, cara media memperlakukan adegan pemerkosaan dan penggambaran perempuan di dalamnya, tak lepas dari pandangan patriarkal yang sudah berakar. Perempuan, kata dia, akan selalu dilihat sebagai satu-satunya objek yang dapat dieksploitasi.
Karena itu, dalam media, perempuan hanya ditampilkan dalam dua cara. Pertama, objek erotis bagi laki-laki (jika film atau serial fiksi berarti karakter laki-laki, jika dokumenter berarti pelaku kekerasan). Kedua, sebagai objek erotis bagi audiens dalam relasi heteroseksual aktif/pasif. Dengan cara pandang ini, tak heran kekerasan perempuan sering kali masuk dalam kategori torture porn atau ‘pornografi penyiksaan’. Ini didefinisikan sebagai penggambaran perempuan lemah tak berdaya yang diperkosa dan disiksa secara brutal atas nama hiburan.
Torture porn menurut Kaya sebenarnya sama saja dengan melakukan erotisasi kekerasan terhadap perempuan. Pasalnya, seksualitas perempuan korban hampir selalu menjadi pusat perhatian. Lewat penempatan tersebut, media sebenarnya juga tak pernah memosisikan pemerkosaan sebagai isu serius melainkan komoditas belaka. Dalam film Vina: Sebelum Tujuh Hari, torture porn diperparah dengan sudut pandang laki-laki alias male gaze.
Akademisi film Laura Mulvey dalam esai Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) menjelaskan tentang ini. Kata dia, male gaze mengobjektifikasi perempuan lewat lensa kamera dan menggambarkan karakternya lewat hasrat laki-laki. Dalam budaya populer, male gaze merekam perempuan sebagai objek pasif yang berkaitan dengan penerimaan kepuasan seksual audiens laki-laki dengan melihat orang lain sebagai objek erotis.
Di film ini, kamera tak hanya menyorot Vina yang tidak berdaya, tapi juga salah satu yang tengah memerkosa Vina dan diperlihatkan puas berejakulasi. Penggambaran semacam ini punya konsekuensi yang fatal, menurut studi Centers of Disease Control and Prevention (CDC) tahun 2020. Konsekuensi ini bertahan lama dan serius bagi korban perempuan di kehidupan nyata.
Maksudnya, itu cenderung meningkatkan budaya victim blaming pada korban dan melanggengkan budaya pemerkosaan. Ini lantaran pemirsa “diajarkan” oleh media, pemerkosaan sebagai tindakan seks, bukan kekerasan.
“Jenis media ini mengirimkan pesan, kekerasan seksual adalah hal yang normal atau menyenangkan bagi korban. Itu menyebabkan pelaku kekerasan percaya, meniru perilaku ini tidak apa-apa,” tulis Olivia Egen, Laura M. Mercer Kollar, dkk dalam studi tersebut.
Dalam kasus Vina, bukannya mendapat pembelajaran soal femisida dan berempati pada korban, banyak penonton justru menudingkan jari pada Vina. Mereka menyalahkan mengapa ia menolak laki-laki pelaku pembunuhan dan pemerkosaan sambil meludah di depannya. Hal ini sempat disampaikan oleh Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan, dalam Instagram Live dengan Jakarta Feminist, Minggu, (12/05).
“Aku sepakat ini tidak sensitif dan tidak memberikan pendidikan pada publik bahwa ini adalah femisida. Bahkan ada komentar netizen yang mengatakan, ‘Makanya jangan menolak laki-laki’ atau ‘Kalau nolak laki-laki jangan kasar’. Ini orang meninggal, tapi kok kita mengatakan itu?” ucap Siti Aminah Tardi.
Baca Juga: Saatnya Tokoh Perempuan di Film Punya Stereotip Baru
Masyarakat Kritis, tapi Industri Tak Mau Berubah
Hingga hari keenam penayangannya, film ini sudah disaksikan oleh 2.548.478 orang. Angka bisa dibilang cukup fantastis, tetapi tentunya tidak bisa dijadikan patokan utama dalam menilai padangan seluruh masyarakat Indonesia.
Buktinya di tengah derasanya antusiasme, masih ada masyarakat Indonesia yang menolak tegas monetisasi korban femisida. Mengutip Kumparan.com, sejak awal perilisan poster, warganet dan pelaku industri film seperti Ian Salim mengingatkan untuk memboikot film ini demi menghormati korban kekerasan seksual.
Penolakan keras terhadap Vina: Sebelum 7 Hari juga bisa dilihat dari komentar dukungan dan jumlah likes (lebih dari 11.000) dalam unggahan Instagram aktivis perempuan Kalis Mardiasih (10/5). Dalam unggahan tersebut, Kalis mengritik pelaku industri dan jaringan bioskop Indonesia yang sekarang hanya berorientasi pada profit.
Penebalan perkawinan antara profit dengan duka, membuat pelaku industri luput terhadap konsen yang sebenarnya tak cuma berakhir pada pemberian izin untuk mengangkat cerita dan keterlibatan mereka dalam produksi. Tetapi konsen juga meliputi berbagai unsur yang kata Kalis termasuk unsur pembangun seperti considered, reversible, informed, specific, dan participatory.
Terbaru, Cine Crib, komunitas film dengan pengikut 283.000 dalam unggahan di YouTube menegaskan semua host mereka tidak akan membahas film Vina sama sekali dalam bentuk apa pun.
“Cine Crib TIDAK AKAN ngasih panggung buat film yang mengeksploitasi kekerasan dan kesedihan dengan cara tidak etis itu,” tulis mereka pada (13/5).
Melihat kerasnya penolakan film ini dengan alasan valid oleh sebagian masyarakat Indonesia memperlihatkan, Anggy Umbara, Dee Company, dan segenap kru yang terlibat menganggap semua masyarakat Indonesia bodoh demi sensualitas. Bagi mereka, film yang laris dan laku di pasaran lebih penting dibandingkan membuat karya humanis, terutama jika berhubungan dengan isu anti-kekerasan seksual.
Mereka yang memboikot film ini ogah dianggap “pasar” oleh para pelaku industri yang miskin empati. Mereka bukan objek pasif, tapi kritis dan bisa membedakan mana yang etis dan tidak. Sebenarnya diskursus soal penonton kritis sudah jauh bergulir. Ambil contoh penonton sinetron. Selama ini, pembuat sinetron membuat cerita berdasarkan “selera pasar” yang dinilai lewat rating TV. Padahal, menurut penelitian Televisi Indonesia: Dinamika struktur dan khalayak (2015), Dwitri Amalia, produser film dan kepala tim peneliti, penonton sinetron pun cukup kritis.
Amalia kerap mendengar kritik dari mulut penonton, terutama berkaitan plot cerita dan penggambaran tokoh perempuan.
“Saat itu lagi populer sinetron judulnya Catatan Hati Seorang Istri. Kita sempet ke satu keluarga, ibunya menonton. Celetukannya, ‘Berkali-kali diselingkuhi tapi kok masih tetep tabah?’ Lalu kami pergi ke keluarga lain. Dengan tontonan yang sama, ada bapak-bapak nyeletuk, ‘Ini enggak masuk akal sinetron. Hanya ngeliatin tangisin setiap episodenya’. Mereka ini mempertanyakan sinetron, kenapa sih potrayal-nya seperti ini? Mereka enggak bisa relate,” ucap Amalia pada Magdalene.
Sayang, imbuhnya, dinamika ini tidak tertangkap oleh pelaku industri sinetron dan membuat mereka terus-terusan memroduksi sinetron formulaik. Hal sama nampaknya juga terjadi dalam film Vina: Sebelum Tujuh Hari. Penonton dipukul rata sebagai pihak pasif dan target pasar empuk untuk meraup keuntungan dari eksploitasi femisida.
Baca juga: Sinetron ‘Buku Harian Seorang Istri’ Lestarikan Patriarki, Wajarkan Kekerasan
Karena itu, daripada menyalahkan penonton, pelaku industri film yang memiliki modal lebih besar harus mawas diri. Mereka punya tanggung jawab untuk membuat film yang lebih sensitif dan humanis. Film seperti ini tidak cuma hadir sebagai hiburan, tapi untuk perubahan (art for change). Bukankah itu yang sebenarnya intensi awal penggarapan film ini?
Aktivis perempuan Tunggal Pawestri dalam wawancaranya bersama BBC Indonesia menyarankan, pembuat film harus konsultasi dengan para aktivis atau lembaga perlindungan penyintas kekerasan seksual. Tujuannya agar bisa memastikan gambaran dalam film cukup sensitif dan tidak eksploitatif terhadap korban atau penyintas kekerasan.
Selain itu, pembuat film perlu mengedepankan standar yang menghargai hak dan martabat manusia, khususnya korban. Salah satu caranya dengan tidak kembali menciptakan narasi menyalahkan atau menyudutkan korban.
Ilustrasi oleh: Karina Tungari