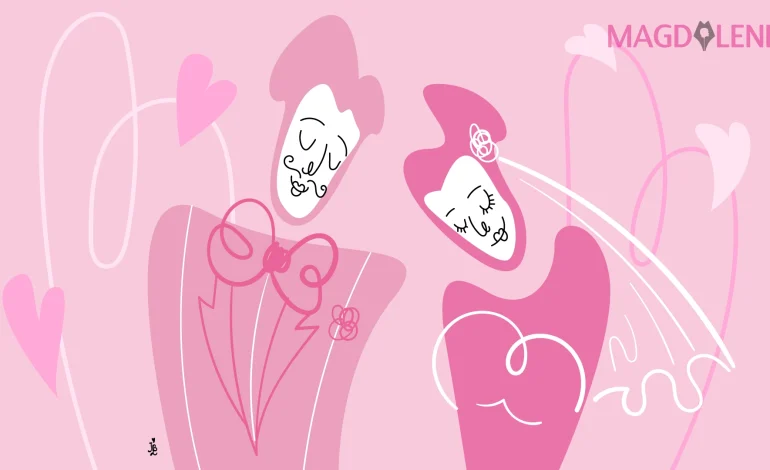
“Suami saya hebat, loh. Dia sering bantu cuci piring di dapur”
Kalimat ini sering terdengar sebagai pujian. Seolah-olah suami adalah sosok baik nan progresif karena membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Namun di balik nada positifnya, tersimpan masalah struktural yang luput disadari.
Pekerjaan domestik dianggap milik istri dan kontribusi suami dilihat sebagai aksi sukarela, bukan kewajiban. Kata “membantu” menandakan posisi subordinat suami dalam pekerjaan rumah tangga, bahwa hanya sedang menolong istri yang dianggap sebagai “pemilik sah” urusan domestik.
Dikotomi ini terus bertahan: suami sebagai pencari nafkah di ranah publik, sedangkan istri sebagai penjaga rumah tangga di ranah domestik. Parahnya, argumen keagamaan kerap digunakan untuk melegitimasi pembagian peran yang timpang ini. Padahal, ini adalah penyederhanaan yang berbahaya, bahkan bentuk miskonsepsi serius dalam fikih keluarga atau hukum keluarga Islam. Meletakkan pekerjaan domestik sebagai tanggung jawab tunggal istri adalah argumen yang tidak memiliki pijakan kokoh dalam filosofi inti hukum keluarga Islam.
Baca juga: ‘Kalau Gitu, Pakai Rok Aja!’ dan Suami yang Tak Lagi Diam-diam Bantu di Dapur
Akad nikah bukan kontrak kerja domestik
Akad nikah dalam Islam bukanlah kontrak kerja domestik. Ia adalah ikatan sakral (mitsaqan ghaliza), perjanjian kuat yang diikrarkan atas nama Allah, dan didasari oleh cinta, kasih, dan amanah. Jika cinta memudar, masih ada kasih. Jika kasih pun hilang, amanah sebagai bentuk tanggung jawab tetap harus dijaga. Dalam aspek sosial, akad nikah melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, termasuk pemenuhan nafkah dan perlindungan nasab.
Perlu digarisbawahi, akad ini tidak pernah mengandung redaksi, “Saya nikahkan anak saya untuk mencuci, memasak, dan membersihkan rumahmu.” Pernikahan bukan perekrutan Asisten Rumah Tangga. Ia adalah ikatan sosial dan spiritual yang melahirkan tanggung jawab timbal balik dalam membangun rumah tangga bersama secara setara.
Lalu dari mana datangnya anggapan bahwa istri bertanggung jawab penuh atas urusan domestik?
Baca juga: Belajar dari Kasus Sabrina, Benarkah Ibu Rumah Tangga Cukup Dibayar dengan Cinta?
Faktanya, para cendekiawan Muslim tidak satu suara dalam hal ini. Dalam bukunya Istri Bukan Pembantu (2019), Ahmad Sarwat menjelaskan bahwa banyak ulama dari berbagai mazhab tidak mewajibkan istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, mereka memandang tugas domestik sebagai tanggung jawab suami. Meski ada sebagian pendapat yang berargumen bahwa pekerjaan rumah merupakan “imbal balik” dari nafkah yang diberikan suami, pandangan ini sebenarnya merupakan hasil tafsir, bukan doktrin mutlak agama.
Sayangnya, tafsir inilah yang kerap dikukuhkan sebagai kebenaran tunggal. Ia menyebar dan menjelma menjadi doktrin sosial yang menyempitkan peran perempuan di ranah domestik. Pandangan semacam ini menjadikan rumah tangga sebagai struktur yang timpang, di mana kontribusi perempuan dianggap kewajiban mutlak, sementara partisipasi laki-laki dipandang sebagai “kebaikan tambahan”.
Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, tanggung jawab nafkah yang dibebankan kepada suami justru mengisyaratkan keterlibatan dalam kerja domestik. Nafkah yang wajib diberikan meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tiga hal ini, secara logis dan praktis, membutuhkan pekerjaan nyata, yakni memasak, mencuci, membersihkan, serta merawat lingkungan rumah. Dengan kata lain, suami tidak sekadar “membiayai”, tapi juga punya tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi secara layak.
Maka, jika tugas domestik dibebankan sepenuhnya kepada istri, itu lebih mencerminkan konstruksi sosial patriarkal ketimbang prinsip keagamaan yang normatif. Budaya patriarki secara global memosisikan laki-laki sebagai aktor utama di ruang publik dan perempuan sebagai pelayan di ranah domestik.
Ketika konstruksi ini dibungkus dengan legitimasi agama, lahirlah keyakinan bahwa perempuan wajib mengurus rumah sebagai “balas jasa” dari nafkah. Padahal, banyak kajian fikih dan gender Islam kontemporer menunjukkan bahwa penafsiran semacam ini sangat dipengaruhi oleh budaya dan konteks sosial tertentu, bukan wahyu itu sendiri.
Baca juga: ‘Pangku’: Perempuan Penopang Ekonomi Ambruk dan Debut yang Percaya Diri
Dari “membantu” menjadi “kerja sama”
Sudah waktunya kita mengoreksi istilah yang selama ini melanggengkan ketimpangan: suami yang mencuci piring, mengganti popok, atau mengepel rumah tidak sedang “membantu” istrinya. Ia sedang menjalankan tanggung jawabnya sebagai mitra dalam rumah tangga.
Dalam konteks keluarga modern, relasi suami dan istri bukan “majikan dan pembantu”, melainkan kerja sama tim atau kemitraan. Jika dianalogikan sebagai perusahaan, keduanya adalah pendiri bersama. Setiap aktivitas domestik—memasak, bersih-bersih, mengurus anak—adalah bagian dari strategi bersama untuk menjaga “perusahaan” ini tetap berjalan sehat.
Suami yang menyapu dan mengepel rumah tidak sedang “membantu” istri, melainkan menjalankan investasinya sendiri untuk “perusahaan” yang sedang dibangun bersama mitranya.
Menggeser narasi dari “membantu” ke “berbagi tanggung jawab” bukan hanya perubahan istilah, tapi perubahan cara berpikir. Ini langkah awal untuk menciptakan rumah tangga yang setara dan adil, bukan hanya bagi pasangan, tapi juga bagi generasi berikutnya yang akan tumbuh dengan nilai-nilai itu sebagai fondasi.
Muhammad Fakhri Amal adalah seorang konsultan independen dari peneliti hukum keluarga Islam yang fokus pada isu-isu gender dan hukum keluarga. Ia mendedikasikan dirinya untuk membantu individu dan organisasai mencipatakan ruang yang lebih adil dan inklusif.






















