Menemani Teman Hamil di Usia 13: Ketika Kepedulian Bisa Dipidana
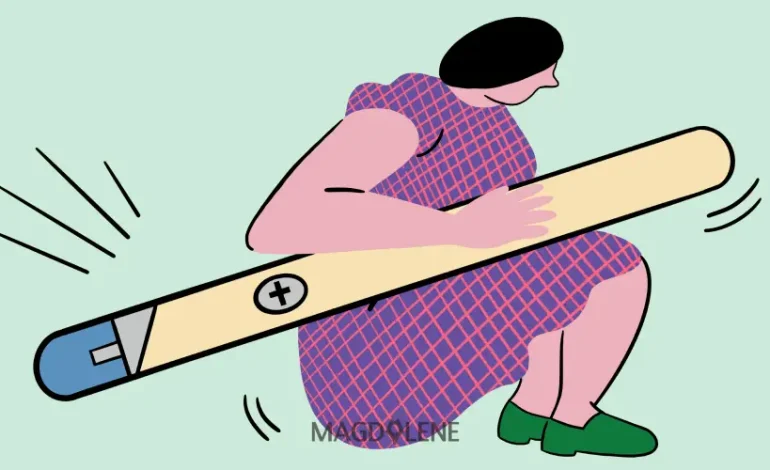
Saya menjadi pendamping sebaya sejak berumur 13 tahun, usia ketika saya dan teman-teman saya masih sibuk mencari jati diri. Saya mendampingi teman yang mengalami Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD) bukan karena punya rencana atau “minat” sejak awal, melainkan karena solidaritas sesama perempuan. Dalam rentang usia 13–17 tahun, saya mendampingi tiga orang teman yang semuanya juga remaja.
Waktu itu saya tidak punya pengetahuan yang cukup, tidak punya akses layanan, dan tidak punya kuasa apa pun. Tapi teman-teman saya datang membawa beban besar tentang tubuh, ketakutan, janin dalam rahim, dan pilihan-pilihan yang terasa mustahil di usia belasan. Yang bisa saya lakukan hanyalah mendengarkan, menemani, dan berusaha tidak menambah luka.
Baca juga: Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) yang Menghantui Perempuan
Saya ingat betapa mencari akses aborsi aman terasa seperti naik tebing tanpa pegangan. Sulitnya setengah mati. Di saat yang sama, saya juga harus berdebat dengan guru agar teman saya tetap boleh ikut ujian nasional, sementara rumor soal kehamilannya sudah terendus sekolah. Ada pula hari-hari ketika saya harus melakukan hal-hal yang terdengar tidak masuk akal, termasuk menampung urine saya sendiri dalam plastik es, karena orang tua mereka curiga melihat perut yang mulai membuncit. Semua dilakukan dalam diam, dalam sembunyi-sembunyi, dengan rasa takut yang lengket di badan.
Hingga hari ini saya tidak pernah benar-benar tahu mengapa mereka memilih bercerita kepada saya. Apakah karena saya dianggap lebih terbuka soal seks? Apakah karena saya menyukai perempuan dan karenanya terasa lebih aman? Atau karena saya tidak menghakimi? Yang saya tahu, mereka datang karena butuh seseorang yang bisa menahan panik bersama mereka. Saya sering merasa tidak cukup. Dan mungkin memang tidak cukup. Tapi di usia itu, itulah kapasitas terbaik yang saya miliki.
Pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian membawa saya bergelut di isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR). Panggilan ini tidak lahir dari jargon kebijakan, melainkan dari curahan hati panjang, tangis tercekat, dan pertanyaan-pertanyaan sulit yang sampai hari ini pun masih saya bawa. Dari sanalah saya belajar menjadi feminis, sebagai keberpihakan pada pilihan, otonomi tubuh, dan martabat manusia.
Bagi saya, pendampingan adalah kerja etis. Ia menuntut keberanian untuk menghormati pilihan, apa pun bentuknya: melanjutkan atau menghentikan, bertahan atau mengakhiri. Pilihan-pilihan ini tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia dibentuk oleh ketakutan, tekanan sosial, kekerasan, kemiskinan, dan sering kali oleh absennya negara. Menghormati pilihan berarti mengakui keruwetan itu, bukan menyederhanakannya menjadi soal “moral pribadi”.
Baca juga: Aborsi Paksa, Bagaimana Hukum Indonesia Mengaturnya?
Ketika cerita berubah menjadi angka
Pada 17 Desember 2025 publik dikejutkan oleh penangkapan tujuh orang dalam kasus aborsi di Jakarta Timur. Polisi menyebut dua klinik yang dituding ilegal telah melayani 361 pasien sejak 2022. Narasi yang dibangun cepat dan tunggal, yakni praktik ilegal, pelanggaran hukum, dan penertiban. Bagi saya itu bukan sekadar statistic, melainkan ratusan cerita orang yang menghadapi kehamilan tidak direncanakan dan tidak menemukan pintu lain yang aman.
Data menunjukkan bahwa kehamilan tidak direncanakan di Indonesia berada di kisaran 10,7 persen hingga 17,5 persen dari total kehamilan. Dampak terbesar adalah pada remaja dan kelompok rentan secara sosial ekonomi, menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017, Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) 2019, dan publikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 2025).
KTD berkorelasi dengan risiko komplikasi kehamilan, kematian ibu, hingga pengasuhan anak yang tidak layak. Pada 2023, angka kematian ibu tercatat 4.129 kasus atau sekitar 305 per 100.000 kelahiran hidup, angka yang masih jauh dari target nasional.
Mudah bagi negara melabeli sebuah aktivitas sebagai ilegal ketika akses yang legalnya sendiri nyaris tidak benar-benar tersedia. Meski aborsi dibolehkan secara terbatas untuk korban kekerasan seksual dan kedaruratan medis, hingga kini tidak ada kejelasan akses. Kementerian Kesehatan belum menunjuk fasilitas resmi penyedia layanan aborsi aman. Aturan terbaru justru mempersempit ruang, bahwa aborsi hanya boleh dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut, oleh dokter spesialis, dengan syarat administratif yang berat.
Lalu bagaimana dengan perempuan yang sudah tidak sanggup menanggung beban ekonomi keluarganya? Bagaimana dengan remaja? Bagaimana dengan mereka yang berada di daerah terpencil atau 3T (tertinggal, terdepan, terluar)? Bagaimana dengan korban kekerasan seksual yang bahkan sering kesulitan untuk sekadar bercerita?
Alih-alih dirayakan sebagai keberhasilan hukum, penangkapan dalam kasus aborsi justru mengungkap kegagalan negara menghadirkan perlindungan atas hak kesehatan dan kehidupan yang bermartabat.
Pengalaman saya mendampingi teman sejak usia belasan tahun memperlihatkan kenyataan pahit, bahwa pendamping sebaya sering hadir karena negara tidak hadir, atau tidak cukup peduli. Pendampingan yang lahir dari empati dan solidaritas justru berhadapan dengan ancaman kriminalisasi yang nyata.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023, khususnya Pasal 463–465, menyatakan bahwa setiap orang yang dianggap membantu, memfasilitasi, atau turut serta dalam praktik aborsi berisiko dipidana, tanpa pembedaan yang jelas antara praktik berbahaya dan pendampingan berbasis keselamatan serta informasi.
Baca juga: Yang Ideal dari Pendidikan Seks Komprehensif Remaja
Ancaman ini diperkuat dalam UU Kesehatan 2023 yang mempertahankan pendekatan pidana dan membuka ruang tafsir luas terhadap aktivitas edukasi kesehatan reproduksi, pendampingan, dan penyebaran informasi kontrasepsi. Dalam kerangka hukum seperti ini, pendamping sebaya ditempatkan dalam posisi serba salah. Mereka tidak diakui sebagai bagian dari sistem perlindungan kesehatan, sekaligus rentan diposisikan sebagai pelanggar hukum.
Bagi saya, ancaman ini terasa sangat personal. Saya mendampingi bukan karena ingin melanggar hukum, melainkan karena mereka adalah teman-teman saya. Jika pada usia 13 tahun saja saya sudah belajar bahwa mendengarkan dan menemani bisa menyelamatkan seseorang dari keputusan yang diambil dalam kepanikan, maka hari ini saya semakin yakin, pendampingan adalah kerja perawatan, bukan kejahatan.
Mengkriminalisasi pendamping sebaya berarti menghukum kepedulian dan memutus salah satu jaring pengaman terakhir di tingkat komunitas. Pada akhirnya, yang paling dirugikan bukan hanya para pendamping, tetapi mereka yang paling rentan. Yang kembali dipaksa menghadapi pilihan-pilihan paling berat dalam hidupnya sendirian, dalam diam, dan dalam ketakutan.
Ilustrasi oleh Karina Tungari






















