Pengalamanku Sebagai Perempuan yang ‘Ditempa’ Kurikulum Kita
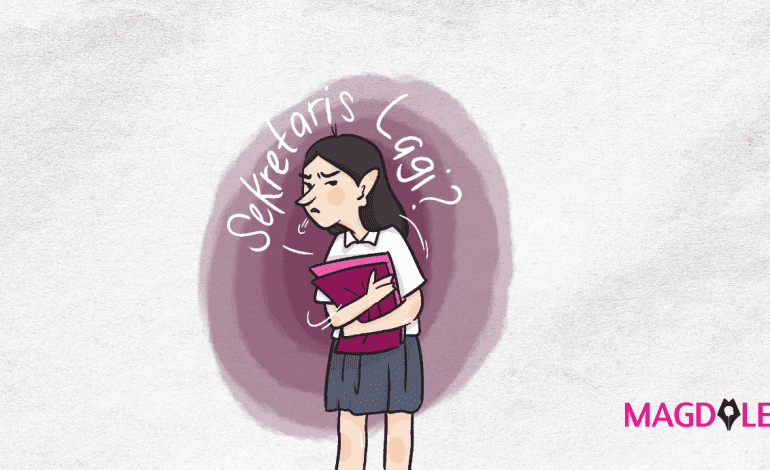
“Alika, kamu ada PR, enggak?” tanyaku pada Alika, murid kelas 1 Sekolah Dasar (SD) yang waktu itu jadi siswa di bimbingan belajar tempatku bekerja paruh waktu.
Yang ditanya menggeleng.
“Kalau gitu, Alika hari ini mau belajar apa? PKn, Bahasa Indonesia, atau Matematika?” tanyaku lagi.
Ia lalu menjawab ingin belajar PKn, singkatan untuk Pendidikan Kewarganegaraan. Buatnya mata pelajaran itu yang paling mudah. Kami lalu membaca buku cetak PKn yang dibawa Alika hari itu. Saat memasuki pembahasan tentang kegiatan sehari-hari, aku berhenti sebentar.
Di sana ada narasi dan ilustrasi tentang pembagian kerja. Anak perempuan digambarkan sedang menyapu lantai dan membantu ibu menjaga adik. Sementara anak laki-laki digambarkan sibuk belajar, dan bersih-bersih kebun bersama ayah. Narasi seperti, “Ibu pergi ke dapur menyiapkan sarapan” atau “Selesai sarapan ayah berangkat kerja” masih aku temui dalam buku cetaknya.
“Jujur, aku sempat tertegun dan kaget. Materi ajar yang ada di buku Alika masih sama dengan narasi yang diajarkan padaku, 18 tahun lalu, ketika aku seumuran Alika. Aku ingat sempat bertanya pada Alika, apakah guru di sekolahnya benar-benar mencontohkan pembagian kerja ini di kelas.”
Baca Juga: Pendidikan Perempuan untuk Siapa?
Dengan suara cemprengnya khas anak usia 7 tahun, Alika bilang, “Iya kak, Bu Guru ngajarinnya gitu di kelas. Kalau anak cewek tugasnya bantuin ibu, kayak nyapu. Bantuin ibu masak. Kalau cowok ya bantuin ayah.”

Mungkin terbilang naif, tapi waktu itu aku kaget karena ternyata pembagian kerja yang bias gender begitu masih ada di kurikulum generasi Alika. Bukankah banyak hal yang bisa berubah, dibangun, atau mungkin digusur dalam jarak 18 tahun?
Pengalaman itu bikin aku berefleksi tentang bagaimana kurikulum kita membentuk Alika, aku, dan perempuan-perempuan Indonesia.
“Jujur, aku sempat tertegun dan kaget. Materi ajar yang ada di buku Alika masih sama dengan narasi yang diajarkan padaku, 18 tahun lalu.”
Bias Gender dalam Pendidikan di Indonesia
Tadinya aku sempat mengira pendidikan Indonesia, kurikulum, serta pendidiknya sudah mulai berubah.
Apalagi semenjak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan, yang disusul Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Namun, ternyata tidak begitu.
Apa yang diajarkan pada Alika tak jauh beda dengan yang dulu diajarkan padaku saat masih kelas 1 SD. Dalam kurikulum terbaru, Kurikulum 2013 atau K-13, profesi-profesi tertentu masih dikaitkan dengan satu gender khusus.
Misalnya, pekerjaan yang berkaitan dengan teknik, seperti pilot atau arsitek, akan ditempelkan pada laki-laki. Sementara yang bersifat mengasuh, seperti guru, perawat, atau sekretaris akan jadi milik perempuan.
Penyajian materi yang bias gender ini kemudian erat dengan fakta, buku teks atau buku pelajaran mengomunikasikan pandangan pengajaran dan pembelajaran yang lekat dengan konteks sosial budaya dan pandangan masyarakat. Terutama, jika pengajarnya sendiri masih mengamini pandangan bias itu, istilahnya hidden curriculum alias kurikulum tersembunyi.
Istilah ini muncul pertama kali dalam buku Introduction of Women’s Studies (1996). Ia adalah bias sosial, yang disadari atau tidak oleh staf sekolah, yang ditanamkan dalam berbagai praktik sekolah. Bentuknya bisa berupa stereotip dalam buku pelajaran, isi pembicaraan di kelas, atau kegiatan ekstrakurikuler.
Salah satu contohnya adalah kebiasaan kita memilih perempuan sebagai sekretaris kelas. Dulu saat di SMA, aku pernah bertanya pada seorang guru, kenapa perempuan yang selalu ditunjuk jadi sekretaris? Jawabannya bikin aku garuk-garuk kepala. Katanya, karena anak perempuan lebih rajin dan lebih rapi menulis.

Padahal, di kelas kami ada Wildan, teman laki-lakiku yang tulisannya terkenal paling bagus dan rapi. Dia juga terkenal rajin, catatannya selalu lengkap dan dipinjami teman-temanku yang lain. Meski kualifikasinya cocok dengan jawaban guruku, Wildan tak pernah ditunjuk jadi sekretaris kelas.
Situasi serupa masih dialami Syafira, siswa SMP kelas 2 yang sekarang bertugas sebagai sekretaris kelas. Sepengalamannya sejak SD, yang ditunjuk jadi sekretaris memang selalu perempuan. Hal semacam ini yang kemudian diinternalisasi siswa dan bisa jadi diyakini sepanjang hidupnya. “Hanya perempuan yang boleh jadi sekretaris” memang tak pernah secara langsung diajarkan oleh guru, tapi berubah jadi persepsi yang diyakini karena praktiknya dijalankan bertahun-tahun.
“Aku, nih sekarang ditunjuk jadi sekretaris,” cerita Syafira. “Kalau ditanya tugasnya apa, sebenarnya, sih banyak. Aku yang nyatet materi di papan tulis, nyatet semua keperluan kelas, ngisi absen, sama nulis agenda kelas (agenda yang dikhususkan untuk mencatat setiap mata pelajaran dan guru yang mengajar),” curhatnya. Namun, Syafira sering kali merasa tidak mendapat apresiasi yang harusnya dia terima dari sang guru.
Baca Juga: Dear Perempuan, Pendidikan Tinggimu untuk Kamu Sendiri
Menurutnya, anak perempuan juga selalu diajarkan untuk lebih menerima keadaan, dan tidak terlalu didorong untuk terbuka mengungkapkan pendapat sebagaimana anak laki-laki.
“Anak perempuan di kelasku cenderung diem,” kata Syafira.
“Kalau aku kadang taku, sih, kayak takut salah, terus diejek atau diomelin. Aku soalnya pernah diomelin pas nanya, pas Bahasa Inggris salah pengucapannya terus gurunya rada tinggi suaranya.”
Efek Bias Gender dalam Pendidikan
Menerima keadaan dan tidak usah terlalu aktif atau pecicilan adalah ajaran yang juga tidak asing buatku. Aku ingat, dulu sempat iri pada kawan-kawan laki-lakiku yang lebih sering dapat perhatian khusus dari guru. Mereka juga cenderung didorong untuk aktif berbicara dan diberikan kesempatan berpendapat.
“Tidak boleh dimungkiri masyarakat kita masih memiliki cara pandang laki-laki dan perempuan memiliki posisi atau nilai yang tidak setara dengan laki-laki ditempatkan lebih tinggi,” kata Budhis Utami, Sekretaris dan Deputi Program Institut Kapal Perempuan, sebuah lembaga swadaya yang fokus dalam gerakan pendidikan alternatif perempuan.
“Sebagai bagian dari masyarakat otomatis cara pandang ini masih tertanam kuat dalam alam bawah sadar para pendidik dan para pengambil kebijakan. Inilah mengapa pendidikan kita sampai sekarang masih belum bisa setara dan adil gender,” tambahnya.
Konstruksi sosial dan budaya patriarki, nyatanya masih jadi momok utama akar dari permasalahan bias gender dalam pendidikan Indonesia. Kata Budhis, dalam konstruksi ini perempuan adalah sang liyan alias warga kelas dua. “Kurikulum boleh jadi netral gender, tapi sayang dalam praktiknya masih bias gender,” ungkap dia.
Anak-anak perempuan dididik untuk menjadi pasif, sehingga sangat sedikit dari kita yang didorong untuk berani bicara dan berpendapat. Ruang gerak pun dibatasi. Didikan macam ini punya efek masalah yang panjang, menurut Budhis. Sering kali perempuan jadi harus bekerja keras dua kali atau bahkan berkali-kali lipat dari laki-laki, karena indikator-indikator kompetisi yang ditentukan konstruksi patriarkal ciptaan laki-laki sendiri.
Dalam penelitian Persistency in Teachers’ Grading Bias and Effects on Longer-Term Outcomes: University Admissions Exams and Choice of Field of Study (2019), Victor Lavy dan Rigissa Megalokonomou dari Universitas Queensland, mengungkapkan fakta bahwa bias gender yang dialami murid perempuan dari gurunya punya efek jangka panjang. Ajaran selama bertahun-tahun tersebut mampu mendistorsi nilai siswa di sekolah dan pilihan studi mereka pasca-sekolah.
Masalah struktural ini yang kemudian bisa menjelaskan discouragement effect alias perasaan lebih rendah diri yang dialami Syafira dan teman-temannya. Pengalaman masa sekolah ini nyatanya akan berdampak ke kehidupan kita sebagai pekerja.
Persentase angka perempuan yang sekolah mungkin makin naik tiap tahunnya. Namun, ternyata makin tinggi jenjang pendidikan perempuan, semakin rendah pula jumlah perempuan yang berpartisipasi di dalamnya.
Sering kali perempuan jadi harus bekerja keras dua kali atau bahkan berkali-kali lipat dari laki-laki, karena indikator-indikator kompetisi yang ditentukan konstruksi patriarkal ciptaan laki-laki sendiri.
Pada 2019, misalnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan dalam perguruan tinggi hanya sebesar 19,89 persen dan hanya sekitar 0,36 persen perempuan yang mengenyam pendidikan S2 dan S3. Hal ini yang berpengaruh pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang masih tertinggal dari laki-laki. TPAK perempuan kerap berjalan stagnan selama 10 tahun dengan terus berada pada persentase 50 persen, sedangkan laki-laki berada pada presentasi 80 persen.
Dwi Yuliawati-Faiz, Ketua Program UN Women Indonesia, juga punya analisis serupa Budhis. Pendidikan Indonesia, katanya, masih bias gender. Hal itu dapat mudah sekali ditemukan pada kurikulum, pendidik, hingga infrastruktur sekolah sehingga jadi poin-poin penghambat kemajuan perempuan.
“Implementasi pendidikan di Indonesia ini root cause-nya itu ada di norm, gender patriarchal norm (norma patriarki) mengenai apakah perempuan bisa memasuki atau pantas menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” kata Dwi.
“Yang pada akhirnya membuat banyak perempuan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, berhenti di tengah-tengah, atau tidak masuk ke pasar kerja.”
Ada banyak aturan norma sosial yang masih dikekalkan dalam hidden curriculum di Indonesia. Padahal, seperti kata Dwi, pendidikan adalah awal semuanya, termasuk kehidupan yang lebih baik dan mimpi panjang untuk hidup setara.

Baca Juga: Jalan Terjal Jadi Kepala Sekolah Perempuan di Indonesia
Kurikulum Harus Bertransformasi
Di level global, pentingnya pendidikan buat perempuan sudah diusahakan sejak 1970-an. Ketika itu, ada kesadaran bahwa selama ini perempuan dipinggirkan dalam proyek pembangunan. Hari ini, program itu masih jadi inti Sustainable Development Goals (SDGs), agenda yang juga mengikat pemerintah Indonesia untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang baik buat perempuan.
Namun, hal itu akan sulit diraih jika pemerintah tidak merevolusi kurikulum kita. Kata, pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan afirmatif, seperti memberikan kuota beasiswa lebih banyak untuk anak perempuan. Sebab, kurikulum kita sekarang yang tampaknya netral gender, nyatanya tak betul-betul berpihak pada perempuan.
“Kenapa kuota ini penting? Ya, agar perempuan bisa lebih semangat belajar dan tentunya untuk meningkatkan partisipasi perempuan di jenjang pendidikan nantinya,” jelas Budhis.
Menurutnya, pemerintah juga perlu mengakui dan sadar, garis start anak perempuan dan laki-laki memang tidak sama sejak awal, karena konstruksi sosial. Setelah itu, membenahi materi pembelajaran siswa dan menyusun materi sendiri yang sensitif gender, lalu mengintegrasikannya ke setiap mata pelajaran.
Budhis sadar, perombakan kurikulum dan metode pengajaran perlu energi besar dan waktu yang bisa jadi lama. Makanya, ia menyarankan para pendidik yang sudah memiliki kesadaran kesetaraan gender untuk mengintegrasikan isu-isu gender dengan materi-materi pembelajaran atau ekstrakulikuler.
Hal itu dilakukan Suminah, guru SMP di Tanggul, Jember. Mimin, panggilan akrabnya, bercerita padaku, tentang usahanya mengintegrasikan isu-isu gender dalam berbagai praktik pembelajaran di sekolah, tempat dia mengajar.
Pendidik yang aktif dalam Gerakan Peduli Perempuan Jember sejak 1998 ini, berusaha memasukan pendidikan gender dalam materi OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler. “Misal pemaparan tentang apa sih gender itu, bedanya sama seks atau jenis kelamin apa, lalu baru masuk kasus atau praktik di desa seperti apa,” ceritanya padaku.
Menurut Mimin, penting untuk mengajarkan murid-muridnya berpikir kritis. “Di desa, perempuan ngomong bayi dan masak (itu wajar). Nah, (lalu) dijelaskan pada mereka, walaupun praktik umumnya demikian, bukan berarti itu takdir perempuan. Toh, nyatanya di desa banyak juga perempuan yang kepala keluarga. Ada juga ayah yang karena tidak bisa kerja, harus melakukan pekerjaan domestik,” cerita Mimin.
Pemerintah juga perlu mengakui dan sadar, garis start anak perempuan dan laki-laki memang tidak sama sejak awal, karena konstruksi sosial. Setelah itu, membenahi materi pembelajaran siswa dan menyusun materi sendiri yang sensitif gender, lalu mengintegrasikannya ke setiap mata pelajaran.
Tak hanya memberikan contoh, Mimin bahkan melakukan tindakan afirmatif dengan memasukkan pelatihan kepemimpinan perempuan dalam Latihan Kepemimpinan Dasar Siswa (LDKS) materi Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).
“Saya juga menerapkan partisipasi anak perempuan sebanyak 50 persen dalam setiap kepengurusan organisasi sekolah atau kepanitiaan. Hal ini dilakukan agar berimbang suara perempuan dan laki-laki. Setara dalam berbagai kegiatan, dan tidak hanya mengandalkan satu perspektif saja,” jelasnya.
Mimin sadar, anak perempuan dan laki-laki tak berangkat dari garis lari yang sama. Ia percaya, tindakan-tindakan afirmatif itu diperlukan agar makin banyak perempuan yang bisa jadi pengambil keputusan.
Diam-diam aku membatin, mengamini niat mulia Mimin. Andai guru macam Mimin adalah mayoritas, mungkin apa yang dirasakan Alika tak mirip-mirip amat sama yang kudapatkan, 18 tahun lalu.
Proyek jurnalistik ini didukung oleh Meedan, organisasi non-profit di bidang teknologi yang punya visi memperkuat literasi digital dan jurnalisme global.






















